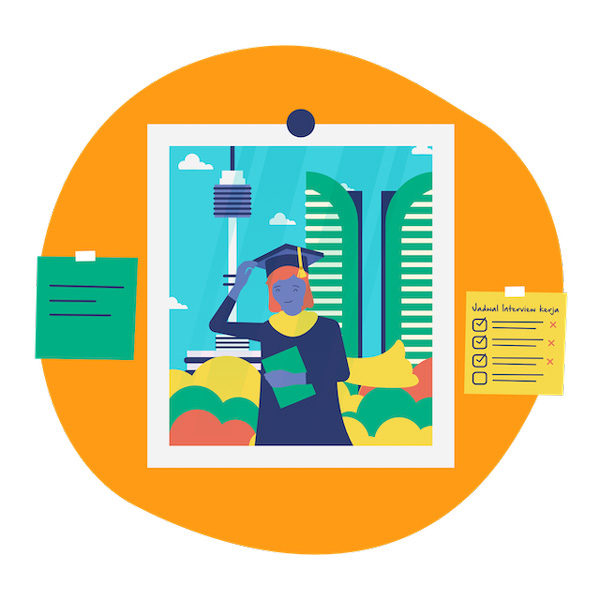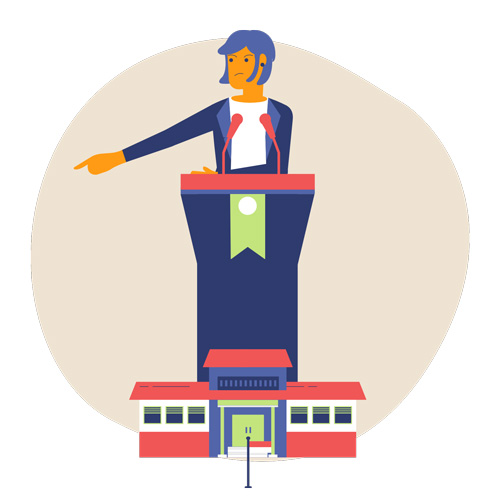
Dimensi Politik dalam Rekrutmen Guru
June 2, 2020
“Kenyamanan” dan Kebebasan dalam Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Orang Asing
June 2, 2020
Catatan Pinggir
Mendidik Desainer, Mendesain Pendidikan
oleh Qonita Shahab
Pengantar Redaksi:
Di Catatan Pinggir ini, Qonita mengisahkan pengalamannya berpartisipasi dalam sistem pendidikan yang berbeda di berbagai negara. Pengalamannya membuat Qonita sadar pentingnya pendidikan desain untuk mencetuskan, menjaga, dan meningkatkan kreativitas.
Isu pendidikan mulai saya pikir ketika usia saya masih belasan tahun. Kala itu, saya belajar di SMA Negeri 3 Semarang dan, kebetulan, angkatan saya merupakan generasi terakhir yang mengalami pembagian jurusan: entah itu fisika, biologi, sosial, maupun budaya (belum menggunakan sistem IPA-IPS).
Walaupun sudah dibagi ke dalam empat spesifikasi keilmuan, nyatanya, minat terhadap ilmu humaniora atau sosial sangat rendah. Setiap tahun, hanya ada satu kelas jurusan sosial dan tidak ada kelas jurusan budaya.
Mayoritas murid saat itu cenderung memilih untuk masuk jurusan fisika. Ada pandangan di kalangan orangtua dan guru yang menganggap bahwa mereka yang masuk jurusan eksakta adalah anak-anak pintar.
Lantas bagaimana dengan saya? Jika boleh berkata, hasil tes bakat saya memperlihatkan skor 65 untuk IPA dan 71 untuk IPS. Namun, saya justru mendapat rekomendasi yang berkebalikan dari hasil tes: masuk IPA. Akhirnya saya pun masuk kelas fisika.
Perjalanan saya di kelas fisika tidak berlangsung lama. Saat ibu saya memperoleh tugas belajar ke Australia, saya mesti ikut meninggalkan SMA dan mengulang pendidikan kelas 11 di South Sydney High School.
Aturan pendidikan yang ditentukan oleh negara bagian New South Wales waktu itu membuat saya bersemangat. Dari lima sampai enam mata pelajaran persyaratan ujian akhir, yang wajib diikuti hanyalah matematika dan bahasa Inggris. Ada sekitar empat hingga lima tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing murid. Saya memutuskan mengambil matematika tingkat tertinggi (melanjutkan pelajaran di Indonesia) dan bahasa Inggris tingkat kedua terendah (bukan penutur asli).
Selain itu, ada aturan yang melarang mengambil IPA lebih dari dua macam. Saya tidak bisa melanjutkan semua IPA (fisika, kimia, biologi) yang saya pelajari di Indonesia. Sisa jadwal pelajaran harus diisi IPS, bahasa, atau kesenian.
Kesan saya dari pengalaman belajar di Australia adalah sistem pendidikan yang tidak mengkotak-kotakkan murid. Tujuannya adalah untuk membantu merealisasikan visi pribadi setiap murid, yang saya kenal sebagai envisioning.
Di akhir kelas 10, murid yang hendak melanjutkan ke universitas sudah dibimbing untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan yang ingin didalami. Bila ingin masuk jurusan bisnis, misalnya, maka murid diharuskan menempuh kelas matematika kedua tertinggi. Sementara jika ingin mengambil jurnalistik, maka wajib mengambil bahasa Inggris tertinggi.
Sisanya, para murid bisa memilih pelajaran untuk pemanasan yang bukan termasuk dalam persyaratan seperti mengambil ekonomi bila ingin kuliah ekonomi atau drama jika ingin kuliah sastra. Di antara teman-teman seangkatan, saya melihat kombinasi unik macam kimia-bisnis-seni rupa serta informatika-olahraga-bahasa Mandarin.
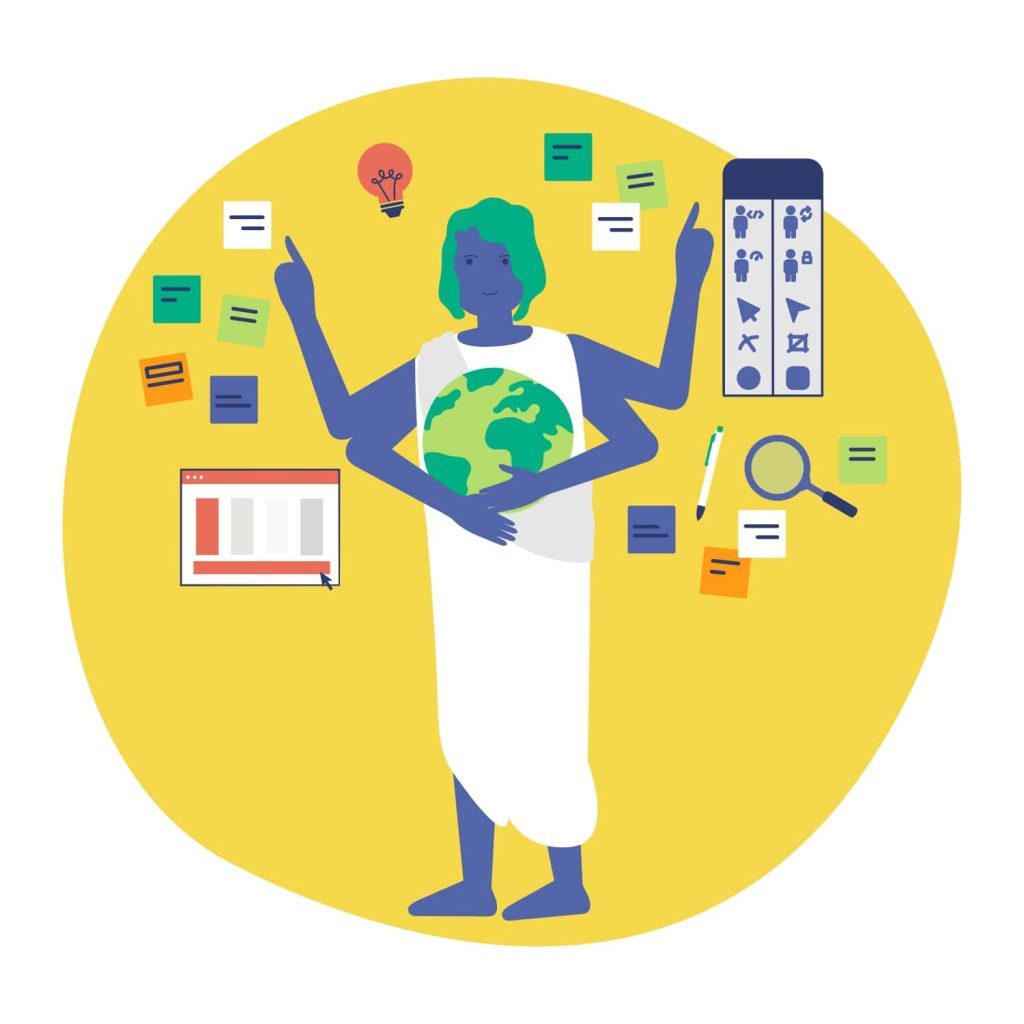
Ketiadaan kotak semacam ini saya jumpai lagi di Belanda, dua dekade setelahnya lewat program profesi ilmu desain. Program ini dikelola oleh Eindhoven University of Technology dengan mitra utama Philips, perusahaan kelas dunia yang lahir di Eindhoven. Program ini menerima lulusan S1 dan S2 dari disiplin ilmu apa saja serta punya kuota untuk tiap disiplin yang terbagi atas: sepertiga teknologi, sepertiga psikologi, dan sepertiga lainnya tersebar di antara bisnis, bahasa, maupun pendidikan.
Dalam prosesnya, kami dibenturkan satu sama lain menurut perbedaan disiplin ilmu yang dirotasi per proyek. Tujuannya adalah supaya kami bisa (terpaksa) saling mengisi dan belajar sehingga dapat memahami bahwa sebuah masalah mampu dipecahkan secara lebih baik lewat pendekatan multidisiplin. Harapannya, ketika lulus, kami dapat mengemban misi kolaborasi lintas disiplin (interdisiplin).
Tapi, saya termasuk sedikit pihak yang meleburkan diri pada ketiadaan batas disiplin ilmu (transdisiplin) dan malah menemukan identitas baru, yaitu desainer. Identitas baru inilah yang mendorong saya untuk lebih dalam mengulik pendidikan desain melalui keikutsertaan program S3 di bidang industrial design di kampus yang sama.
Kurikulum pendidikan S1 di fakultas tempat saya menimba ilmu di Belanda disebut competency-centered, yaitu tidak ada kuliah wajib dan mahasiswa dibebaskan mencari identitas dirinya dengan memilih kompetensi yang ingin dijadikan modal kontribusi ke masyarakat. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning yang mengharuskan mahasiswa memilih proyek tertentu sebelum memilih mata kuliah yang mendukung proyek tersebut.
Contohnya kira-kira begini. Pada suatu semester, Ujang mendaftar ke proyek A yang memerlukan keahlian seperti kompetensi Memahami Manusia, Rasa & Bentuk, dan Proses Bisnis. Proyek A sedang mencari solusi alternatif bagi pendidikan anak balita dengan sponsor perusahaan mainan anak. Dengan mengambil mata kuliah terkait proyek tersebut, maka ketiga kompetensi itu bakal ia miliki.
Di semester berikutnya, Ujang ingin mengembangkan kompetensi Memahami Manusia. Ia mendaftar ke proyek B untuk mengembangkan suatu teknologi tepat guna di sebuah desa di Spanyol. Dalam deskripsinya, tertulis bahwa proyek dapat menumbuhkan kompetensi Memahami Manusia, Kesadaran Budaya, dan Integrasi Teknologi.
Proses empati seorang desainer seringkali disebut sensemaking. Pasalnya, desainer menggunakan segenap indera dan metode (bukan ilmu sosial saja) untuk memahami kompleksitas sebuah permasalahan. ~ Qonita Shahab Share on XMenurut kurikulum saat itu, seorang desainer merupakan pencipta peluang (opportunity creator). Desainer bukan ahli teknologi, bisnis, maupun manusia. Ia menjadi penghubung antarbidang tersebut dan memfasilitasi lahirnya solusi multidisiplin.
Karena fasilitasi multidisiplin tidak ada rumusnya, maka ilmu desain bukanlah ilmu optimisasi. Jika seorang ahli ilmu optimisasi memecahkan masalah dengan mencari solusi terbaik, maka seorang desainer memecahkan masalah dengan belajar dari hasil kreasinya. Desainer melakukan prototyping, yaitu membentuk solusi sementara yang diikuti dengan refleksi, sehingga terjadi perulangan kreasi-refleksi menuju solusi akhir. Setiap mahasiswa ditugasi melakukan refleksi di awal, tengah, dan akhir proyek.
Di akhir semester, setiap mahasiswa maju dalam sidang evaluasi keberhasilan proyek. Pada sidang tersebut, mahasiswa menyajikan portfolio-nya sekaligus merefleksikan perkembangan kompetensinya. Dalam kasus Ujang, ia akan menghadapi para penguji yang bertugas merespons refleksinya: apakah ia benar-benar telah menguasai keahlian Memahami Manusia?
Bagi yang mengenal saya, mungkin banyak yang bertanya mengapa saya memutuskan menjadi pelaku kreatif padahal saya alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Semua bermula dari mata kuliah Human-Computer Interaction (HCI) yang secara garis besar membahas tentang memahami manusia untuk menciptakan teknologi yang mudah digunakan.
Tampaknya tes bakat semasa SMA memang sudah tepat merekomendasikan IPS. Buktinya, selama belajar HCI, saya jatuh hati kepada ilmu psikologi kognitif yang dapat dimanfaatkan untuk memahami manusia, yaitu cara berpikir manusia. Kemudian saya kian tertarik memahami manusia melalui ergonomi (kerja tubuh manusia), antropologi (budaya dan kemanusiaan), dan sosiologi (hubungan antarmanusia).
Ternyata, menyukai ilmu jaringan komputer juga menjadi bukti mengapa saya selalu tergugah untuk melihat relasi apa saja (sebagian atau keseluruhan, langsung atau tidak langsung, searah atau bolak-balik, statis atau dinamis). Cara berpikir seperti ini (systems thinking) menjadi bekal dalam memahami masalah kompleks, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya kreativitas.
Proses empati seorang desainer seringkali disebut sensemaking. Pasalnya, desainer menggunakan segenap indera dan metode (bukan ilmu sosial saja) untuk memahami kompleksitas sebuah permasalahan. Mengidentifikasi masalah saja tidak cukup, karena perlu pendalaman konteks untuk menentukan prioritas pemecahannya. Contohnya, desainer yang terlibat dalam pencarian solusi masalah banjir di perkotaan. Ia mengamati kondisi perkotaan sebelum terjadi banjir dan menemukan perilaku buang sampah di sungai. Maka, keputusan yang diambil ialah menghentikan perilaku ini, alih-alih membuat saluran banjir.
Seperti dalam kisah saya di atas, ilmu desain telah dikenal secara umum sebagai proses “sensemaking-envisioning-prototyping” atau “feel-imagine-do”. Sedangkan menurut Kiran Bir Sethi, seorang ibu dan desainer asal India, ilmu desain adalah “feel-imagine-do-share” (FIDS). Ia memimpin gerakan Design For Change (DFC), sebuah pendidikan desain untuk anak-anak. Konsep “share” sengaja ia tambahkan untuk mengajarkan anak-anak berbagi hasil karya dengan semangat “I Can!”.
Gerakan DFC dimulai pada 2009 dan telah mendunia. Pada 2015, Noura Books bahkan menerbitkan buku bertajuk Aku Bisa! yang merekam kiprah para pendidik di Indonesia yang mengaplikasikan pendekatan FIDS di setiap sekolah. DFC juga menerbitkan buku Design Thinking Guide -sebagai bahan ajar sekaligus belajar konsep FIDS.
Misi DFC secara umum adalah menyiapkan anak-anak (usia SD sampai SMP) untuk menghadapi tantangan perubahan zaman yang begitu cepat, untuk profesi yang sekarang belum ada, dengan teknologi yang belum ditemukan, dan guna memecahkan masalah yang belum terlihat. Sejauh ini, para pengajar yang telah menerapkan kurikulum FIDS menemukan bahwa anak didiknya menjadi lebih berempati dan percaya diri, sehingga berkontribusi pada peningkatan prestasi di sekolah.
Ilmu desain perlu pula diaplikasikan dalam pendidikan tinggi, karena lebih dekat dengan momentum dunia kerja dan diharapkan dapat menciptakan banyak profesi baru untuk kehidupan yang lebih memanusiakan manusia. Kebetulan sekali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, Nadiem Makarim, menyatakan perlunya mengambil mata kuliah lintas fakultas.
Ada setidaknya dua proposal yang ingin saya tawarkan guna merespons wacana Nadiem. Pertama, pemberlakuan sistem major-minor, yaitu major dalam bidang masing-masing dan minor dalam ilmu desain. Peserta minor berasal dari berbagai major yang dikumpulkan dalam satu kelas sehingga mahasiswa terbiasa bekerja secara lintas jurusan.
Konsep FIDS diterapkan dalam berbagai proyek agar mahasiswa mengalami proses kreasi dan refleksi dengan intens. Tujuan dari sistem ini yaitu menciptakan kolaborator (praktisi interdisiplin) yang mampu menghadapi permasalahan kompleks.
Ilmu desain perlu pula diaplikasikan dalam pendidikan tinggi, karena lebih dekat dengan momentum dunia kerja dan diharapkan dapat menciptakan banyak profesi baru untuk kehidupan yang lebih memanusiakan manusia. ~ Qonita Shahab Share on XKedua, sistem double minor, yaitu major dalam ilmu desain (50 persen) dan dua minor (masing-masing 25 persen). Tujuannya adalah memperbaiki pendidikan desain yang saat ini cenderung berfokus pada jenis kreasinya, entah itu grafis, interior, maupun kriya. Dengan tambahan dua minor, maka mahasiswa desain dapat mengaplikasikan FIDS dalam kombinasi ilmu. Pendidikan desain tak lagi ditujukan untuk membentuk creator, tapi juga melahirkan fasilitator (praktisi transdisiplin).
Misalnya, pemerintah butuh desainer yang paham kebijakan publik serta antropologi untuk berkontribusi pada terciptanya pelayanan umum yang mudah diakses semua masyarakat. Atau, contohnya lagi, perusahaan teknologi butuh desainer yang mengerti teknologi digital dan psikologi untuk membantu membangun teknologi yang ramah penggunaan.
Saat ini kolaborasi adalah keniscayaan, sehingga setiap profesi perlu dididik sebagai kolaborator. Hal ini juga dapat meredam efek negatif spesialisasi, yaitu ego keilmuan yang melihat masalah melalui satu disiplin ilmu saja. Walaupun demikian, saya melihat perlunya lebih banyak fasilitator. Selain kreatif, mereka juga berpeluang tinggi menjadi polymath (memiliki berbagai keahlian). Mereka adalah katalis perubahan, sebab berani berkreasi lebih cepat untuk dipelajari dan dibagikan ke kolaborator-kolaborator yang tepat.
Jika cara mendidik kolaborator dapat dipelajari dari negara-negara maju (Don Norman), maka cara mendidik fasilitator dapat dipelajari dari budaya kita. Orang Indonesia dikenal “serba bisa”, karena kondisi yang memudahkan belajar banyak hal di luar pendidikan formal. Satu karakter bisa memegang berbagai peran di masyarakat. Kedalaman ekspresi karakter ini menghasilkan resiliensi yang tinggi dalam menghadapi tantangan perubahan zaman (Ezio Manzini).
Catatan ini saya tutup setelah mengamati tingginya resiliensi masyarakat Indonesia dalam menghadapi krisis pandemi selama tiga bulan terakhir. Betapa banyaknya wujud kreativitas lahir dari FIDS yang sudah diterapkan masyarakat Indonesia tanpa kurikulum. Jika FIDS diajarkan melalui pendidikan formal, harapannya dapat menyentuh separuh penduduk Indonesia. Mereka bukan saja bisa membuat perubahan, tapi juga transformasi (perubahan yang memiliki visi). Bagi saya, pendidikan, sampai kapanpun, adalah mekanisme transformasi kolektif.
Jauh sebelum kenal ilmu desain, di masa kecil Qonita Shahab suka menggambar model-model rumah dan di masa remaja pernah mengajar anak-anak TK membaca. Saat mengenal internet, seketika ia terpukau karena internet menciptakan peluang kolaborasi antar manusia sedunia. Qonita menikmati profesi desainer, karena menggunakan empati dan bisa kreatif sekaligus sistematis. Ia pernah terlibat dalam berbagai proyek multidisiplin, seperti membuat pegawai kantoran tidak malas bergerak, membuat pengemudi mobil lebih kooperatif di jalan tol, menggembleng desainer-desainer muda di sebuah startup digital, mencari peluang mainan edukatif terjangkau masyarakat ekonomi lemah, dan mencari peluang teknologi untuk pasien diabetes. Qonita sempat mencicipi hidup di Australia, Korea Selatan, Belanda, dan Amerika Serikat yang totalnya 17 tahun. Pada 2019, ia kembali ke Indonesia untuk merefleksikan pengalaman mancanegaranya menurut budaya Indonesia, sambil mencoba tetap berkarya sebagai desainer.
Artikel Terkait
Kontribusi Film untuk Pendidikan
Untuk meratakan kesempatan pendidikan dan memberikan ruang baru bagi para guru dan siswa, Anggun berinisiatif mendirikan Sinedu.id (Sinema Edukasi).Refleksi Kritis Penerima Beasiswa
Sejak remaja, Raisa ingin sekali tinggal di luar negeri. Ia pun berambisi melanjutkan pendidikan S2 di luar negeri dengan mencari beasiswa. Di Catatan Pinggir ini, Raisa menceritakan pengalaman kuliah di luar negeri yang tidak selalu semanis harapannya.“Kenyamanan” dan Kebebasan dalam Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Orang Asing
Pengalaman mengajar Bahasa Indonesia membuat Amalia Puri Handayani dan Marissa Saraswati memikirkan kembali posisi perempuan dan relasi kuasa antara orang asing dengan orang Indonesia dalam pendidikan. Yuk, simak Catatan Pinggir mereka ini.