
Mendidik Desainer, Mendesain Pendidikan
June 2, 2020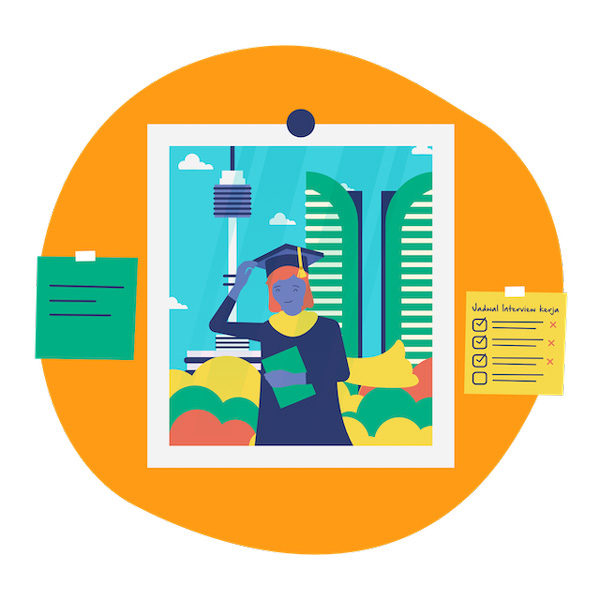
Refleksi Kritis Penerima Beasiswa
June 3, 2020
Catatan Pinggir
“Kenyamanan” dan Kebebasan dalam Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Orang Asing
oleh Amalia Puri Handayani dan Marissa Saraswati
Pengantar Redaksi:
Pengalaman mengajar Bahasa Indonesia membuat Amalia Puri Handayani dan Marissa Saraswati memikirkan kembali posisi perempuan dan relasi kuasa antara orang asing dengan orang Indonesia dalam pendidikan. Yuk, simak Catatan Pinggir mereka ini.
“Apa bedanya bukan dan tidak?”
Kami tidak bisa langsung menjawab, perlu waktu untuk berpikir. Keduanya merupakan kata yang digunakan ketika menegasikan sesuatu. Seperti not dan no dalam bahasa Inggris. Tapi, apa bedanya not dan no?
I do not know.
No, I do not.
Kami malah semakin tidak paham, apalagi dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. Lagi pula kenapa mencoba menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan bahasa Inggris?
Padahal, bahasa Inggris bukan untuk semua orang di Indonesia. Hanya segelintir orang yang bisa belajar bahasa Inggris. Artinya, bahasa Inggris adalah sebuah kemewahan, privilise.
Sementara itu, bahasa Indonesia yang sebenarnya kita gunakan sehari-hari seringnya tak kita anggap sebagai pengetahuan. Kami tahu bagaimana menggunakannya, tetapi tidak tahu kenapa bukan atau tidak digunakan. Kita coba gunakan dalam kalimat.
Saya tidak tahu.
Saya bukan laki-laki.
Tidak digunakan untuk menegasikan kata kerja. Bukan digunakan untuk menegasikan kata benda. Digunakan sehari-hari–bahkan di semua pelajaran semasa sekolah sampai kuliah, bahasa Indonesia kerap dilihat sekadar alat dan dianggap bukan ilmu pengetahuan.
Sebagai mahasiswa yang berusaha mencari penghasilan tambahan sekaligus menambah daftar pengalaman di CV kala itu, kami bergabung di sebuah lembaga pengajaran bahasa Indonesia yang dimiliki orang asing. Perusahaan ini menyasar kelompok ekspatriat untuk memperlancar urusan bisnis, diplomasi, sampai rumah tangga. Biaya yang dipatok pun berstandar internasional.
Tak ada bahasa Indonesia yang sama. Kami terlalu menyederhanakannya menjadi satu entitas, dengan Jakarta sebagai pusatnya. ~ Amalia Puri & Marissa Saraswati Share on XKritik yang kami ajukan pada saat itu adalah persoalan honor bagi guru. Sebelumnya, kami tidak pernah tahu berapa banyak uang yang harus dibayar murid untuk mengambil paket belajar bahasa Indonesia. Ketika tahu, kami cukup bergidik. Mengapa kami hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil dari keseluruhan? Sebagian besar uang itu masuk sebagai profit perusahaan, sedangkan guru yang meluangkan waktu, energi, dan pengetahuannya malah diberikan sedikit porsi. Kami digerus perusahaan yang dimiliki orang asing.
Kami tidak terima keadaan itu dan berniat memberikan pendapatan yang lebih besar kepada guru sebagai penyokong utama. Maka itu, kami memutuskan untuk berhenti dan membuka lembaga baru. Kami membuka rekrutmen guru dengan memprioritaskan pengajar perempuan.
Perusahaan tempat kami mengajar sebelumnya menerapkan hal serupa dengan alasan perempuan dengan sifat mengayominya dianggap lebih cocok untuk profesi ini. Bagi kami, alasannya tidak ada hubungannya dengan stereotipe terhadap perempuan, melainkan membuka kesempatan bagi perempuan untuk menambah pengalaman dan mendapatkan penghasilan.
Kebijakan untuk terbuka kepada guru terkait dengan penghasilan yang didapat juga dijalankan. Kami memberi tahu uang yang didapat: porsi besar untuk guru dan sisanya akan kami gunakan pengembangan kapasitas lembaga dan guru. Salah satu keuntungan yang didapat dialokasikan untuk membuat modul pengajaran baru dan membiayai pelatihan guru.
Awalnya, modul yang kami gunakan didapat dari lembaga tersebut. Metode yang digunakan banyak melibatkan murid untuk berpartisipasi: percakapan, misalnya. Topik artikel yang dipilih kerap memposisikan perempuan sebagai asisten rumah tangga (disebut sebagai pembantu dalam modul), cara berkomunikasi dengan mereka, termasuk sopir.
Banyak contoh soal tentang ibu rumah tangga dan perannya dalam mendidik anak tanpa campur tangan suaminya. Perempuan melakukan pekerjaan domestik. Posisi sebagai manajer, bos, atau dokter ditempati laki-laki. Kami menggunakannya selama beberapa tahun. Kami melanggengkan posisi perempuan yang memenuhi stereotipe di masyarakat. Tanpa kritik.

Oleh karena itu, kami membuat modul baru untuk memposisikan perempuan secara lebih adil dan setara dalam artikel, percakapan, dan contoh soal.
Kesadaran melihat posisi perempuan bukan akhir refleksi kami. Ternyata, kami juga abai melihat relasi kuasa dalam hubungan orang asing dengan orang Indonesia. Pada sistem belajar-mengajar konvensional, posisi guru lebih superior daripada murid. Anggapannya, guru adalah pemilik seluruh pengetahuan yang harus dibagikan kepada murid. Hal ini menempatkan guru dengan lebih banyak power dalam ruang kelas. Lain soalnya dalam pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. Guru kerap memandang dirinya inferior di hadapan murid asingnya–hanya karena ras mereka.
Beberapa pemikir, seperti Paolo Freire, kerap kali mengkritik relasi kuasa dalam pendidikan. Freire, yang berasal dari Brasil, mengatakan bahwa tidak ada pendidikan yang netral. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk memberi “kenyamanan” atau kebebasan. Ketika murid asing yang sedang belajar bahasa Indonesia tidak memposisikan guru atau pelajaran sebagai prioritas, kami cenderung memakluminya demi menjaga kenyamanan murid.
Kami punya pengalaman, bukan hanya sekali, ketika sudah datang ke lokasi pengajaran–rumah atau kantor, mereka membatalkannya atau mengubah jam belajar begitu saja dengan berbagai alasan. Bahkan, tanpa susah-susah memberitahu guru sebelum melakukan perjalanan tersebut. Tanpa menyadari relasi kuasa yang tidak seimbang, kami terus berkompromi.
Tak hanya berkompromi, bahkan tak jarang kami menegaskan posisi hierarki mereka. Misalnya melalui contoh yang kami berikan di ruang kelas.
“Apa itu jam karet?” tanya murid.
“Orang Indonesia sering datang terlambat. Jadi, kalau punya janji dengan orang Indonesia, Anda harus menunggu beberapa lama sampai mereka datang. Itu hal biasa di Indonesia. Kami sampai punya istilah jam karet.”
Seakan-akan semua orang Indonesia sama. Kami kerap melegitimasi stereotipe yang mereka sematkan kepada orang Indonesia. Pada saat yang sama, itu membuat posisi mereka terus meninggi daripada orang Indonesia.
Bahasa Indonesia yang digunakan orang dari wilayah barat sampai timur Indonesia pun berbeda-beda. Tak ada bahasa Indonesia yang sama. Kami terlalu menyederhanakannya menjadi satu entitas, dengan Jakarta sebagai pusatnya.
Sedihnya, kami melakukannya dengan tidak sadar. Kami mencoba memperbaikinya melalui hal-hal kecil. Salah satunya adalah preferensi jam belajar mengajar. Kami berdiskusi dengan guru. Waktu guru pun menjadi prioritas untuk mengajukan jam belajar alih-alih terus-menerus memberikan keleluasaan murid untuk memilihnya.
Hanya segelintir orang yang bisa belajar bahasa Inggris. Artinya, bahasa Inggris adalah sebuah kemewahan, privilise. ~ Amalia Puri & Marissa Saraswati Share on XKesadaran demikian baru merasuk tujuh tahun kemudian. Itu pun diresapi bukan melalui pengajaran bahasa Indonesia, melainkan melalui pembelajaran hal-hal di luar lembaga bahasa kami. Belajar memang tak bisa hanya dari satu bidang ilmu. Refleksi kami, belajar dari banyak bidang ilmu bisa memperkaya spektrum pembelajaran.
Kesadaran dan pemahaman akan adanya relasi kuasa dalam pendidikan, seperti di ruang kelas pengajaran bahasa Indonesia, tidak bersifat linear seperti sebuah pencerahan yang langsung membuka mata. Tapi, lebih seperti perjalanan bolak-balik yang harus terus-menerus dipelajari.
Satu dekade kemudian, lembaga bahasa kami sudah tidak ada. Meski dengan berat hati, kami memutuskan untuk menutupnya. Kami sadar betul bahwa modul perlu dilihat lagi secara berkala untuk melihat relevansi dan kemutakhiran nilai. Selain itu, perlu juga melakukan refleksi terhadap metode pengajaran–termasuk belajar bersama kembali antarguru–yang lebih membebaskan, baik bagi murid maupun guru.
Artinya, keputusan kami bukan karena lembaga itu tak berjalan atau tak lagi dibutuhkan, tapi karena kami sadar kami bersikap tak adil pada pendidikan jika tak melakukannya tanpa komitmen penuh.

Amalia Puri adalah perempuan yang menaruh perhatian pada feminisme, khususnya hak kesehatan reproduksi dan seksulitas, teknologi, dan bahasa. Setelah mengemban pendidikan linguistik Indonesia dan kajian gender di Universitas Indonesia, ia menyelesaikan master bidang Social Policy for Development di ISS, Erasmus University, Den Haag. Saat ini, selain menjadi bagian dari PurpleCode Collective dan Women on Web, ia bekerja paruh waktu sebagai peneliti di PPH Atma Jaya.

Marissa Saraswati merupakan salah satu editor Anotasi. Marissa baru saja menyelesaikan studi magister di bidang Women and Gender Studies di San Francisco State University.
Artikel Terkait
Kontribusi Film untuk Pendidikan
Untuk meratakan kesempatan pendidikan dan memberikan ruang baru bagi para guru dan siswa, Anggun berinisiatif mendirikan Sinedu.id (Sinema Edukasi).Refleksi Kritis Penerima Beasiswa
Sejak remaja, Raisa ingin sekali tinggal di luar negeri. Ia pun berambisi melanjutkan pendidikan S2 di luar negeri dengan mencari beasiswa. Di Catatan Pinggir ini, Raisa menceritakan pengalaman kuliah di luar negeri yang tidak selalu semanis harapannya.“Kenyamanan” dan Kebebasan dalam Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Orang Asing
Pengalaman mengajar Bahasa Indonesia membuat Amalia Puri Handayani dan Marissa Saraswati memikirkan kembali posisi perempuan dan relasi kuasa antara orang asing dengan orang Indonesia dalam pendidikan. Yuk, simak Catatan Pinggir mereka ini.




