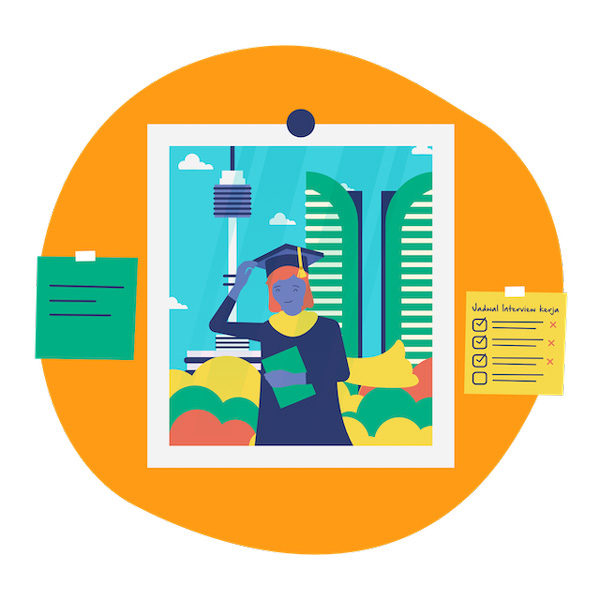Spektrum Lansia yang Terlewat
May 27, 2020
Pedagogi : Praktik = Teori
June 1, 2020Makna
Belajar Berani dari Soelastri
oleh Amalia Astari
Pertemuan pertama saya dengan Soelastri terjadi tiga tahun lalu di perpustakaan Universitas Leiden di negeri kincir angin, Belanda. Tanpa sengaja pandangan saya melayang ke arah sosoknya yang tengah bersandar santai di pojok ruang baca koleksi sastra Indonesia. Waktu itu Soelastri yang pertama membuka pembicaraan, “Gila! Kau tahu tidak? Dulu pemerintah kolonial hanya menyediakan 180 sekolah dasar Hindia-Belanda untuk enam puluh juta penduduk pribumi. Dan lucunya, Ki Hajar Dewantara di saat yang bersamaan bisa membangun sekolah Taman Siswa dengan jumlah yang sama hanya dalam waktu sepuluh tahun. Itu semua karena antusiasme dan kesungguhannya untuk memajukan rakyat Indonesia bukan malah niat menindas seperti si ramboet djagoeng itu!”
Dengan menggebu-gebu Soelastri menceritakan pengalamannya saat dulu ia berjuang sebagai tenaga pengajar di sekolah dasar tanpa mendapat kucuran subsidi dari pemerintah kolonial. Bersama suaminya, Soedarmo, mereka jatuh bangun mendirikan sekolah bebas untuk jiwa-jiwa yang merindukan kebebasan. Sekolah yang dibangun dengan semangat nasionalisme dan dipupuk oleh idealisme para tenaga pengajar berpikiran merdeka. Sekolah nasionalis yang pada akhirnya dicap sadis oleh pihak berkuasa sebagai wilde school atau sekolah liar. Soelastri, adalah seorang perempuan pribumi yang mampu berdiri tegak melawan dominasi pemerintah kolonial yang mempersulit pribumi untuk mengenyam bangku pendidikan. Sungguh saya sangat mengagumi keberaniannya. Padahal, menjadi perempuan di masa penjajahan adalah sebuah neraka yang paling menyiksa. Seperti yang Elleke Boehmer tulis di bukunya Colonial and Postcolonial Literature , perempuan pribumi adalah kaum yang dua kali, bahkan tiga kali lipat lebih termarjinalisasi di dalam struktur masyarakat Hindia Belanda: “as it is called, doubly or triply marginalized.” Bukan hanya terlahir sebagai ras dengan kelas sosial yang paling rendah, mereka juga kurang beruntung karena terlahir sebagai perempuan di struktur masyarakat Hindia Belanda yang dominan maskulinitas.
Meski Soelastri berani berdiri tegak melawan dominasi tersebut, sayangnya, Soelastri teman saya ini tidak benar-benar nyata. Dia hanya sebuah tokoh fiksi dari novel Buiten het Gareel karangan Soewarsih Djojopoespito yang pertama kali terbit di tahun 1940.
Novel ini merupakan sebuah produk luar biasa langka: hanya sedikit novel berbahasa Belanda karangan penulis perempuan Indonesia yang berhasil menembus pasar penerbitan Belanda. Selain Soewarsih, buku Door Duisternis tot Licht karya Kartini terlebih dahulu diterbitkan di tahun 1911. Keduanya sama-sama memaparkan kontemplasi perempuan Indonesia yang harus berjuang melawan represi kekuasaan adat dan kolonial.

Namun seperti yang Goenawan Moehammad tulis di Catatan Pinggirnya berjudul Perempuan di Luar Garis yang Lurus, Soewarsih nyatanya berbeda dengan Kartini. “Penuturannya lebih kompleks, lebih intim, lebih terbuka dan dengan latar yang lebih luas dibanding surat-surat Kartini.“
Bagi saya, yang membedakan Soewarsih dan Kartini muncul terutama dari penciptaan tokoh fiksi Soelastri dan suaminya Soedarmo dalam novel Buiten het Gareel yang kemudian di tahun 1975 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Manusia Bebas.
Soelastri dan Soedarmo digambarkan sebagai pasangan suami istri berprofesi guru yang berjuang di periode tahun 1932-1938, saat pemerintah Belanda menerbitkan peraturan sekolah liar (wilde school ordinatie). Sistem pendidikan yang dibuat pemerintah Belanda sebelum tahun 1932 seolah menjepit pribumi di posisi serba salah: di satu sisi pemerintah kolonial menginginkan standarisasi sistem pendidikan setara Belanda dengan mengadaptasi materi ajar Belanda di sekolah Hindia Belanda (verindisching), namun di sisi lain pemerintah kolonial juga tidak rela mengucurkan dananya untuk membiayai sekolah di tanah jajahan mereka.
Dengan rasionalitas yang dihadirkan lewat kedua tokoh ini, Soewarsih berhasil mengkritik ide kolonial yang kerap menggambarkan pribumi sebagai kelompok yang terbelakang. ~ Amalia Astari Share on XMenyikapi hal ini pemerintah kolonial mengurangi sekolah khususnya untuk kalangan pribumi dan pada akhirnya membebaskan pribumi untuk mendirikan lembaga pendidikan sendiri tanpa kucuran subsidi pemerintah Belanda. Tak disangka, kebijakan ini malah berbalik menjadi senjata makan tuan. Di titik inilah lahir kesadaran nasionalisme rakyat Indonesia lewat lembaga pendidikan yang independen dari pemerintah kolonial. Seperti judul terjemahan novel Soewarsih, sekolah-sekolah nasionalis ini yang kemudian menciptakan para ‘manusia bebas‘ yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Lewat tokoh Soelastri dan Soedarmo, Soewarsih mampu merenungkan tekanan-tekanan yang dihadapi kelompok pribumi, khususnya perempuan di masa pergerakan nasional. Tokoh Soelastri dan suaminya digambarkan mampu memerangi dominasi serta maskulinitas Barat dengan cara yang cenderung unik. Kedua tokoh ini, dengan kesadaran protagonis mereka membuktikan pribumi mampu berdiri sejajar dengan penguasa Belanda lewat gagasan modern yang mereka miliki.
Lewat percakapan tokoh Soelastri dan Soedarmo, kedua tokoh ini menolak mitos dan kebiasaan Timur yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah saat Soelastri menolak kesaktian ‘dukun beranak‘ dan lebih percaya akan kemahiran bidan. “Wij zijn toch moderne vrouwen. Durf je je heus aan een doeken toevertrouwen?“ (Bukankah kita perempuan modern? Apakah kamu masih bisa percaya pada dukun?). Tidak hanya itu, Soelastri dan Soedarmo juga menolak keras poligami. Bagi mereka poligami mampu mengubah manusia menjadi binatang “…polygamie maakt van een mens een dier“. Hal ini ironis karena di media arus utama pada masa ini, masih banyak penulis pribumi yang mati-matian membela pernikahan poligami.
Dengan rasionalitas yang dihadirkan lewat kedua tokoh ini, Soewarsih berhasil mengkritik ide kolonial yang kerap menggambarkan pribumi sebagai kelompok yang terbelakang. Oposisi biner adalah sebuah strategi yang digunakan pemerintah kolonial untuk membentuk gambaran pribumi sebagai ‘kelompok liyan’ yang lebih inferior dibanding para penguasa kolonial.
Belajar, hingga saya bisa lebih pintar dari mereka dan pada akhirnya sanggup mengalahkan mereka. Layaknya Soelastri, yang belajar “menjadi Belanda” untuk kemudian berdiri tegak melawan kekuasaan Belanda. ~ Amalia Astari Share on XDalam konteks narasi kolonialisme di Hindia Belanda, pribumi sering digambarkan inferior dalam hal intelektualitas dibanding orang Belanda. Strategi ini, menurut Boehmer digunakan pihak berkuasa untuk melegitimasi kekuasaan mereka di tanah jajahan. Stereotip kolonial ini jelas tidak ditemukan dalam sosok Soelastri.
Lebih dari itu, kritik atas intelektualitas kolonial dihadirkan bukan hanya lewat tokoh saja melainkan juga lewat bahasa yang Soewarsih gunakan dalam buku ini. Dengan menulis dalam bahasa Belanda, Soewarsih seolah mengadaptasi kemahiran penguasa kolonial dan di saat yang bersamaan juga menggunakan bahasa Belanda – yang merupakan simbol superioritas intelektual di Hindia Belanda – sebagai media untuk membela kaum pribumi. Dalam narasi kolonial, strategi ini disebut Boehmer sebagai strategi mimikri: mereka belajar berbicara dengan mengadopsi dan mengadaptasi perkataan penjajah untuk kemudian melawan para penjajah (“Adopting and adapting the white man’s tongue, they learned to speak up for themselves”). Layaknya Soelastri dan Soedarmo yang dikisahkan tidak hanya mumpuni berbahasa Belanda namun juga sanggup berpikir modern layaknya orang Belanda.
Tokoh Soelastri yang diciptakan Soewarsih Djojopoespito pada akhirnya menyadarkan saya bahwa cara terbaik melawan kekuasaan yang merepresi kebebasan adalah dengan berani belajar menjadi salah satu dari mereka. Belajar, hingga saya bisa lebih pintar dari mereka dan pada akhirnya sanggup mengalahkan mereka. Layaknya Soelastri, yang belajar “menjadi Belanda” untuk kemudian berdiri tegak melawan kekuasaan Belanda.
Bacaan Lebih Lanjut
| Referensi dan Bacaan Lanjutan Boehmer, Elleke (2009). Colonial and postcolonial literature: Migrant metaphors. Oxford: Oxford Univ. Press. Djojopuspito, Soewarsih., Du, P. E., & Termorshuizen, G. (1986). Buiten het gareel: Een Indonesische roman. ‘s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar. Mohammad, Goenawan (2013). Catatan Pinggir: Perempuan di Luar Garis yang Lurus. |

Amalia Astari adalah kandidat Ph.D Universität zu Köln dan pengajar Program Studi Belanda, Departemen Susastra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
Artikel Terkait
Kontribusi Film untuk Pendidikan
Untuk meratakan kesempatan pendidikan dan memberikan ruang baru bagi para guru dan siswa, Anggun berinisiatif mendirikan Sinedu.id (Sinema Edukasi).Refleksi Kritis Penerima Beasiswa
Sejak remaja, Raisa ingin sekali tinggal di luar negeri. Ia pun berambisi melanjutkan pendidikan S2 di luar negeri dengan mencari beasiswa. Di Catatan Pinggir ini, Raisa menceritakan pengalaman kuliah di luar negeri yang tidak selalu semanis harapannya.“Kenyamanan” dan Kebebasan dalam Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Orang Asing
Pengalaman mengajar Bahasa Indonesia membuat Amalia Puri Handayani dan Marissa Saraswati memikirkan kembali posisi perempuan dan relasi kuasa antara orang asing dengan orang Indonesia dalam pendidikan. Yuk, simak Catatan Pinggir mereka ini.