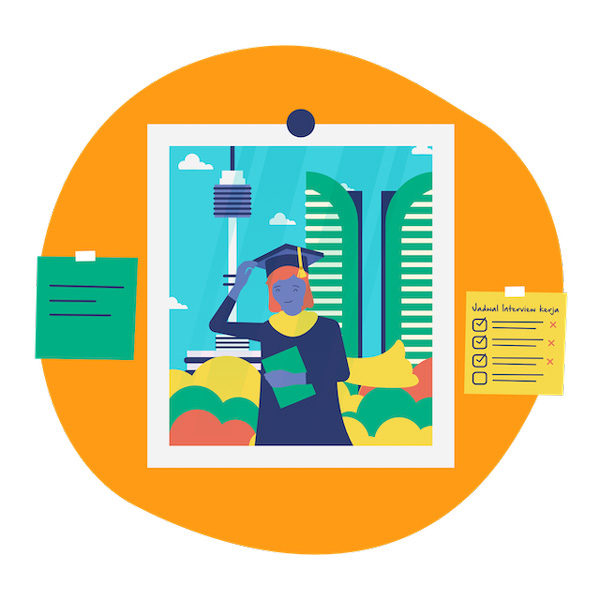Sabhrina Gita Aninta
March 18, 2021
Berdamai Dengan Inner Child
March 31, 2021
RESENSI BUKU
Mempertanyakan Gagasan tentang Sekolah
oleh Muhammad Fakhri
Semenjak kecil kita sudah dipersiapkan untuk sekolah. Rasanya hampir mustahil manusia modern tidak bersekolah ketika ia mampu. Menyekolahkan anak memang merupakan suatu kewajiban untuk keluarga yang menjaganya.
Lalu, ada masalah apa dengan sekolah? Bukankah sekolah memberikan pendidikan begitu penting sehingga dapat menjadi senjata yang paling kuat yang bisa kita pakai, seperti kata Nelson Mandela?
Sebelum menjawab pertanyaan di atas, mari bicarakan apa yang muncul di bayangan kita ketika mendengar kata sekolah. Bangku-bangku di dalam ruang kelas yang tersusun rapi, mungkin? Guru yang mengajar dan siswa yang diajar? Nilai tiap mata pelajaran dalam rapor tiap semester? Masuk sekolah pagi, datang terlambat, lalu dihukum?
Hal-hal tersebut rasanya memang dialami oleh hampir semua orang yang pernah bersekolah.
Lalu pertanyaan saya: Apa tujuan dari sekolah? Sejak kapan sekolah ada? Mengapa sekolah begitu lama dan memiliki jenjang yang begitu banyak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dalam buku Sekolah itu Candu oleh Roem Topatimasang. Seperti yang ditulis oleh Toto Raharjo, penyunting buku ini, Sekolah itu Candu merupakan catatan hasil kegelisahan penulis selama mempelajari Ilmu Pendidikan di kampus IKIP (1976-1980). Pertama kali terbit tahun 1998, buku ini berisi 16 tulisan yang memuat berbagai topik tentang praktik sekolah dan kritiknya.
Asal-Usul dan Ragam Sekolah
Tidak banyak yang tahu bahwa kata sekolah berasal dari bahasa Yunani, yaitu skhole/scola/scolae, yang secara harfiah berarti waktu luang. Di Yunani dulu, laki-laki dewasa (yang kemudian diikuti oleh putra-putrinya) mengisi waktu luang dengan cara mendatangi tempat atau orang tertentu untuk bertanya dan belajar tentang berbagai hal. Seiring berkembangnya zaman, para orangtua menerima ide skhole sebagai tempat bermain, belajar, dan berlatih untuk putra-putrinya. Dari sini, fungsi scola materna (pengasuhan ibu) beralih kepada scola in loco parentis (pengasuhan anak oleh figur selain orang tua asli). Semakin lama, anak-anak yang dititipkan untuk menerima ilmu semakin banyak, sehingga menuntut pengasuh yang lebih banyak pula. Pengasuh-pengasuh ini diberi upah oleh para orangtua.
Setelah itu, mulai ada beberapa tokoh yang mengembangkan ide tentang sekolah. Dalam Didactica Magna, Johannes Amos Comenius menyebut pentingnya pelembagaan pola dan proses pengasuhan anak. Pelembagaan ini perlu dilakukan secara teratur menurut sistem yang memperhatikan keragaman latar belakang dan perkembangan anak. Untuk pemikirannya, Comenius disebut-sebut sebagai bapak pendidikan modern. Usul Comenius ini kemudian dilanjutkan oleh Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi membuat pengelompokkan anak asuh secara berjenjang dengan pendalaman mata pelajaran yang bertahap. Inilah“Sistem Klasik Pestalozzi” yang dikenal dengan kelas yang bertingkat–sistem yang kita gunakan saat ini.
Tradisi sekolah sebetulnya tidak hanya ada di Yunani kuno. Bangsa Tiongkok kuno juga sudah mulai bersekolah 2000 tahun sebelum masehi. Setengah abad setelahnya, kaum Brahmana India juga membangun sekolah-sekolah Veda.
Sistem sekolah modern saat ini berkiblat pada tradisi Yunani kuno. Begitu juga sistem sekolah modern Indonesia, yang dikenalkan dengan tradisi ini melalui politik balas budi di zaman kolonial.
Gagasan dan praktik sekolah dari yang tadinya sekadar pengisi waktu luang, kini telah berubah menjadi sistem lembaga pendidikan modern yang kompleks.
Meski begitu, ini bukan berarti tidak ada sekolah yang menyimpang (dalam gagasan maupun praktik) dari sekolah modern pada umumnya. Dalam buku ini, Roem menunjukkan berbagai model sekolah, mulai dari universitas, akademi, hingga sekolah-sekolah yang tidak lazim seperti sekolah-sekolah yang tidak memiliki daftar mata pelajaran baku, tidak memiliki jadwal resmi, atau memiliki kelas-kelas yang tidak terbagi. Sayangnya, sekolah-sekolah ‘menyimpang’ ini tidak terlalu populer. Biasanya, mereka juga kurang dipahami oleh banyak orang. Roem sendiri menggugat gagasan sekolah modern di buku ini: “Semua sandangan kehormatannya (sekolah) yang sudah (menjadi tradisi) selama ratusan atau bahkan ribuan tahun boleh saja diubah: boleh tetap ada, tetapi juga boleh tak ada, bahkan boleh ditiadakan sama sekali!”
Sekolah Tidak Netral
Sekolah tidak pernah netral. Ada tujuan (kekuasaan) di dalamnya. Sekolah tidak bebas nilai. Seragam dan penyeragaman lainnya, misalnya, merupakan usaha pemerintah untuk menjaga status quo (melestarikan nilai-nilai resmi yang berlaku).
Bahkan, sekolah pun bisa berperan ganda sebagai barak militer. Pengalaman penulis bertemu dengan Jane, aktivis kemanusiaan dari New York yang bercerita tentang kunjungannya ke Palestina. Jane bercerita tentang anak-anak Palestina yang sejak kecil dikondisikan untuk memiliki naluri perang agar curiga terhadap apa saja dan siapa saja yang asing untuk mereka. Mereka diminta menghafal taktik gerilya, teknik sabotase, dan diberi pelatihan paramiliter. Usaha Jane, yang berharap dapat mengembalikan naluri alamiah anak-anak, tidak membuahkan hasil. Menurut Jane, kisah anak Palestina tidaklah jauh berbeda dengan anak-anak Indonesia, di Jakarta. Di Indonesia, banyak anak-anak yang harus mengorbankan masa kecilnya untuk melakukan pekerjaan orang dewasa demi menyambung hidup. Anak-anak ini ada di jalanan ibukota, trotoar, dan perempatan lampu merah. Mereka tidak bersekolah. Saat mereka mendapat kesempatan bersekolah pun, mereka tetap tidak punya waktu cukup untuk belajar, apalagi bermain dan menikmati waktu senggang.
Sekolah juga punya tujuan ekonomi. Roem mengkritik pengelolaan sekolah yang semakin mirip dengan pengelolaan perusahaan. Kemiripan ini ditemukan di berbagai bidang, mulai dari administrasi, manajemen, anggaran, efisiensi, promosi, relasi, hingga arus permintaan dan penawaran. Kini, sekolah seperti berada dalam lingkungan pasar bebas. Menurut Ivan Illich dalam Deschooling society, “(pengelola) sekolah saat ini sudah menjadi pengusaha tanpa nama terbesar”. Beragam tokoh dan ahli membuat kiasan tentang pendidikan. Tetapi nyatanya sekolah tampaknya lebih sederhana; ia adalah pasar! Lulusan sekolah adalah calon sekrup dalam mesin perekonomian. Mereka adalah faktor produksi utama yang jumlahnya tidak terbatas.
Dampak dari tujuan kekuasaan ini akhirnya membuat masyarakat terlepas dari akar sosialnya. Dalam bagian Robohnya Sekolah Rakyat Kami, penulis bercerita panjang lebar tentang terlepasnya sekolah dan masyarakat di ujung utara kaki pegunungan Latimojong-Rantemario dari akar sosial-budayanya. Akar kolektivitas yang mengedepankan semangat membangun dan menuai bersama biasanya terjaga lewat kegiatan sederhana seperti membabat rumput, memperbaiki pagar rusak, melabur dinding, atau membersihkan selokan bersama. Namun, kegiatan-kegiatan ini pun hilang semenjak dibangun ulangnya sekolah dengan bangunan ‘modern’ yang mengikuti gaya sekolah di perkotaan.
Pandangan dominan dalam pendidikan, terutama di Indonesia, selalu berfokus pada isu akses fasilitas. . . . (M)enurut Roem ada hal lain yang tidak kalah penting namun sering terlupakan; makna pendidikan itu sendiri. ~ Muhammad Fakhri Share on XMempertanyakan, Meragukan, hingga Membunuh Sekolah
Roem seolah-olah selalu mempertanyakan, “Pada dasarnya, apa itu sekolah?” Pertanyaan ini hadir salah satunya dalam cerita tentang anak-anak di Sekolah Dasar Mantigola, perkampungan tertua orang Bajo, Sulawesi Tenggara. Anak-anak tersebut setiap pagi dan siang hari ditugaskan sekolahnya secara berkelompok untuk menjemput dan mengantarkan guru-gurunya yang tinggal di daratan Pulau Kaledupa. Anak-anak yang lalai, malas, atau lambat akan dikenai hukuman. Salah satu hukuman yang disukai para guru adalah untuk mencari ikan segar di laut untuk kemudian dibawa pulang oleh para guru. Tidak hanya guru, siswa yang dihukum pun ternyata menanggapi hukuman ini dengan riang dan ceria.
Di momen itu, Roem kembali bertanya, “Jangan-jangan, justru hukuman menangkap ikan itulah ‘sekolah’ mereka yang sebenarnya?” Ia melanjutkan, “Jangan-jangan, itulah yang sebenarnya tak mampu dipahami oleh para perencana, pembuat kebijakan, pakar, dan pengelola pendidikan selama ini? Karena kurangnya pemahaman, kurikulum sekolah sering kali tidak membumi dan cara-cara penyajiannya di dalam ruang kelas menjadi sangat membosankan.”
Sekolah seolah terlepas dari realita sosial di sekitarnya. Inilah yang terjadi di dusun Galung-Galung di Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya isu akses untuk bersekolah saja yang perlu diangkat. Urgensi adanya sekolah di dusun pun tak kalah penting. Sekolah dianggap begitu penting, sehingga mereka rela bersusah payah jalan jauh. Sementara, sejak dahulu hingga sekarang orang sekitar dusun tetap kesulitan menghadapi masalah yang sama dalam bertani: tidak ada sarana irigasi, langkanya benih padi, hingga tidak adanya alat untuk memecah berbagai biji. Lalu, sekolah buat apa?
Ada banyak yang diragukan tentang sekolah di buku ini. Mulai dari perannya dalam membentuk watak dan perilaku, perannya dalam memproduksi pengetahuan ilmiah dan teknologi, hingga kecocokan latar belakang sekolah dan pekerjaan. Roem mengutip Everett Reimer, teoritikus pendidikan yang juga berteman dengan Ivan Illich, “Sekolah (mungkin) sudah mati”.
Nyatanya, sekolah sudah menjadi candu. Kisah Eko Sulistyo, seorang pelajar yang dikeluarkan dari sekolahnya karena meneliti pandangan kaum remaja soal kehidupan seksual, menunjukkan hal itu. Setelah itu, dia juga ditolak oleh berbagai perguruan tinggi, walaupun pada akhirnya rektor IPB menerimanya tanpa tes. Semua orang lega dan senang dengan solusi itu. Tetapi, apa yang sesungguhnya terjadi menurut Roem adalah sekolah sudah tertanam dalam ketidaksadaran kolektif, sehingga setiap orang merasa wajib mengikutinya. Jika gagal mengikuti, maka yang salah dan kalah adalah orang yang tersebut.
Pandangan dominan dalam pendidikan, terutama di Indonesia, selalu berfokus pada isu akses fasilitas. Meski kemudahan akses fasilitas merupakan isu yang juga penting, menurut Roem ada hal lain yang tidak kalah penting namun sering terlupakan; makna pendidikan itu sendiri. Untuk menegaskan ini, Roem membahas ironi dalam penerapan teknik kodifikasi dan dekodifikasi dari Paulo Freire dalam Pemberantasan Buta Huruf (PBH) yang melupakan gagasan utama Freire: metode conscientization (membangun kesadaran) dan humanisasi. Buku ini merangkum berbagai topik tentang sekolah yang tidak biasa dibahas. Penulisnya membawa pembaca untuk tidak hanya memikirkan ulang gagasan tentang sekolah, tetapi juga mempertanyakan dan meragukannya. Tentu, ini bukan hal yang mudah mengingat sekolah sudah merupakan bagian dari dan turut menjaga status quo. Karenanya, ia pun dijaga oleh lembaga dan tatanan kekuasaan yang mapan.
Muhammad Fakhri baru saja lulus dari Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran. Fakhri hobi berkomentar di media sosial dan saat ini sedang tertarik pada isu kerentanan kerja. Ia bisa dihubungi melalui Twitternya, @mhd_fakhrii
Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini