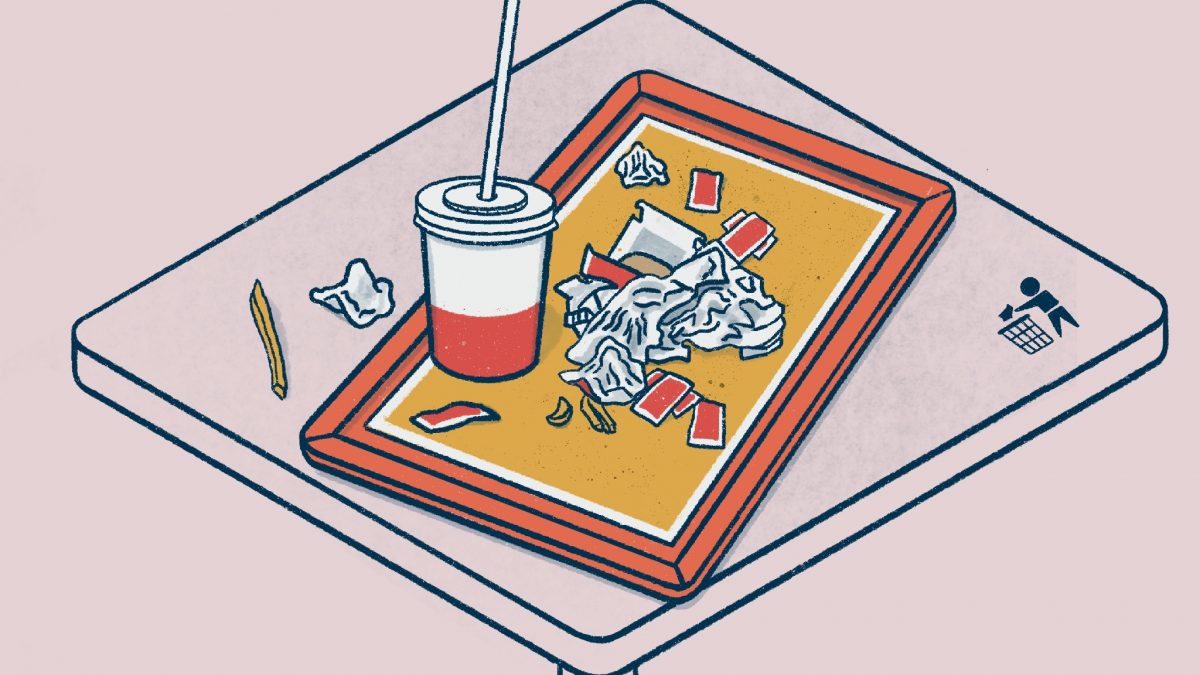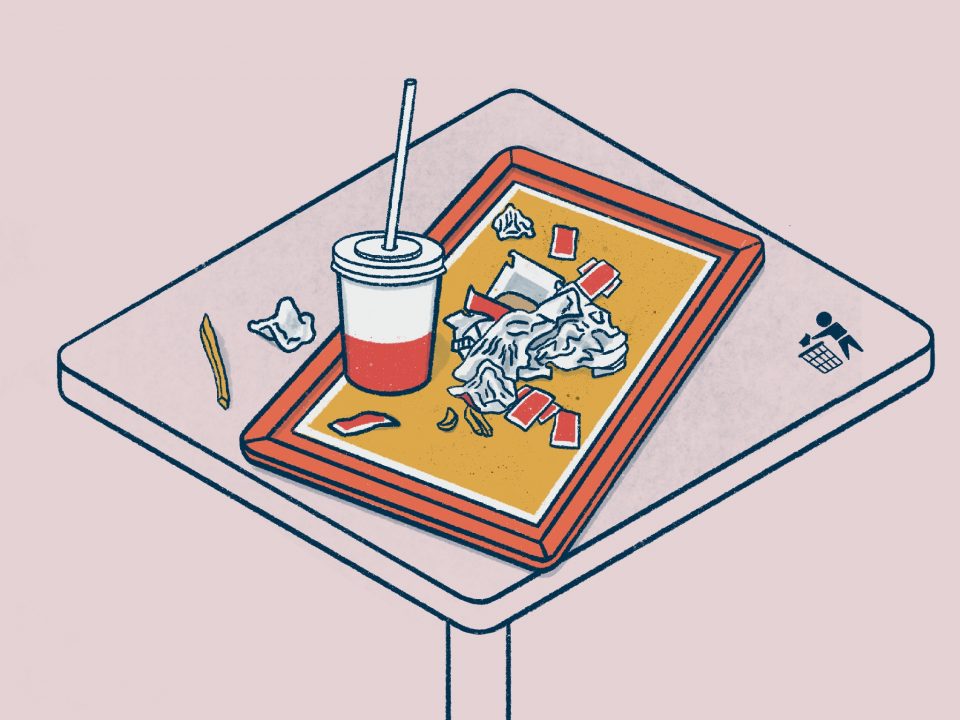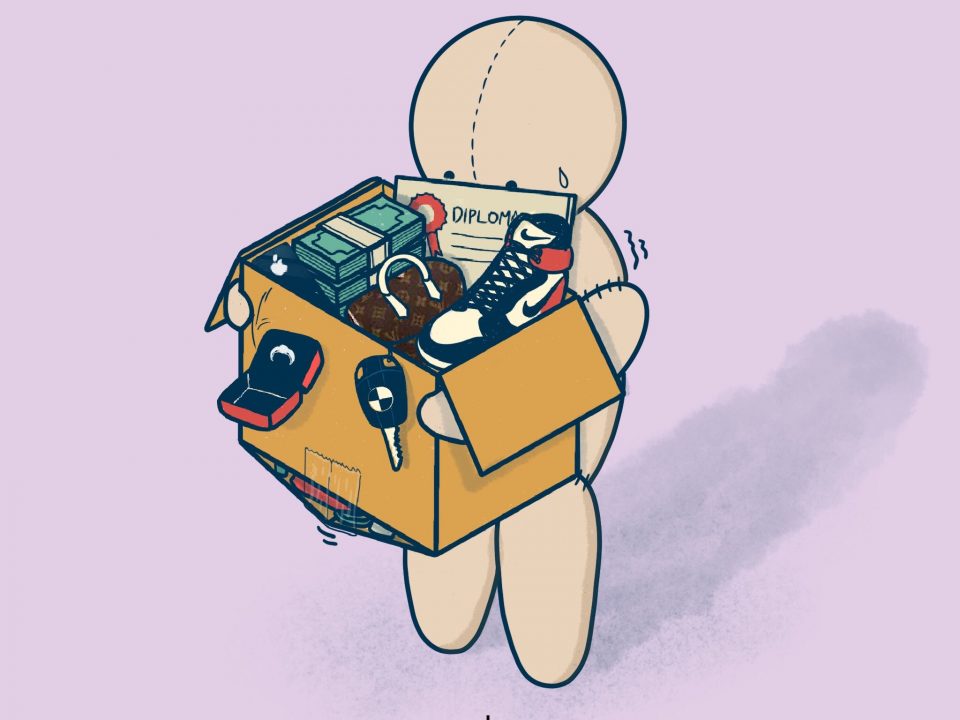Dari Dangdut hingga Frankfurt
October 17, 2019
Fitria Sis Nariswari
October 18, 2019Makna
Mendudukkan Lagi Budaya, Sebelum Terlalu Jauh
oleh Aloysius Bram
Salah satu poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan strategi kebudayaan akhir tahun 2018 lalu adalah meminta masyarakat menghidupkan kebudayaan Indonesia. Seperti dikutip Kompas.com, Jokowi bilang perkembangan dunia yang semakin kompleks turut membawa budaya Indonesia bersentuhan dengan budaya lain. Untuk itulah Jokowi merasa bahwa budaya Indonesia harus dikuatkan.
Alih-alih diamini, pernyataan Jokowi sebenarnya bisa kita perdebatkan. Soalnya ada kesan persentuhan “budaya Indonesia” dengan “budaya lain” merupakan fenomena termutakhir dari dunia yang bergerak akhir-akhir ini saja.

Beberapa waktu lalu misalnya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menginstruksikan jajarannya di kementerian yang ia pimpin untuk menghubungi Instagram. Pasalnya, Kemekominfo menemukan sebuah akun yang mereka rasa perlu untuk ditindak. Akun tersebut dianggap Rudiantara “menerabas dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia” lantaran mempromosikan LGBT.
Pernyataan Rudiantara menarik sebagai pintu masuk untuk membicarakan budaya. Bagaimana tidak, secara kultural Indonesia justru memiliki berbagai budaya atau tradisi yang memperkenalkan gender di luar spektrum “pria-harus-maskulin” dan “perempuan-harus-feminin”. Sesuatu yang Rudiantara ingkari (atau bahkan tak ia ketahui) dari pernyataannya.
Suku Bugis, misalnya, mengakui calalai atau laki-laki yang lemah gemulai seperti perempuan, calabai atau perempuan yang tomboy seperti laki-laki dan bissu, seorang yang bukan laki-laki dan bukan pula perempuan.
Nah, dengan fakta itu bukankah apa yang dilakukan oleh Rudiantara kontradiktif dengan instruksi bosnya sendiri yaitu Presiden RI? Kalau memang kita harus menguatkan budaya Indonesia, siapkah kita untuk adil untuk mengedepankan bentuk-bentuk pengakuan terhadap entitas lain yang selama ini masih dianggap bukan “bagian dari masyarakat Indonesia?” Lantas sebenarnya apa dan bagaimana itu budaya?
Budaya: sehari-hari yang rumit dan tak pernah kita sadari
Sebelum terjerembab pada jargon, ada baiknya kita mengenali kembali apa budaya itu. Makna istilah budaya saat ini kerap dipertukarkan secara serampangan karena sering terdengar di ruang publik. Atas nama budaya, sesuatu diklaim menjadi milik dari sekelompok orang. Di sisi lain, atas nama budaya pula orang diminta untuk menjadi permisif kepada kelompok yang lain. Naasnya, tanpa tinjauan dan penelusuran kritis, hal itu malah menjadi pembenaran untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu.
Padahal makna budaya tak bisa diikat begitu saja. Hari ini para cendekia tidak lagi menempatkan budaya sebagai “benda mati”, –dalam bentuk pusaka, pakaian adat, rumah tradisional dan semacamnya- yang kemudiandiaku dengan stempel kepemilikan seperti barang-barang pribadi kita.
Ernst Cassirer, filsuf kebudayaan di era pertengahan pertama abad ke-20, bilang bahwa budaya adalah pembeda. Secara fundamental, dalam buku berjudul Manusia dan Kebudayaan (1990), Ernst menyebut budaya bukan hanya pembeda antara manusia yang satu dengan yang lain. Namun yang paling hakiki adalah pembeda antara manusia dan makhluk biologis lainnya.
Budaya tak melulu bersifat adiluhung. Keberadaan budaya tak ubahnya udara yang kita hirup sehari-hari. Ia ada mulai dari bentuk yang paling kecil yakni bagaimana persepsi kita terhadap sekeliling. ~ Aloysius Bram Share on XHewan dan tanaman bisa bertahan hidup dengan mengembangkan mekanisme biologis untuk mengenali tanda –segala yang materiil dan bisa diproses melalui inderawi. Namun manusia melampaui hal itu.
Manusia berusaha memahami diri. Setelah memahami dirinya, manusia berusaha memahami persoalan yang ada di sekitarnya lalu beranjak mengatasinya melalui kreasi akal-budi. Bagi Cassirer setidaknya serangkaian proses itu adalah apa yang disebut sebagai budaya.
Cassirer punya istilah sendiri untuk merujuk pada apa yang kini dipahami sebagai budaya yaitu “simbol”. Manifestasi simbol itu tampak pada lima hal: mitos dan agama, bahasa, seni, sejarah, serta ilmu pengetahuan.
Tetapi, Cornelis Anthonie Van Peursen dalam bukunya Strategi Kebudayaan (1988) menolak pengklasifikasian sempit mengenai budaya beserta bentuk-bentuknya. Dengan tegas ia merujuk bahwa segala bentuk usaha manusia dalam mengutak-utik lingkungannya sah disebut sebagai budaya.
Entah tentang menggarap ladang atau membuat sebuah laboratorium untuk menyelidiki ruang angkasa, entah tentang mencuci tangan atau memikirkan suatu sistem filsafat, hidup manusia selalu mengutik-utik lingkungan hidup alamiahnya. Persis di situlah semua sah dinamakan kebudayaan. Kira-kira begitu yang diyakini oleh Van Peursen.
Bagi Van Peursen hal itu sekaligus menunjukkan bahwa budaya tak bersifat statis. Budaya merupakan rangkaian pengubahan riwayat: manusia selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada. Tak berhenti disitu, manusia juga lalu membagikannya.
Mengulas definisi budaya, tak lengkap rasanya bila tak menyitir Raymond Williams, penulis asa Inggris. Bagi saya, ulasan budaya dari Williams menyediakan paparan yang cukup representatif dari serenteng definisi yang ada. Williams bilang ada beberapa karakter dari definisi budaya. Namun dalam pembahasan ini, penulis akan merujuk pada definisi yang dirasa paling tepat guna.
Williams dalam tulisannya Culture and Society (1963) mencoba menawarkan definisi budaya sebagai seperangkat cara hidup manusia. Itu berarti ada makna dan nilai yang dipegang oleh sekelompok masyarakat dalam melakoni hidup dan realitas.
Meski begitu, makna serta nilai dalam serangkaian cara hidup itu bersifat implisit namun juga eksplisit. Untuk itu karya Williams, bersama beberapa koleganya, dikenal sebagai sosok kanon dalam aliran kajian budaya (cultural studies) yang mencoba untuk memahami budaya melalui berbagai metode.
Salah satu cara memahami budaya adalah bahwa dengan memandang budaya sebagai faktor determinan dalam proses pembentukan persepsi manusia atas realitas. Salah satunya diperantarai melalui bahasa. Itulah mengapa mazhab strukturalisme menempatkan seluruh praktik kebudayaan sebagai teks.
Ariel Heryanto, sosiolog dari Indonesia yang juga seorang guru besar di Monash University, Australia, dalam artikelnya yang berjudul Agenda Studi Kebudayaan (tayang di Harian Kompas, 25 Maret 1991) menyebut orang yang “ketularan” persepsi dari pihak lain akan melihat adanya realitas yang dianggap sebagai kebudayaan. Kecocokan dengan “makna kebudayaan” yang mengendap dalam benaknya, menjadi sebab. Pada titik itulah budaya dibagikan.
Orisinalitas budaya, benarkah?
Dari karakteristik budaya yang telah disampaikan secara terbatas, paling tidak kita bisa menyadari bahwa konsep mengenai orisinalitas dan/atau otentisitas budaya bisa diragukan –sesuatu yang dalam uraian ini menjadi pintu masuk kita mengenali lagi “budaya”. Bagaimana tidak? Hal ini mengingat orang yang ketularan dan cocok dengan satu cara pandang tidak membiarkannya mengendap begitu saja. Ia melakukan proses-proses berikutnya: memberi wujud baru.
Kepentingan otoritas tertentu sajalah yang kerap secara manasuka menyematkan konsep “kebudayaan nasional”, “kebudayaan Indonesia”, “kebudayaan tradisional”, “kebudayaan asli” sebagai alat legitimasi kuasa –sebagaimana sudah dibuktikan pada awal paparan ini.
Konsep orisinalitas budaya bisa berbahaya. Otoritas terkait, katakanlah negara, bisa berdalih hal itu digunakan untuk menumbuhkan sikap-sikap cinta tanah air. Dan tak hanya negara, dengan pola serta bentuk yang serupa ada saja otoritas lain yang memanfaatkannya.
Tanpa tinjauan kritis, jargon-jargon demikian bisa berefek runyam. Tanpa disadari, ia bisa mengkristal dalam benak kita dan menjadi cukup runcing untuk mengoyak relasi antar masyarakat dalam bentuk sikap-sikap primordial dan “sok-merasa-paling” atas satu bentuk budaya.
Memang sudah sejatinya budaya tak pernah statis bentuk dan pemahamannya. Ia akan terus bergulir sepanjang manusia masih terus memenuhi muka bumi. ~ Aloysius Bram Share on XBagi Antonio Gramsci, pemikir asal Italia, hal itu tak mengherankan. Menurutnya ada kondisi dalam kehidupan kita sehari-hari dimana pihak-pihak yang berkepentingan menjalankan agendanya. Hal itu dilakukan melalui kepemimpinan intelektual, moral, dan perspektif –atau singkatnya budaya- akan sesuatu.
Menariknya, hal itu dijalankan bukan dengan kekerasan. Namun dengan cara membentuk konsesus di tengah masyarakat. Konsep yang dalam buku Selections from Prison Notebook (1967) itu disebut sebagai hegemoni, menunjukkan bahwa budaya tidak hanya dibagikan namun juga bisa “dipaksakan”. Naasnya meskipun dipaksakan, hegemoni dianggap natural dan seakan semuanya memang begitu adanya.
Cendekiawan Amartya Sen dalam bukunya Kekerasan dan Identitas (2016) merujuk fenomena yang saat ini masih berlangsung yakni dikotomi antara “budaya barat” dan “budaya timur”. Amartya menyebut kolonialisme dan imperialisme ambil peran dominan atas terbentuknya dikotomi itu. Tak berlebihan menyebut “budaya barat” kerap dianggap lebih superior. Eksesnya bermacam-macam. Pada tataran lebih luas, ia bisa memunculkan inferioritas antara kelompok yang satu dengan lainnya. Hal yang menarik rasa inferior itu bisa menjelma dalam berbagai bentuk mulai dari obsesi berlebihan terhadap Barat, penjiplakan mentah-mentah hingga dendam kesumat.
Paparan di atas hanyalah segelintir ulasan saja mengenai budaya. Sejatinya, uraian definitif mengenai budaya sangatlah banyak. Bahkan saking banyaknya definisi itu ada anekdot: berjalan menyusuri sebuah perpustakaan dengan buku-buku bertema budaya akan memakan waktu berhari-hari.
Budaya tak melulu bersifat adiluhung. Keberadaan budaya tak ubahnya udara yang kita hirup sehari-hari. Ia ada mulai dari bentuk yang paling kecil yakni bagaimana persepsi kita terhadap sekeliling. Namun yang harus kita akui, tak setiap saat pula kita menyadarinya.
Alih-alih menerima dengan begitu saja, sikap-sikap untuk terus menelaah dan mempertanyakan bentuk kebudayaan justru harus dikedepankan. Sikap itu justru menjadi katalis. Selain itu memang sudah sejatinya budaya tak pernah statis bentuk dan pemahamannya. Ia akan terus bergulir sepanjang manusia masih terus memenuhi muka bumi.
Bacaan lebih lanjut
| Referensi Cassirer, Ernst. 1990. Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei tentang Manusia. Jakarta: Gramedia Gramsci, Antonio. 2007. Prison Notebooks. New York: Columbia University Press Heryanto, Ariel. 1991. Agenda Studi Kebudayaan. Harian Kompas, 25 Maret 1991 Sen, Amartya. 2016. Kekerasan dan Identitas. Yogyakarta: Marjin Kiri Van Peursen, C.A. 1988. Strategi Kebudayaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius Williams, Raymond. 1963. Culture and Society. Harmondsworth: Penguin |
| Bacaan Lanjutan Bennet, Andy. 2005. Culture and Everyday Life. California: Sage Hall, Stuart. 1992. ‘Cultural studies and its theoretical legacies’, in Cultural Studies, edited by Lawrence Grossberg, Cary Nelson and Paula Treichler, London: Routledge. Storey, John. 2015. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. New York: Routledge. Oswell, David. 2006. Culture and Society: An Introduction to Cultural Studies. California: Sage |

Aloysius Bram Lulusan konsentrasi studi, Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tertarik dengan bidang-bidang kajian budaya, media dan anak muda. Setelah pernah bekerja di salah satu media bisnis-investasi di Jakarta, kini mengisi gerak komunitas anak muda bernama ketjilbergerak di Yogyakarta. Di samping menulis lepas dan melakukan penelitian untuk isu-isu komunikasi, turut pula mengasuh situs seni dan budaya Serunai.co. Suka berceloteh di potongpendek.home.blog.
Artikel Terkait
Mendudukkan Lagi Budaya, Sebelum Terlalu Jauh
Salah satu poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan strategi kebudayaan akhir tahun 2018 lalu adalah meminta masyarakat menghidupkan kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan perkembangan dunia yang semakin kompleks turut membawa budaya Indonesia bersentuhan dengan budaya lain. Untuk itulah Jokowi merasa bahwa budaya Indonesia harus dikuatkan.Dari Dangdut hingga Frankfurt
“Suka dengerin musik apa?” suatu saat teman kencan saya bertanya seperti itu. Saya diam sejenak. “Dangdut. Sekarang, sih, lagi suka dengerin Via Vallen atau Nella Kharisma.” jawab saya pada akhirnya. Lalu, saya melihat raut muka teman kencan saya sedikit berubah. Tiba-tiba dia mengajak saya pulang. “Adakah yang salah dengan dangdut?”Budaya dan Konstruksi Sosial: Bagaimana Kita Memahami Dunia
Pernahkah kamu bertanya, bagaimana kita bisa menilai suatu hal, perilaku, atau fenomena sosial tertentu sebagai baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas? Siapa yang menentukannya?