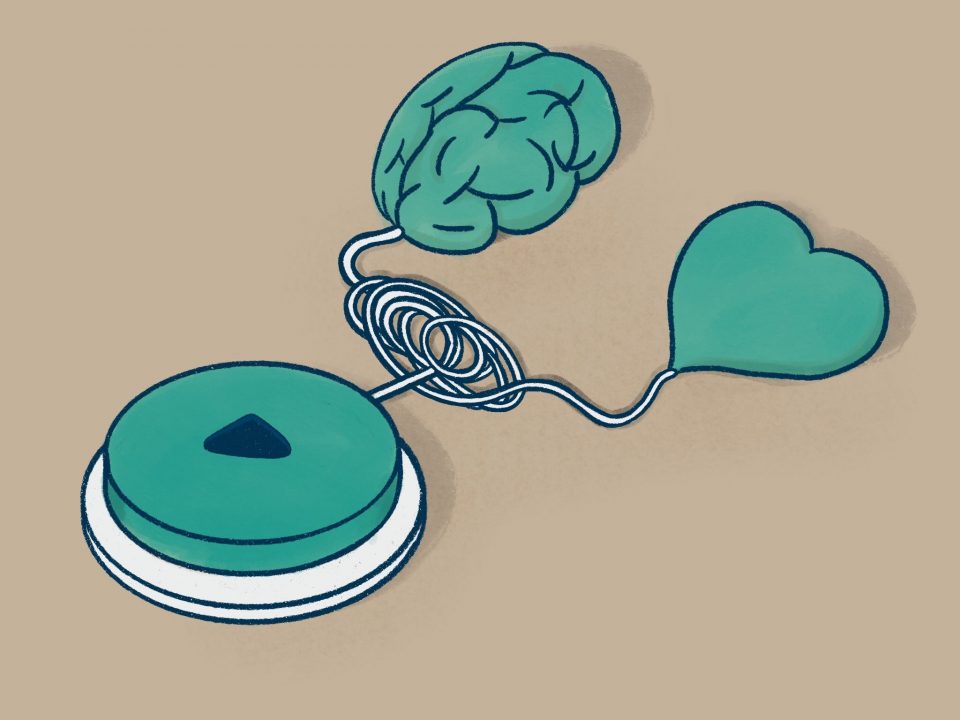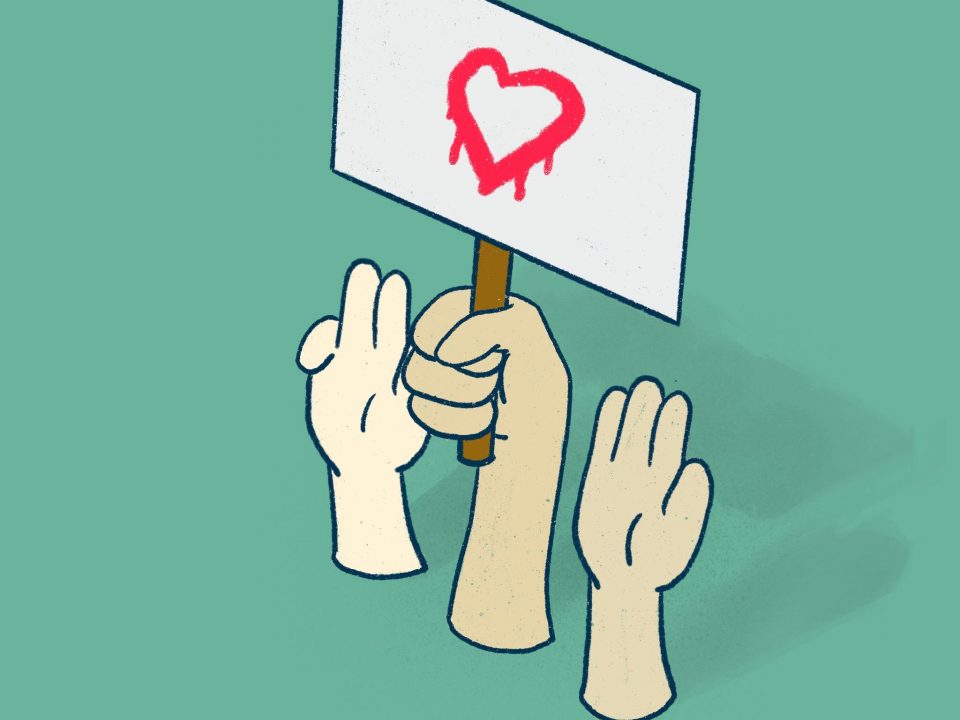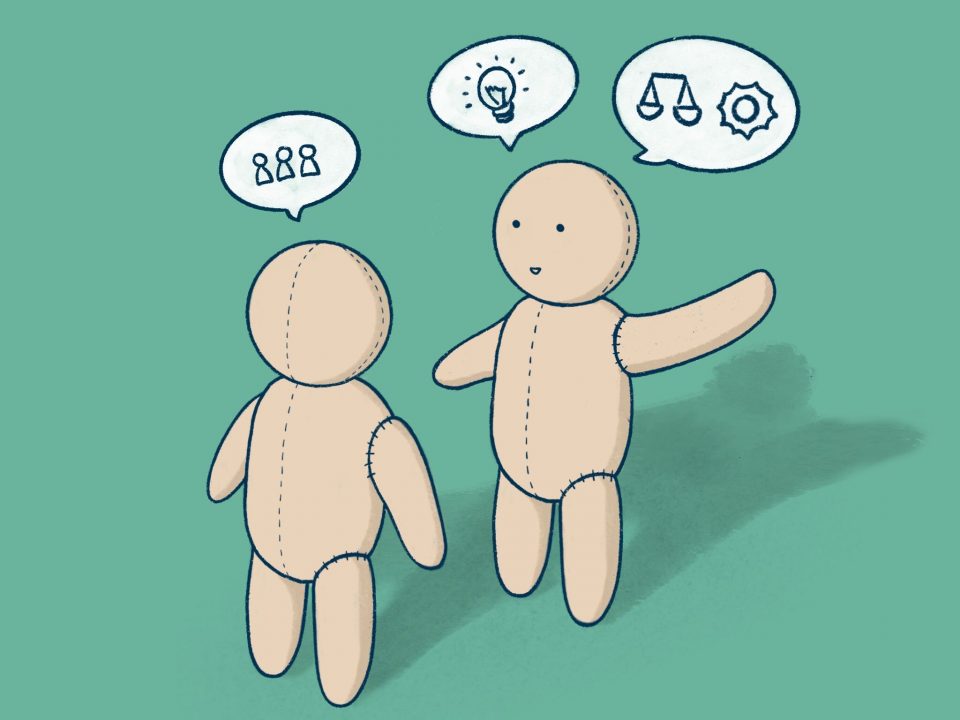Melawan Pembungkaman: Bagaimana Pers Mahasiswa Menumbuhkan Demokrasi di Kampus?
December 15, 2023
Hak yang Dirampas: Masyarakat dalam Pusaran Bisnis Kelapa Sawit
January 10, 2024
Photo by Kompas
OPINI
Membangun Dinasti di Negara Demokrasi: Geliat Politik Keluarga di Indonesia
oleh Virdika Rizky Utama
Politik dinasti, fenomena politik ketika kekuasaan diwariskan dalam keluarga dari generasi ke generasi, menjadi topik perdebatan di negara-negara demokrasi. Praktik ini mengingatkan pada tradisi monarki yang bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yang menekankan kesetaraan dalam partisipasi politik.
Di Indonesia, fenomena itu mencerminkan neopatrimonialisme, yaitu praktik kekuasaan yang diterapkan menurut sistem patrimonial tradisional (pewarisan) di mana berlangsungnya regenerasi kekuasaan politik didasarkan pada ikatan genealogis (keturunan) dan mengesampingkan meritokrasi (pemilihan pemimpin politik berdasarkan kompetensi dan capaian prestasi).
Artikel ini akan membahas interaksi antara politik dinasti dan demokrasi di Indonesia, terutama pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengaitkannya dengan sejarah politik Indonesia yang kaya dan dinamis.
Bercokolnya Politik Dinasti di Indonesia
Membahas fenomena politik dinasti di Indonesia bisa kita mulai dari berkuasanya pemerintahan Orde Baru di bawah komando Presiden Soeharto (1967-1998). Dalam sejarah Indonesia modern (setelah masa penjajahan), rezim otoriter Soeharto secara terang-terangan meletakkan dasar bagi berlangsungnya praktik politik dinasti. Selama masa pemerintahannya, ada banyak anggota keluarga Soeharto yang diberikan peran dan pengaruh politik yang signifikan, menandakan adanya praktik dinasti politik secara nyata.
Contohnya, Siti Hardiyanti Rukmana, salah satu anak Soeharto, mendapat hak istimewa dengan menjadi anggota MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mewakili Fraksi Partai Golkar sejak 1992 sampai 1998. Stempel sebagai anak Soeharto kemudian membawa namanya makin meroket dengan menjadi Menteri Sosial pada 1998.
Masih belum seberapa, anak Soeharto lainnya juga memperoleh hak istimewa yang memungkinkannya mampu mengakumulasikan kekayaan melalui sektor bisnis yang menggurita. Tommy Soeharto, misalnya, tercatat sebagai pengusaha muda papan atas (usianya pada waktu itu masih 30-an tahun) berkat 32 tahun langgengnya kekuasaan sang ayah.
Tren politik dinasti juga terlihat nyata di era Indonesia kontemporer (Indonesia pasca-Soeharto), khususnya selama periode pemerintahan Presiden Jokowi. Jokowi memang awalnya dianggap bukan bagian dari elit politik tradisional, karena ia bukan keturunan elit dan menapaki tangga karier politiknya dari ‘bukan siapa-siapa.’ Seiring berjalannya waktu, watak Jokowi rupanya tidaklah jauh berbeda dengan elit politik kebanyakan. Ia pun kini ikut mendirikan dinasti politik dengan mendukung keluarganya terjun ke dunia politik praktis.
Hal ini terlihat dari ‘terpilihnya’ sang putra, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wali Kota Solo periode 2021-2024 dan kini diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto. Publik pun mencatat bahwa Gibran tidak begitu saja terpilih sebagai cawapres, melainkan diuntungkan berkat pengesahan revisi Undang-Undang Pemilu tentang batas usia capres dan cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin sang paman, Anwar Usman.
Selain itu, Kaesang Pangarep, anak kedua Jokowi, juga diangkat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia hanya dua hari setelah ia bergabung. Belum lagi, Bobby Nasution, menantu Jokowi, juga menjabat sebagai Wali Kota Medan dan diproyeksikan akan melaju menjadi Gubernur Sumatera Utara pada periode mendatang.
Fenomena ini jelas mencerminkan watak politik dinasti yang dibangun Jokowi selama periode kepemimpinannya. Ini pun memicu diskusi tentang dampak politik dinasti terhadap ekosistem demokrasi Indonesia.
Politik Dinasti perlu Kita Lawan, Mengapa?
Kebangkitan politik dinasti di Indonesia memiliki beberapa implikasi terhadap tatanan demokrasi.
Pertama dan terutama, politik dinasti yang mengarah pada pemusatan kekuasaan politik ke dalam keluarga-keluarga tertentu merusak etos kesetaraan kesempatan politik yang merupakan inti dari demokrasi. Ini menimbulkan kekhawatiran akan langgengnya kekuasaan elit dan meminggirkan (memarjinalisasi) calon-calon politik dari kalangan non-elit.
Kedua, berbagai pertanyaan mengenai kompetensi para penerus politik dinasti pun terus mengemuka. Kita layak mempertanyakan: apakah mereka memenuhi syarat dan kapasitas untuk menduduki posisi politik tertentu ataukah posisi mereka didapat semata-mata karena hubungan kekeluargaan? Isu ini menyerang jantung pemerintahan dan mencederai prinsip meritokrasi yang seharusnya dikedepankan.
Ketiga, politik dinasti di Indonesia tidak terbatas pada kekuasaan di tingkat nasional saja, tetapi juga meluas ke berbagai tingkatan pemerintah daerah. Contoh paling nyata adalah Provinsi Banten yang dikuasai oleh keluarga mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Praktik ini bisa berakibat fatal bagi budaya politik dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.
Di daerah-daerah yang dikuasai oleh politisi berbasis keluarga, sering kali terjadi pengaburan batas antara kepentingan pribadi keluarga dan kepentingan layanan publik. Pengaburan ini berpotensi menelurkan keputusan pemerintahan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok atau individu tertentu, namun mengorbankan kepentingan masyarakat lebih luas.
Keempat, praktik politik dinasti secara signifikan memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sehat. Ketika kesuksesan politik diperoleh melalui garis keturunan keluarga, alih-alih prestasi individu dan kinerja pelayanan publik, sinisme atau ketidakpercayaan masyarakat akan menjadi tak terhindarkan lagi.
Selain bisa merusak kualitas demokrasi, dominasi keluarga tertentu di arena politik juga dapat menghambat keragaman suara dan ide—yang memiliki arti penting bagi semangat dan ketahanan masyarakat yang demokratis.
Di bawah pemerintahan Jokowi, hubungan antara keluarga dan politik menimbulkan pertanyaan krusial mengenai arah masa depan demokrasi Indonesia. Meskipun Jokowi naik ke tampuk kekuasaan sebagai sosok yang merakyat, ia kini ikut-ikutan mengakomodasi ambisi politik keluarganya. Menguatnya politik dinasti di era ini bisa kita pandang sebagai bentuk kemunduran drastis berdemokrasi, mengingat Indonesia pernah berdarah-darah memperjuangkan demokrasi sepanjang rezim Soeharto dan meminimalisir praktik politik dinasti.
Adapun membandingkan rezim Jokowi sekarang dengan rezim sebelumnya akan sangat membantu memahami dinamika yang kini terjadi. Selain sifatnya yang otoriter, rezim Soeharto menjadi penanda bagi hadirnya pengaruh keluarga dalam dunia politik. Pasca-Suharto, para pemimpin, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, juga memiliki anggota keluarga yang terlibat dalam politik praktis. Namun, skala keterlibatan dan visibilitas (keterlihatan) keluarga di rezim Jokowi saat ini bisa dibilang lebih mencolok.
Jika dibandingkan dengan dinasti politik di negara-negara lain, seperti Bush dan Kennedy di Amerika Serikat, Gandhi di India, dan Marcos di Filipina, Indonesia menunjukkan perbedaan. Keluarga-keluarga politik tersebut biasanya memberikan jeda waktu dan menerapkan etika tertentu sebelum anggota keluarga mereka terjun ke politik. Namun, di Indonesia, Presiden Jokowi yang masih aktif menjabat malah mendukung anaknya menduduki posisi politik yang tinggi. Langkah itu telah menimbulkan perdebatan tentang etika, karena ‘keberhasilan’ karier politik anak Jokowi didukung oleh intervensi MK yang dipimpin oleh sang adik ipar.
Memastikan inklusivitas politik, menjaga kualitas tata kelola pemerintahan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip meritokrasi adalah senjata melawan politik dinasti ~ Virdika Rizky Utama Share on XNamun, penting dicatat bahwa banyak negara demokrasi lain di seluruh dunia yang masih terus bergulat dengan pengaruh dinasti politik. Masing-masing memiliki dampak yang berbeda terhadap proses demokrasi di negara mereka. Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana sistem di masing-masing negara mengelola dan mengurangi pengaruh dinasti untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi tidak tercederai.
Menumpas Politik Dinasti di Indonesia
Di Indonesia, mengatasi tantangan politik dinasti membutuhkan pendekatan yang beragam. Memperkuat institusi dan proses demokrasi sangatlah penting. Hal itu termasuk memastikan berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan adil, menumbuhkan masyarakat sipil yang dinamis, mendorong pers yang bebas, dan meminta politisi mempertanggungjawabkan kebijakan yang digagasnya. Langkah-langkah ini akan membangun lingkungan politik yang bisa lebih menghargai prestasi dan kualitas pelayanan publik, daripada hubungan kekeluargaan.
Selain itu, mengingat persepsi masyarakat terhadap politik dinasti sangatlah penting dalam membentuk lanskap politik di masa depan, penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang dampak merusak (destruktif) dari praktik politik dinasti. Pemilih yang terinformasi dengan baik lebih mungkin memilih kandidat pemimpin berdasarkan kualifikasi dan gagasan kebijakan yang ditawarkan, daripada nama keluarga atau koneksi mereka. Karakter semacam ini penting untuk terus ditumbuhkan demi mengurangi langgengnya praktik politik dinasti secara bertahap.
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kerangka hukum dan peraturan mengenai partai politik dan pencalonan. Kita membutuhkan aturan untuk mencegah monopoli posisi politik oleh keluarga tertentu dan membuka keran partisipasi politik yang lebih luas. Sebagai contoh, peraturan yang mendorong transparansi dalam pendanaan politik dibutuhkan untuk mencegah sumber daya dimanfaatkan oleh keluarga tertentu saja.
Terakhir, peran kepemimpinan diperlukan untuk memutus siklus politik dinasti. Pemimpin yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau keluarga perlu terus mendapat sorotan (spotlight) dan dijadikan contoh baik. Dalam konteks ini, warisan politik dinasti yang dibangun Jokowi akan terus diawasi dengan ketat, sebab cara dia menyikapi politik dinasti dan warisannya akan memiliki implikasi jangka panjang bagi demokrasi Indonesia.
Ke depan, demokrasi Indonesia yang berhadapan dengan meningkatnya praktik politik dinasti akan menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan banyak aspek. Oleh karenanya, memastikan inklusivitas politik, menjaga kualitas tata kelola pemerintahan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip meritokrasi harus menjadi perhatian utama.
Catatan Akhir
Bangkitnya politik dinasti dalam demokrasi Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, bukan hanya menjadi sebuah anomali (penyimpangan) lokal, melainkan juga cermin yang merefleksikan tantangan-tantangan yang lebih luas dalam sistem demokrasi di seluruh dunia. Pertemuan antara warisan keluarga dan kekuasaan politik ini mendorong kita untuk mempertanyakan kembali dasar cita-cita demokrasi: meritokrasi, kesetaraan, dan perwakilan murni oleh rakyat.
Ketika menavigasi medan politik dinasti yang kompleks ini, Indonesia menjadi sebuah studi kasus penting bagi negara-negara demokrasi di mana pun, yang menantang warga negara dan para pembuat kebijakan, untuk merenungkan masa depan yang sedang mereka bangun.
Akankah prinsip-prinsip demokrasi cukup tangguh bertahan dalam ujian pengaruh dinasti, atau akankah mereka tunduk di bawah beban tradisi dan kekuasaan keluarga?
Jawabannya terletak pada kewaspadaan dan keterlibatan aktif masyarakat Indonesia serta tekad mereka untuk mendefinisikan demokrasi bukan berdasarkan warisan segelintir orang, melainkan berdasarkan kehendak kolektif dan aspirasi banyak orang.

Virdika Rizky Utama, biasa dipanggil Virdi, adalah peneliti politik di PARA Syndicate, Jakarta. Saat ini, Virdi adalah mahasiswa pascasarjana Ilmu Politik di Shanghai Jiao Tong University (SJTU), China. Virdi juga dikenal sebagai pemerhati Nahdlatul Ulama (NU) dan telah menulis dua buku tentang Gus Dur. Bukunya yang paling terkenal adalah Menjerat Gus Dur (NUMedia, 2019) dan publikasi terbarunya adalah sebuah novel berjudul “Panggil Saja Mutia” (Islamidotco, 2023).
Artikel Terkait
Mengapa Kita Tak Bisa Jadi Pemilih yang Rasional
Meskipun dalam teori politik dan demokrasi seorang warga negara sering digambarkan sebagai manusia rasional, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita sering dikuasai emosi. Memikirkan kembali Pemilu 2019 yang baru saja lewat, di Catatan Pinggir kali ini, Laila Achmad membahas mengenai sulitnya menjadi seorang pemilih rasional.Membayangkan Demokrasi di Indonesia: Trauma Kolektif dan Toleransi
Lirik lagu Mars Pemilu 2019 mencerminkan semangat demokrasi modern Indonesia dengan lugas hanya dalam sembilan baris singkat. Lagu ini menggarisbawahi pentingnya hak pilih rakyat bagi keberlangsungan negara Republik Indonesia sebagai negara demokrasi muda yang hampir berusia 74 tahun. Lalu bagaimana keadaan demokrasi Indonesia saat ini?Politik: Seni Berpikir Kritis Bukan Apatis
Ini akan terdengar sebagai suatu pembuka bacaan yang klise, namun kata ‘Politik’ sudah menjadi bagian dari makanan sehari-hari kita sebagai masyarakat Indonesia. Namun, apakah Politik itu menjadi asupan yang kita santap dengan penuh antusiasme?