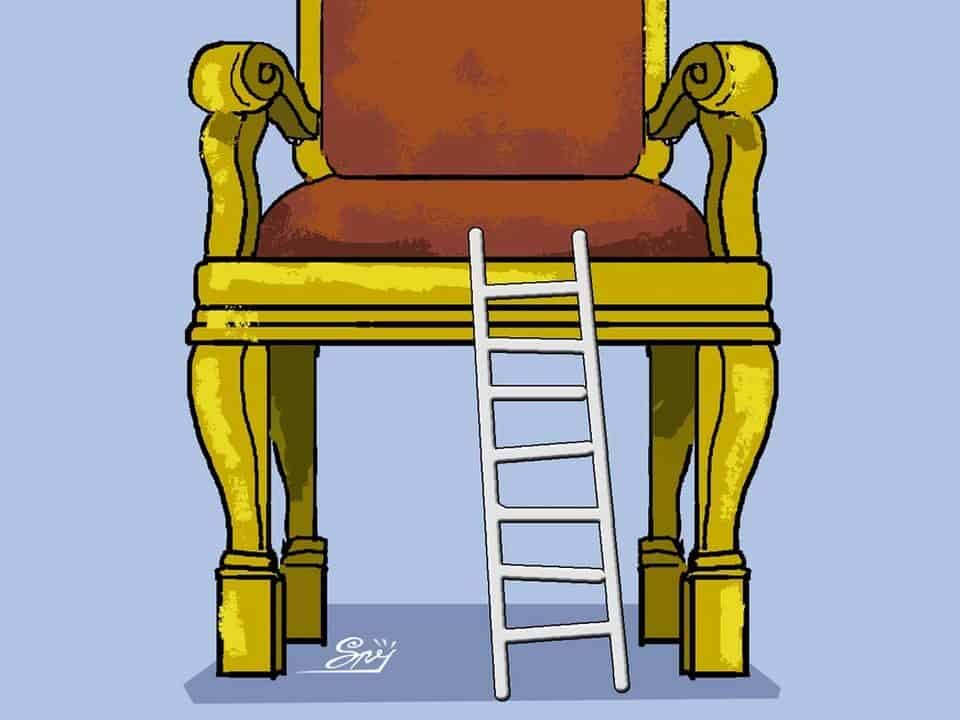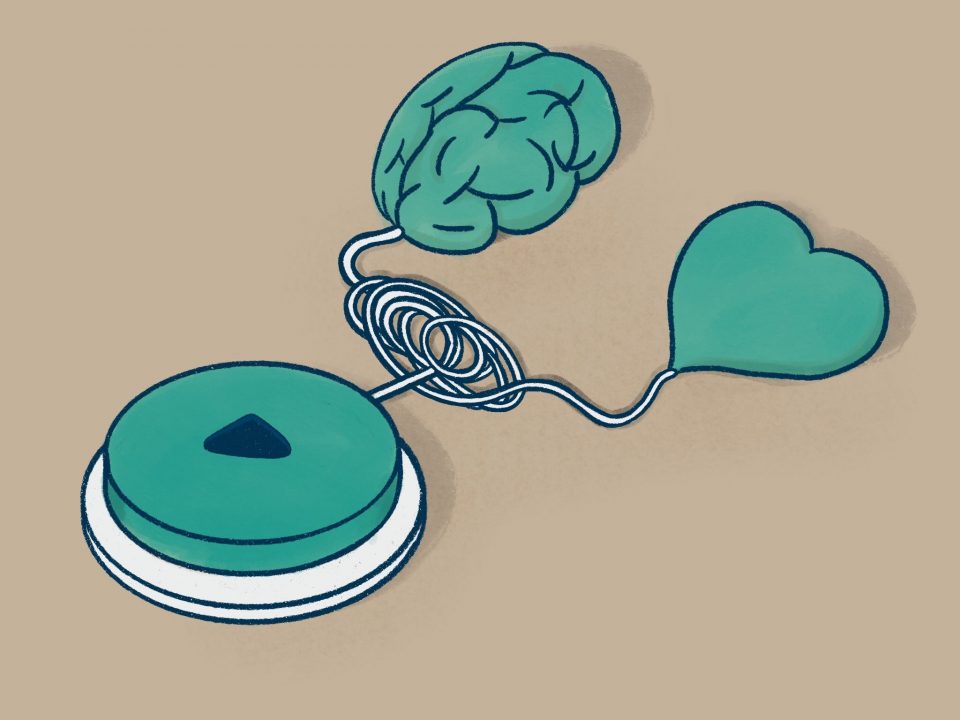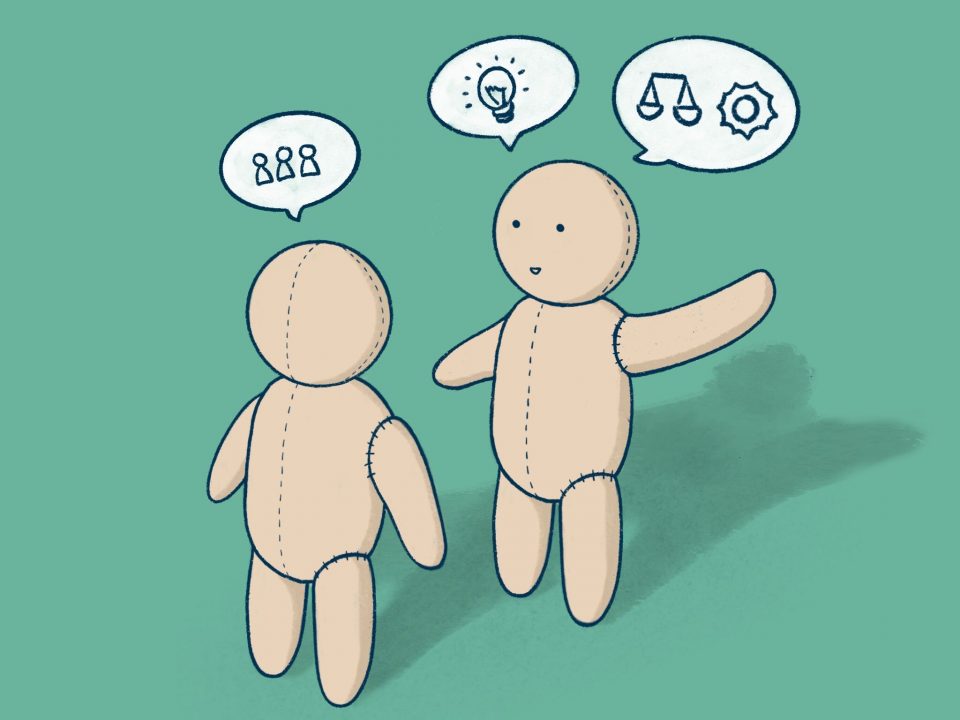Bedol Desa dan Kisah Pengorbanan Masyarakat Wonogiri
May 18, 2024
Sistem Politik Indonesia Nilainya D
May 28, 2024
Photo by UNUSIA
OPINI
Kritik untuk Ulil Abshar Abdalla: Menormalisasi Penindasan Menggunakan Sosok Jokowi
oleh Muhammad Ifan Fadillah
Pada 14 Februari 2024 lalu, masyarakat Indonesia merayakan ‘pesta’ demokrasi. Bagi saya, itu bukanlah pesta dalam arti yang sesungguhnya, melainkan lebih cocok disebut sebagai kondisi awal dari kehancuran yang lebih mendalam.
Mengapa saya menyebutnya sebagai awal dari kehancuran? Hal itu dimulai dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei nasional yang berkesimpulan bahwa perolehan suara pasangan nomor urut 02, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, unggul sekitar 58-59 persen. Angka tersebut jauh melampaui dua kompetitor mereka: Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Senada dengan hasil hitung cepat itu, Komisi Pemilihan Umum pun menetapkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran adalah pemenang Pemilu 2024 yang sah.
Hasil perolehan suara tersebut menjadi pukulan telak bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama para aktivis dan kaum terdidik yang mereka manifestasikan melalui platform X (sebelumnya Twitter). Cuitan (tweet) mereka yang membludak kebanyakan menyimpulkan bahwa kemenangan Prabowo merupakan titik awal dari dirampasnya kebebasan sipil di Indonesia.
Ketakutan para aktivis dan kaum terdidik itu tentu saja beralasan. Kita sama-sama tahu kalau ada banyak sekali preseden buruk yang telah dipertontonkan oleh Prabowo dalam meraih kursi kekuasaan. Variabel yang paling nyata adalah sosok Prabowo Subianto yang tidak bisa dipisahkan dari catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait penculikan mahasiswa pada 1997-1998. Preseden lain yang tak kalah penting adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden yang pada akhirnya menjadi karpet merah bagi anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, melenggang mulus mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden.
Anomali Ulil
Berbanding terbalik dengan yang dirasakan para aktivis dan kaum terdidik di platform X, salah satu intelektual Islam liberal Indonesia, Ulil Abshar Abdalla, menuliskan opininya di media online Kompas. Ia berkesimpulan bahwa kemenangan Prabowo-Gibran sebenarnya adalah manifestasi dari kehendak rakyat yang masih menginginkan pembangunan Indonesia ala Jokowi. Bahkan, di akhir tulisannya, Ulil menyarankan agar kita bersikap sedikit humble (rendah hati) menerima kenyataan bahwa rakyat Indonesia tidak menginginkan narasi-narasi progresif, seperti isu kemunduran demokrasi, yang sering disuarakan oleh para aktivis. Bagi Ulil, rakyat menginginkan sesuatu yang berbeda dari narasi-narasi tersebut.
Sayangnya, Ulil tidak menjelaskan panjang lebar dan spesifik terkait narasi apa yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat. Alih-alih menjelaskan alasan struktural dan material mengapa masyarakat lebih memilih Prabowo-Gibran, Ulil, dengan naifnya, menyimpulkan bahwa keinginan rakyat berbeda dari keinginan kalangan terdidik atau yang disebutnya sebagai ‘middle class intellectual bias’ yang menginginkan perubahan.
Berangkat dari itu, tulisan ini saya garap dengan titik pijak berseberangan dengan kesimpulan Ulil. Saya mencoba melihat kemenangan Prabowo-Gibran sebagai hasil dari tetap dipertahankannya seluruh penindasan yang terjadi di Indonesia, seperti masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan sulitnya akses pada pendidikan.
Ayo Bicara Fakta!
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, latar belakang pendidikan pendukung Prabowo Subianto mayoritas adalah berpendidikan dasar (63,2 persen), berpendidikan menengah (30,8 persen), dan berpendidikan atas (6,8 persen). Sementara dalam status ekonomi, pemilih Prabowo paling banyak datang dari kalangan menengah bawah (44 persen) dan disusul oleh mereka dari kalangan ekonomi bawah (36,8 persen). Sebagian kecil kelas menengah atas juga memberikan dukungannya pada Prabowo (15,6 persen), termasuk juga kalangan ekonomi atas (3,6 persen).
Data di atas bisa membuktikan bahwa mayoritas yang memenangkan pasangan Prabowo-Gibran berasal dari kalangan masyarakat miskin dan berpendidikan dasar. Saya harus menggarisbawahi bahwa fakta ini bukan untuk menyalahkan masyarakat miskin dan berpendidikan dasar yang tidak bisa berpikir rasional dalam pemilu. Saya ingin menunjukkan kalau keberadaan mereka merupakan bentuk nyata dari masalah ketimpangan struktural yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan presiden sebelumnya, dan menjadi faktor penunjang kemenangan Prabowo-Gibran.
Kita tahu kalau Presiden Joko Widodo, sejak awal pemerintahannya, cenderung lebih berpihak pada corak kebijakan neo-developmentalisme atau neoliberalisme, yaitu kebijakan yang menyerahkan segala aspek kehidupan rakyat pada mekanisme pasar dengan tujuan akumulasi keuntungan bagi segelintir orang. Corak kebijakan itu menyulut terjadinya ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam berbagai hal.
Klaim saya di atas tentu sangat beralasan ketika kita melihat data dan fakta yang ada. Tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, menurut data Oxfam, menunjukkan bahwa harta empat orang terkaya di Indonesia setara dengan akumulasi kekayaan milik 100 juta penduduk. Dilansir dari Katadata, World Inequality Database juga memaparkan fakta bahwa rata-rata kekayaan 1% penduduk terkaya di Indonesia jauh berada di atas rata-rata penduduk nasional. Rata-rata kekayaan 1% penduduk terkaya terus meningkat jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang cenderung stagnan.
Jika kita lihat rentang waktu yang lebih jauh pada 2000, rata-rata kekayaan 1% penduduk teratas baru mencapai Rp 494 juta. Sementara itu, rata-rata kekayaan penduduk nasional hanya sebesar Rp 35,07 juta. Dalam 20 tahun setelahnya, tepatnya pada 2020, rata-rata kekayaan 1% penduduk teratas melonjak menjadi Rp 2,07 miliar, sementara rata-rata kekayaan penduduk nasional masih sebesar Rp 142,2 juta. Fakta itu masih diperparah dengan tingkat pengangguran di Indonesia yang jumlahnya mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023.
Dalam aspek pendidikan, kita juga melihat fakta terjadinya peningkatan uang kuliah setiap tahun akibat diterapkannya kebijakan PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri – Berbadan Hukum) di kampus-kampus besar di Indonesia. Masalah struktural ini–ketimpangan ekonomi dan akses pendidikan tinggi yang kian langka–berkontribusi membuat masyarakat Indonesia sulit berpikir kritis dan rasional dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses pemilihan capres-cawapres pada Pemilu 2024. Mereka yang miskin, pengangguran, dan tidak bisa mengakses pendidikan tinggi adalah objek dari program pemberian bansos (bantuan sosial) dan serangan fajar saat menjelang hari Pemilu. Apakah mereka menginginkankan hal itu? Tentu saja, tapi itu adalah akibat dari kondisi ketidakadilan struktural yang mereka hadapi.
Bagi saya, berbagai permasalahan struktural itulah yang menjadi alasan sebenarnya mengapa Prabowo-Gibran berhasil memenangkan pemilu. Kita tidak bisa naïf mengatakan bahwa kemenangan Prabowo-Gibran adalah karena para pemilih menyukai pembangunan Indonesia ala Jokowi. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah mereka merupakan korban dari 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo yang menindas rakyat dan hanya menguntungkan para elit politik dan kapitalis besar. Menjadi catatan penting bagi kita sebagai masyarakat sipil bahwa besar kemungkinan jika seluruh kebijakan Joko Widodo akan tetap dilanjutkan oleh pasangan Prabowo-Gibran, jika kita meninjau narasi kampanye yang sering mereka dengungkan
Catatan Akhir
Tulisan ini saya tutup dengan kalimat dari tokoh pendidikan progresif Henry Giroux yang bisa menjadi bahan refleksi atas kondisi yang kita hadapi saat ini. Giroux mengatakan bahwa dalam ideologi neoliberal, pasar menjadi tempat untuk mengorganisir seluruh masyarakat. Setiap orang sekarang menjadi pelanggan atau klien. Kebebasan dalam hal ini bukan lagi tentang kesetaraan, keadilan sosial, atau kesejahteraan masyarakat, tetapi segala hal yang terkait dengan perdagangan barang, modal keuangan, dan komoditas. Struktur itu membuat budaya bisnis mengatur struktur tata kelola sekolah, pengetahuan dipandang sebagai komoditas, dan siswa diperlakukan secara reduktif sebagai konsumen dan pekerja.
Mereka yang miskin, pengangguran, dan tidak bisa mengakses pendidikan tinggi adalah objek dari program pemberian bansos dan serangan fajar saat menjelang hari Pemilu. ~ Muhammad Ifan Fadillah Share on XRealitas di atas semakin lama semakin memperparah ketimpangan masyarakat dalam mengakses layanan dasar, utamanya pendidikan dan penghasilan yang layak. Lambat laun, nalar kritis dan rasionalitas mereka pun ditumpulkan, sehingga mudah dijadikan objek politik uang dalam rangka memenangkan kontestasi pemilu, tak peduli seberapapun buruknya latar belakang dan gagasan yang ditawarkan sang calon pemimpin.

Muhammad Ifan Fadillah adalah penjaga toko yang bekerja sampingan jadi pengajar di kampus.
Artikel Terkait
Membangun Dinasti di Negara Demokrasi: Geliat Politik Keluarga di Indonesia
Politik dinasti jadi penyakit demokrasi. Bagaimana demokrasi Indonesia bergulat dengan politik dinasti?Mengapa Kita Tak Bisa Jadi Pemilih yang Rasional
Meskipun dalam teori politik dan demokrasi seorang warga negara sering digambarkan sebagai manusia rasional, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita sering dikuasai emosi. Memikirkan kembali Pemilu 2019 yang baru saja lewat, di Catatan Pinggir kali ini, Laila Achmad membahas mengenai sulitnya menjadi seorang pemilih rasional.Politik: Seni Berpikir Kritis Bukan Apatis
Ini akan terdengar sebagai suatu pembuka bacaan yang klise, namun kata ‘Politik’ sudah menjadi bagian dari makanan sehari-hari kita sebagai masyarakat Indonesia. Namun, apakah Politik itu menjadi asupan yang kita santap dengan penuh antusiasme?