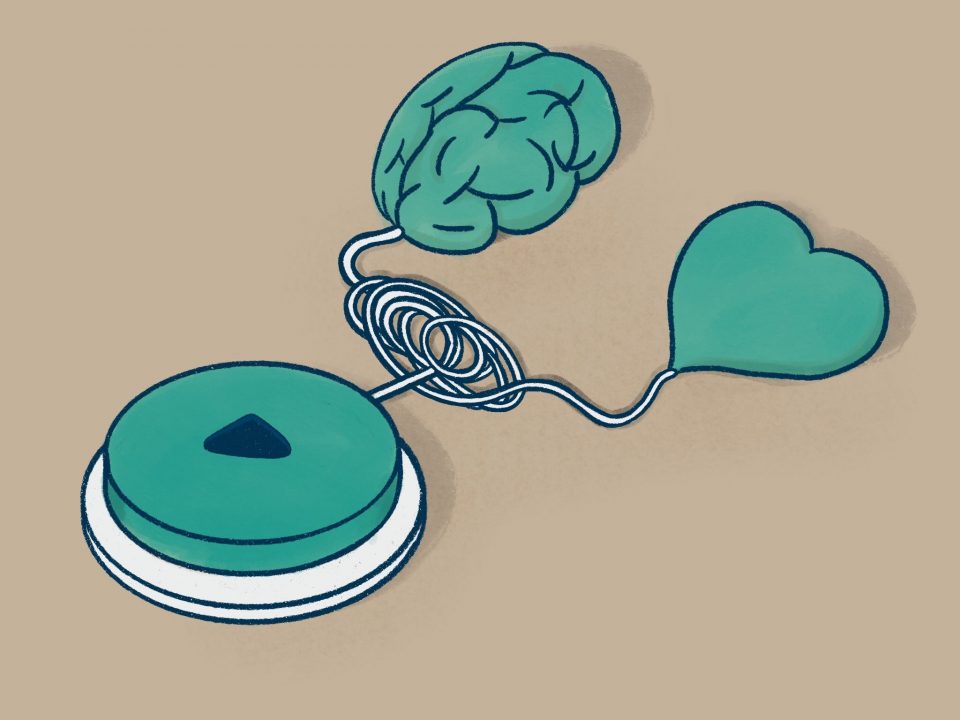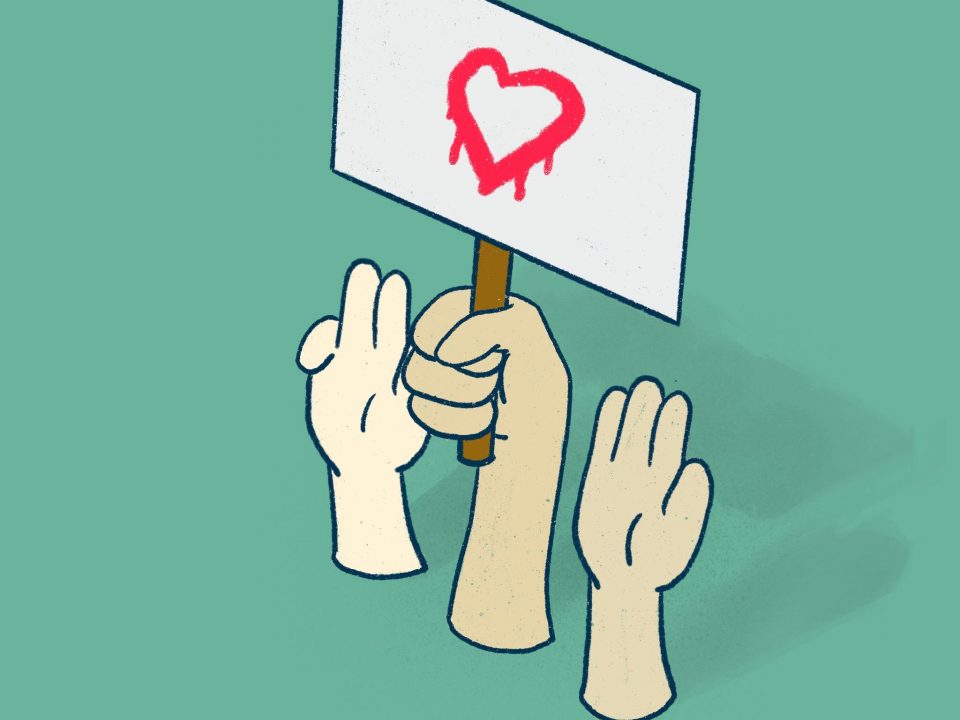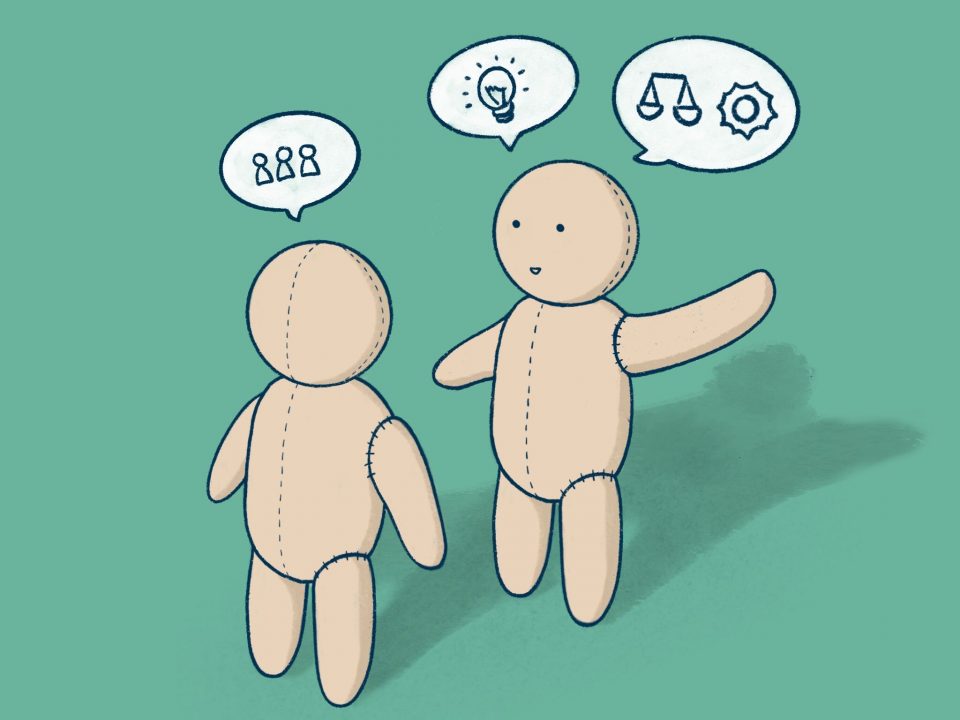Menilik Istilah ‘Diaspora’, Memandang Perpindahan Manusia
August 24, 2024
Di Balik Gempita Hilirisasi Nikel
September 14, 2024
Photo by Rmol
OPINI
Kekuasaan dan Intrik Politik ‘Raja Jawa’ dalam Arus Demokrasi Indonesia
oleh Maulana Malik Ibrahim
Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar baru saja selesai dilaksanakan pada 21 Agustus 2024. Dalam musyawarah tersebut, para elit politik sepakat memilih politisi Bahlil Lahadalia sebagai calon tunggal sekaligus pemenang kontestasi pemilihan ketua partai.
Tidak banyak orang yang terkejut ketika Bahlil terpilih sebagai ketua umum. Bahlil merupakan salah satu orang dekat Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo, sehingga bukan hal yang aneh untuk dia memenangkan kursi ketua umum partai. Bukan terpilihnya Bahlil sebagai ketua umum, fenomena yang menarik justru mengarah pada sambutan Bahlil dalam pidato kemenangannya yang menggiring pada intrik tafsir-tafsir politik tertentu:
“Soalnya ‘Raja Jawa’ ini, kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tau…. Sudah lihat kan barang ini, ya tidak perlu saya ungkapkanlah.”
Pernyataan tersebut menyulut perdebatan publik hingga memunculkan tafsir kuat bahwa ‘Raja Jawa’ yang dimaksud Bahlil adalah Jokowi. Istilah ‘Raja Jawa’ yang identik dengan ‘kekuasaan absolut penguasa’ tersebut memperkeruh kegaduhan demokrasi yang terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Hal itu memperkuat anggapan bahwa Jokowi memang gemar bermanuver politik, terutama terlihat dari tumbangnya Airlangga Hartarto dari tampuk kekuasaan Partai Golkar, Revisi UU Pilkada (Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah), dan ketidaknetralan sikapnya selama Pemilihan Presiden 2024.
Lantas, berdasarkan pernyataan Bahlil Lahadalia, apakah hal tersebut hanya sebuah kelakar atau memang benar-benar menunjukkan ambisi Jokowi yang ingin menjadi seperti ‘Raja Jawa’ dan apa implikasinya bagi demokrasi di Indonesia?
Jokowi: Kekuasaan dan Ambisi Menjadi ‘Raja Jawa’ (?)
Terdapat analisis menarik ihwal pernyataan ‘Raja Jawa’ dalam semiotika (makna yang terkandung dalam bahasa). Istilah yang ditujukan pada Presiden Jokowi itu meneguhkan anggapan kalau kekuasaan Jokowi sifatnya mutlak. Indonesianis (ahli mengenai isu Indonesia) Benedict Anderson, dalam tulisannya yang berjudul “The Idea Power in Javanese Culture”, menjelaskan bahwa penguasa Jawa atau Raja Jawa selalu menitikberatkan titik pusat kekuasaan pada dirinya sendiri. Hal itu dilihat sebagai pemenuhan akan harapan ataupun nubuat yang melihat zaman sebagai siklus kehidupan manusia; masa lalu yang jaya, masa kini yang suram, dan masa depan yang gemilang. Dari pernyataan di atas, seorang raja akan memberikan dan mengumbar janji-janji untuk menuntaskan permasalahan pelik pada zaman tersebut.
Tidak hanya itu, raja selalu menyiapkan penggantinya di masa-masa sebelum ia meninggalkan tampuk kekuasaan, menggerakkan seluruh sumber daya untuk mengantarkan para pewaris raja hingga mencapai kekuasaan, dan setelahnya menciptakan imajinasi karakter yang presisi seperti raja sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai upaya agar raja sebelumnya tidak kehilangan pengaruh ataupun legitimasi dengan cara melakukan regenerasi kekuasaan secara feodal.
Penjelasan di atas tergambar jelas dari manuver politik yang dilakukan Presiden Jokowi di akhir masa kepemimpinannya. Pertama, kita dapat merasakan cawe-cawe Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024, di mana sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pengerahan sumber daya dan kapitalisasi dukungan secara terang-terangan diberikan oleh Jokowi kepada pasangan calon tersebut. Tentunya, hal itu merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia yang seharusnya bebas dari intervensi kekuasaan dan menciptakan ruang kompetisi politik yang adil untuk seluruh warga negara.
Kedua, preseden sebagai ‘Raja Jawa’ terlihat dalam revisi UU Pemilihan Kepala Daerah yang sengaja dikerjakan secara serampangan untuk memuluskan jalan putra mahkota kedua Jokowi, Kae Sang Pangarep, sebagai Gubernur/Wakil Gubernur di sebuah daerah. Analisis itu didukung oleh tulisan ilmuwan politik Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, Eve Warburton, dan Diedo Fossati berjudul “Elites, Masses, and Democratic Decline in Indonesia” yang menjelaskan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia memilih berdasarkan preferensi penguasa dan hal tersebut dapat diarahkan dengan mudah. Hal itu disebabkan oleh lemahnya budaya demokrasi substansial di Indonesia dan menguatnya demokrasi elektoral setelah Orde Baru. Kekhawatiran itu dikuatkan oleh banyaknya politik uang yang marak terjadi selama berlangsungnya pemilihan umum di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Konteks ‘Raja Jawa’ tidak hanya memiliki justifikasi melalui fenomena Pilpres dan Pilkada 2024 yang memberikan karpet merah kepada anak-anak Jokowi. Maraknya pengembangan proyek infrastruktur super megah juga dapat dilihat sebagai simbol-simbol kekuasaan dan dapat dijadikan romantisasi di masa depan. Sekali lagi, Anderson juga menekankan hal itu, bahwa kekuasaan seorang raja di teritori Jawa perlu disimbolisasi bukan hanya dalam bentuk pengaruh, melainkan juga bangunan-bangunan fisik. Pengejawantahan abstraksi Anderson dapat dilihat dari ambisi Jokowi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai objek warisan kekuasaan yang dapat ditinggalkan dan dikenang oleh masyarakat Indonesia. Kekuasaan dan pengaruh itu tentunya sangat membahayakan bagi arena demokrasi yang telah diwujudkan setelah reformasi 1998.
Lalu, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah Jokowi meneruskan kekuasaan dan ambisinya menjadi raja dalam negara demokrasi?
Gerakan Masyarakat Sipil dalam Pengawalan Arus Demokrasi
Ungkapan Bahlil Lahadalia mengenai ‘Raja Jawa’, secara terang-terangan, mengganggu iklim demokrasi di Indonesia. Hal itu dapat dimaknai sebagai sebuah pertanda bahwa keinginan Jokowi adalah ‘titah’ yang harus sesegera mungkin dilaksanakan. Dalam negara demokrasi, tentunya setiap keputusan perlu melewati mekanisme diskursus publik dan tidak dapat secara sewenang-wenang disahkan. Namun, kita semua menyaksikan ada banyak sekali kebijakan yang menuai pro-kontra di ruang publik, tetapi tetap saja disahkan, seperti UU KPK yang ditolak secara masif oleh banyak elemen di tahun 2019 dengan tajuk gerakan “REFORMASIDIKORUPSI” dan penolakan terhadap UU Omnibus Law dan KUHP dengan tajuk gerakan “MOSITIDAKPERCAYA” di tahun 2020. Terakhir, ada pula gerakan kolektif yang diciptakan baru-baru ini untuk menolak revisi UU Pilkada dengan tajuk “PERINGATAN DARURAT”.
Hadirnya ketiga gerakan masyarakat sipil di atas menandakan masih berfungsinya alat-alat kontrol demokrasi yang diwujudkan melalui gerakan sosial. Meskipun demikian, tidak berselang lama ketika gerakan sosial tersebut mengendur, undang-undang yang telah diprotes tetap saja disahkan. Pengesahan-pengesahan ini nampaknya tidak lain merupakan keinginan Jokowi untuk memuluskan jalannya kepentingan pemerintah agar meneguhkan pengaruh dan kekuasaannya. Dalam konteks ini, masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dalam pengambilan kebijakan, sehingga terjadi protes-protes yang besar untuk mengawal proses demokrasi kontemporer.
Ben Blend, dalam bukunya yang berjudul Man of Contradictions: Joko Widodo and The Struggle to Remake Indonesia, menjelaskan bahwa Jokowi cenderung menguji terlebih dahulu proses pembuatan kebijakan untuk melihat respon masyarakat, lalu membahasakan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya secara politis. Tidak jarang, pola itu dapat masyarakat lihat melalui ungkapan “apa yang dikatakan oleh Jokowi, maka lihatlah dengan sebaliknya dalam realitas”. Hal-hal seperti itu lah yang membuat masyarakat merasakan kegusaran sosial dan memandang bahwa kelompok masyarakat cenderung dipermainkan oleh elite politik dalam pembuatan kebijakan.
Masyarakat tidak memerlukan simbolisasi ‘Raja’ ataupun ‘Ratu’. Kita juga tidak memerlukan politik dinasti, karena di negara demokrasi yang harus diutamakan adalah transparansi, arena politik yang kompetitif dan merata. ~ Maulana Malik… Share on XPerkembangan gerakan masyarakat sipil perlu diperbesar agar mampu memberikan daya tekan pada elite politik. Analisis ini diberikan karena melihat fenomena ‘pembatalan/penundaan’ pengesahan kebijakan ketika terdapat gerakan sosial yang dilakukan oleh berbagai macam elemen, seperti mahasiswa, buruh, akademisi, dan pelajar. Perlunya tekanan ini adalah untuk mengontrol kekuasaan sewenang-wenang Jokowi yang diasosiasikan sebagai ‘Raja Jawa’ dan lembaga legislatif dalam sistem politik Indonesia. Masyarakat perlu menunjukkan siapa yang memiliki kedaulatan dalam negara demokrasi, bukan presiden Jokowi, DPR, ataupun lembaga negara yang lainnya. Melainkan, pemilik kedaulatan yang sejati ialah rakyat yang memberikan mandat kepada orang-orang yang ada di pemerintahan hari ini.
Masyarakat, sekali lagi, tidak memerlukan simbolisasi ‘Raja’ ataupun ‘Ratu’. Kita juga tidak memerlukan politik dinasti, karena di negara demokrasi yang harus diutamakan adalah transparansi, arena politik yang kompetitif dan merata, serta kemakmuran yang bermakna. Maka dari itu, gerakan masyarakat sipil perlu terus hidup untuk mengawal dan menjaga proses demokrasi di Indonesia, serta memastikan tekanan terhadap pihak-pihak yang ingin membangkitkan romantisme feodalisme.

Maulana Malik Ibrahim adalah seorang mahasiswa baru S2 yang hari ini rasa-rasanya geram melihat tindak-tanduk pejabat dan ingin mengeluarkan uneg-uneg lewat tulisan.
Artikel Terkait
Mengapa Kita Tak Bisa Jadi Pemilih yang Rasional
Meskipun dalam teori politik dan demokrasi seorang warga negara sering digambarkan sebagai manusia rasional, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita sering dikuasai emosi. Memikirkan kembali Pemilu 2019 yang baru saja lewat, di Catatan Pinggir kali ini, Laila Achmad membahas mengenai sulitnya menjadi seorang pemilih rasional.Membayangkan Demokrasi di Indonesia: Trauma Kolektif dan Toleransi
Lirik lagu Mars Pemilu 2019 mencerminkan semangat demokrasi modern Indonesia dengan lugas hanya dalam sembilan baris singkat. Lagu ini menggarisbawahi pentingnya hak pilih rakyat bagi keberlangsungan negara Republik Indonesia sebagai negara demokrasi muda yang hampir berusia 74 tahun. Lalu bagaimana keadaan demokrasi Indonesia saat ini?Politik: Seni Berpikir Kritis Bukan Apatis
Ini akan terdengar sebagai suatu pembuka bacaan yang klise, namun kata ‘Politik’ sudah menjadi bagian dari makanan sehari-hari kita sebagai masyarakat Indonesia. Namun, apakah Politik itu menjadi asupan yang kita santap dengan penuh antusiasme?