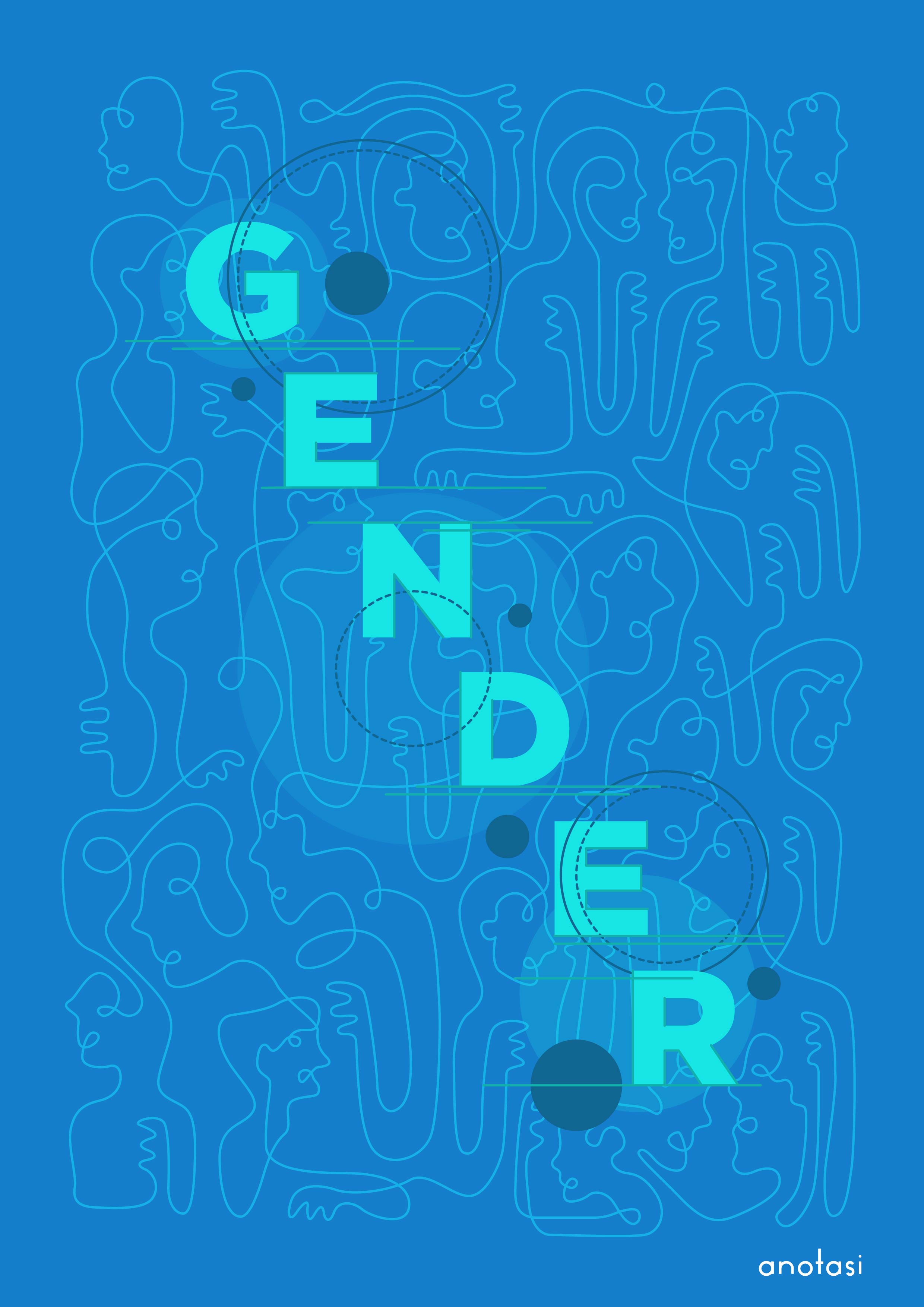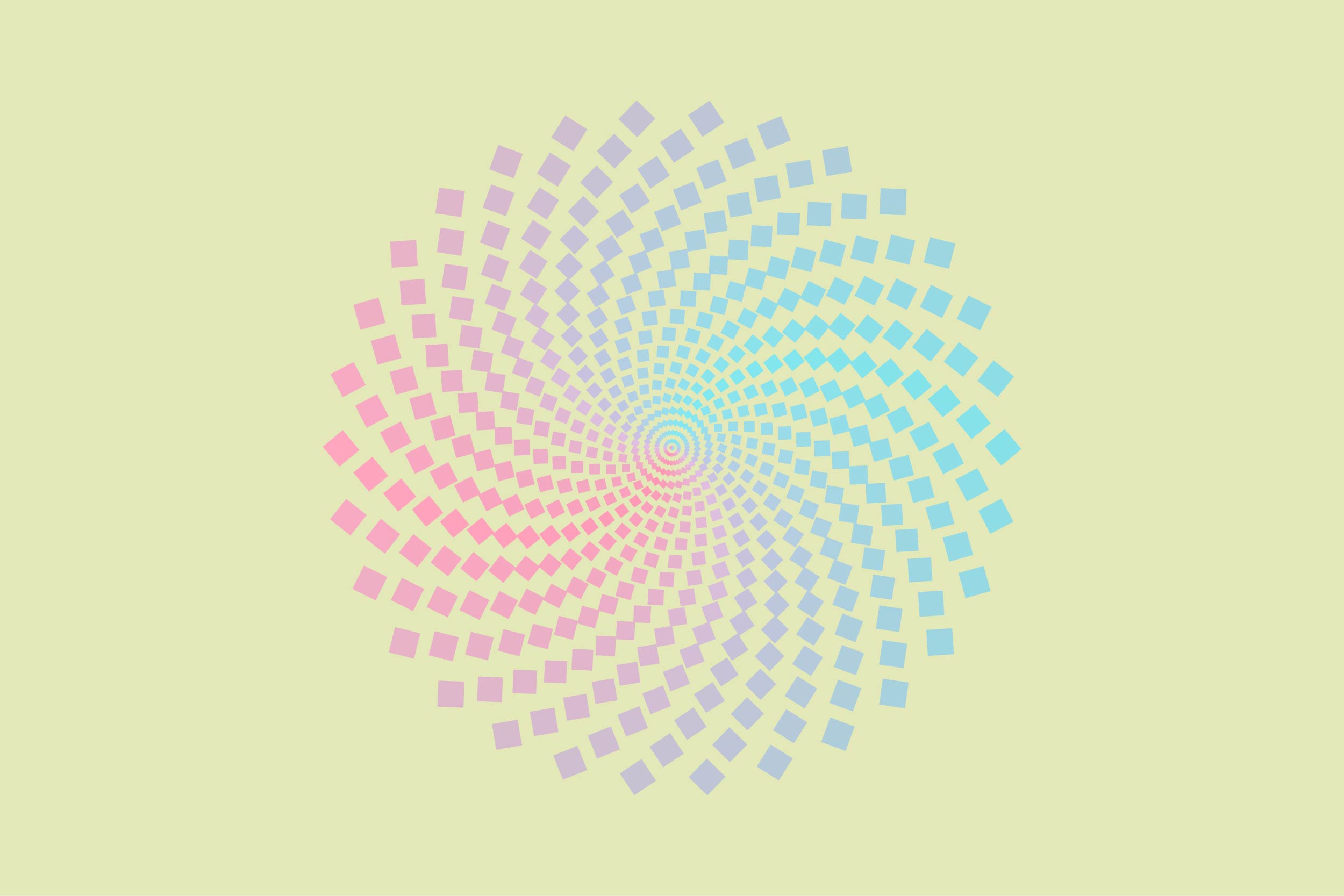Politik Kartel yang Entah Berlanjut Sampai Kapan
November 25, 2024
Photo by Konde
OPINI
Merawat Siasat dalam Meretas Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
oleh Eni Puji Utami
Ada masanya tangan saya gemetar setiap mendapat notifikasi pesan di layar gawai. Hujatan dan ancaman berulang dari akun-akun tidak dikenal hampir seharian memicu panik. Atas saran seorang kawan, saya mengganti user name Twitter (saat ini X) dan mengubah pengaturannya dari publik ke privat, agar jangkauannya lebih terkendali. Cemas pun mereda, meski tidak sepenuhnya.
Kondisi seperti itu kemudian bertahun-tahun saya temui pada setiap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang mengakses layanan pengaduan, di mana saya menjadi salah satu pendampingnya. Mereka datang dengan perasaan sedih, marah, kecewa, cemas, takut, dan bingung–perasaan yang tidak pernah berdiri sendiri dan bisa berubah kapan saja.
Menyalahkan diri sendiri cenderung dialami oleh sebagian besar korban KBGO yang datang meminta bantuan. Seringkali, peristiwa yang mereka sampaikan tidak kronologis, barangkali karena terlalu rumit bagi mereka untuk mengartikulasikan kompleksitas perasaan dan fakta. Ada keyakinan yang tidak sepenuhnya bisa mereka utarakan dengan lugas. Meskipun itu tampak konkret, tidak ada lagi bukti yang bisa mereka tunjukkan. Sudah sepatutnya kita mengganti istilah ‘maya’ untuk menamai kekerasan yang ditransmisikan oleh teknologi, sebab bentuk dan dampaknya begitu nyata. Bahkan, kekerasan fisik dan trauma lain juga menyertai, baik sebelum maupun setelah mendapati KBGO. Kekerasan berlapis dan dampak yang terakumulasi itu menjadi salah satu karakter kontinum (keberlanjutan) kekerasan, menurut Liz Kelly dalam bukunya Surviving Sexual Violence.
Lantas, mengapa membahas isu KBGO menjadi semakin relevan hari ini? Jawabannya tidak lain karena jumlah kasus KGBO masih sangat tinggi, meski angkanya fluktuatif. Jenisnya juga semakin beragam seiring perkembangan teknologi. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) misalnya, merilis jumlah kasus KBGO setiap tahun; 6 kasus (2017), 97 kasus (2018), 281 kasus (2019), 940 kasus (2020), 1721 kasus (2021), 2776 kasus (2022), dan 1271 (2023). Melonjak begitu cepat dan fluktuatif, peningkatan jumlah kasus KBGO secara signifikan terlihat selama pandemi COVID-19, yakni antara 2020 hingga 2022. Sepanjang pandemi, interaksi manusia dengan teknologi, khususnya internet, memang lebih intensif. Namun, pandemi bukan satu-satunya faktor penyebab naiknya jumlah kasus KBGO. Jauh sebelum internet muncul, kekerasan berbasis gender sudah ditransmisikan melalui SMS (Short Message Service) dan telepon.
Kini, pengetahuan publik tentang KBGO mulai tumbuh, sehingga istilah ini pun menjadi populer. Pengada layanan juga semakin banyak dan mudah diakses. Semakin banyak korban melapor, catatan aduan juga menunjukkan peningkatan signifikan. Tren tersebut tiba-tiba berubah setelah pandemi, di mana jumlah aduan kasus KBGO mulai menurun. Kita patut berbaik sangka, barangkali hal itu menandakan kalau para korban KBGO sudah mulai bersiasat dan membangun solidaritas di komunitas akar rumput. Mereka punya cara-cara alternatif untuk mewujudkan keadilan yang tidak tunggal. Hal itu tentu menjadi kabar baik mengingat inisiatif mereka membantu lembaga layanan dalam mengelola energi dan sumber daya yang terbatas. Berkat inisiatif itu, kekuatan solidaritas komunitas semakin menguat dan upaya meretas KBGO pun tidak hanya diletakkan pada pundak lembaga pemberi layanan.
Siasat Melawan Narasi Tunggal Keadilan
Garis jingga di sebagian langit menandai sebentar lagi gelap. Saya menuju sebuah warung kopi untuk bertemu dengan salah satu kawan korban KBGO. Sepeda motor berjalan dengan agak lesu, seakan membersamai pikiran saya yang cukup sulit menemukan cara untuk menyampaikan kenyataan pada seseorang itu di warung kopi nanti. Sebagian cerita sudah saya dengar, prediksi kemarahan berapi-api tidak bisa diabaikan begitu saja.
Setibanya di sana, saya bertemu dengan sekawanan orang muda penuh semangat. Mereka menyampaikan rencana strategi untuk membantu korban kembali pulih. Ternyata, seorang kawan korban menghimpun banyak dukungan untuk menyusun langkah bersama, mencoba jalan lain yang belum pernah saya temui pada kasus serupa. Perasaan saya menjadi terang benderang, gelap hanya berlaku untuk suasana malam yang menemani obrolan kami. Mereka bersiasat, saat banyak pihak barangkali masih berjibaku melawan definisi keadilan yang sesat.
Khususnya pada kasus KBGO, orang banyak merujuk pada peraturan perundang-undangan dan penanganan berbasis hukum sebagai acuan keadilan. Terwujudnya keadilan dilihat ketika pelaku sudah ditangkap dan ukuran ganti rugi korban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, indikator keberhasilan sebuah advokasi adalah kebijakan yang memandatkan segala perangkat penegak hukum untuk menjerat pelaku. Benar bahwa pelaku perlu mendapatkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Kita juga perlu merayakan buah dari advokasi panjang dengan terbitnya berbagai aturan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang saat ini sudah disempurnakan melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
Mari kita terus mengingat semangat sekawanan orang muda yang menghimpun donasi terbuka untuk membantu pemulihan finansial korban KBGO akibat pemerasan atas upaya penyebaran orientasi seksualnya; komunitas perempuan di Poso yang melibatkan ketua adat agar pelaku berhenti mengancam, sehingga korban dapat melanjutkan hidupnya dengan tenang. Saya rasa masih banyak siasat lainnya. Tanpa mengecilkan peran dan fungsi dari aturan-aturan hukum, ruang yang sama besarnya juga perlu kita siapkan untuk menghimpun bentuk-bentuk keadilan lainnya, yang barangkali tidak terbesit dalam pikiran kita sebelumnya. Selayaknya penanganan KBGO yang tidak tunggal, definisi atas keadilan pun beragam.
Selama saya mendampingi para korban KBGO bersama TaskForce KBGO, sadar dengan sumber daya yang dimiliki tidak cukup untuk melakukan upaya litigasi, karena keinginan para korban sangatlah beragam. Perasaan cemas, marah, takut, dan kecewa yang mengganggu aktivitas para korban dapat dikelola dengan menyediakan telinga untuk mereka, mengupayakan pengembalian akun, membantu agar pelaku berhenti mengancam, mengupayakan penghapusan konten, dan memulihkan nama baik korban.
Hal itu juga muncul dalam temuan ketika saya menjadi bagian dari riset Rekoleksi Persaudarian: Menamai Kekerasan, Merawat Pemulihan Kolektif bersama PurpleCode Collective. Definisi atas keadilan menjadi sangat luwes. Meski korban menghendaki sebuah tindakan kepada pelaku, keadilan tidak terbatas pada melaporkan pelaku ke polisi dan memenjarakan mereka. Dari proses pendampingan dan riset tersebut, saya berkaca bahwa definisi keadilan perlu melihat keinginan dan kebutuhan korban. Pun, keinginan dan kebutuhan korban harus muncul dari proses asesmen, bukan sekadar melempar satu pertanyaan lalu dijawab dan kita kunci sebagai sebuah kebutuhan absolut. Kondisi marah, cemas, bingung, dan kecewa perlu diregulasi sebelum mengambil keputusan. Korban perlu tahu risiko dan segala kemungkinan yang akan terjadi dari langkah yang mereka pilih. Juga, menjadi kewajiban pendamping untuk menjelaskan berbagai alternatif pilihan berikut konsekuensinya sebelum korban menjatuhkan keputusan.
Itulah, tidak mudah menjadi pendamping, sebaiknya jangan dilakukan sendiri, apalagi hanya oleh satu organisasi. Membersamai satu korban KBGO perlu setidaknya dua hingga tiga orang, agar energi nya terbagi; satu orang berperan mendengarkan dan menemani korban, satu orang menjadi representasi tim pendamping untuk menghadapi pelaku, seorang lainnya akan bertugas atas data dan informasi yang dihimpun agar tetap aman. Meski masing-masing orang memiliki peran utama, segala keputusan dalam pendampingan, termasuk rujukan tetap dibicarakan bersama. Ini hanya gambaran satu kasus, bagaimana dengan banyak kasus yang masuk? Solidaritas dari berbagai pihak, individu maupun kolektif sangat diperlukan untuk meretasnya bersama-sama.
Jurnalisme sebagai Bagian dari Penanganan Holistik
Seorang korban KBGO kerap datang dengan lebih dari satu jenis kekerasan yang menimpanya. Data yang dihimpun TaskForce KBGO tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa hampir semua NCII (Non Consensual Dissemination of Intimate Images atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan) selalu bertaut dengan sextortion (ancaman/pemerasan bernuansa seksual). Begitu juga dengan jenis KBGO lainnya. Tidak jarang ada yang mengalami lebih dari dua jenis KBGO dan lintas platform, bahkan luring. Misalnya, pada kasus pengancaman disertai upaya menyebarkan orientasi seksual seseorang yang bermula dari sebuah aplikasi kencan dan berlanjut pada pemerasan lewat aplikasi pinjaman online (pinjol), identitas pelaku sulit diidentifikasi, sehingga sukar untuk ‘memegang ekor’ pelaku. Situasi itu semakin menggelisahkan karena ancaman yang diberikan juga terus dilakukan melalui WhatsApp.
Melihat kompleksitas KBGO, penanganannya pun tidak boleh tunggal. Selama ini, penanganan kasus KBGO dilakukan melalui pendekatan psikososial, teknologi, dan hukum. Belakangan, khususnya sekitar tiga bulan terakhir, beberapa media sedang gencar melakukan kampanye KBGO melalui panggilan menulis kepada jurnalis dan kontributor tentang KBGO, baik yang dikompetisikan maupun tidak. Upaya itu menyadarkan saya tentang pentingnya media sebagai bagian dari distribusi pengetahuan tentang KBGO.
Penanganan KBGO yang holistik bukan hanya dengan menghukum pelaku dan memulihkan korban, melainkan juga bagasi pengetahuan yang harus terus diperkaya oleh informasi yang tepat untuk melawan disinformasi gender sebagai bagian dari akar… Share on XJika kembali pada definisi keadilan yang tidak tunggal, penanganan yang holistik barangkali bukan hanya dengan menghukum pelaku dan memulihkan korban, melainkan juga bagasi pengetahuan yang harus terus diperkaya oleh informasi yang tepat untuk melawan disinformasi gender sebagai bagian dari akar KBGO. Orang-orang yang terpapar informasi tersebut dapat turut melakukan mitigasi, bahkan menciptakan strategi penanganan alternatif lainnya.
Kerja media dalam mengupayakan strategi penanganan alternatif juga menjadi ruang belajar bagi jurnalis dan perusahaan media tentang ragam keadilan itu sendiri. Hal itu juga menjadi bahan yang bisa terus direfleksikan agar liputan dan terbitan yang mereka kerjakan tidak eksploitatif; alih-alih memberi ruang bersuara, namun luput soal etika.

Eni Puji Utami merupakan anggota dari Jaringan Etnografi Terbuka (JET), sebuah jaringan yang mendorong proses produksi pengetahuan dengan semangat kolaboratif, partisipatif dan inklusif serta menghubungkan peneliti dan komunitas untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Minatnya pada film, sastra, dan kajian budaya semakin berkembang ketika terlibat dalam pengelolaan festival film pada 2012-2021. Ia tidak bisa menandai sejak kapan isu kekerasan berbasis gender menjadi bagian dari kesehariannya, barangkali karena sejak awal tidak ada intensi menjadikannya dekat, tetapi banyak peristiwa yang membuatnya saling bertaut.
Artikel Terkait
Laki-laki dalam Cengkeraman Patriarki
Masyarakat patriarki membayangkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama keluarga, memiliki karakter dominan, tidak emosional, dan tidak rapuh“XX” & “XY” dan Segala Sesuatu yang Mengikutinya
Di artikel ini, Naomi menekankan pentingnya mempertanyakan kembali gagasan-gagasan mengenai gender dan seksualitas yang sering dianggap sudah berterima dan wajar-wajar saja di keseharian kita.Melerai Kekusutan Gender dan Jenis Kelamin
Sebelum seorang bayi lahir, kita sangat terbiasa untuk menanti ‘jenisnya’. Laki-lakikah? Atau perempuan? Begitu tahu, kita sesegera mungkin menentukan warna barang untuknya. Tapi, apa iya jenis kelamin harus menjadi tolak ukur kejantanan atau kewanitaan seseorang?