
Kuasa Bahasa Di Balik Kebijakan Penanganan COVID-19
October 28, 2020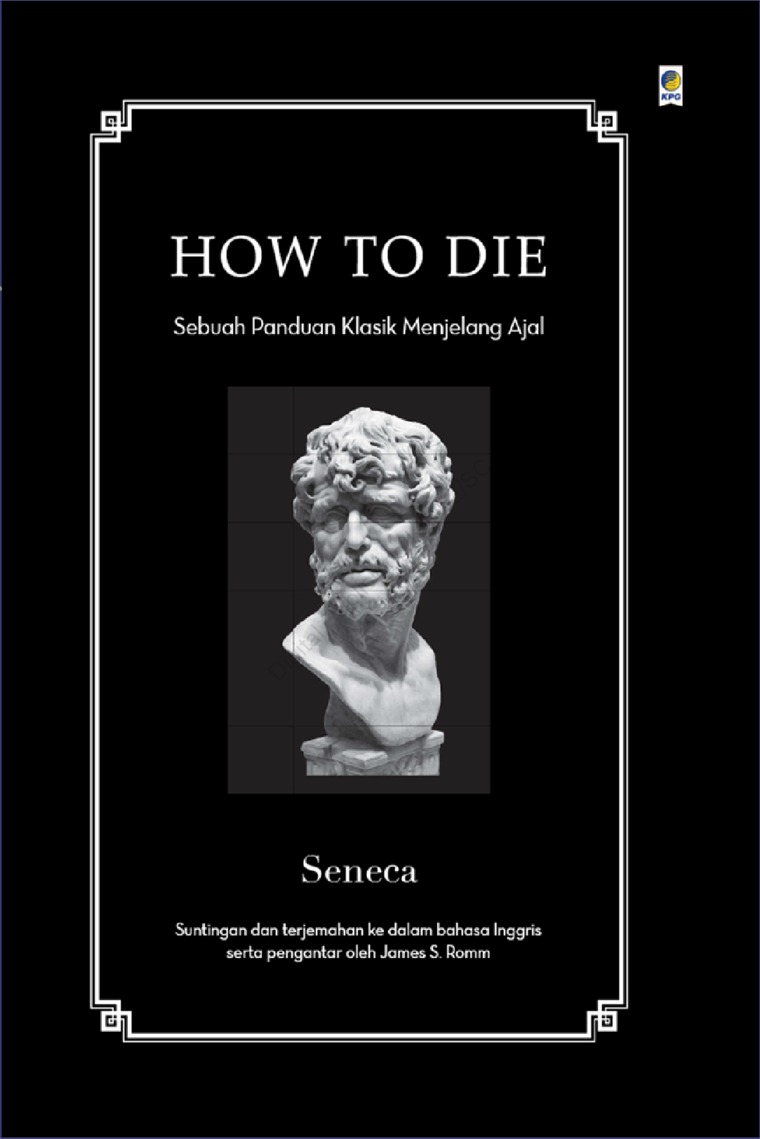
Memperkarakan Kematian
November 6, 2020
OPINI
Jika Membaca Adalah Bentuk Aksi, Lalu Bagaimana Dengan Menulis?
oleh Wahid Kurniawan
Saya tak bisa untuk tidak setuju dengan pernyataan Hestia Istiviani dalam esainya “Membaca adalah Bentuk Aksi” yang menegaskan membaca adalah bentuk aksi yang tak bisa dipandang sebelah mata.
Menurutnya, dengan membaca, kita berupaya untuk lebih peka dan peduli terhadap kondisi yang bahkan belum sempat ada di bayangan kita. Saya pun merasakan sendiri persis seperti yang ia paparkan dalam esainya.
Misalnya, lewat membaca salah satu novel Yoko Ogawa, The Memory Police, saya jadi bisa membayangkan sebuah pulau tak bernama yang terdera perasaan kehilangan hingga berlarut-larut. Di pulau tersebut, penduduknya secara kolektif mengalami hilang ingatan atas benda-benda yang ada di sekitar mereka. Kapal, bunga mawar, pita, parfum, bahkan buku-buku raib dari ingatan para penduduk. Di pulau itu juga terdapat Polisi Kenangan yang bertugas memastikan warganya benar-benar melupakan eksistensi dari benda-benda itu. Bila kedapatan ada orang yang masih mengingat benda-benda tersebut, mereka akan dibawa pergi oleh Polisi Kenangan.
Novel itu memang tergolong sebagai distopia, yakni sebuah cerita yang melibatkan tempat imajiner penuh keburukan. Tapi, lewat novelnya itu, Yoko Ogawa ingin menyodorkan kenyataan dalam fiksinya tentang bagaimana manusia kerap melupakan makna dari benda-benda di sekitarnya. Benda yang kerap tidak dipandang spesial, sesungguhnya memiliki arti, sekecil apa pun itu. Sejalan dengan pernyataan Hestia di awal tadi, aksi yang lantas saya pikirkan dari membaca novel tersebut adalah untuk menghargai eksistensi dari banyak benda serta kenangan yang dibawanya. Sebab, mereka berperan dalam memberi warna di kehidupan yang saya jalani ini.
Masalah membaca selesai sampai di situ. Selanjutnya, saya jadi memikirkan, kalau membaca adalah bentuk aksi, lalu bagaimana dengan menulis? Barangkali, sebagian dari pembaca sudah menjawab pertanyaan itu bahkan sejak membaca judul tulisan ini. Kurang lebih jawabannya begini, “Menulis adalah bentuk aksi juga, dong! Bahkan, lebih nyata lagi, kawan. Sebab kata-kata bisa menjelma menjadi pedang!”
Baik, baik, saya tak mendebat jawaban tersebut. Menulis, sebagaimana membaca, memang bisa memberi pengaruh, jawaban, dukungan, bahkan memantik sebuah perubahan. Itu semua bukan omong-kosong belaka. Tulisan bisa memengaruhi seseorang atau kelompok dalam berpikir dan menentukan sikap. Sebaliknya, dari tulisan buruk seperti narasi hoaks, bisa juga memicu kegaduhan yang tingkat bahayanya tak main-main.
Sampai sini, mungkin pembaca bertanya lagi, “Lalu di mana jawabanmu? Untuk apa tulisan ini dibuat kalau jawabannya sama?”
Benar, jawaban saya memang hampir sama dengan yang saya terka tadi. Namun, untuk menjawab pertanyaan itu, saya lebih suka menggunakan kalimat, “Menulis adalah bentuk perpanjangan dari aksi.” Saya katakan begitu karena di mata saya kedudukan menulis satu tingkat lebih tinggi dari membaca. Dengan menulis, kepekaan dan kepedulian atas apa yang kita dapat dari sebuah bacaan bisa tersalurkan.
Misalnya, setelah membaca novel Yoko Ogawa tadi, saya jelas tak ingin situasi ketika buku-buku lenyap dan dianggap tak bernilai benar-benar terjadi di dunia nyata. Ditambah lagi, saya sadar bahwa budaya membaca buku masih belum dilakukan secara baik di lingkungan pertemanan saya. Oleh karena itu, setelah membaca sebuah buku—apalagi buku yang luar biasa bagusnya, saya selalu tergerak untuk menuliskan ulasan dari buku tersebut, baik berupa catatan singkat maupun telaah panjang, supaya orang lain bisa ikut merasakan sedikit percikan dari pengalaman membaca yang mengasyikkan itu.
Yah, walaupun apa yang saya tulis itu lebih sering tak mendapat sambutan yang antusias, tetapi tak sia-sia juga. Sebab biasanya, setelah mengunggah catatan atau ulasan di media sosial, atau suatu kali mereka membacanya di sebuah media cetak dan online, ada saja teman yang bertanya soal buku yang habis dibaca itu. Benar, beberapa teman saya itu jadi turut penasaran dan berniat membacanya. Nah, dengan begitu, aksi yang saya lakukan pada akhirnya tidak berhenti di saya saja, kan?
Itu baru contoh kecil dan sederhana. Bentuk dari perpanjangan aksi itu masih banyak wujudnya. Satu contoh besar, sebulan ke belakang dunia kesusastraan kita sempat memanas. Dalam sebuah penghargaan tahunan, yakni penganugerahan sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud yang diumumkan September kemarin, yang keluar sebagai juara tahun ini—lagi-lagi—adalah karya dari para penulis laki-laki. Hal itu lantas menimbulkan polemik yang memang sedari lama mendera, bahwa apa betul dari sekian banyak karya penulis bukan laki-laki tidak ada yang layak menduduki penghargaan tersebut?
Beberapa penulis perempuan mempertanyakan keputusan penghargaan itu, sebut saja Anindita S. Thayf yang dengan tajam membeberkan penganugerahan tersebut sebagai cerminan kondisi kesusastraan kita yang kental dengan unsur patriarkinya. Kata Anindita, lewat politik penghargaan tersebut, terbaca dengan jelas bahwa pengarang laki-laki lebih superior daripada pengarang perempuan.
Saya sepakat. Saya rasa banyak karya para penulis perempuan yang layak dan baik untuk masuk dalam penganugerahan tersebut. Setidaknya, itulah kesadaran yang ada pada dirinya setelah membaca beberapa karya para penulis perempuan tanah air selama ini. Namun, fokus saya bukan dari kesadaran pribadi itu, melainkan kesadaran kolektif yang juga dirasakan oleh banyak orang di luar sana. Dari pengamatan saya, tidak sedikit pihak-pihak yang menyadari ketimpangan ini, sehingga mereka yang memang bergerak di ranah perbukuan, baik para penulis maupun penerbit, belakangan ini banyak menghadirkan karya-karya dari para penulis perempuan.
Banyaknya kanal media massa, baik cetak maupun online, menjadi medium yang tepat untuk menyuarakan kepekaan, kepedulian, atau perlawanan kita. Masalahnya, kita mau atau tidak? ~Wahid Kurniawan Share on XStrategi tersebut memang tidak langsung membuahkan hasil berupa masalah yang lekas terselesaikan, tetapi keberadaannya bisa mengubah tatanan yang sudah sedemikian mengakar ini. Maka dari itu, dikarenakan kepekaan atas kondisi yang timpang dan tak adil, para penulis perempuan di luar sana mencoba mengatasinya dengan tulisan-tulisan terbaik mereka.
Jika saya membandingkan mereka yang berjuang melawan ketidakadilan dalam dinamika kesusastraan dengan apa yang saya lakukan, rasanya memang terpaut jauh sekali. Tapi, kalau dipikir-pikir, kita toh punya kapasitasnya masing-masing, kan? Kepekaan yang saya sadari kebetulan mengenai rendahnya budaya membaca di lingkungan pertemanan saya, sehingga kapasitas yang dapat saya lakukan, ya, sekadar tindakan kecil seperti yang disebutkan tadi. Sementara terhadap yang ada di luar sana, saya percaya, setiap orang yang tergerak membaca buku bakal menemukan perpanjangan dari aksi yang sudah ia lakukan itu. Perpanjangannya, tentu saja, disalurkan lewat tulisan-tulisan. Dan, bukankah perpanjangan aksi ini telah banyak dilakukan? Bagi mereka yang akrab dengan tema-tema tertentu, seperti feminisme, tentu sering menggaungkan perlawanan terhadap ketidakadilan melalui tulisan-tulisan yang tajam nan menggugah. Belum lagi bagi yang mengakrabi ilmu ekonomi, politik, atau sosial, mereka pun kerap menampilkan ide-ide cemerlang dalam bentuk tulisan-tulisan.
Oleh karena itu, saya selalu percaya apapun latar belakang dan bahan bacaannya, kita sangat bisa memperpanjang aksi seperti contoh-contoh tadi. Kondisi saat ini pun sedemikian memudahkan kita. Sekarang ini, kita mengenal dengan baik media sosial, belum lagi banyaknya kanal media massa baik cetak maupun online, dan itu semua menjadi medium yang tepat untuk menyuarakan kepekaan, kepedulian, atau perlawanan kita. Masalahnya, kita mau atau tidak?

Wahid Kurniawan, pembaca buku yang tak tahan godaan. Saat ini tengah menempuh pendidikan Sastra Inggris di Universitas Teknokrat Indonesia. Ia bisa dihubungi melalui Twitter dan Instagram: @karaage_wahid
Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini







