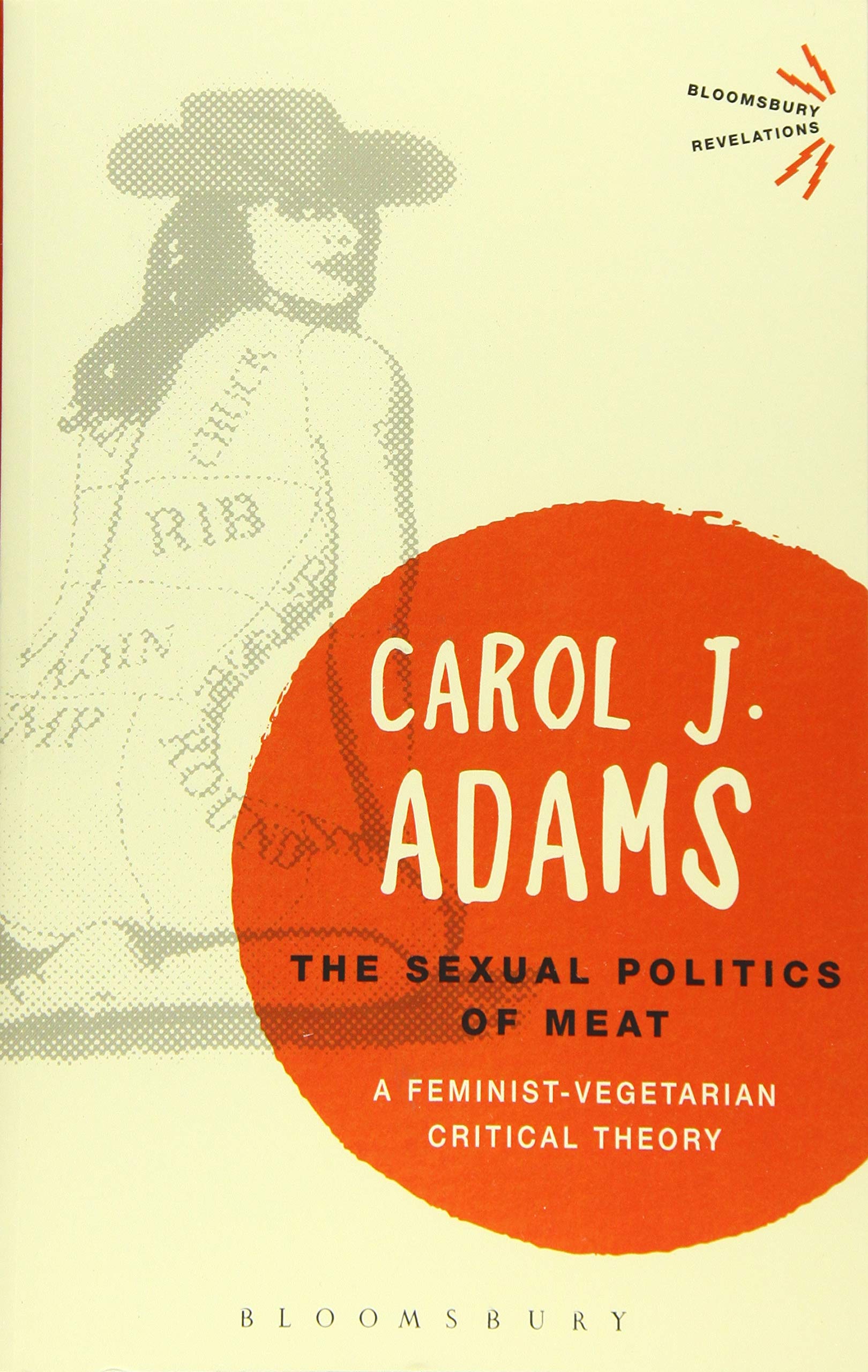
Sexual Politics of Meat karya Carol J. Adams
November 10, 2020
Rancangan Kolonial, Subsistensi, dan Tata Kota Indonesia Pascawabah
November 27, 2020
OPINI
Kamala Harris dan Dimensi Kelas yang Kita Lewatkan
oleh Abdullah Faqih
Atmosfer pesta demokrasi di Amerika Serikat terasa tensinya sampai ke Indonesia. Warga Indonesia, sebagaimana juga warga dunia lainnya, kini sedang menyoroti kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat.
Meskipun tinggal di tempat yang jauhnya ribuan kilometer, hal itu tidak menghalangi kita untuk ikut meramaikan perbincangan hangat soal kemenangan Biden dan Harris. Sebelum keduanya terpilih, banyak di antara kita yang bahkan juga turut mengekspresikan pilihan politiknya: memilih Trump atau Biden?
Rasanya memang masuk akal, mengingat Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai negara super power. Memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang sedemikian hebat membuat Amerika Serikat dianggap seolah-olah adalah penguasa dunia. Para pakar percaya bahwa berbagai kebijakan ekonomi dan militer yang diambil oleh penguasa Amerika Serikat secara tidak langsung akan berkontribusi menentukan nasib warga negara di belahan dunia lainnya. Tidak salah apabila kita pun merasa perlu untuk ikut mencurahkan perhatian pada pertarungan politik di negeri itu.
Dari sekian banyak hal-hal penting soal pemilihan umum di Amerika Serikat, terpilihnya Kamala Harris sebagai wakil presiden adalah satu hal yang paling menarik untuk didiskusikan. Harris disebut sebagai perempuan pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang berhasil menduduki kursi sebagai wakil presiden. Selain itu, Harris juga adalah seorang berkulit hitam sekaligus seorang Asian-American (birasial). Interseksi ketiga identitas Harris itu menjadi sesuatu yang berarti, mengingat isu soal warna kulit, identitas gender, dan ras selama ini masih kerap dijadikan pembenaran untuk peminggiran dan opresi—bahkan di negara seperti Amerika Serikat sekalipun.
Maka, ketika Harris meraih kemenangan sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat, hal itu dipandang sebagai bentuk keberhasilannya dalam menghancurkan penghalang (barrier) atas posisi politik tertinggi di Amerika Serikat yang selama ini dicengkeram dalam bias laki-laki berkulit putih (selain Barack Obama). Hal itu pula yang membuat kelompok feminis liberal, pejabat publik di berbagai negara, hingga aktivis pejuang hak-hak kelompok minoritas untuk ikut larut merayakan kemenangan Harris. Mereka memandang bahwa kemenangan Harris telah memberikan harapan kepada perempuan minoritas lainnya: berakhirnya opresi dan peminggiran seolah-olah sudah semakin dekat. Dengan kata lain, perempuan minoritas juga memiliki kekuatan untuk meruntuhkan tembok-tembok ketidakadilan yang selama ini mengurung mereka di ‘ruang bawah tanah.’ Sinyal kuat itu tidak hanya ditangkap oleh perempuan minoritas di Amerika Serikat, melainkan juga tersebar ke seluruh penjuru dunia.
Kemenangan Harris yang disebut-sebut mewakili perempuan minoritas itu memang patut untuk dirayakan. Tetapi, kita juga tidak boleh melewatkan sesuatu yang lebih penting dari sekadar keterwakilan atau representasi, yaitu perihal dimensi kelas sosial dan politik meritokrasi.
Tanpa mengurangi rasa hormat atas perjuangan dan kapasitas Harris, saya berpikir bahwa penting juga untuk melihat berbagai keuntungan (privilese) yang telah dinikmati Harris dan berkontribusi membentuk dirinya menjadi seperti sekarang ini. Sepak terjang Harris di dunia politik yang telah dimulainya sejak puluhan tahun silam memang tidak perlu diragukan. Ia bahkan telah bertransformasi menjadi sosok yang kritis (dan politis) sejak berusia 13 tahun. Ia kemudian melesat menjadi aktivis, jaksa, dan senator yang gigih membela hak-hak warga kulit hitam dan perempuan. Memakai kacamata Pierre Bourdieu tentang habitus, modal, dan arena, kehebatan Harris itu tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan sosialnya (terutama keluarga) dan berbagai kapital yang dia miliki sejak awal.
Fakta mengenai latar belakang keluarga Kamala Harris sebagai imigran dan kelompok minoritas yang mencari penghidupan di Amerika Serikat adalah hal yang tidak terbantahkan. Namun, fakta lain bahwa keluarga Harris adalah kelompok minoritas yang pada akhirnya memperoleh berbagai keuntungan sosio-kultural—pendidikan, ilmu pengetahuan, dan akses ke ruang publik—adalah sesuatu yang juga tidak boleh dilewatkan. Ayah Kamala Harris, Donald J. Harris, adalah seorang doktor ilmu ekonomi dari salah satu perguruan tinggi terbaik di Amerika Serikat, University of California at Berkeley (UC Berkeley). Ia kemudian menjadi profesor emeritus di bidang ilmu ekonomi di Stanford University dan telah banyak menyumbangkan analisis untuk sektor perekonomian di negara asalnya, Jamaika. Ibu Kamala Harris, Shyamala Gopalan, juga bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang yang menduduki salah satu kasta tertinggi dalam kepercayaan Hindu di India, Tamil Brahmin. Gopalan juga meraih pendidikan setingkat master dan doktoral di UC Berkeley dalam bidang ilmu gizi dan endokrinologi (cabang ilmu kedokteran yang mempelajari gangguan sistem endokrin), sebelum akhirnya bekerja sebagai ahli penyakit kanker payudara di institusi yang sama.
Terlalu larut merayakan kemenangan Harris dan sepenuhnya memercayakan keterwakilan perempuan minoritas kepadanya akan membuat kita jadi kabur dalam melihat dimensi kelas sosial. ~A. Faqih Share on XSejak masih mengenyam pendidikan tinggi, kedua orang tua Kamala Harris juga sangat giat memperjuangkan hak-hak kelompok kulit hitam. Hal itu yang kemudian ikut memengaruhi Kamala Harris dan saudara perempuannya, Maya Harris, menjadi sosok yang juga aktif terlibat untuk mengadvokasi isu serupa. Artinya, kita dapat mengatakan bahwa Kamala Harris sesungguhnya adalah perempuan minoritas yang tidak benar-benar lahir dari ‘kantong-kantong penderitaan.’ Jika melihat latar belakang keluarganya, berbagai keuntungan sosio-kultural itu sebenarnya juga sudah ditakdirkan menjadi miliknya. Dia tinggal di lingkungan yang mampu mendukungnya tumbuh menjadi versi terbaik dirinya. Terbukti, Kamala Harris berhasil menamatkan pendidikan di bidang ilmu politik dan ekonomi di Howard University, salah satu perguruan tinggi paling bersejarah bagi masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Ia juga berhasil meraih gelar juris doctor (gelar untuk para profesional di bidang hukum) dari University of California, Hastings College of the Law. Dengan demikian, Kamala Harris sejak awal telah memiliki berbagai kapital sosial dan kultural yang amat menguntungkan. Kapital-kapital itu tentu saja tidak dinikmati oleh semua perempuan, terlebih lagi perempuan minoritas seperti dirinya.
Saya berpikir bahwa terlalu larut merayakan kemenangan Harris dan sepenuhnya memercayakan keterwakilan perempuan minoritas kepadanya akan membuat kita jadi kabur dalam melihat dimensi kelas sosial. Berhenti pada keterwakilan atau representasi saja juga akan menjadikan kita luput untuk mempertimbangkan bahwa ada banyak sekali perempuan lain di luar sana—yang tidak ditakdirkan memiliki kesempatan dan menikmati berbagai keuntungan seperti Kamala Harris—yang masih terjebak di ruang bawah tanah. Hal itu senada dengan apa yang ditulis oleh Nancy Fraser dalam bukunya Feminism for the 99%. Menurut Fraser, pengakuan dan keterwakilan hanya memungkinkan segelintir perempuan istimewa yang sudah memiliki keuntungan sosial, budaya, dan ekonomi cukup besar untuk naik ke berbagai posisi yang setara dengan laki-laki. Politik meritokrasi yang memberikan penghargaan pada perempuan-perempuan berbakat semacam itu tentu saja hanya akan menguntungkan kelompok dari kelas sosial mereka sendiri. Feminisme yang tujuan utamanya adalah memperjuangkan keadilan sampai pada akar-akarnya jadi tersamarkan oleh figur-figur perempuan istimewa yang dianggap sebagai representasi dari keberhasilan gerakan feminisme. Jika sudah demikian, alih-alih ‘kemenangan’ itu semakin dekat, cita-cita feminisme justru semakin jauh.
Menurut saya, kemenangan Kamala Harris cukup perlu dipandang sebagai momentum untuk menjadikan gerakan perempuan menjadi semakin militan dalam memperjuangkan keadilan yang lebih substansial. Sejenak, bolehlah kita ikut hanyut merayakan kemenangan Harris. Kita juga boleh ikut meletakkan harapan di pundak Harris soal keterwakilan perempuan minoritas yang sedang berjuang melawan peminggiran. Tetapi, kita juga harus sepenuhnya sadar bahwa, meminjam istilah Nancy Fraser dalam Feminism for the 99%, Kamala Harris hanyalah 1% perempuan istimewa yang telah dilimpahi berbagai macam privilese sejak awal. Sementara itu, masih ada 99% perempuan lain yang hak-haknya masih perlu untuk terus diperjuangkan. Akan menjadi sia-sia apabila sekarang kita terlalu larut merayakan kemenangan Harris, tetapi Harris ternyata menjadi bagian dari sistem dan struktur yang mengopresi kehidupan perempuan. Saya tentu saja tidak berharap demikian, mengingat Harris sendiri memastikan di dalam pidato kemenangannya, “…Untuk membasmi rasisme sistemik yang ada dalam sistem peradilan dan masyarakat kita… Meski saya mungkin perempuan pertama di jabatan ini, saya tidak akan menjadi yang terakhir.”
Memang, keberhasilan Harris merebut kursi Wakil Presiden Amerika Serikat tidak akan berdampak langsung pada kehidupan kita yang tinggal di ribuan kilometer jauhnya dari benua Amerika. Tetapi, menurut saya, kita tetap perlu menjadikan fenomena kemenangan Kamala Harris ini sebagai momentum untuk tidak berhenti memandang ‘keberhasilan’ gerakan perempuan dari segi keterwakilannya saja, melainkan juga tidak melupakan perempuan-perempuan lain yang hidup dalam struktur kelas sosial yang tidak menguntungkan dan pengalaman mereka yang beraneka ragam. Tidak kalah penting dari itu, kita juga perlu memastikan bahwa selain keterwakilan segelintir perempuan istimewa itu dapat merobohkan sistem yang opresif dan menindas, namun juga dapat membuka peluang bagi lebih banyak perempuan lainnya untuk ikut terlibat di dalam gerakan.

Abdullah Faqih, sedang bersekolah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini







