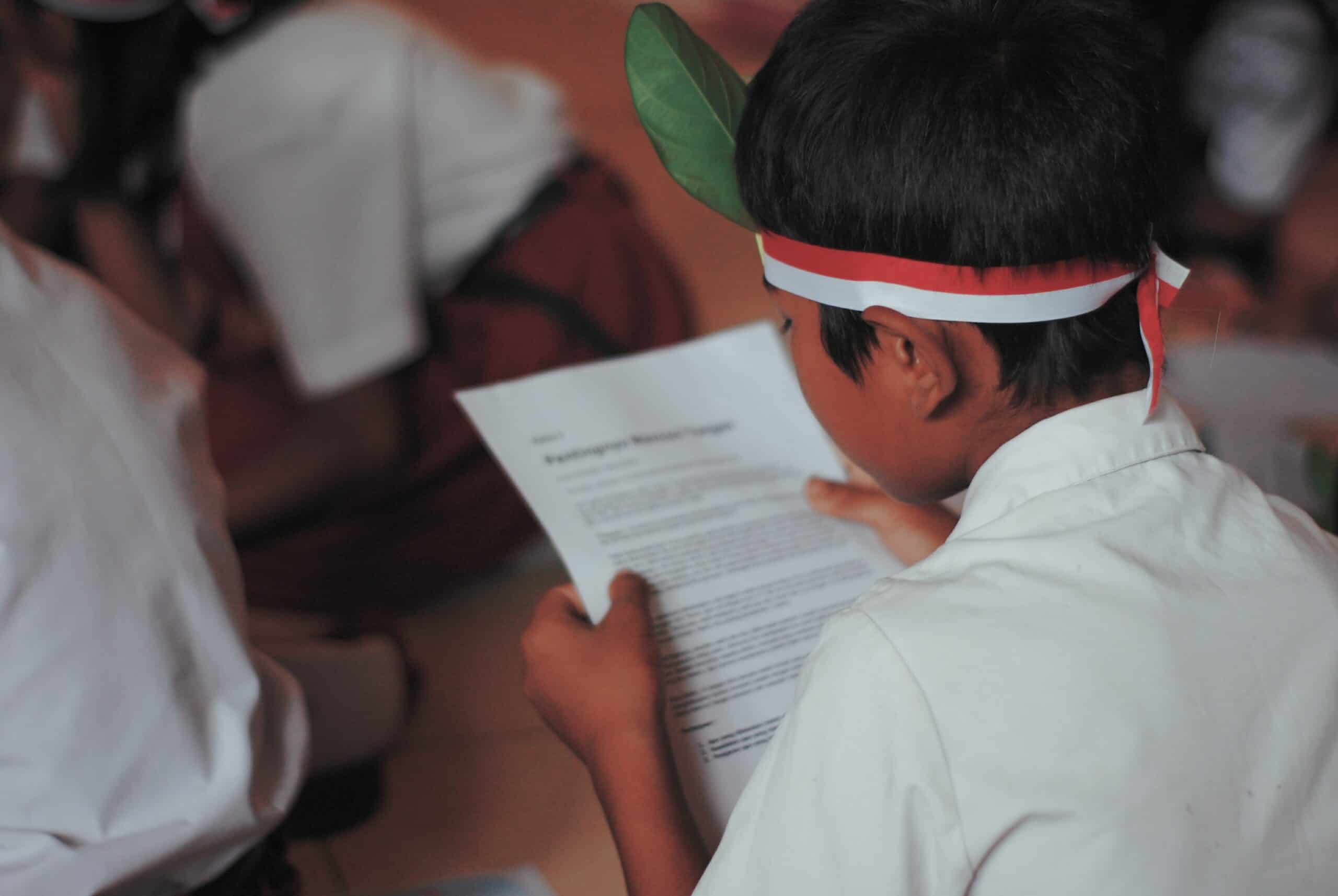
Hakikat Pendidikan yang Hampir Terlupakan
March 28, 2022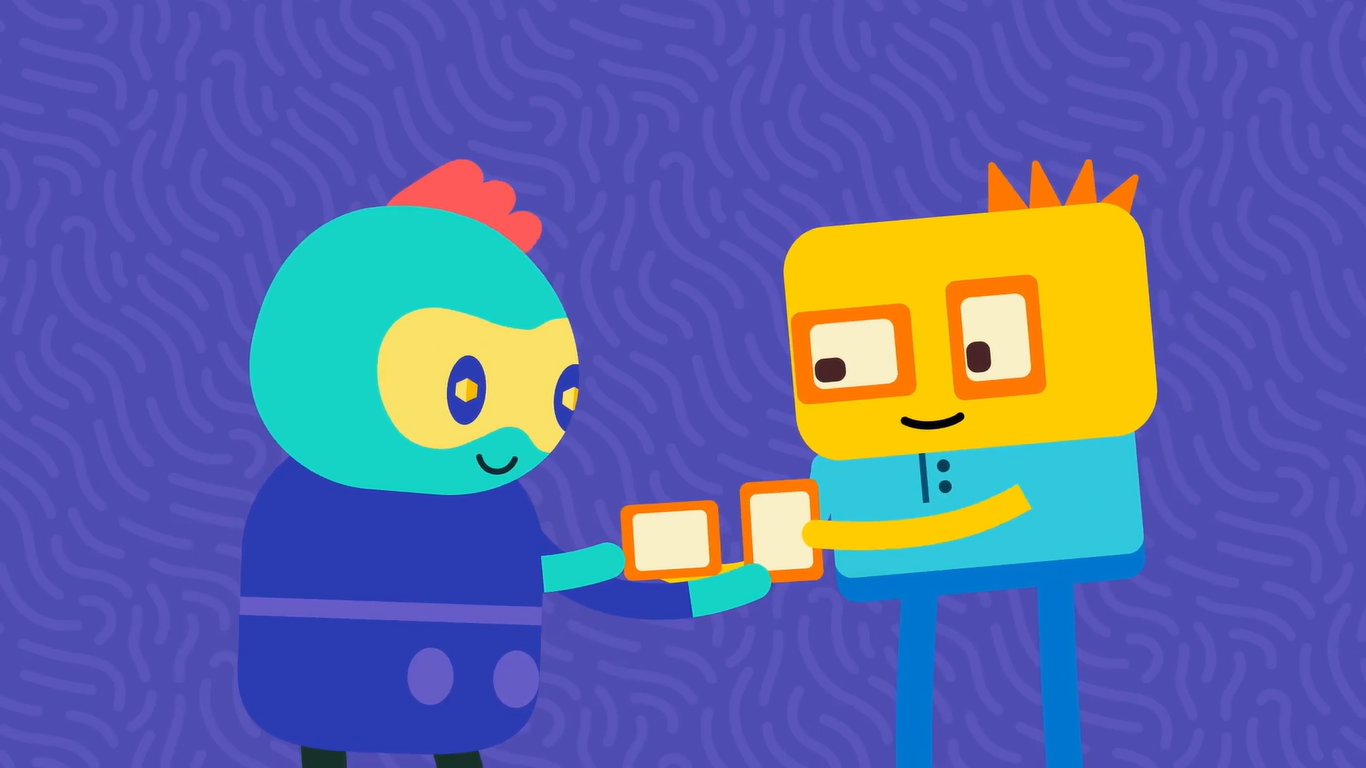
Di Balik #SeribuLensa bersama Artgenie
April 15, 2022
OPINI
Seperti Dendam, Dominasi Harus Diredam Tuntas
oleh Si Luh Ayu Pawitri
Berlatar belakang akhir tahun 80-an, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas menjadi sebuah film percintaan yang memiliki gaya yang seratus persen berbeda. Film ini membawa narasi besar tentang maskulinitas, tidak hanya terselubung, namun juga muncul dalam tiap adegan yang ada. Latar kekerasan di sepanjang film menjadi sebuah budaya yang tumbuh karena orde pemerintahan yang mengamini kekerasan pula. Kasus-kasus kekerasan seksual dan objektifikasi perempuan karena dominasi yang terjadi antar sesama manusia pun terlihat gamblang dalam film ini.
Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas bagi saya adalah kumpulan trauma individu dan trauma kolektif yang ditata dengan plot yang begitu kompleks.
Film dimulai dengan kisah preman Bojongsoang yang tak bisa ereksi. Ereksi menjadi ciri maskulinitas dalam kehidupan masyarakat kita. Seolah kejantanan paling utama diukur dari seberapa bisanya kelamin Anda “berdiri”. Lelaki yang tak bisa ngaceng itu bernama Ajo Kawir. Ajo tak memiliki ketakutan pada apapun. Ia suka berkelahi, balapan liar, dan sesekali membunuh orang dengan beberapa alasan.
Hasrat berkelahinya sangat tinggi, namun hanya karena ia tak bisa ereksi, kejantanannya dipertanyakan dan dijadikan olok-olok. Ia memperoleh stigma dari lingkungannya hingga kehilangan rasa percaya diri ketika memulai hubungan dengan perempuan bernama Iteung.
“Apa yang akan kau lakukan dengan laki-laki yang tak bisa ngaceng?” tanya Ajo pada Iteung.
Kerasnya “Dunia Laki-Laki”
Berlatar belakang akhir tahun 80-an, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas menjadi sebuah film percintaan yang memiliki gaya yang seratus persen berbeda. Tekstur grain dan jadul yang dihadirkan melalui kamera film 16mm ini menambah apik karya garapan Edwin yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama oleh Eka Kurniawan.
Musik-musik yang dihadirkan juga dipilih untuk mendeskripsikan suasana 80-an, namun juga tak membatasi gerak imajinasi kita hanya sebatas pada genre yang populer pada saat itu. Lagu dangdut saat nikahan Ajo dan Iteung, lagu rock seperti Laron-Laron dari Makara juga menjadi pemanis yang tak berlebihan.
Sejak awal film ini memang membawa narasi besar tentang maskulinitas, tidak hanya terselubung, namun juga muncul dalam tiap adegan yang ada. Balas dendam Ajo dengan Pak Lebe, perkelahiannya dengan Budi, dan pembunuhan yang ia lakukan. Hanya satu adegan perkelahian yang bisa dinikmati, yaitu ketika ia berkelahi dengan Iteung. Ajo dan Iteung memang saling pukul, namun ada gestur lain yang coba diungkapkan Ajo (Marthino Lio) dan Iteung (Ladya Cheryl) dalam film ini.
Dominasi Harus Diredam, Tuntas
Latar kekerasan di sepanjang film menjadi sebuah budaya yang tumbuh karena orde pemerintahan yang mengamini kekerasan pula. Terbukti di beberapa adegan diceritakan bahwa pensiunan militer menjadi orang yang kejam, pemerkosa, dan pembunuh. Cerita ini tumbuh sejak Ajo dan kawannya Tokek melewati masa kecilnya.
Tak dapat dipungkiri Ajo yang sekarang adalah Ajo yang tumbuh dari masa lalu tersebut. Banyak sekali trauma yang harus dilewati, sampai pada saat ia bertemu Iteung, trauma tersebut seolah tak hanya dimiliki oleh satu pihak. Inilah yang saya sebut sebagai pengalaman kolektif yang terjadi akibat trauma masing-masing individu dalam wajah pemerintah Orde Baru kala itu.
Potret Soeharto juga secara gamblang muncul dalam berita di surat kabar, himbauan yang harus dipercayai masyarakat kala pemerintah mengumumkan fenomena gerhana matahari pada tahun 1983. Masyarakat tak boleh berada di luar rumah dan tak boleh menatap gerhana agar mereka tak mengalami kebutaan. Himbauan itu seolah menjadi keramat dan dipercaya.
Pada saat itu Gerhana Matahari Total (GMT) hanya terjadi di Pulau Jawa, suasana mencekam dirasakan masyarakat. Di tengah gelapnya situasi tersebut, negara juga hadir menjadi hantu menakutkan, menghimbau masyarakat untuk masuk ke rumah. Himbauan ini sangat instruksional sehingga menimbulkan beberapa distorsi informasi, padahal GMT masih dapat disaksikan dengan pelindung khusus agar tidak menyebabkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana negara menjadi alat yang sangat canggih dalam mendominasi wacana publik kala itu.
Bangun, Bajingan!
Saya benci mengakui bahwa dalam film ini kasus-kasus kekerasan seksual juga terjadi. Dominasi yang terjadi antar sesama manusia lagi-lagi menyebabkan posisi perempuan sebagai yang dieksploitasi. Dari sistem yang toksik, dari sistem yang diktator. Artinya bahwa sejak zaman dahulu pun objektifikasi pada perempuan terjadi. Dewi Candraningrum menjelaskan bahwa dalam kacamata media, perempuan lebih banyak direpresentasikan sebagai objek berita ketimbang aktor, pembuat, dan subjek berita.
Dominasi yang terjadi antar sesama manusia lagi-lagi menyebabkan posisi perempuan sebagai yang dieksploitasi. ~Si Luh Ayu Pawitri Share on XObjektifikasi perempuan dalam sistem yang diktator pun lebih terlihat gamblang, perempuan kerap dianggap sebagai pendukung suaminya. Orde Baru menggambarkan itu melalui wajah PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Perempuan dianggap sebagai tiang penting dalam stabilitas keluarga bahkan negara. Hal ini yang kemudian menjadikan perempuan sebagai “alat” atas lingkungannya.
Dalam sebuah scene, tak secara gamblang, Ajo mengisyaratkan bahwa ia tak mau berurusan dengan perempuan. Seolah urusan dengan perempuan hanya hal-hal di luar ranah publik; ranjang misalnya. Saya tak menyalahkan Ajo atau lelaki yang tumbuh dalam budaya patriarki. Karena sebenarnya laki-laki juga mendapat imbas dari pandangan patriarki ini. Bahwa lelaki secara naluriah dan alamiah haruslah ngaceng menunjukkan betapa rapuhnya maskulinitas itu. Laki-laki pun harus tunduk pada sistem yang diciptakan selama ini tentang standardisasi kejantanan itu sendiri.
Bahwa lelaki secara naluriah dan alamiah haruslah ngaceng menunjukkan betapa rapuhnya maskulinitas itu. ~Si Luh Ayu Pawitri Share on XEdwin berhasil mengemas film ini sebagai kisah cinta yang absurd, namun romantis secara bersamaan. Di satu sisi, Edwin membuat saya lupa bahwa yang utama dalam film ini sebenarnya adalah kisah cinta Ajo dan Iteung. Runyamnya situasi politik pada saat itu, mencuatnya kekerasan membuat kisah cinta mereka seolah menjadi hal yang harus disingkirkan dahulu. Padahal, hadirnya cinta di antara merekalah yang membangkitkan dendam dan kekerasan yang ada pada diri mereka.
Pengorbanan yang dilakukan keduanya cukup untuk membuktikan betapa mereka sebagai individu hanyalah korban dari sistem yang manipulatif. Trauma masa lalu juga membuat mereka jengah untuk membalaskan dendamnya. “Hantu-hantu” masa lalu akan hadir menagih janji. Itu semua terbukti dan berhasil diwadahi dalam film ini.
Premanisme, pembunuhan, perkosaan, dan sedikit wajah pabrik yang mengambil potret di wilayah Rembang (pantura) menjadi sesuatu yang politis. Ternyata pemerintahan Soeharto pada saat itu meninggalkan trauma yang menjadi budaya kekerasan di akar rumput.
Pembangunan juga menjadi sesuatu yang marak dilakukan, yang sampai saat ini menyisakan banyak kerusakan lingkungan. Meski ini tak berjalan serta-merta, namun benang merahnya dapat ditarik. Pembangunan telah menggerogoti masyarakat akar rumput dan lingkungannya, seperti perlawanan petani Kendeng terhadap pabrik semen yang masih diperjuangkan sampai hari ini.
Dominasi telah usai, saatnya ia diredam tuntas. Layaknya dendam yang sudah terbayarkan, dominasi juga seharusnya dimusnahkan dari muka bumi. Agar tiada lagi dominasi terhadap sesama manusia, bahkan alam dan makhluk hidup yang ada di bumi.
Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas | Sutradara: Edwin | 2021 | Indonesia

Si Luh Ayu Pawitri, perempuan yang lahir dan besar di Bali serta sehari-hari bekerja di NGO Lingkungan. Menulis membuatnya hidup.
Dapat dihubungi melalui akun sosial media Instagram: @sayupawitri dan Twitter: @sayupawitri
Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini







