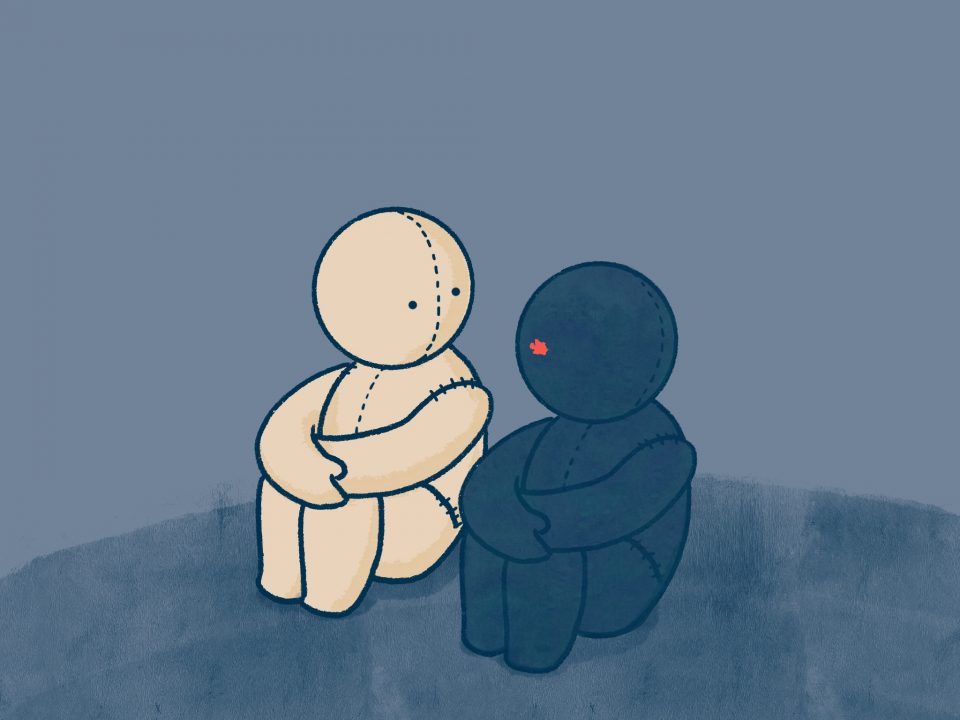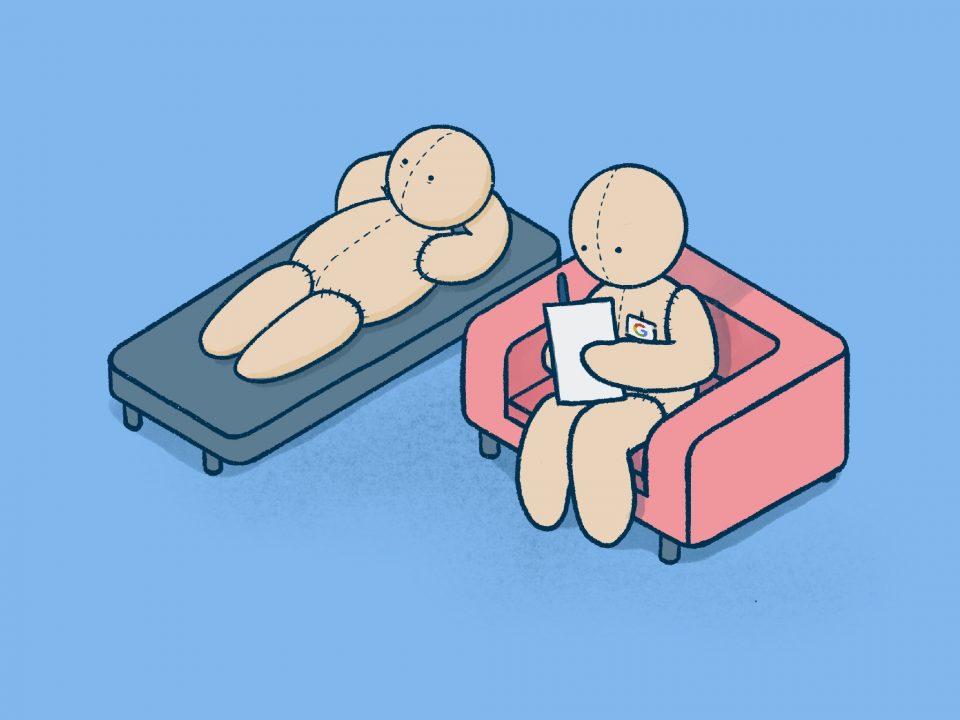Memaknai Politik melalui Kacamata Mereka yang Teropresi
October 23, 2023
Biarkanlah Anak Bermimpi!: Menyingkap Makna Keluarga
October 31, 2023
Photo by Jacopo Maia on Unsplash
OPINI
Dari Manakah Makanan Kita Berasal?: Refleksi Kritis tentang Pangan
oleh Monika Swastyastu
Sehari-hari, kita selalu dihadapkan pada pertanyaan “makan apa?” disertai dengan pertimbangan-pertimbangan atas pilihan makan kita.
Terkadang, pilihan makan itu jatuh pada makanan yang praktis, cepat, dan hemat. Terkadang juga mengikuti suasana hati (mood) sebagai pelampiasan atas hari yang buruk atau sebagai apresiasi diri (self reward) atas terlaluinya sebuah pencapaian. Tidak jarang pula, pilihan makan itu bergantung pada apa yang muncul pada FYP (For You Page) sosial media kita.
Terdengar sangat sederhana, tapi seperti kata pepatah “you are what you eat (kamu adalah apa yang kamu makan)”, sosiolog terkemuka Pierre Bourdieu juga menjelaskan bahwa selera makan bukan hanya soal pilihan pribadi, tapi juga dapat mencerminkan dinamika kekuasaan, struktur sosial, dan penanda kelas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan makan sehari-hari tidak sesederhana yang kita bayangkan.
Obsesi terhadap Beras dan Ilusi Swasembada Pangan
“Belum kenyang jika tidak makan nasi” adalah istilah yang sering kita dengar. Beras, hingga saat ini, masih menjadi salah satu makanan pokok yang dikonsumsi paling tinggi di Indonesia. Pada 2022, beras yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sebanyak 81,044 kilogram per kapita per tahun. Dibagi 365 hari dalam setahun, maka rata-rata setiap orang di Indonesia mengonsumsi 0,222 kg beras dalam sehari.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprediksi, salah satu dampak El Nino yang melanda tahun 2023 membuat produksi beras nasional berkurang 5 persen. Selain faktor tata kelola dan geopolitik global, penurunan produksi beras nasional ini memicu melonjaknya harga beras hingga mencapai rekor tertinggi.
Menjadi lebih memprihatinkan ketika tren konsumsi terigu meningkat, dimana pada 2020 mencapai 26,6 persen dan meningkat mencapai 28 persen pada 2021. Jika tren ini tumbuh terus, pada 2050, konsumsi terigu sebagai pangan pokok Indonesia bisa mendekati 50 persen dan itu seluruhnya didapatkan dari impor pangan.
Kefanatikan kita terhadap beras tidak lepas dari program revolusi hijau yang digagas oleh Presiden Soeharto pada 1970-1980 dengan tujuan menggenjot produksi beras nasional lewat peningkatan produktivitas pertanian (program intensifikasi). Sayangnya, inisiatif itu berdampak buruk pada lingkungan hidup, seperti menimbulkan kepunahan keanekaragaman hayati, degradasi ekosistem, penggerusan adat istiadat, dan perubahan iklim. Dampak paling utama yang sangat terasa adalah ketergantungan konsumsi kita terhadap beras rupanya tidak hanya terjadi di Jawa, tetapi juga di pulau-pulau lain di Indonesia.
Seakan tidak belajar dari dampak revolusi hijau, perubahan lahan besar-besaran mencetak sawah terjadi di Merauke dalam proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang diresmikan oleh pemerintah pada 2010. Program itu merupakan bagian dari program strategis lumbung pangan food estate di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yaitu pengembangan kawasan terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sejak itu, sekitar 1,2 juta hektar tanah dan hutan yang sebelumnya merupakan tanah ulayat dan ruang hidup salah satu suku lokal di Papua, Marind Anim, dirampas. Sebelum program food estate diinisiasi, mereka sudah terbiasa mengonsumsi makanan dari hutan, seperti sagu, umbi-umbian, serta daging dari hasil berburu dan meramu. Kini, mereka harus bergantung pada makanan yang dibeli dari luar kampung, seperti beras dan mie instan. Masalah gizi buruk pun menjadi ancaman baru. Itu adalah sebuah ironi yang muncul dari ambisi pembangunan demi cita-cita kemandirian (swasembada) pangan.
Ketahanan Pangan, Tapi Tidak Berdaulat Pangan
Keprihatinan akan tingginya konsumsi beras yang tidak bisa dikejar dengan produksi nasional membuat pemerintah gencar melakukan program ketahanan pangan lewat pangan lokal. Sayangnya, ‘niat baik’ itu masih dilakukan dengan pola pikir khas perkebunan raksasa tanaman tunggal (monokultur).
Pada 2021, misalnya, pemerintah membuka food estate perkebunan singkong sebesar 31.000 hektar di daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang rencananya akan dijadikan karbohidrat alternatif non-beras. Ironisnya, rencana itu diikuti dampak lingkungan yang mengkhawatirkan, yaitu pembukaan 600 hektar hutan alam selama 2021 yang telah menimbulkan terlepasnya 61.000 ton karbon yang memperparah efek rumah kaca.
Dampaknya, bencana banjir di beberapa daerah pun sering terjadi. Selain itu, hutan Gunung Mas yang tadinya menjadi sumber penghidupan warga Dayak, kini terbengkalai tanpa hasil panen singkong sama sekali. Kedua contoh kasus food estate ini menunjukkan usaha menuju ketahanan pangan nasional yang tidak berdaulat pangan.
Kedaulatan pangan, menurut organisasi La via Campesina, seharusnya menjunjung hak masyarakat atas pangan yang sehat dan sesuai dengan budaya yang dihasilkan melalui metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kita juga perlu memberikan mereka hak untuk mendefinisikan pangan dan sistem pertanian mereka sendiri.
Pada tingkat pemerintah daerah, program-program pangan lokal banyak yang hanya sebatas “merayakan” diversifikasi kuliner lokal melalui festival seni dan kebudayaan dan kerap kali luput melihat aspek keberlanjutan jangka panjang. Hingar bingar perayaan program pangan lokal biasanya hanya terjadi ketika ada pendanaan yang menyokong atau di bawah naungan program pemberdayaan ala NGO (Organisasi Non-Pemerintahan). Kebanyakan, walaupun tidak semua, program-program ini datang dan pergi, silih berganti dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Pelatihan-pelatihan kewirausahaan tentang pangan lokal biasanya tidak mampu melihat pangan lokal sebagai sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir, yaitu dari proses produksi, konsumsi, hingga pengelolaan sampah. Ketidaksinambungan ini biasanya hanya membuat bingung peserta lokakarya yang telah berhasil mengolah produk lokal tapi tidak bisa mengakses pasar. Begitu pula dengan petani yang telah mengubah lahannya menjadi ladang karbohidrat alternatif non-beras yang masih dihargai sangat murah di pasaran, bahkan di bawah harga beras.
Sebuah Refleksi
Sebagai seseorang yang tinggal di kota, dekat dengan akses pasar dan supermarket, memiliki berbagai macam hak istimewa (privilege) untuk memilih makan apa tiap harinya atau bahkan hanya perlu scrolling telepon genggam dan memilih makanan dari aplikasi pesan-antar, agaknya sulit membayangkan bahwa kita benar-benar sedang menghadapi krisis pangan. Padahal, sehari-hari kita mengalami ketidaksinambungan dalam proses konsumsi, yaitu ketika sebagai konsumen, kita merasa asing (alienasi) dengan asal-usul makanan yang hadir di meja makan.
Tidak hanya manusia, dalam sebuah krisis pangan juga terdapat spesies lain, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan yang saling berkelindan. ~ Monika Swastyastu Share on XMeminjam istilah antropolog asal Amerika Serikat, Anna Tsing, dalam bukunya The Mushroom at the End of the World, yakni “art of noticing”, ia memperhatikan hubungan kompleks antara manusia dengan non-manusia. Tsing menunjukkan bahwa keterhubungan antara manusia dan alam bisa membuka sebuah kesadaran pada hubungan yang seringkali tidak terlihat dan tersembunyi dalam konteks kapitalisme global. Di kehidupan sehari-hari, konsep ini bisa kita gunakan untuk mencermati tidak hanya manusia, tapi juga bagaimana dalam sebuah krisis pangan terdapat spesies lain, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan yang saling berkelindan di dalamnya.
Selain berpikir kritis dan berkesadaran tentang darimana makanan kita berasal, memahami sebuah ekosistem yang terdiri dari multispesies yang saling terhubung dapat membantu kita untuk lebih memahami cara beradaptasi dan resiliensi dalam menjalani hidup yang lebih berkelanjutan.

Monika Swastyastu adalah lulusan Program S2 Antropologi, Universitas Gadjah Mada. Ia merupakan peneliti di Bakudapan Food Study Group.
Artikel Terkait
Memerangi Maskulinitas Beracun, Tanggung Jawab Siapa?
Memerangi maskulinitas beracun bukan berarti mengutuk laki-laki atau atribut laki-laki, melainkan untuk memerangi dampak berbahaya dari maskulinitas tradisional, seperti dominasi dan persainganMenjadi Admin Akun Psikologi: Bukan Sekadar Berbagi, Tapi Juga Menerima
Di Catatan Pinggir ini, Ayu Yustitia berkisah tentang pengalamannya menjadi admin media sosial Pijar Psikologi. Ayu tersadar bahwa bahwa banyak orang di luar sana yang merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Pengalaman ini mendorong Ayu untuk mendorong kita semua untuk lebih baik kepada diri sendiri dan orang di sekitar kita.Tanya Kenapa
Di usianya yang muda, Putri Hasquita Ardala sudah mengenyam banyak pengalaman tentang pentingnya kesehatan mental. Di Catatan Pinggir ini, Putri mengingatkan kita semua tentang panjangnya jalan menghadapi depresi dan bagaimana kita semua perlu meminta bantuan.