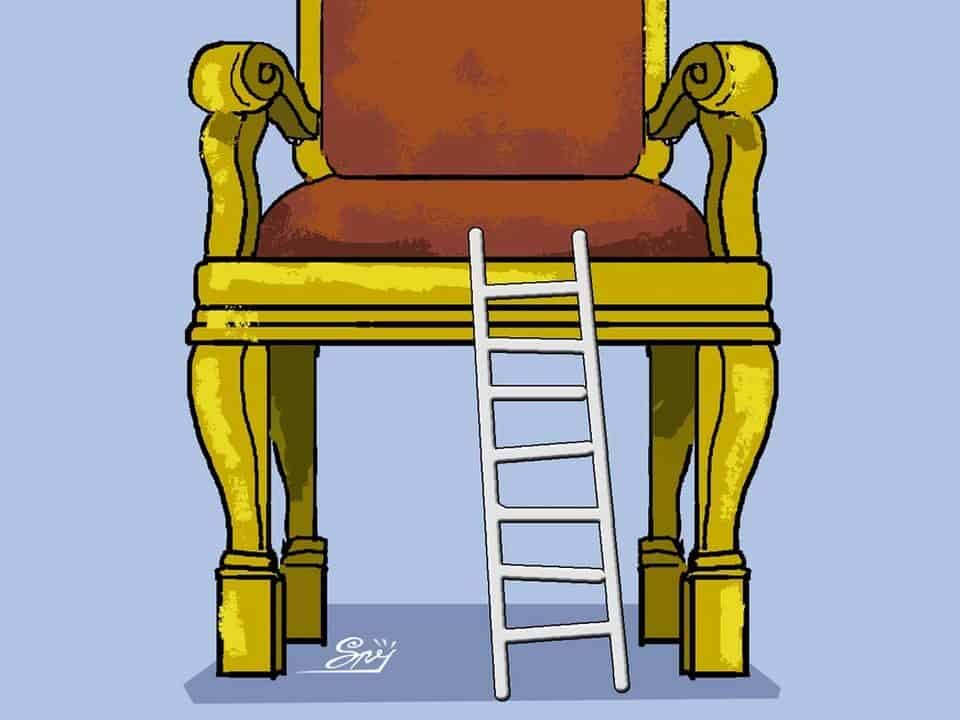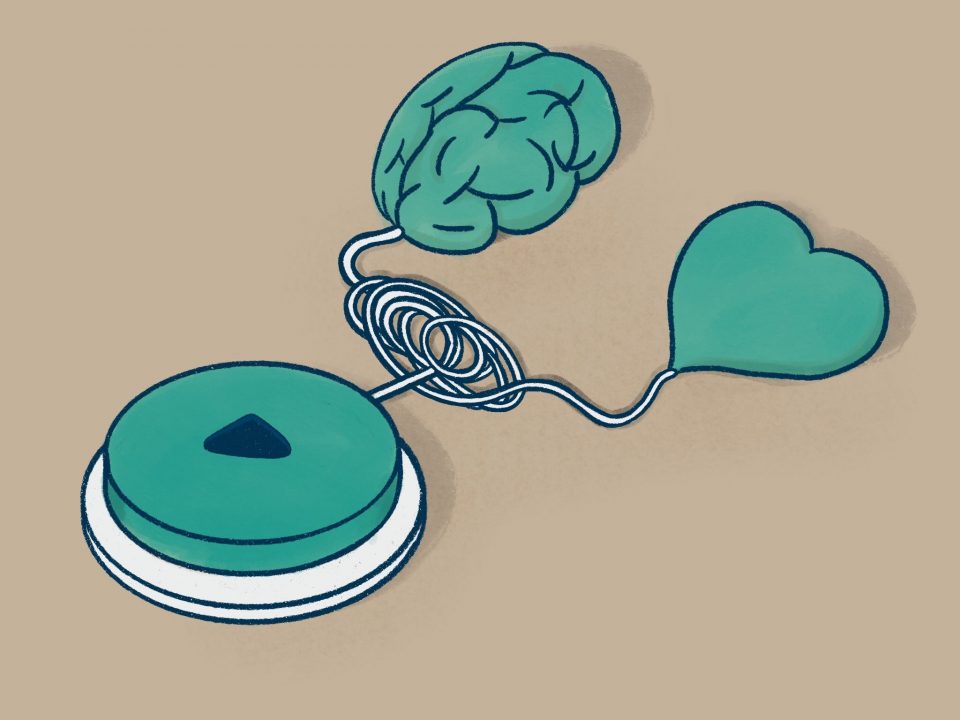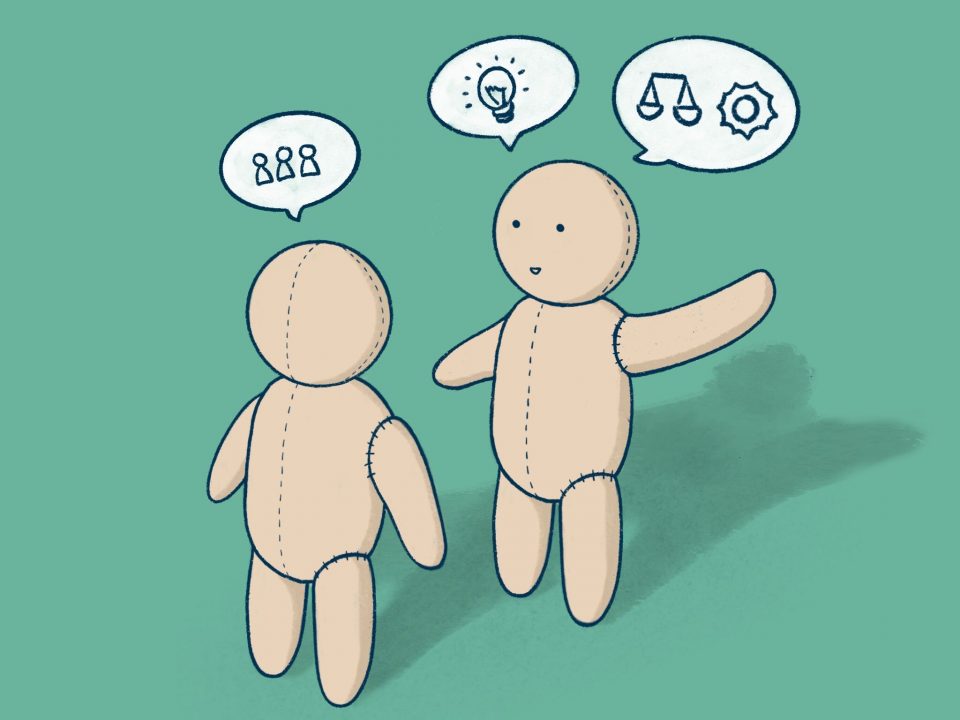Antara Baik dan Jahat: Mempersoalkan Dualitas Sifat Dasar Manusia
December 12, 2023
Menjadi Pejabat Publik yang Baik
December 13, 2023
Photo by Clay Banks on Unsplash
OPINI
Apa yang Salah dari Pernyataan Aktivisme Seyogianya Jujur dengan Ambisi Uang dan Ketenaran? Semuanya!
oleh Geger Riyanto
Belum lama ini, Abigail Limuria, salah satu pemrakarsa Bijak Memilih, mengedarkan video dirinya berbicara di hadapan audiens anak-anak muda. Dalam video tersebut, Abigail berpesan kepada para aktivis untuk terbuka dengan perasaannya. Mereka harus jujur, mereka ada di sana untuk uang dan ketenaran. Bila tidak begitu, mereka akan cepat ambruk lantaran letih dan penat.
Video ini menuai kritik dari kiri-kanan. Tentu saja, tak sulit menemukan permasalahan dari pernyataan Abigail. Siapa yang memiliki kesempatan untuk mendulang cuan (uang) dan ketenaran dari aktivisme? Memang ada, tapi tak sebanyak yang dibayangkan Abigail.
Ketika ada satu orang direktur organisasi nirlaba internasional yang menjadi pusat perhatian media, dielu-elukan oleh anak muda, dan disegani oleh orang-orang berpengaruh, ada ratusan orang yang bekerja menjalankan programnya dan mereka tak tersorot. Untuk satu orang yang dapat hidup berlimpah di apartemen mewah ibu kota dan melompat-lompat ke berbagai negara serta pertemuan internasional, ada banyak relawan yang bekerja dengan telaten dan hanya bakal nampak ketika kegiatan lokal diliput.
Orang-orang di tingkat tapak ini tidak akan pernah menemukan dirinya di panggung berkilau semacam itu, bahkan bila mereka punya kesempatan mengulang hidupnya berkali-kali.
Dan saya belum bilang alasan para relawan ini bekerja. Mereka bekerja di bawah janji bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang baik. Bagi para relawan advokasi lingkungan misalnya, mereka melihat organisasi payung mereka sebagai satu dari sangat sedikit pilihan untuk bernegosiasi dengan kekuatan perusak yang tak bisa mereka bendung sendiri.
Di jaringan advokasi minoritas gender, kerja-kerja relawan menjadi cara untuk merawat hubungan dan satu-satunya yang bakal membeking mereka ketika situasi memburuk. Tak jarang, mereka sudah dibuang oleh keluarga. Yang mereka punya adalah teman-temannya dan mereka tak bisa membiarkan orang-orang terdekat ini bekerja sendiri.
Kita sering mendengar satu kata didengung-dengungkan dalam aktivisme, terkadang secara tidak proporsional dan terlalu diromantisir: warga.
Misalnya, warga bergerak bersama, menggugat pemerintah atas pelanggaran hak-hak mereka.
Atau, warga berkumpul, saling membantu tanpa mengharapkan uluran negara.
Bahkan, ketika sebuah program cuma berhasil menggalang segelintir peserta—itu pun dari jaringan dekat para penyelenggara sendiri—idiom “warga” tetap dipakai untuk menggambarkan mereka dan aktivitasnya. Hal itu karena masyarakatlah sumber legitimasi aktivisme, bukan cuma sumber tenaganya. Dan partisipasi masyarakat harus datang secara tulus, bukan karena ada iming-iming material.
Dus, bukan gestur yang elok bila seseorang yang dikenal di jaringan aktivisme nasional tiba-tiba mengemukakan secara publik aktivisme tak sebaiknya dilepaskan dari motivasi uang dan ketenaran. Dengan memerah kerja sukarela siapa uang itu bisa diperoleh? Dengan berdiri di atas perjuangan kolektif siapa ambisi pribadi para aktivis ditunaikan?
Para relawan serta pekerja di level tapak pun tahu kalau uang dan ketenaran yang beredar di antara para aktivis tingkat tinggi ini tak kecil nilainya.
Gestur Abigail menyulut sekam yang sudah lama tertumpuk.
Bias Kelas Menengah
Pernyataan Abigail bukannya tidak bisa dipahami. Kalau kita mau memakluminya sebagai aspirasi kelas menengah, apa yang dikatakannya manusiawi belaka.
Ada waktu-waktu di mana mereka yang berkarier penuh di bidang nirlaba memikirkan kembali keputusannya menceburkan diri ke bidang itu. Saya kenal mereka. Kalau pun Anda tak mengenal mereka, bukan hal yang sulit untuk membayangkan situasi mereka.
Seperti kelas menengah lainnya, karier menjadi persoalan yang selalu menghantui. Apakah mereka sedang melakukan kerja yang berarti dalam tahapan hidup mereka sekarang? Akankah mereka tetap berkutat dengan rutinitas melelahkan yang sama sepuluh tahun lagi, mandek meski umur terus menguap dan tak akan kembali lagi? Mengapa mereka mempersulit diri dengan bekerja di bidang ini ketika ada hidup yang mudah terbentang di hadapan, hanya bila mereka tak keras kepala dengan idealisme mereka?
Beberapa mengambil keputusan bodoh, menghancurkan semua yang telah mereka bangun selama puluhan tahun ketika disodorkan dengan opsi kehidupan yang lebih nyaman—jauh lebih nyaman.
Namun, kita tak perlu selalu memaklumi pernyataan semacam yang diucapkan Abigail—tidak ketika kata-kata tersebut tak peka dengan pengistimewaan brutal dalam dunia aktivisme.
Ranah aktivisme, ranah yang dibangun di atas nilai-nilai kesetaraan, adalah ranah yang sarat ketimpangan. Bila Anda pulang dari bersekolah di luar negeri, lebih-lebih dari kampus-kampus prestisius, jalan untuk menapaki karier yang menanjak di bidang ini terbuka lebar. Anda akan diterima dengan tangan terbuka di sebuah organisasi nirlaba besar, dipanggil di mana-mana, berkesempatan menjumpai para pemegang keputusan dan mengumpulkan lencana dari hajatan-hajatan penting.
Ranah aktivisme, ranah yang dibangun di atas nilai-nilai kesetaraan, adalah ranah yang sarat ketimpangan. ~ Geger Riyanto Share on XTahu-tahu saja, menginisiasi sebuah program semudah membuka WhatsApp dan menghubungi kenalan Anda. Nama Anda beredar di antara para direktur dan pekerjaan-pekerjaan konsultasi paling basah membanjir.
Tentu saja, sekolah bukan satu-satunya penentu privilese (hak istimewa) di ranah ini. Perkoncoan dengan para pengambil keputusan dan veteran, kelancaran berkomunikasi dengan bahasa asing—lantaran lahir di luar negeri—bahkan hubungan keluarga juga punya kontribusi.
Namun, sebagaimana privilese di mana-mana, mereka yang memilikinya pun cuma segelintir. Dan di mata para pemeluk keistimewaan, aktivisme secara tak mengherankan nampak seperti arena panjat tebing. Jalur menanjak ke atas terbentang tidak terbatas—perlombaan berebut pengaruh, pengakuan, dan akses ke jaringan strategis berlangsung secara buas.
Percayalah, selagi itu terjadi, kedengkian sudah membara di antara mereka yang kerja-kerjanya di bawah diklaim, memungkinkan para petinggi memanjat ke atas. Tak jarang, organisasi-organisasi nirlaba internasional kondang bertumpu pada inisiatif-inisiatif lokal yang sudah lama berlangsung, dipertahankan ngos-ngosan dengan subsidi silang atau bahkan karena itu sudah melekat dalam kehidupan pelakunya. Organisasi-organisasi besar ini datang dengan pendanaan seadanya, instrumen yang mesti diisi sendiri oleh komunitas dan mengklaim kerja-kerja tersebut miliknya.
Selanjutnya, dengan reputasi mancanegaranya, dengan betapa dikenalnya mereka di antara anak-anak muda beraspirasi, mereka mudah saja memonopoli perhatian. Hal yang sama dilakukan oleh nama-nama pemeluk keistimewaan. Lantas, dengan nama yang dibesarkan melalui cara demikian, mereka dapat mengamankan kedudukan atau lebih banyak lagi pundi-pundi pendanaan.
Di partai politik dan perusahaan saja, ketimpangan pusat-daerah memicu kekisruhan, bagaimana dengan bidang nirlaba? Dengan sumber daya yang terbatas—sangat terbatas—tak semua akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pekerjaan di ranah ini. Sayangnya, kita sedang berbicara tentang satu bidang yang legitimasinya dibangun di atas keadilan.
Kita berbicara perihal ranah yang mungkin paling tidak pantas bila punggawanya mencapai ketinggian hidup yang bahkan tak bisa diimajinasikan para relawannya.
Tapi, ketimpangan ini terjadi. Apakah saya perlu bilang ada punggawa yang mengepul tanah di sudut-sudut paling indah Indonesia, sementara yang lain diminta untuk bekerja dengan kerelaan?
Ketimpangan ini disadari oleh sebagian manajemen organisasi nirlaba dan senantiasa menjadi momok menakutkan. Banyak yang insaf dengan privilese berada di pusat atau menjadi sosok kunci yang dikenal. Dibayang-bayangi rasa bersalah, mereka berusaha melakukan yang benar sembari memastikan organisasi tetap berjalan, yang hanya bisa dilakukan dengan mempertahankan business-as-usual (aktivitas yang berjalan seperti biasa) organisasi nirlaba, yaitu bertumpu di atas kerja-kerja kerelawanan.
Tapi, tak mengherankan sama sekali pula bila para aktivis-manajemen organisasi nirlaba internasional secara polos berujar bahwa baginya aktivisme merupakan ajang kontestasi kesuksesan pribadi. Mereka bisa jadi tidak terpapar dengan realitas kedengkian para relawan dan pekerja tapak. Tentu saja. Para relawan dan pekerja tapak tidak akan mau mengorbankan sedikit modal yang mereka punya untuk bernegosiasi dengan kesulitan hidup atau naik derajat secuil. Pilihan orang-orang di bawah tidak banyak—tidak sebanyak yang jelas-jelas dimiliki oleh para pemeluk keistimewaan. Mereka hanya akan menampilkan wajah dan sambutan paling ramah kepada para aktivis-manajemen, penentu nasib mereka.
Mereka tidak memiliki banyak saluran untuk mengekspresikan kegerahannya, tapi kanal ini bukannya tidak ada, sebut saja akun bocoran perasaan para pekerja nirlaba ini. Dan sesegera Anda mengunjunginya, sesegera itu pula Anda sadar betapa terlilitnya dunia aktivisme oleh kekuasaan yang tidak memperkenankan orang-orang bawahnya berbicara.
Dengar satu ungkapan dari akun tersebut: “Dampak seluas-luasnya, dana seminim-minimnya.”
Dengar satu lagi yang lain: “Katanya regenerasi, tapi kok yang tampil si senior lagi?”
Pengikut akun ini di atas sepuluh ribu. Hal ini berbicara sesuatu.
Apa yang Etis Dilakukan Pemilik Privilese?
Dengan apa sebaiknya saya menutup esai sinis ini? Dengan tidak berhenti sinis, tentunya—dengan memperdengarkan kepada Anda celoteh menggurui seseorang tentang aktivisme.
Aktivis, menurut orang ini, ada di mana-mana. Anda tak perlu berada di dalam lingkaran feminis, organisasi akar rumput, atau bersorak-sorak di unjuk rasa untuk dapat dibilang aktivis. Anda bisa berada di dalam organisasi seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia, atau yang lainnya untuk memperjuangkan misi Anda.
Wejangannya terdengar biasa saja, sampai dengan Anda tahu bahwa orang ini bekerja di badan PBB dan ia tengah membela diri dari kesinisan-kesinisan soal apa yang dilakukannya bukanlah aktivisme. Ia kurang-lebih menyampaikan bahwa kerja-kerjanya memandori simpul-simpul lokal dan menjadi perantara dari uang-uang besar bisa jadi lebih manjur ketimbang kerja-kerja mereka yang ada di lapangan.
Saya bisa memahami dari mana kesinisan terhadap orang ini muncul. Para pekerja tapak dan relawan sekadar ingin memberikan nilai lebih pada apa yang mereka lakukan. Organisasi nirlaba besar yang memayungi akan bilang kerja mereka tak ternilai, tapi kerja-kerja mereka pada kenyataannya tak ada nilainya dibandingkan kerja-kerja sang aktivis badan PBB. Ia mendapatkan gaji puluhan, kalau bukan ratusan juta Rupiah, saya yakin. Para pekerja tapak dan relawan mendapatkan ucapan terima kasih.
Ketimpangan semacam ini adalah penghinaan, betapapun kita berargumen berbelit-belit bahwa hierarki diperlukan agar kerja-kerja nirlaba bisa terus berjalan. Hanya satu hal yang boleh dan etis dilakukan oleh pemilik privilese di hadapan mereka yang terhina: bungkam.
Dengan cerocos sang aktivis badan PBB di hadapan yang terhina, saya tak heran kalau banyak yang ingin menimpuk sang aktivis badan PBB dengan sepatu.
Saya akan menimpuknya dengan sepatu Nabi Adam, kalau bisa.

Geger Riyanto adalah seorang antropolog yang mengajar di Departemen Antropologi Universitas Indonesia. Ia juga merupakan peneliti pascadoktoral di Asia Research Centre, Universitas Indonesia, berfokus pada riset-riset tentang perubahan ekologi. Disertasinya, berangkat dari riset etnografi tentang hubungan di antara masyarakat perantau dari Sulawesi Tenggara dan kelompok adat di Maluku, dinobatkan sebagai disertasi antropologi terbaik di negara-negara berbahasa Jerman oleh Frobenius Institute pada 2023. Tulisan-tulisannya terbit di media seperti Remotivi dan IndoProgress maupun jurnal akademik seperti Anthropology and Humanism, The Asia Pacific Journal of Anthropology, Oceania, dan Indonesia and the Malay World.
Artikel Terkait
Membangun Dinasti di Negara Demokrasi: Geliat Politik Keluarga di Indonesia
Politik dinasti jadi penyakit demokrasi. Bagaimana demokrasi Indonesia bergulat dengan politik dinasti?Mengapa Kita Tak Bisa Jadi Pemilih yang Rasional
Meskipun dalam teori politik dan demokrasi seorang warga negara sering digambarkan sebagai manusia rasional, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita sering dikuasai emosi. Memikirkan kembali Pemilu 2019 yang baru saja lewat, di Catatan Pinggir kali ini, Laila Achmad membahas mengenai sulitnya menjadi seorang pemilih rasional.Politik: Seni Berpikir Kritis Bukan Apatis
Ini akan terdengar sebagai suatu pembuka bacaan yang klise, namun kata ‘Politik’ sudah menjadi bagian dari makanan sehari-hari kita sebagai masyarakat Indonesia. Namun, apakah Politik itu menjadi asupan yang kita santap dengan penuh antusiasme?