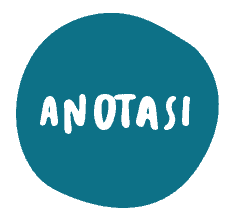Sejarah mencatat peran penting media dalam menyuarakan pesan-pesan perubahan pada gerakan aktivisme sosial.
Pada Reformasi 1998, media membantu gerakan sosial mempublikasikan demonstrasi yang terjadi di berbagai kota, sehingga demonstrasi yang sama bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa di kota lain.
Akhir-akhir ini, aktivisme sosial tidak hanya dilakukan dalam bentuk gerakan aksi secara luring (luar jaringan), melainkan juga daring (dalam jaringan). Kehadiran media digital, terutama media sosial, membantu menyebarkan informasi yang ada sekaligus menyediakan ruang diskusi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
Pada tulisan ini, saya akan menganalisa perkembangan teknologi media pada masing-masing era yang membantu menyebarkan pesan gerakan sosial di masa itu. Ada dua moda media yang akan saya bahas, yaitu media konvensional berupa media cetak (koran dan majalah) dan media digital.
Agenda Setting pada Media Massa: Membangun Agenda Publik
Media massa membantu aktivisme sosial dalam bentuk menciptakan agenda setting (pengaturan agenda) untuk mendukung isu yang sedang diperjuangkan. Agenda setting adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh dua ilmuwan terkemuka, Maxwell McComs dan Donald Shaw, yang mengatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk memengaruhi masyarakat mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian. Hal itu dilakukan media dengan memuat berita-berita tertentu yang dianggap penting.
Pada Reformasi 1998, media membantu membentuk opini publik dengan memuat berita yang berisi rentetan peristiwa yang mengarah pada penggulingan Orde Baru. Berdasarkan penelitian Paul Frank, dari Central Queensland University, pada bulan-bulan awal 1998, muncul peningkatan pemberitaan di media-media Indonesia mengenai gerakan protes mahasiswa ataupun yang dilakukan oleh kelompok lainnya.
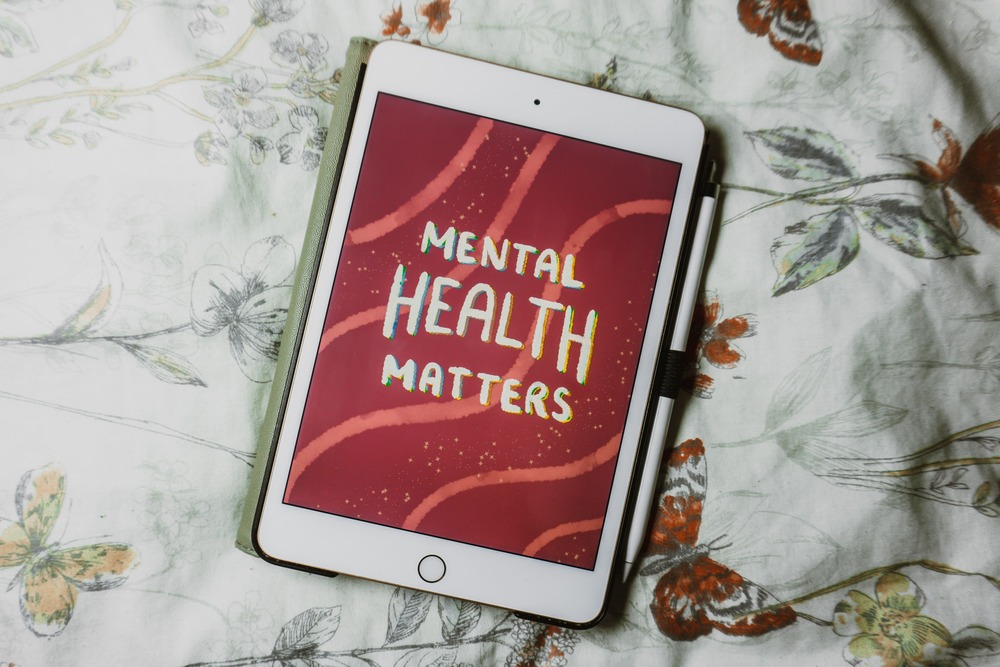
Media juga memuat berita-berita yang mendukung penggulingan Orde Baru. Pada berita yang mengulas krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu, media juga banyak memuat pendapat tokoh-tokoh oposisi, seperti Amien Rais dan Megawati.
Media juga sengaja memuat hasil polling (pengumpulan suara) dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang menolak ide pencalonan Soeharto sebagai Presiden untuk masa pemerintahan ke-7. Seluruh rentetan peristiwa itu sudah cukup untuk membentuk agenda publik bahwa pemerintahan Orde Baru sudah tidak relevan lagi, sekaligus membantu mengamplifikasi (memperluas) gerakan protes mahasiswa.
Kekurangan dari media massa adalah adanya sifat kelembagaan yang dimiliki oleh media itu sendiri. Di satu sisi, sifat kelembagaan memberikan akses pada sistem gatekeeping (pengeditan), dimana informasi yang dipublikasikan di media massa sudah melalui proses verifikasi dan filterisasi (penyaringan) oleh pihak redaktur. Akan tetapi, sifat kelembagaan mempengaruhi angle (sudut pandang) pemberitaan dari media itu. Kadangkala, media sengaja memilih tidak memberitakan informasi yang perlu diketahui oleh publik karena informasi tersebut dapat memengaruhi reputasi pihak yang memiliki afiliasi dengan media.
Pada Reformasi 1998, media massa di Indonesia semuanya berpihak pada gerakan sosial. Cukup masuk akal, mengingat, pers di Indonesia mengalami represi dan pembatasan oleh rezim Soeharto selama ia berkuasa. Selain itu, pada masa itu, terjadi krisis ekonomi, sehingga pers memiliki celah untuk memberitakan kejelekan rezim Soeharto. Meskipun demikian, tidak dapat dimungkiri kalau ada banyak media massa yang menjadi corong pemerintah atau pemilik media massa yang berafiliasi secara politik dengan rezim yang berkuasa. Akibatnya, mereka tidak memberitakan gerakan sosial yang terjadi yang berdampak pada pesan gerakan sosial tidak tersebar secara luas.
Media Sosial: Gerakan Sosial Tidak dalam Bentuk Fisik
Kehadiran media sosial memberi warna baru dalam gerakan sosial. Melalui media sosial, pengguna tidak hanya dapat bertukar informasi, melainkan juga dapat menciptakan jejajaring kerja sama. Menurut penelitian Mundt dan rekan, dari University of Massachusetts terkait gerakan Black Lives Matter, media sosial dapat berfungsi sebagai tempat untuk membangun koneksi, memobilisasi massa dan sumber daya yang dapat digunakan, membangun koalisi, menciptakan narasi alternatif untuk menantang narasi utama.
Kehadiran media sosial memberi warna baru dalam gerakan sosial. Melalui media sosial, pengguna tidak hanya dapat bertukar informasi, melainkan juga dapat menciptakan jejajaring kerja sama. ~ Rizkiya Ayu Maulida Share on XSalah satu kelebihan dari media digital yang tidak dimiliki oleh media konvensional adalah terbatasnya kontrol pemerintah terhadap konten yang bersirkulasi (beredar) di media digital secara masif. Kebebasan ini penting, karena fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi menjadi tidak dapat berjalan optimal apabila dihinggapi oleh kepentingan yang lain. Selain itu, media sosial dapat menjadi playground atau lokasi dari dimobilisasinya gerakan sosial itu sendiri. Hal tersebut dapat kita lihat pada penggunaan hastag (tanda pagar/tagar), keywords (kata kunci), dan visual yang sama yang secara bersamaan diluncurkan oleh para pengguna. Keberhasilan untuk membuat suatu isu menjadi viral ataupun trending topic (topik terpopuler) di media sosial, isu tersebut sangat berpotensi untuk dapat disebarkan ke media online, bahkan menjadi perbincangan di dunia luring.
Konvergensi Media dan Gerakan Nyata
Aktivisme di dunia maya harus diikuti gerakan konkret di luar jaringan, sehingga dapat menimbulkan efek yang dituju. Pada Gerakan Peringatan Darurat yang terjadi beberapa waktu lalu misalnya, kita dapat melihat betapa efektifnya perpaduan antara media konvensional, media digital, dan gerakan secara luring. Gerakan Peringatan Darurat berawal ketika netizen (warganet) secara serentak mengunggah gambar visual Garuda Berwarna Biru dengan tulisan ‘Peringatan Darurat’ di platform Twitter (sekarang X) dan Instagram, pada 21 Agustus 2024, sebagai respon atas keputusan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang menganulir Putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Satu hari setelahnya, timbul aksi di berbagai kota di Indonesia yang diorganisasi oleh berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa. Gerakan itu dibantu oleh berbagai media massa yang menyiarkan gerakan yang terjadi dan memberi konteks kepada masyarakat mengenai kronologi peristiwa dengan versi yang sudah terverifikasi. Hasil dari perpaduan antara gerakan di media sosial dan gerakan dunia luring tersebut membawa hasil yang dicita-citakan publik, yaitu pengesahan RUU Pilkada dibatalkan.

Dalam jangka panjang, diskursus di media sosial mengenai isu publik sangat berguna sebagai sistem kontrol jalannya roda pemerintahan. Tidak bisa dipungkiri, media sosial memberikan fungsi public sphere (ruang publik), yang menurut filsuf Habermas, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi dan berkomunitas mengenai isu-isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Hanya saja, kita perlu pengelolaan agar media sosial tidak mengarah pada witch-hunting, yaitu netizen menyerang salah satu individu yang dapat dijadikan sasaran kemarahan dengan menggunakan isu-isu yang bukan prioritas utama. Selain itu, aktivisme di media sosial juga harus diikuti dengan tindakan di luar jaringan, agar dapat menimbulkan efek yang lebih nyata. Jika tidak, para partisipan hanya akan merasakan apa yang oleh Evgeny Morozov sebut dengan ‘slacktivism’, dimana partisipan merasa sudah melakukan aksi perubahan yang nyata dengan hanya berpartisipasi dalam diskusi di media sosial.

Rizkiya Ayu Maulida adalah Dosen Ilmu Komunikasi yang memiliki spesialisasi pada topik Komunikasi Publik di Lembaga Pemerintah dan Aktivisme Digital. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada dan Master of Arts (M.A) di School of Media and Communication di University of Leeds, UK. Ia senang berbagi perspektif personal di Instagram @rizkiyamaulida