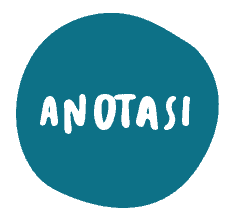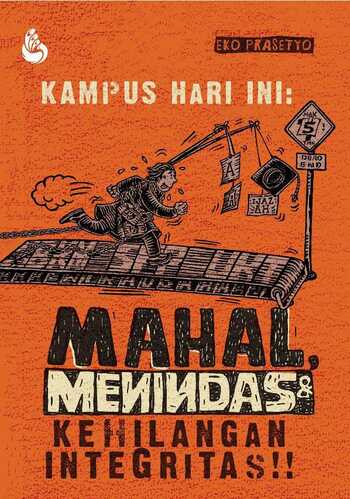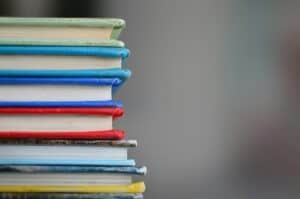“Universitas tidak bisa lagi disebut berwatak korporasi. Hari ini, ia tak ubahnya sebuah peternakan yang memaksa peliharaanya berkorban demi tujuan terselubung neoliberalisme.”
Suram. Kata itu paling menggambarkan bagaimana kondisi universitas hari ini. Biaya perkuliahan kian mahal dan makin mencekik mahasiswa. Dosen dituntut mengejar publikasi hingga harus mengorbankan moral dan etika akademiknya. Birokrasi kampus tak ubahnya badut-badut kepanjangan tangan dari kekuasaan yang tugasnya mengekang kebebasan akademik semata.
Masalah-masalah di atas bak penyakit kronis yang menggerogoti universitas hari ini. Bisa dibilang, institusi itu sudah berjalan lunglai karena telah divonis mendekati ajalnya. Penyakitnya turun menjadi semacam wabah ke dalam diri individu-individu di universitas hingga membuat mereka hanya menjadi manusia hipokrit (munafik) dan mengejar kepentingan material semata.
Padahal, universitas sudah mengadopsi apa yang disebut-sebut oleh Kementerian Pendidikan sebagai sebuah terobosan kurikulum yang memerdekakan, yaitu “Kampus Merdeka-Merdeka Belajar”. Kenyataannya, ini malah menjadi racun pembunuh institusi ini dari dalam dan menyulap kampus menjadi semacam korporasi penjual pengetahuan saja.

Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, bahkan tak bergeming sama sekali ketika dilayangkan sejumlah permasalahan dan kritik terhadap kondisi universitas. Tak pernah sekalipun ia menanggapi keluhan biaya kuliah mahal yang bahkan sampai membuat mahasiswa meregang nyawa. Saat peringatan Hari Pendidikan pada 2 Mei lalu, ketika sejumlah demonstrasi digelar untuk menuntut pendidikan tinggi gratis, Nadiem malah tak menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Malahan, ia menggelar pesta besar merayakan keberhasilan semu “Kurikulum Merdeka”.
Dus, seabrek permasalahan universitas itu yang coba diserukan secara provokatif oleh Eko Prasetyo dalam bukunya Kampus Hari Ini: Mahal, Menindas dan Kehilangan Integritas. Eko membongkar kebobrokan kampus dalam berbagai hal serta bagaimana institusi ini menjalankan praktik penindasan kepada segenap sivitas akademika yang mendiami universitas.
Universitas Hitam Indonesia
Neoliberalisme pendidikan tinggi—penyerahan urusan pendidikan pada mekanisme pasar—bukan hanya terjadi di Indonesia. Tunduknya universitas terhadap mekanisme pasar dan sistem manajerialisme korporasi lebih merupakan sebuah tren global. Sebelum Eko menerbitkan bukunya, seorang Profesor Sekolah Bisnis di University of Technology Sydney (UTS), Peter Flaming, menerbitkan buku bertajuk Dark Academia: Matinya Perguruan Tinggi.
Flaming, dalam bukunya, banyak memotret banalitas pasar yang menjungkirbalikkan universitas dari tujuan luhurnya sebagai tempat pengembangan pengetahuan untuk kemajuan manusia. Ia juga melukiskan bagaimana naiknya biaya kuliah di Amerika dan Inggris menjadikan universitas hanya bisa dimasuki oleh golongan elit. Bahkan, di bagian paling menyedihkan, Flaming memasukkan kisah salah satu dosen yang memilih bunuh diri akibat tak kuat menahan tekanan publikasi yang dituntut oleh pimpinan universitas.
Kembali ke Indonesia, Eko mengamini hal serupa dengan Flaming. Logika manajerialisme sebagai turunan neoliberalisme dalam mengembangkan sistem pengelolaan publik juga jadi biang keladi kehancuran universitas di negeri ini. Bahkan, Eko tak segan menyebut sistem itu sebagai bentuk penjajahan terhadap kampus untuk menyeragamkan semua orang.
“Sistem pembelajaran membuat logika pasar jadi budaya akademik dan itu tak terjadi di Indonesia saja. Di berbagai negara maju, hal yang sama terjadi. Seluruh proses pembelajaran musti diukur. Seluruh ukuran kinerja yang berpusat pada akreditasi.” (hlm. 57)
Ukuran-ukuran itu merusak moral dan etika akademik, karena tujuan penelitian hanyalah semata meraih insentif sebesar-besarnya. Majalah Tempo edisi 21 April 2024 sempat menyoroti hal itu. Sebelumnya, salah satu Guru Besar Universitas Nasional, Kumba Digdowiseiso diprotes oleh akademisi dari Universiti Malaysia Terengganu (UMT) karena mencatut nama 24 dosen di sana tanpa izin.
Mahasiswa, dalam perjalanannya di universitas hari ini, tak ubahnya seperti subjek paria: sudah dibenturkan biaya kuliah mahal, mereka juga ikut menanggung beban publikasi ~ Mukhtar Abdullah Share on XTak berhenti sampai di situ, Kumba juga menerbitkan publikasi dengan jumlah di luar nalar untuk ukuran sebuah penelitian ilmiah. Hasil penelusuran Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), menunjukkan sepanjang tahun 2023 Kumba menerbitkan 314 artikel. Sedangkan per April 2024 lalu, ia bahkan sudah mempublikasi 163 artikel atas nama dirinya.
Namun, dari kasus Kumba, hal yang menarik justru yang paling tertindas adalah mahasiswa. Koordinator KIKA, Satria Unggul, dalam keterangannya kepada Tempo mengatakan Kumba memperbanyak publikasi dengan cara menitipkan namanya di dalam karya ilmiah mahasiswa bimbingannya.
Kasus Kumba yang memanfaatkan mahasiswa itu perlu digarisbawahi. Ini bisa jadi adalah pembeda mendasar dampak neoliberalisme universitas antara di Amerika dan Indonesia. Kultur feodal dalam tradisi akademik di Indonesia sudah barang tentu mengorbankan strata paling bawah, yaitu mahasiswa, meskipun sistem itu sebenarnya juga menindas segenap penghuni universitas.
Mahasiswa, dalam perjalanannya di universitas hari ini, tak ubahnya seperti subjek paria (ada di posisi paling rentan) dari keseluruhan sistem yang menindas. Sudah dibenturkan biaya kuliah mahal, mereka juga ikut menanggung beban publikasi. Jika melawan, jawabannya hanya satu: birokrasi kampus pasti melakukan pembungkaman. Terbaru, salah satu mahasiswa Universitas Riau, Khariq Anhar, dilaporkan ke kepolisian dengan pasal UU ITE, karena memprotes kenaikan biaya kuliah di kampusnya.
Secercah Harapan
“Habis gelap terbitlah terang”, kalimat itu bak sebuah harapan akan hadirnya jalan alternatif dalam menghadapi penyakit kronis universitas hari ini. Selain memberikan kritik tajam, Eko juga menghadirkan sebuah antitesa (pertentangan) dari berbagai praktik penindasan di perguruan tinggi Indonesia. Hal itu ditempuh dengan cara mengembalikan institusi pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan pengetahuan yang bersifat emansipatoris atau membebaskan.
Menghadirkan alternatif di universitas tentu membutuhkan kerja keras jangka panjang, khususnya dalam kasus naiknya biaya perkuliahan dan hilangnya kebebasan akademik. Salah satu tawaran Eko adalah dengan mengaktifkan dan memasifkan kembali protes-protes yang dimotori oleh mahasiswa dalam merespon kondisi kampusnya.
“Protes mengajak semua kalangan untuk memproduksi berbagai nilai kontra dari komersialisasi pendidikan, plagiasi yang terjadi hingga tata kelola kampus yang menjurus pada korupsi. Protes adalah upaya melakukan konfrontasi atas itu semua. Protes ajakan petualangan pada mahasiswa untuk keluar dari zona nyamannya.” (hlm. 155)
Ajakan protes ini kenyataanya berbenturan dengan realitas kebanyakan mahasiswa di universitas. Ciri individualistis karena pengaruh neoliberalisme mengakar kuat hingga harus dipecahkan terlebih dahulu. Selain itu, belum banyak gerakan mahasiswa melakukan protes terhadap kampusnya sendiri atas berbagai praktik culas ini. Meskipun beberapa waktu belakangan, seperti di Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, mahasiswanya melakukan protes kenaikan biaya perkuliahan.

Namun, protes-protes tadi belum mendapat sambutan dari kawan-kawan mahasiswa lain di berbagai universitas di Indonesia. Bahkan, kecenderungan hari ini, beberapa aktivis mahasiswa kampus merasa takut memprotes institusinya sendiri dan cenderung memilih melakukan demonstrasi di luar kampus. Padahal, gerakan-gerakan besar sejatinya selalu dimulai ketika mahasiswa berhasil mengorganisir kawan-kawannya sendiri untuk melakukan perlawanan.
Fenomena di atas juga sebetulnya telah direspon oleh Eko Prasetyo dalam pidato kebudayaanya di acara Anti Oligargigs di Universitas Gadjah Mada pada 18 November 2023. Pada kesempatan itu Eko memberikan tamparan keras ke mahasiswa dengan mengatakan, “Anaknya penampilannya radikal tapi pikirannya konservatif. Anaknya pikirannya progresif tapi tidak pernah melakukan perlawanan sama sekali. Tidak pernah ada pemogokan pembayaran UKT di sini.”
Kesimpulannya, buku ini merupakan sebuah pantikan serius terhadap praktik neoliberalisme di universitas di Indonesia. Eko, secara apik, menghadirkan sebuah bahasan rumit lewat bahasa propaganda yang sangat mudah dicerna. Bukan hanya menampilkan masalah, Eko secara tegas juga mengajak pembaca untuk terlibat aktif dalam mewujudkan alternatif dari kondisi suram universitas dengan melakukan protes. Seyogyanya, ini menjadi tamparan keras untuk seluruh penghuni kampus, baik rektor, dosen atau mahasiswa.

Mukhtar Abdullah adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Sehari-hari, ia hanya kongkow di kampus dan sesekali menuliskan isi pikirannya.