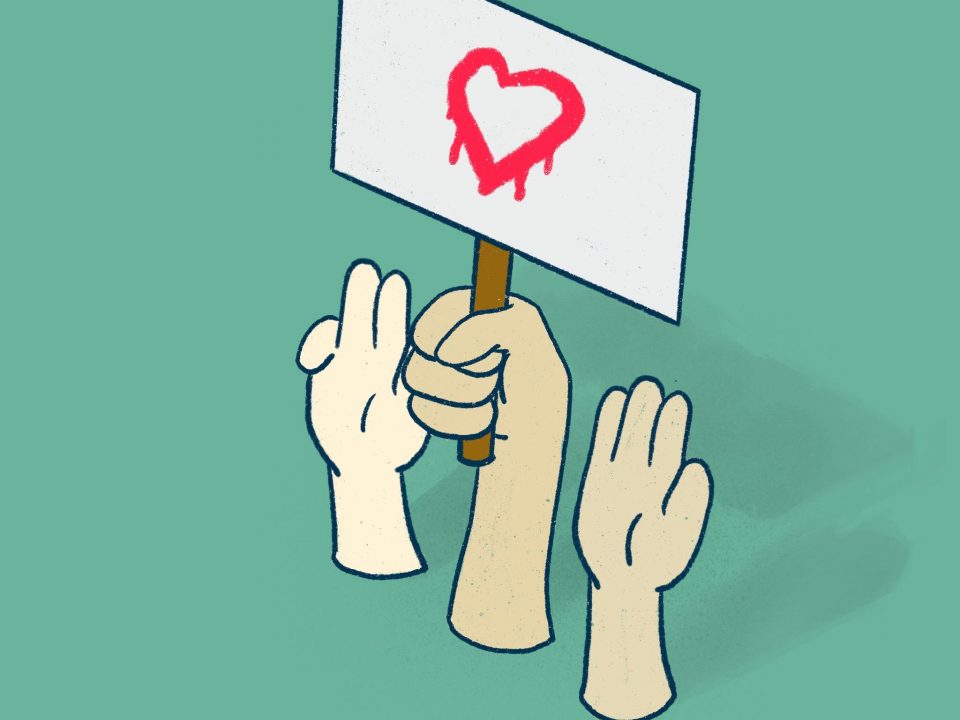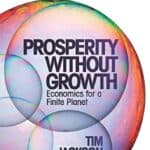
Pertumbuhan Ekonomi: Neraca Menuju Akhir Dunia
April 23, 2024
Potensi Menguatnya Dinasti Jokowi di Pilkada 2024
April 26, 2024
Photo by Solen Feyissa on Unsplash
OPINI
Benarkah Media Sosial Mengancam Demokrasi?
oleh Andina Dwifatma
Kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sering kali diasosiasikan dengan media sosial, khususnya TikTok. Konon, keduanya terpilih karena pengguna TikTok senang dengan joget gemoy dan mars “oke gas oke gas.”
Potongan-potongan klip kelakuan nyeleneh (cringe) Gibran selama debat juga beredar luas di sana, memberinya image sebagai ‘si paling savage’ dan cerdas, meskipun IPK-nya (Indeks Prestasi Kumulatif) ketika kuliah tidak seberapa.
Tetapi, apa iya media sosial sebegitu powerful-nya? Benarkah Prabowo-Gibran menang karena TikTok? Peristiwa pemilu kali ini bahkan disebut sebagai “kemenangan media sosial, kemunduran demokrasi”. Layakkah gejala kemasyarakatan sebesar kemunduran demokrasi diatribusikan nyaris seluruhnya kepada media sosial?
TikTok yang Canggih atau Kita yang Tak Pintar?
To be fair, Prabowo-Gibran memang bukan satu-satunya pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang memanfaatkan TikTok sebagai platform strategi pemenangan terbesar mereka. Di seluruh dunia, para politisi terang-terangan berkampanye di TikTok selama pemilu berlangsung, dan taktik itu berhasil. Mulai dari Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr di Filipina hingga Nayib Bukele di El Salvador, semuanya berterima kasih pada TikTok. Bahkan, pilpres di Amerika Serikat yang akan datang juga terang-terangan disebut sebagai “the first major TikTok election” saking krusialnya peran platform tersebut.
Tetapi, semua gejala itu tidak cukup hanya dibaca sebagai kecanggihan algoritma media sosial dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat. Fakta bahwa laman #FYP (For Your Page) TikTok bisa membentuk preferensi politik tidak hanya menunjukkan betapa presisinya teknologi tersebut bekerja, tetapi juga—dan barangkali lebih penting—betapa lemahnya kesadaran bernegara dan pendidikan politik masyarakat itu sendiri.
Menjelang pemilu lalu, seruan agar masyarakat tidak larut dalam kehebohan “pesta” demokrasi dan melupakan esensi dari pemilu itu sendiri sesungguhnya sudah digaungkan. Seruan itu mengajak rakyat agar jangan sampai terpaku pada akrobat figur-figur pasangan calon presiden dan wakil presiden sampai tidak memperhatikan betul-betul program yang sebenarnya mereka tawarkan. Sebab, partai politik pun tidak akan repot-repot memastikan programnya terlaksana jika hal itu tidak pernah dituntut oleh masyarakat.
Jika kemudian rakyat ternyata tidak sepeduli itu dan lebih memilih presiden karena menggemaskan dan berjanji akan mengenyangkan, hal itu menunjukkan bahwa cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa masih jauh dari tercapai. Rakyat tidak punya imajinasi tentang kehidupan yang sesungguhnya layak mereka dapatkan. Hak-hak mendasar, seperti air dan udara bersih, ruang publik yang aman dan nyaman, akses pendidikan dan kesehatan yang layak, dan kesetaraan gender yang semakin membaik, belum mengarus-utama. Hal inilah yang menyebabkan konten gemoy dan joget mudah merebut hati pengguna media sosial. Dengan kata lain, bukan TikTok-nya yang canggih, tapi kita-kita saja yang masih bodoh.
Argumen ini sekaligus juga menolak analisis yang menyatakan bahwa kemenangan Prabowo disebabkan oleh isu-isu seperti kemunduran demokrasi atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hanya laku di kalangan terdidik. Pemikiran seperti itu, selain elitis, juga berbahaya, karena seolah-olah menganggap urusan rakyat banyak hanyalah soal isi perut. Jika asumsi semacam itu terus terpelihara, pendidikan tidak akan pernah menjadi prioritas pembangunan manusia di Indonesia. Bukankah massa yang tidak terdidik akan selalu mudah dikibuli penguasa?
Banjir Konten Tumbuhkan Rasa Apati
Profesor di University of Melbourne, Australia, Vedi Hadiz, dalam salah satu wawancaranya, menyebut bahwa salah satu alasan rakyat kecil cenderung pasrah, menerima, dan tidak protes ketika diinjak-injak oligarki adalah karena itu realitas yang mereka alami sehari-hari. Mereka sudah terbiasa melihat hukum serta akses pendidikan dan kesehatan bisa dibeli dengan uang. Logika yang berlaku sangat neoliberal: kalau Anda tidak bisa mengakses hukum, pendidikan, dan kesehatan pada level yang sama, itu adalah salah Anda karena miskin.
Itulah mengapa kalau ada konten artis pamer harta atau orang kaya pamer kuasa di Instagram, yang muncul adalah komentar-komentar seperti “orang kaya, bebas dong”, “iri bilang, bos” dan sejenisnya. Kekayaan dianggap sebagai konsekuensi logis dari kerja keras para artis dan pengusaha. Mereka menganggap warganet (netizen) yang mau kaya juga harus ikut hustle culture (bekerja sekeras mungkin sampai melampaui batas kemampuan diri sendiri). Mereka yang mencoba berpikir kritis soal hal itu malah dilabeli sebagai SJW alias social justice warriors yang berkonotasi buruk.
Konten gemoy dan joget mudah merebut hati pengguna media sosial menunjukkan kalau bukan TikTok-nya yang canggih, tapi kita-kita saja yang masih bodoh. ~ Andina Dwifatma Share on XHal itu semakin diperparah dengan kecenderungan penguasa yang secara sangat sadar menjadikan media sosial sebagai pengacau perhatian masyarakat. Dengan memanfaatkan para buzzers (pendengung), pengguna media sosial dibanjiri banyak sekali isu yang berganti-ganti, sehingga tidak ada yang benar-benar sempat mengambil momen untuk mendeliberasi (mencerna) isu-isu yang penting bagi publik.
Keadaan itu tentu menumpulkan sensitivitas masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah. Rasa frustrasi berganti menjadi apati dan mereka yang punya uang lebih pun akhirnya memilih nge-twit atau pasang status seperlunya saja tentang politik, lalu sibuk perang tiket konser Coldplay atau iPhone terbaru. Dengan kata lain, impian demokrasi bahwa kelas menengah akan menjadi “pengeluh ulung” (professional complainers) yang menjalankan fungsi check-and-balance (mengontrol dan mengimbangi) pada kinerja pemerintah sepertinya jauh panggang dari api.
Karena itu, tidak perlu heran jika rakyat oke-oke saja dengan anak presiden yang mendadak maju menggantikan bapaknya—bukankah penguasa berarti bebas berbuat apa saja dan mereka yang menentang itu jangan-jangan cuma iri? Sekali lagi, media sosial hanya membantu mengamplifikasi kesadaran palsu yang turut melanggengkan ketidakadilan di masyarakat. Bibit ketidakpedulian (ignorance) dan keengganan berpikir kritis itu sudah ada dan sulit sekali perginya.
Sedikit Luapan Optimis
Saya minta maaf bila tulisan ini terkesan muram dan menumpulkan motivasi pembaca. Tetapi, yang kita hadapi ini sungguh merupakan perjuangan semesta yang tidak bisa diselesaikan dengan makan siang semata. Jalan keluarnya hanya satu: perbaikan yang serius di sektor pendidikan dan kesehatan. Rakyat yang pintar dan sehat akan mampu belajar, berefleksi, dan menuntut haknya sebagai warga negara. Harapannya, rakyat secara aktif bisa menjalankan fungsi check-and-balance yang jelas terhadap penguasa.
Dalam hal ini, ruang-ruang semacam Anotasi yang sedang Anda baca sekarang atau kerja jurnalistik macam Project Multatuli dapat menjadi contoh baik yang perlu didukung. Keberadaan internet dan platform media sosial dapat menjadi simpul (hub) pengetahuan dan kedalaman sudut pandang jika dikelola dengan baik dan didukung warga. Yang perlu menjadi catatan barangkali adalah seperti apa pesan itu dikemas. Selain memberi fakta dan informasi, kanal-kanal progresif perlu menyertakan call-to-action yang jelas pada audiens. Lebih bagus lagi jika melibatkan para figur publik yang disukai rakyat—itu pun kalau belum keburu direkrut menjadi buzzers.

Andina Dwifatma adalah Kandidat Doktor di Faculty of Arts, Monash University, Australia. Minat penelitiannya meliputi kajian media, gender, dan Islam di ranah digital. Esai-esainya telah terbit di berbagai publikasi di Indonesia, termasuk The Jakarta Post, Tirto, The Conversation, dan Kumparan. Selain meneliti dan mengajar, Andina juga menulis karya sastra. Novel terbarunya, “Lebih Senyap dari Bisikan”, terpilih sebagai “Buku Sastra Pilihan Tempo 2021 Kategori Prosa”. Andina saat ini bekerja sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Artikel Terkait
Matinya Cendekiawan Kampus
Kaum terpelajar menjadi anak tiri dengan berbagai macam tekanan yang lahir dari struktur opresif negara. Negeri ini lahir dari rahim kaum terpelajar. Namun, negeri ini seperti dibesarkan oleh kultur kekerasan yang sangat kuat dan cendekiawan dicurigai sebagai kelompok yang akan merubah status quo kekuasaan. Apakah memang negeri ini bukan tempat yang nyaman bagi para kaum terpelajar?Selamat Hari Pers Nasional, Ricky!
Terlepas dari wacana mana yang lebih dominan, perayaan hari pers nasional selalu terasa jauh dan asing serta tidak dekat dengan kita sebagai masyarakat biasa.Membayangkan Demokrasi di Indonesia: Trauma Kolektif dan Toleransi
Lirik lagu Mars Pemilu 2019 mencerminkan semangat demokrasi modern Indonesia dengan lugas hanya dalam sembilan baris singkat. Lagu ini menggarisbawahi pentingnya hak pilih rakyat bagi keberlangsungan negara Republik Indonesia sebagai negara demokrasi muda yang hampir berusia 74 tahun. Lalu bagaimana keadaan demokrasi Indonesia saat ini?