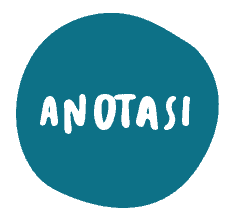Politisi Budiman Sudjatmiko telah mengumumkan rencana membangun Bukit Algoritma di Sukabumi, Jawa Barat. Dia mengharapkan kawasan tersebut kelak bisa menjadi “rumah” bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi seperti Silicon Valley di Amerika Serikat. Rencana senilai 18 triliun itu langsung menuai perdebatan. Sebagian pihak tentu menyambut berita ini dengan gembira, karena menganggapnya sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, sebagian lainnya justru mempertanyakan kesiapan ekosistem di tanah air, khususnya sumber daya manusia. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyuarakan kecurigaan banyak orang saat meminta proyek itu tidak jadi sekadar gimmick.
Dalam tulisan ini, saya tidak bermaksud membahas peluang atau tantangan proyek tersebut. Saya juga tidak akan menganalisa perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Justru, saya akan berfokus pada perspektif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kehadiran teknologi digital di masyarakat. Tulisan ini bermaksud membedah euforia digital dan mengungkap hal-hal yang biasanya disembunyikan dalam narasi ini.
Ketika frasa ‘Silicon Valley’ disebut, sepertinya kita langsung bisa menebak arah percakapan tersebut. Kebanyakan orang akan mengaitkannya dengan kemajuan teknologi dan dominasi ekonomi oleh Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Facebook, dan Amazon. Tidak dapat dipungkiri, lima perusahaan itu memang terkenal akan asetnya. Menurut studi the Digital Commonwealth, di tahun 2018, total keuntungan yang dihasilkan lima perusahaan ini bahkan sudah lebih besar dari pendapatan perkapita 90 persen dari negara-negara di dunia.
Di Indonesia, Presiden Joko Widodo sendiri nampaknya sedang getol mengampanyekan ekonomi 4.0. Hal ini tentunya didukung dengan kemunculan beberapa perusahaan berbasis digital, seperti Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Ketiganya kemudian berkembang menjadi perusahaan digital unicorn (tingkatan bisnis startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari US$1 miliar). Selain itu, ada pula Go-Jek yang sudah tumbuh jadi perusahaan decacorn (perusahaan yang mempunyai nilai valuasi sebesar US$10 miliar) pertama di Indonesia. Pada beberapa kesempatan, Presiden Jokowi pun nampak secara rutin mempromosikan keberhasilan ini. Seperti saat beliau menghadiri KTT ASEAN ke-37 dan Hannover Messe di Jerman. Selain itu, Presiden Jokowi juga sering menekankan pentingnya kecakapan digital sebagai kunci pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Narasi yang sama juga digunakan oleh Budiman Sudjatmiko ketika beliau memaparkan rencana pembangunan Bukit Algoritma. Dalam wawancara dengan TEMPO, Budiman mengatakan bahwa lahan Cikidang akan dimanfaatkan untuk pengembangan kecerdasan buatan, nanoteknologi, bioteknologi, semi-konduktor dan energy storage. Sementara dalam wawancara bersama Asumsi, Budiman menggambarkan bukit itu sebagai “tempat di mana masalah-masalah alam dan sosial akan dipecahkan lewat matematika, komputer, ilmu pengetahuan, dan filsafat.” Ini adalah klaim luar biasa dan perlu kita teliti lebih dalam.
Selain melupakan kesenjangan akses internet yang ada di Indonesia, techno-solutionism juga seringkali membuat kita lupa akan masalah sebenarnya. ~Rio Tuasikal Share on XJanji 4.0
Yang penting untuk dicatat dari narasi Silicon Valley adalah pernyataan bahwa kehadiran perusahaan teknologi, dan bahwa teknologi itu sendiri, akan membawa perubahan sosial. Kemunculan pasar digital seperti Amazon, diharapkan mampu membuka jalan bagi pengusaha kecil untuk menjangkau konsumen global. Hal tersebut bisa mereka lakukan dengan mudah, tanpa perlu memiliki toko fisik. Sementara itu, Facebook juga menyediakan lapak beriklan yang murah. Iklan-iklan ini nantinya bisa langsung diarahkan ke target pasar sesuai dengan jejak digital pengguna. Optimisme Silicon Valley ini terangkum dalam pernyataan Eric Schmidt, “If we get this right, I believe we can fix all the world’s problems (Kalau kita melakukannya dengan benar, saya percaya kita mampu menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia).”
Cara pandang serupa juga muncul di Indonesia. Gojek, misalnya, yang selalu menekankan dampaknya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia. Perusahaan tersebut mengklaim sudah berkontribusi senilai 44 triliun Rupiah per akhir 2018. Selain Gojek, ada juga RuangGuru yang menyatakan misinya adalah untuk “menyediakan dan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas melalui teknologi.” Narasi ini seolah-olah menyatakan bahwa kesenjangan pendidikan akibat kemiskinan dapat diselesaikan dengan kehadiran aplikasi, coding, atau algoritma yang tepat.
Ketika membicarakan ‘big tech company’, kita cenderung mengesampingkan dampak-dampak tersembunyi dari kehadiran perusahaan tersebut. Amazon, misalnya, yang memfasilitasi Jeff Bezos jadi orang terkaya dalam sejarah peradaban manusia, sementara ribuan pekerja gudang Amazon bekerja dalam situasi rentan dan dilarang berserikat. Contoh lainnya adalah Facebook, yang membocorkan data pribadi penggunanya. Tidak hanya itu, pada 2014, Facebook juga dituding melakukan eksperimen psikologi terhadap hampir 700 ribu orang tanpa sepengetahuan mereka.
Di Indonesia sendiri, Gojek sang decacorn kebanggaan tumbuh pesat di atas status rentan para pengemudinya. Dengan memberikan status ‘mitra’, Gojek seakan melepaskan diri dari kewajiban untuk memberikan gaji tetap, tunjangan, dan hak-hak lain yang dijamin dalam UU Ketenagakerjaan. Di sisi lain, janji RuangGuru untuk memperluas akses pendidikan juga dengan ironisnya melupakan fakta kesenjangan ekonomi dan keterbatasan akses digital. Dengan membuat aplikasi berbasis Android atau iOS, RuangGuru tentu hanya tersedia bagi siswa yang memiliki komputer, telepon pintar, dan akses internet. Aplikasi digital tersebut tentu tidak dapat dijangkau oleh mereka yang gaji bulanannya hanya cukup untuk makan sehari-hari, tidak mampu membeli ponsel Android, atau tidak memiliki akses internet karena keterbatasan finansial. Alih-alih memperluas akses, RuangGuru justru memperluas kesenjangan pendidikan.
Jangan Terkecoh Techno-Solutionism
Semangat perusahaan teknologi untuk menawarkan perubahan sosial, namun melupakan masalah yang sudah ada di masyarakat, disebut oleh pengamat politik dan teknologi, Evgeny Morozov, sebagai techno-solutionism. Dalam bukunya To Save Everything, Click Here, Morozov mengkritik klaim Silicon Valley yang seolah-olah jadi solusi bagi berbagai masalah dunia. Padahal, solusi yang mereka tawarkan tersebut justru mengabaikan masalah yang sudah ada di masyarakat.
Paradigma techno-solutionism ini sangatlah berbahaya, khususnya karena tersembunyi dalam semangat ekonomi digital. Selain melupakan kesenjangan akses internet yang ada di Indonesia, techno-solutionism juga seringkali membuat kita lupa akan masalah sebenarnya.
Pengaburan masalah dengan menggunakan teknologi ini pernah terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Pada tahun 2017, nelayan setempat mengeluh hasil tangkapannya berkurang. Di saat yang sama, warga setempat juga khawatir pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang saat itu sedang berlangsung akan mengganggu mata pencaharian mereka sebagai nelayan.
Sayangnya, bukannya menyelesaikan masalah yang ada, Gubernur Ridwan Kamil justru memperkenalkan aplikasi nelayan smartfishing.com pada 2018 dan Laut Nusantara pada 2019. Kedua aplikasi ini memang dapat membantu nelayan mencari ikan lewat satelit. Tapi kita patut bertanya, apakah hasil tangkapan berkurang karena nelayan yang tidak bisa mencari ikan, atau apakah ikan yang memang menghilang karena faktor lain?
Aplikasi nelayan itu kini tidak terdengar lagi suaranya. Yang jelas, pada 2020, organisasi lingkungan WALHI melaporkan jaring nelayan Indramayu sering rusak. Hal ini diduga disebabkan oleh kapal tongkang pengangkut batu bara yang hilir mudik di daerah penangkapan. Akibatnya, warga Indramayu dan Cirebon menggugat PLTU itu ke pengadilan. Sayangnya, semua masalah ini nampaknya kalah oleh hingar bingar aplikasi nelayan.
Jangan sampai kita terbuai oleh ilusi kemajuan yang ditawarkan teknologi, dan melupakan masalah kesenjangan yang masih harus diselesaikan. ~Rio Tuasikal Share on XIlusi 4.0
Kisah tersebut menjadi ilustrasi bagaimana daya pikat teknologi dapat mengaburkan, bahkan menyembunyikan, masalah sebenarnya. Amazon menjadi bukti bahwa, ketika pemerintah tidak mampu menjamin hak-hak pekerja, kehadiran teknologi justru hanya akan memfasilitasi ketamakan para pemegang kuasa. Selain itu, RuangGuru juga menunjukkan bahwa akses teknologi memiliki batasan dan tidak selalu dapat dinikmati semua orang.
Apabila pemerintah berencana untuk membangun Bukit Algoritma, pembangunan macam apa yang diharapkan? Jika sampai sekarang pemerintah masih belum mampu menjamin hak-hak pekerja, saya rasa pembangunan Bukit Algoritma hanya akan meneruskan eksploitasi pekerja. Selain itu, jika pemerintah juga belum bisa mengatasi kesenjangan ekonomi dan pendidikan, Bukit Algoritma hanya akan melayani konglomerat yang haus keuntungan. Tanpa membicarakan koneksi internet yang jomplang, Bukit Algoritma hanya akan menguntungkan segelintir orang.
Tidak dapat dipungkiri, perusahaan berbasis teknologi memang dapat membawa kemakmuran, asalkan diregulasi dengan baik. Selain itu, janji-janji dari perusahaan teknologi perlu dibuktikan dengan pertumbuhan yang adil bagi semua pihak. Terakhir, jangan sampai kita terbuai oleh ilusi kemajuan yang ditawarkan teknologi, dan melupakan masalah kesenjangan yang masih harus diselesaikan.
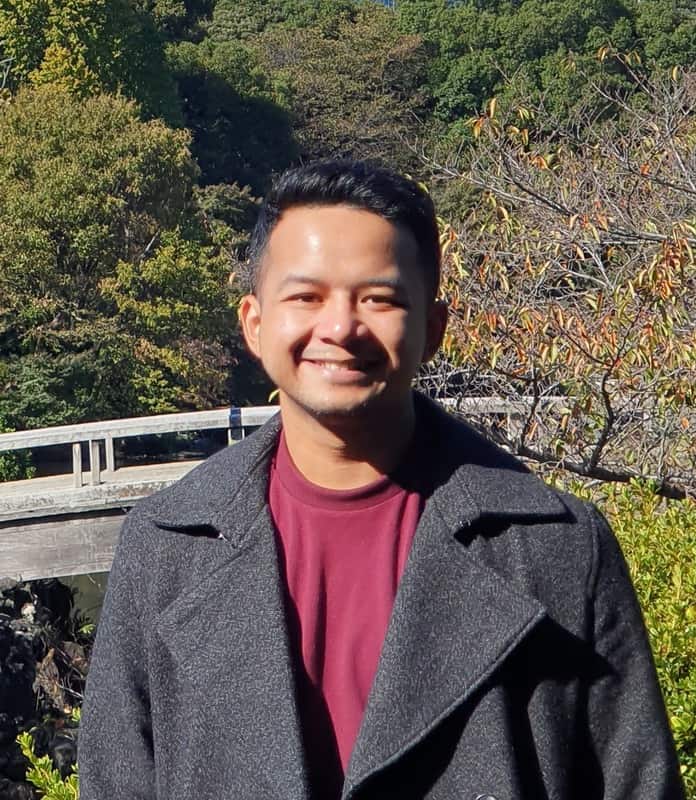
Rio Tuasikal tengah menyelesaikan studi MA Media and Communications di Goldsmiths, University of London, Inggris. Sebelumnya dia bekerja sebagai jurnalis selama 6 tahun bagi Kantor Berita Radio (KBR) dan Voice of America (VOA), meliput dari Indonesia dan Amerika Serikat. Sebagai pewarta, dia fokus memberitakan isu-isu kelompok minoritas, kesenjangan, dan hak asasi manusia.
Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini