Kehendak bebas banyak diamini sebagai konsep tanpa celah dan tak terbantahkan. Namun, bagi Robert Sapolsky, seorang akademisi asal Amerika Serikat, kehendak bebas adalah ilusi, kebohongan belaka yang dengan masifnya menipu manusia.
Konsep yang menjadi lawan bagi kehendak bebas adalah determinisme. Determinisme menekankan bahwa hidup dan jalannya kehidupan adalah suatu konsekuensi dari sebuah keharusan yang tak terelakkan.
Konsep determinisme bukanlah hal baru. Materialisme historis yang digagas filsuf terkemuka Karl Marx, misalnya, menyatakan bahwa determinisme dipengaruhi oleh kondisi material dan hubungan produksi yang kemudian menentukan struktur sosial, politik, dan budaya suatu masyarakat.
Ada pula determinisme teologis atau sering disebut sebagai konsep predestinasi, sebuah kepercayaan yang meyakini bahwa nasib setiap individu, bahkan segala hal yang terjadi di alam semesta ini, telah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi, terdapat beberapa inkonsistensi internal dalam determinisme teologis sehingga sering memunculkan perdebatan.
Robert Sapolsky sebagai profesor biologi, neurologi, dan bedah saraf pun memberikan alternatif penjelasan lain mengenai determinisme yang sangat menarik dalam bukunya yang berjudul Determined: A Science of Life Without Free Will.
Kita Tidak Pernah Bebas, Bahkan Sejak dalam Niat
Manusia kerap kali merasa spesial dengan mengategorikan diri sebagai spesies yang memiliki kesadaran pada pengalaman subjektif yang penuh kesadaran (consciousness). Namun, konsep itu sangatlah bermasalah dan tidak memiliki bukti. Sebaliknya, tindakan kita yang sepenuhnya di luar apa yang kita sebut kesadaran justru didukung oleh temuan yang kuat.
Benjamin Libet, seorang ahli neurosains, melakukan studi provokatif pada 1983. Ia melakukan eksperimen sederhana, dimana subjek diminta mencatat saat mereka merasa ingin bergerak, sementara aktivitas otak mereka diukur menggunakan elektroensefalogram (tes untuk mengukur aktivitas listrik otak/EEG) untuk mendeteksi apa yang disebut ‘readiness potential’ (potensi kesiapan). Libet menemukan bahwa otak mulai mempersiapkan gerakan sekitar 300 milidetik sebelum subjek menyadari keinginan tersebut.

Mengacu pada studi Libet itu, kesadaran menjadi sekadar rekonstruksi atau narasi yang dibuat oleh otak untuk memberikan ilusi kontrol. Kesadaran hanya muncul sebagai semacam ‘komentar naratif’ setelah proses ‘pra-sadar’ sudah berjalan.
Artinya, jika kesadaran sebagai elemen paling penting dalam mencetuskan niat saja adalah ilusi, maka dampaknya linear (sejalan) dengan proses konstruksi niat. Singkatnya, kita tidak memiliki kebebasan, tidak juga kontrol terhadap niat. Itu relevan dengan yang dikatakan oleh Sapolsky, “We are never free to intend what we intend” yang artinya “kita tidak benar-benar bebas menentukan apa yang kita mau.
Kita Tidak Muncul dari Kehampaan
Jika kita tidak memiliki kebebasan terhadap niat, lalu dari mana niat, atau lebih jauh lagi, dari mana tindakan muncul? Berangkat dari hal itu, Sapolsky menjelaskan mengenai ‘waktu sebelum’ dimana kita tercipta dari lapisan-lapisan sejarah.
Lapisan pertama, detik hingga menit sebelum tindakan, dipengaruhi oleh rangsangan indrawi. Aroma yang kita hirup, objek yang kita lihat (bersama asosiasi atau kemelekatan yang menyertainya), atau apakah sesuatu tampak indah atau menjijikkan: semuanya memengaruhi respons kita.
Lapisan kedua, menit hingga jam sebelum tindakan, melibatkan kondisi fisiologis dan emosional. Sapolsky menyoroti peran hormon seperti testosteron, oksitosin, dan glukokortikoid. Pada lapisan ketiga, minggu hingga tahun sebelum tindakan, tindakan kita berkaitan dengan neuroplastisitas, yakni kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi dalam struktur dan fungsi sebagai respons terhadap pengalaman, pembelajaran, atau cedera.
Lapisan berikutnya mencakup masa remaja, masa kanak-kanak, kondisi dalam kandungan, DNA, hingga warisan leluhur yang membentuk dasar perilaku kita. Semua lapisan itu saling berhubungan dan berperan dalam membentuk tindakan kita saat ini.
Sebagai contoh, saat seseorang memilih es krim vanilla, alih-alih stroberi, untuk menyegarkan tenggorokan di bawah terik matahari, atau justru sebelum itu, saat seseorang lebih memilih untuk memakan es krim, alih-alih air, untuk menghilangkan dahaga, bukan ditentukan pada tindakan saat itu, bukan dari kehampaan belaka, juga bukan didasarkan pada kehendak bebas. Namun, tindakan tersebut sudah ditentukan detik hingga menit, menit hingga jam, minggu hingga tahun, atau mungkin ratusan ribu tahun sebelumnya.
Semua Terbungkus dalam Kebohongan tentang Dunia yang Adil
Memercayai eksistensi kehendak bebas sering dikaitkan dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menentukan nasib mereka, seolah-olah hidup berjalan di atas prinsip keadilan sempurna. Namun, jika kita melihat dari perspektif bahwa manusia lahir dengan perbedaan bawaan, keyakinan ini menjadi bermasalah.
Di dalam bukunya, Robert Sapolsky menunjukkan bahwa faktor-faktor, seperti struktur otak, kadar hormon, dan pengalaman awal kehidupan sangat memengaruhi perilaku dan keputusan seseorang. Dengan kata lain, apa yang tampak sebagai ‘pilihan bebas’ sering kali merupakan hasil dari determinan biologis dan sosial yang bekerja di balik layar.
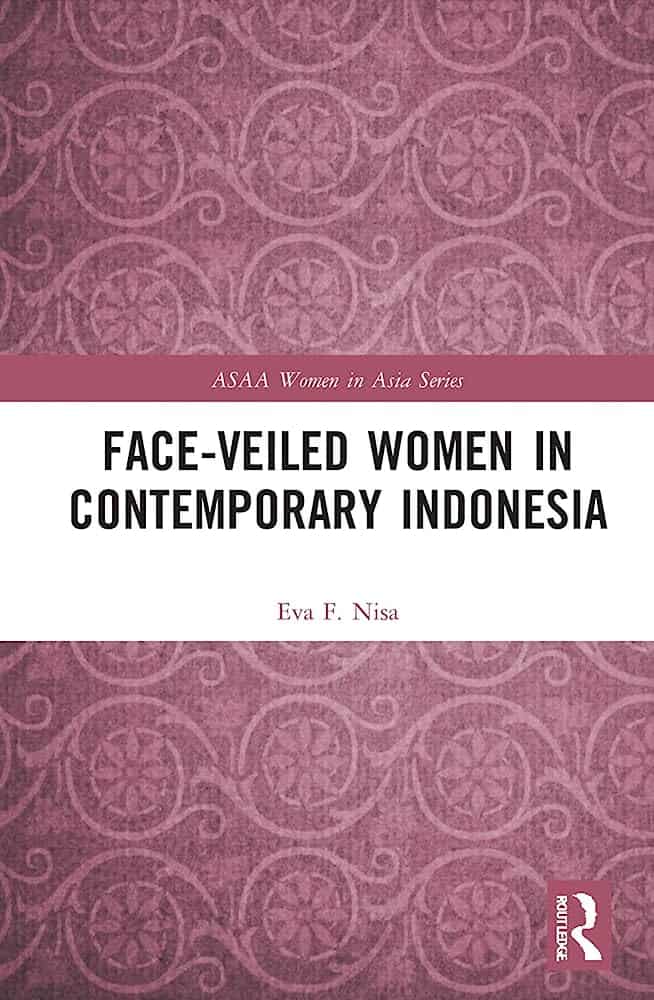
Ketika kita percaya bahwa semua orang memiliki kehendak bebas, kita cenderung menghakimi mereka yang ‘gagal’ sebagai manusia yang kurang usaha atau motivasi, tanpa menyadari bahwa mereka mungkin dibatasi oleh kondisi yang tidak mereka pilih sejak lahir. Hal itu mengukuhkan ketidakadilan struktural, karena menutupi perbedaan awal tersebut di balik ilusi mengenai keberhasilan yang sepenuhnya bergantung pada usaha individu.
Hukuman untuk Keadilan atau Kepuasan?
Jika kehendak bebas tidak ada, maka sistem penghukuman konvensional terhadap kejahatan menjadi tidak relevan, karena tindakan manusia tidak berasal dari pilihan sadar, melainkan hasil dari pengaruh biologis dan lingkungan.
Bagi Sapolsky, hukuman, dari waktu ke waktu, terus dijalankan seolah keadilan telah ditegakkan. Namun, objektivitas, keberpihakan, tingkat relevansi, dan fakta ilmiah kerap kali dikesampingkan. Selain itu, hukuman cenderung tidak hadir untuk menciptakan rasa keadilan, tapi justru kepuasan atas keinginan balas dendam, karena saat menyaksikan orang dihukum, otak mengaktifkan sirkuit dopamin yang memunculkan rasa senang.
Di sisi lain, hukuman dengan berbagai bentuk reformasinya, dari yang penuh kerumunan dan kekerasan hingga yang dilakukan dengan ‘lebih manusiawi’, pada intinya tetap memiliki kesamaan, yaitu merupakan bagian dari sentralisasi kekuasaan dan legitimasi negara.
Karantina Medis: Sebuah Alternatif
Ada dua pendekatan dalam amatan Sapolsky yang, meskipun masih menerima premis kehendak bebas, setidaknya menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang memikirkan dengan serius alternatif radikal terhadap kejahatan, seperti terbentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta gagasan keadilan restoratif. Hanya saja, dua model inisiatif tersebut masih sering terjebak pada bias. Baginya, alternatif yang paling masuk akal adalah karantina medis.
Kejahatan, bagi Sapolsky, sama seperti penyakit medis lainnya. Adapun adaptasinya ke dalam kriminologi, Sapolsky mengacu pada pemikiran Derk Pereboom, yang berpendapat bahwa orang berbahaya muncul karena masalah seperti kontrol impuls, kecenderungan kekerasan, atau ketidakmampuan berempati.
[bctt tweet=”Ketika kita percaya bahwa semua orang memiliki kehendak bebas, kita cenderung menghakimi mereka yang ‘gagal’ sebagai manusia yang kurang usaha atau motivasi, tanpa menyadari bahwa mereka mungkin dibatasi oleh kondisi yang tidak mereka pilih sejak lahir ~ Amina Gaylene”]
Jika kita benar-benar menerima bahwa kehendak bebas adalah tidak ada, maka kejahatan bukanlah kesalahan mereka, melainkan hasil dari gen, kehidupan janin, kadar hormon, dan sifat biologis mereka. Namun demikian, publik tetap perlu dilindungi dari hal-hal yang merugikan.
Dalam model karantina medis, pelaku kejahatan akan dibebaskan dan dikembalikan ke masyarakat setelah memenuhi kriteria tertentu. Namun, mereka akan tetap dikarantina selama dianggap sebagai ancaman.
Sapolsky tidak memiliki ilusi bahwa karantina medis ini akan memengaruhi sistem peradilan pidana. Namun, ia yakin pendekatan ini merupakan cara radikal dan baru untuk mengatasi kriminal bagi kita yang tidak memiliki kehendak bebas.

Amina Gaylene adalah penulis asal Cianjur yang menyukai tempe goreng ketumbar dan bulan.




