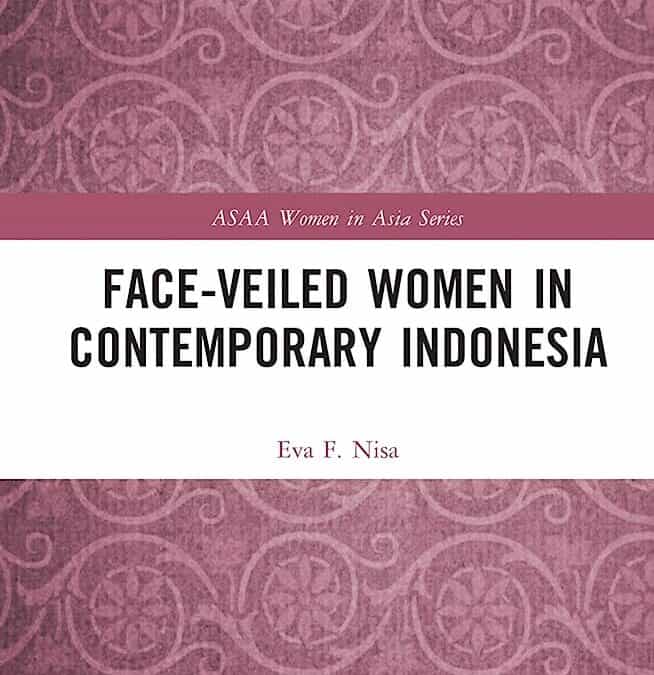Nasib Pekerja Akademik di Kabupaten
June 20, 2023
Ketika Nakes Melawan dan Alasan Perlunya Menunda RUU Kesehatan
June 30, 2023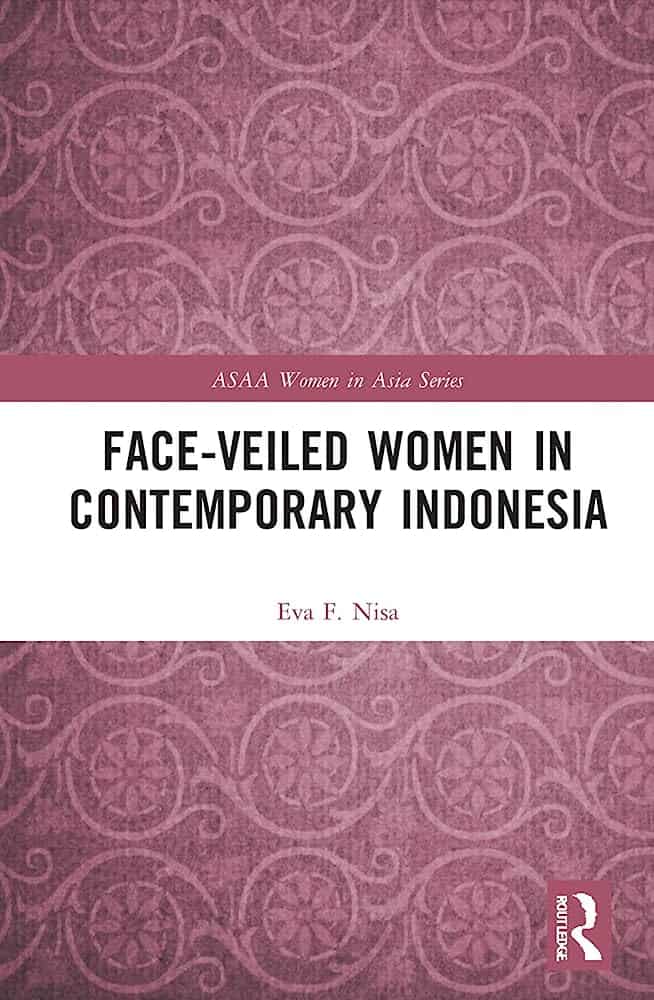
RESENSI BUKU
Habitus dan Agensi Ketaatan dalam Kelompok Muslimah Bercadar
oleh Izmy Khumairoh
Dinamika fenomena agama yang terjadi di kalangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari berbagai peristiwa yang muncul dan memengaruhi kehidupan sehari-hari. Terkait praktik pemakaian jilbab di kalangan Muslimah, preferensi individu tidak dapat dimaknai sebagai bentuk ketaatan Muslimah dalam menutup auratnya belaka.
Kita cukup sering mendengar argumen feminis barat dan liberal tentang penggunaan jilbab: bahwa keputusan perempuan Islam untuk berjilbab sebenarnya dilandasi oleh kesadaran palsu dan merupakan bentuk representasi subordinasi serta opresi oleh rezim patriarkal Islam.
Dalam bukunya yang berjudul Face-veiled Women in Contemporary Indonesia, Eva F. Nisa menawarkan sudut pandang lain mengenai pilihan pemakaian cadar lewat studi kasus pada kelompok Jama’at Tabligh dan Salafi di Indonesia. Alih-alih ‘meliyankan’ pilihan para Muslimah yang memiliki ekspresi beragama berbeda ataupun non-konvensional (dengan bercadar), sikap tersebut justru dapat dikategorikan sebagai bentuk agensi Muslimah dalam menggunakan kapasitasnya untuk menginterpretasikan teks agama guna bermobilisasi di ruang publik.
Otoritas Keagamaan dan Pendisiplinan Tubuh
Bersandar pada gagasan bahwa Islam memiliki praktik non-monolitik, Eva berargumen bahwa kemunculan ragam cara pandang dalam pemahaman ajaran agama menjadi tak terhindarkan. Dengan menggunakan kacamata sosio-kultural, perbedaan preferensi cara menutup aurat dipandang bukan sebagai anomali, melainkan gejala umum yang menunjukan bahwa setiap individu memiliki cara sendiri-sendiri dalam menginternalisasi nilai yang berlaku serta mewujudkannya dalam bentuk perilaku tertentu.
Eva menekankan bahwa hasil penerjemahan atas normativitas praktik bercadar dapat dibaca melalui gagasan ‘teknik tubuh’ ala Marcel Mauss, seorang Sosiolog asal Prancis. Mauss menekankan bahwa tiap perilaku dan gerak fisik yang dimiliki oleh individu adalah bagian dari hasil enkulturasi. Dengan demikian, praktik bercadar dapat dianggap sebagai hasil pembiasaan individu atas norma dan aturan yang hidup di lingkungan sekitar lewat pengaturan tampilan fisik.
Perwujudan adaptasi atas tatanan sosial yang menubuh ini berevolusi menjadi aneka habitus atau yang dimaksud oleh Pierre Bourdieu sebagai rangkaian perilaku yang dihasilkan atas sosialisasi. Habitus ketaatan Muslimah Indonesia lantas berdinamika dan berubah seiring waktu, sebagai contoh: cadar berkearifan lokal Rimpu Mpida yang digunakan perempuan Bima tradisional, penggunaan kerudung (penutup kepala longgar) oleh perempuan pasca naik haji di era kolonialisme, hingga pemakaian jilbab (penutup kepala ketat) di kalangan pelajar sebagai simbol perjuangan kebangkitan Islam di Indonesia era pasca Orde Baru.
Jama’at Tabligh dan Salafi merupakan kelompok Islam dari luar Nusantara yang dianggap sebagai subkultur karena memiliki misi kontradiktif dengan kelompok Islam arus utama, yaitu membawa agenda pemurnian Islam.
Kelompok Jama’at Tabligh lahir di Asia Selatan. Misi pemurnian mereka didukung oleh aspirasi untuk mensterilisasi ajaran Islam yang telah terkontaminasi nilai-nilai Hinduisme. Pembuatan jarak ini merupakan upaya untuk mendiferensiasi diri dengan kelompok Islam arus utama di Indonesia yang dianggap telah ‘rusak’, yang salah satu indikasinya adalah mengalami kemerosotan (dekadensi) akidah lewat penampilan yang menyerupai masyarakat Arab sebelum Islam.
Kehadiran ajaran Islam lain dengan daya otoritatif lebih besar berpotensi memicu lahirnya subjektivitas beragama yang berbeda dan mengganti nilai ajaran lampau yang terlanjur terinternalisasi sejak dini di lingkungan keluarga. Konsep ‘kode moral’ yang digagas oleh Michel Foucault, seorang filsuf asal Prancis, dapat menjelaskan peristiwa tersebut sebagai pelekatan seperangkat nilai dan tindakan baru melalui hak prerogatif sosok yang lebih superior.
Akibatnya, tokoh agama tertentu merasa memiliki legitimasi penuh untuk mendorong perempuan menerapkan cara hidup Islami secara harfiah demi mencapai impian sebagai Muslimah sejati. Dalam prosesnya, pengadopsian cara beragama yang baru kerap mengalami gesekan dengan pemangku otoritas lama. Contohnya, muncul kekhawatiran orangtua akan pilihan anak perempuan mereka yang memilih bercadar, sebagaimana fenomena resistensi penggunaan jilbab yang terjadi di tahun 1980an.
Adab berpakaian dalam keseharian menjadi salah satu kode moral yang harus diperhatikan oleh kedua kelompok yang diteliti, baik bagi perempuan maupun laki-laki (misalnya, penggunaan celana di atas mata kaki oleh laki-laki Salafi). Meski demikian, tekanan lebih besar ditujukan kepada perempuan, karena berbusana Muslimah sesuai syariat dianggap dapat menghindari fitnah.
Konstruksi tubuh perempuan dalam ajaran Islam memang kerap digambarkan sebagai pintu gerbang menuju zina dan sumber ancaman yang dapat mengganggu stabilitas religiusitas lawan jenis, terlebih dalam bentuk tatapan, sebagaimana yang termuat dalam Q.S. An-Nur Ayat 30–31. Hal itu memunculkan keyakinan bahwa pemakaian cadar (terutama bagi kelompok Salafi), yang banyak dipromosikan oleh tokoh agama secara hegemonik, dapat menekan daya interpretasi individu perempuan terhadap keberadaan ayat-ayat terkait pendisiplinan tubuh.
Agensi Perempuan Muslim: Bercadar Tak Berarti Teropresi
Eva berargumen bahwa perempuan yang memilih rasa patuh dan berdamai dengan konfigurasi sosial yang berlaku juga merupakan bentuk agensi, meskipun kepatuhan tersebut mengandung watak penindasan atau tidak sesuai dengan ekspektasi feminisme. Hal ini turut disuarakan oleh salah satu respondennya yang mengaku bahwa dengan bercadar ia sedang menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan diri sendiri lewat aktualisasi diri sebagai khalifah di muka bumi.
Tidak hanya dalam berpenampilan, usaha untuk menjadi seorang yang puritan turut terejawantahkan dalam tindakan gaya hidup halal, seperti preferensi jenis olahraga (berkuda dan memanah) dan menghindari ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan non-mahram) di area publik.
Nilai-nilai ajaran agama yang diimplementasikan secara holistik itu nyatanya tidak membatasi ruang gerak Muslimah bercadar di dunia nyata maupun di dunia maya. Keberadaan media sosial justru membantu menggemakan gagasan visualisasi tentang bercadar yang sebelumnya telah diinisiasi oleh media populer lain, seperti film dan buku. Ruang siber menjadi area perpanjangan diseminasi ajaran pemurnian agama bagi kedua kelompok serta menjadi kendaraan dalam upaya menormalisasi penggunaan cadar, utamanya pasca aksi terorisme di Indonesia. Meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat mengeluarkan fatwa terkait pembatasan aktivitas dalam media sosial, internet nyatanya menjadi sarana pengkajian ajaran agama yang dianggap aman bagi perempuan serta medium demonstrasi ekspresi beragama. Contohnya adalah eksistensi Niqab Squad di Instagram yang diyakini sebagai bentuk agensi ketaatan.
Ketika internet dan media sosial menawarkan kebebasan, ketersediaan ruang privilese bagi perempuan bercadar di dunia nyata pun berkembang. Contoh aktualnya ada dalam institusi pendidikan. Jenjang perkuliahan menjadi periode krusial dalam pengenalan gerakan revivalis bagi mahasiswi, terlebih bagi mereka yang berasal dari lingkungan keluarga dengan fondasi keagamaan yang tidak ketat. Universitas tidak hanya menjadi wadah pengajaran, tapi juga sarana penggalian pengalaman lain dengan lingkup interaksi yang lebih luas. Hal ini lantas memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan pencarian doktrin agama yang mampu memberikan nilai kepastian dan pedoman yang lebih lugas.
Implikasinya, mahasiswi dari rumpun keilmuan yang dominan mampu mengasah rasionalitas, validitas dan logika dengan mudah bergabung dengan kelompok Salafi karena memiliki personalitas dan prinsip yang komplementer. Momentum hijrah dirayakan sebagai bentuk hidayah yang menandakan modernitas alih-alih konservatisme, utamanya dengan menanggalkan pengalaman keislaman yang lama dan memilih gaya beragama baru, salah satunya dengan bercadar. Meskipun demikian, patut dicatat bahwa maraknya fenomena mahasiswi bercadar mengalami beberapa penolakan dari civitas akademika karena cadar dianggap menghambat proses komunikasi antara dosen dan mahasiswi.
Hal itu berbeda dengan institusi pendidikan berbasis keagamaan. Pesantren, misalnya, memiliki sistem operasi yang sangat kental dengan ciri dan sifat khas ‘institusi total’ ala Erving Goffman, seorang Sosiolog asal Amerika Serikat. Seluruh individu dalam lingkungan pesantren mengalami homogenisasi dan dikondisikan untuk menganut ideologi yang sama lewat tahapan resosialisasi norma dan nilai baru, utamanya terkait citra ideal seorang Muslimah sejati.
Meminjam ide Michel Foucault, bentuk kehidupan dalam pesantren bagaikan panoptikon: sulit bagi siswi untuk menghindari sensor pengawasan, apalagi memilih cara beragama yang berbeda. Sifat pesantren yang mengisolir penghuni dari dunia eksternal serta memiliki tata tertib yang mengikat menjadi salah satu faktor resosialisasi dapat berjalan lancar tanpa perlawanan.
Hal ini selaras dengan pernyataan Saba Mahmood, Antropolog asal Pakistan, tentang subjektivitas kesalehan yang tampak sebagai agensi dan sikap taat, meskipun dalam bayang-bayang orang lain, yaitu otoritas tokoh pesantren dan orangtua. Dampaknya adalah siswi yang belum matang dan mengerti esensi bercadar hanya patuh terhadap aturan berbusana demi mengikuti ‘aturan main’ yang ada.
Visibilitas perempuan bercadar di arena non-domestik juga dapat ditemukan dalam kegiatan keagamaan, khususnya dalam kelompok Salafi. Perempuan diperkenankan terlibat dalam agenda dakwah dan memimpin ta’lim dengan syarat memiliki bekal pengetahuan agama yang mumpuni serta pembabaran dilakukan tanpa nada otoritatif. Selain itu, syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah memegang prinsip ikhtilat serta menjaga kejernihan motivasi berdakwah dan menjaga martabat kelompok.
Perbedaan cara berdakwah yang signifikan antara sesama perempuan bercadar lintas kelompok keagamaan didasari oleh pemaknaan nilai ketaatan yang berbeda. Sebagai contoh kasus, Niqab Squad menggunakan media sosial sebagai alat agar suara perempuan bercadar lebih didengar, sedangkan kelompok lain merasa cara tersebut telah melanggar ajaran (dianggap ikhtilat).
Meskipun demikian, bentuk partisipasi perempuan aktif berdakwah sekaligus menunaikan habitus ketaatan sukses menantang stereotipe perempuan bercadar bahwa mereka terkurung dan tertindas. Apa yang dilakukan para Muslimah bercadar justru menunjukkan fenomena ‘kesalehan publik’, membuat sosok-sosok perempuan yang ‘tak terlihat’ menjadi ‘terlihat’ meski di ruang gender yang terbatas.
Menantang Stigma Muslimah Bercadar
Dalam buku ini, Eva telah secara cermat mengupas kompleksitas kesalehan perempuan dan agensi dalam koridor agama serta keseharian Muslimah bercadar.
Pada mulanya, tampak sukar untuk memaknai cadar tanpa mengasosiasikannya dengan berbagai label dan stigma yang terlanjur melekat pada mereka, seperti cadar sebagai produk Arabisasi, pengantin jihad, lambang represi, dan lain-lain. Namun, Eva mendorong pembaca untuk melihat realita dari sisi seberang: bahwa bercadar tidak ada bedanya dengan bentuk kebiasaan lain yang merupakan buah dari cara individu memahami etika dan nilai moral yang hidup di sekitarnya.
Hasil penelitian Eva menjadi jawaban atas absennya wacana tentang habitus dan agensi ketaatan dari diskusi tentang perempuan Muslim. Hal itu dimotivasi oleh kekhawatiran bahwa perjuangan untuk mengangkat citra Islam sebagai agama yang anti-diskriminatif akan sia-sia jika tidak turut menimbang aspek agentif dari praktik bercadar. Hal ini dapat diantisipasi dengan menaruh konteks historis, politik dan sosio-kultural sebagai basis perspektif dalam meninjau kelompok agama tertentu.
Sebagai penutup, Eva menganjurkan cara melihat bentuk agensi yang lebih seimbang pada Muslimah bercadar dengan turut memberikan fokus pada proses pembentukan diri yang mereka alami, alih-alih fokus pada isu kesalehan semata.

Izmy Khumairoh adalah seorang pengajar muda di program studi Antropologi Sosial Universitas Diponegoro, Semarang. Ia memiliki ketertarikan pada isu seputar interseksi agama, utamanya dengan aspek gender.
Ia dapat dihubungi melalui akun sosial media Instagram @izmyk atau Twitter @izmy_khu
Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini