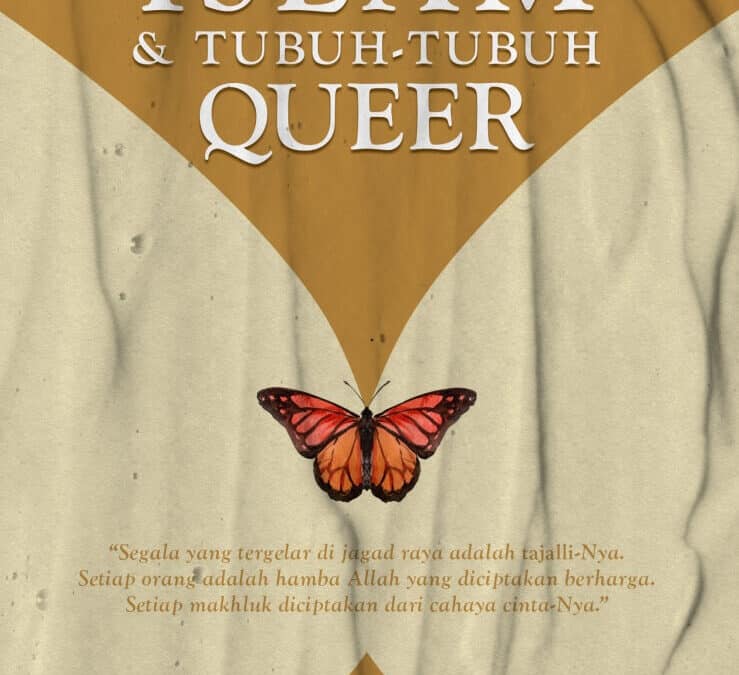Ruang Berbagi: Siasat Sektor Informal dalam Perebutan Kuasa Ruang-ruang Kota
July 25, 2023
Kedewasaan itu Diperoleh atau Dipelajari?: Sekilas tentang Metakognisi
August 7, 2023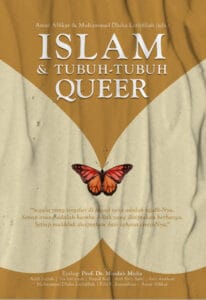
RESENSI BUKU
Islam dan Tubuh-tubuh Queer: Jendela ke Pemikiran Religius yang Ramah Queer
oleh Silvy Rianingrum
Banyak muslim yang tanpa ragu dan malu menyerukan kebencian terhadap komunitas queer atau LGBTQIA+ (lesbian, gay, biseksual, transgender, queer/questioning, aseksual, dan yang lainnya). Kebencian yang bermula dari perbedaan paham ini kemudian membentuk sistem yang diskriminatif, melembaga, dan sering digunakan sebagai alat politik identitas. Alhasil, marginalisasi dan kriminalisasi terhadap kelompok queer pun merajalela.
Marginalisasi dan kriminalisasi tersebut kerap dilegitimasi oleh institusi keagamaan, terutama Islam. Tapi, apakah benar agama yang menjunjung tinggi keadilan dan mengakui keterbatasan kekuasaan manusia ini membiarkan penganutnya bertindak semena-mena, bahkan melegitimasi pembunuhan terhadap makhluk-Nya? Apakah ada ruang bagi kelompok queer dalam Islam dan komunitas muslim? Apa yang Islam katakan mengenai identitas queer?
Menghayati Spiritualitas dalam Inklusivitas
Buku Islam dan Tubuh-tubuh Queer yang diterbitkan secara terbatas oleh YIFoS (Youth Interfaith Forum on Sexuality), sebuah forum pemuda lintas iman dan seksualitas, pada 2022, menjawab segala pertanyaan di atas.
Buku itu memuat sembilan esai yang membincangkan identitas dan tubuh-tubuh queer dalam perspektif spiritual Islam yang inklusif dan adil. Inklusivitas dan keadilan ini menjelma dalam kutipan hangat pada sampul depan: “Segala yang tergelar di jagad raya adalah tajalli-Nya. Setiap orang adalah hamba Allah yang diciptakan berharga. Setiap makhluk diciptakan dari cahaya cinta-Nya.”
Kutipan itu menyerukan keterbukaan untuk saling menghargai dan menumbuhkan semangat kemanusiaan progresif menuju masyarakat tanpa sekat. Akan tetapi, apakah masyarakat egaliter (setara) dapat kita capai di tengah kondisi umat muslim saat ini?
Transformasi tersebut di atas, menurut Andi Faizah, dalam esainya “Menghayati Spiritualitas dalam Inklusivitas”, tidak mungkin kita capai selama penilaian religiositas masyarakat muslim Indonesia masih bersifat hitam-putih dan berpaku pada simbol. Padahal, agama lebih dari sekadar simbol. Agama pada dasarnya mengharuskan penghayatan spiritual agar keimanan personal dapat mewujud menjadi aksi kemanusiaan yang nyata. Oleh karena itu, pembelajaran agama perlu mencakup pendewasaan iman yang membawa berkah bagi kehidupan, inklusivitas dan keterbukaan yang mendorong kerja sama pemecahan masalah, dan penekanan atas perdamaian dalam perbedaan dan keragaman.
Tanpa pembelajaran yang demikian, agama hanya akan membuat penganutnya arogan, merasa paling benar, dan gemar meliyankan orang lain. Contoh peliyanan ini tercermin dalam ujaran, “Kita Indonesia, bukan Eropa!” yang umumnya dilontarkan oleh para queerphobic, yaitu kelompok pembenci queer. Padahal, keberagaman orientasi seksual dan identitas gender adalah sebuah keniscayaan di tengah masyarakat. Peliyanan ini pun kemudian berkembang menjadi diskriminasi yang sistemik.
Ketidakadilan dan Tanggung Jawab Moral Muslim
Febi R. Ramadhan, kandidat doktor antropologi dari Northwestern University, dalam esainya “Komunitas LGBTQ+, Ketidakadilan, dan Tanggung Jawab Moral Muslim” berpendapat bahwa kekejaman sistematis terhadap komunitas tersebut juga berakar dari kesalahpahaman penerjemahan, tafsir, dan anakronisme istilah. Kendati demikian, Febi setuju bahwa al-Mustad’afin fi-l-Ard, yakni orang-orang yang mengalami ketidakadilan dan penindasan, adalah istilah yang tepat bagi komunitas LGBTQIA+. Ini karena mereka mengalami ketidakadilan, penindasan dan kerentanan dalam keseharian mereka yang mencakup kerentanan ekonomi, sosial, kesehatan, dan keamanan. Febi lalu menguraikan urgensi bagi umat Islam untuk membantu mereka dengan mempertanyakan, “Ketika komunitas LGBTQIA+ mengalami ketidakadilan dan penindasan dalam kehidupan mereka sehari-hari, apa yang harus umat Islam lakukan?”
Menurutnya, bersikap toleran pada komunitas LGBTQIA+ tidaklah cukup, karena kita tidak secara langsung membela dan memperjuangkan keselamatan serta hak-hak mereka sebagai al-Mustad’afin fi-l-Ard. Febi berpendapat bahwa kita perlu memulainya dengan menanggalkan dan meninggalkan bias serta sentimen negatif terhadap mereka. Hal itu akan menghasilkan pikiran dan tindakan yang adil, sehingga kita dapat berkontribusi nyata dalam pemenuhan hak asasi manusia, baik yang dimiliki individu maupun kelompok queer. Febi, pada dasarnya, menyerukan pelibatan kesadaran diri untuk turut andil dalam mewujudkan masyarakat yang ramah queer dan ruang aman yang adil tanpa diskriminasi dan kriminalisasi.
Selain itu, esai Febi juga dengan sangat komprehensif menyajikan perseteruan kebahasaan yang mengotak-ngotakan dan memutus rantai kesejarahan dalam memahami komunitas LGBTQIA+. Terkait aspek kesejarahan, banyak yang menganggap komunitas LGBTQIA+ sebagai fenomena baru dan sebuah anomali setelah “pemusnahan” umat Nabi Lut. Akibatnya, banyak pula yang menggunakan kisah Nabi Lut dalam Alquran sebagai alasan dan legitimasi atas diskriminasi dan kriminalisasi queer.
Reinterpretasi Kisah Kaum Lut
Arif Nuh Safri, cendekiawan Muslim pro-queer, dalam esainya “Reinterpretasi Kisah Kaum Lut: Sebuah Pemula” menjabarkan reinterpretasi atas kisah Nabi Lut yang termaktub dalam Alquran. Ia membahas tiga istilah yang muncul berulang kali dalam QS. 29:28 dan QS. 7:80, yaitu al-fāhisya (kekejian), mā sabaqakum bi-hā min ahad (belum pernah dilakukan oleh orang), dan al-‘ālamīn (alam semesta). Menurutnya, ketiga istilah tersebut adalah kunci dalam memahami kisah Nabi Lut dan kaumnya.
Istilah al-fāhisya secara umum berarti kekejian atau segala bentuk perbuatan yang dilakukan secara sadar dan terus berulang, bahkan berlebihan atau melampaui batas hingga menghasilkan kehinaan diri. Arif menuliskan bahwa kekejian yang dimaksud dalam kisah Nabi Lut tidak merujuk pada homoseksualitas, melainkan pada sodomi secara paksa atau perkosaan sebagai bentuk penaklukan atas tamu dan orang lain yang dianggap musuh. Kekejian, dalam konteks itu, juga berarti penyamunan (qat’ al-sabīl), perselingkuhan, pedofilia, pesta seks di ruang publik dan berbagai kejahatan seksual lainnya. Kekejian lainnya juga mencakup pembangkangan terhadap Nabi Lut. Singkatnya, kekejian yang selama ini merujuk pada kisah Nabi Lut berkaitan pada kejahatan seksual terhadap tamu dan penolakan terhadap Nabi Lut sebagai utusan Allah.
Istilah mā sabaqakum bi-hā min ahad dan al-‘ālamīn , menurut Arif, berhubungan dengan sejarah dan keragaman biologis makhluk hidup. Dengan menggunakan penjelasan ilmiah mengenai homoseksualitas dalam kingdom animalia, Arif berusaha membuktikan bahwa homoseksualitas bagi homo sapiens adalah hal yang natural dan semestinya terjadi (meant to be) karena kehendak Allah.
Untuk menguatkan argumennya, Arif mengulas eksistensi homoseksualitas dalam sejarah, misalnya di Mesir sejak 2400 SM dan di Italia sejak 5000-9600 SM; bahwa homoseksualitas sudah ada sejak lama sebelum kaum Nabi Lut yang diperkirakan hidup pada 1861 SM di Aur, Babilonia. Hal ini membuktikan bahwa homoseksualitas bukanlah hal baru, sebagaimana yang sering didengungkan oleh segelintir orang. Homoseksualitas adalah salah satu kehendak Allah, sehingga kita perlu mengakui keberagaman tersebut.
Memangkas Ganjal Perkawinan Non-Heteroseksual
Aan Anshori, cendekiawan dan aktivis pejuang hak LGBTQIA+, dalam “Memangkas Ganjal Perkawinan Non-Heteroseksual” berpendapat bahwa pencerabutan sistemik atas hak berkeluarga bagi kelompok queer didasarkan pada hukum yang bersifat queer phobic. Itu juga didasarkan pada pemahaman masyarakat muslim yang memandang identitas gender dan seksualitas dalam perspektif biner dan heteronormatif .
Bineritas dan heteronormativitas Aan sebut sebagai sebuah rezim. Rezim itu kemudian menguasai jaringan ilmu pengetahuan, direproduksi terus menerus, dan seolah menjadi sesuatu yang absolut dalam Islam. Aan berpandangan bahwa rezim ini senantiasa membelokkan Islam dari tujuan utama kehadirannya, yaitu sebagai rahmatan lil-alamin (rahmat bagi seluruh alam). Pembelokan itu dilakukan melalui dua cara, yaitu ekspansi militeristik dan prokreasi untuk meneruskan garis keturunan umat Islam.
Ekspansi militeristik merujuk pada invasi dan penjajahan wilayah di bawah kepemimpinan muslim. Aan meyakini bahwa invasi dan penjajahan itu merupakan alat untuk mengonversi keyakinan penduduk di tanah jajahan. Dalam hubungannya dengan reproduksi pandangan bineritas dan heteronormativitas dalam Islam, invasi dan penjajahan menelurkan lebih banyak pengikut Islam, sehingga ilmu pengetahuan Islam yang biner dan heteronormatif pun memiliki generasi penerus. Artinya, semakin banyak pengikut Islam, semakin banyak pula yang mempercayai bineritas dan heteronormativitas. Pada akhirnya, hal itu membuat sikap queerphobia semakin merajalela dan sikap tersebut dianggap inheren atau menubuh dalam Islam.
Meskipun kaya akan informasi, esai yang ditulis oleh Aan Anshori sejatinya memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, Aan tidak menyertakan surat dan ayat Alquran yang krusial sebagai penguat argumennya. Salah satu contohnya adalah ketika Aan menuliskan, “Bahkan yang menurut saya luar biasa, kitab suci ini (Alquran) secara eksplisit menyinggung keberadaan sosok unik, yang sangat mungkin masuk kategori non-heteroseksual.” Pada bagian itu, Aan tidak menyebutkan surat dan ayat Alquran yang dimaksud, walaupun ia mengklaim bahwa Alquran secara eksplisit sudah menyinggung keberadaan sosok tersebut.
Contoh lainnya adalah ketika Aan mengutarakan, “Baik ayat Alquran maupun realitas (ayat kauniyyah) telah mengonfirmasi hal itu (bahwa tidak berarti semua pemilik penis pasti menyukai pemilik vagina secara seksual)” dan ketika Aan mengatakan bahwa Alquran menyebutkan adanya lima tujuan pernikahan. Tidak adanya sumber surat dan ayat Alquran yang spesifik membuat, argumen yang termuat dalam esai ini terkesan terlampau personal sebagai hasil interpretasi penulis tanpa menyertakan sumber ajeg yang mampu mengkonsolidasikannya.
Selain itu, Aan juga membuat pernyataan yang rancu, yaitu “Penaklukkan dan penjajahan ke wilayah di luar Makkah dan Madinah menjadi opsi utama yang dilakukan sejak Nabi Muhammad hingga imperium Ottoman.” Pernyataan ini menyiratkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang militan yang menyetujui ekspansi militeristik dan penjajahan.
Pernyataan tersebut cukup bertentangan dengan pandangan Juan Cole, ahli sejarah Islam asal Amerika Serikat, dalam bukunya Muhammad: Prophet of Peace amid the Clash of Empires (2018) dan wawancaranya dengan Literary Hub. Juan menyebut, “Dia (Nabi Muhammad) adalah pedagang yang terjebak pada situasi dimana masyarakat Madinah harus membela diri.” Dengan kata lain, keputusan dan tindakan militeristik Nabi Muhammad pada masa itu merupakan bagian dari bentuk pertahanan diri (self-defense) dan sebuah upaya yang sarat akan nilai perdamaian (peacemaking) serta melawan aksi pembantaian, perang, dan perseteruan agama yang sudah berlangsung lama.
Secara keseluruhan, buku kumpulan esai Islam dan Tubuh-tubuh Queer ini adalah permulaan yang cukup memadai untuk mendekonstruksi pandangan kaku terhadap individu queer dan komunitas LGBTQIA+. Buku ini juga menawarkan berbagai pandangan baru yang dapat membantu pembaca mempelajari Islam dan betapa luasnya ruang yang diciptakan Allah untuk menerima dan mengakomodasi kehadiran kelompok queer. Tak hanya itu, buku ini juga menggarisbawahi bahwa keberagaman tubuh dan seksualitas adalah keniscayaan sebagai wujud kebesaran Allah.

Silvy Rianingrum adalah penggemar Kafka dan pembaca poligamis yang suka menulis. Saat ini, ia mengajar bahasa Inggris di Jakarta.
Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini