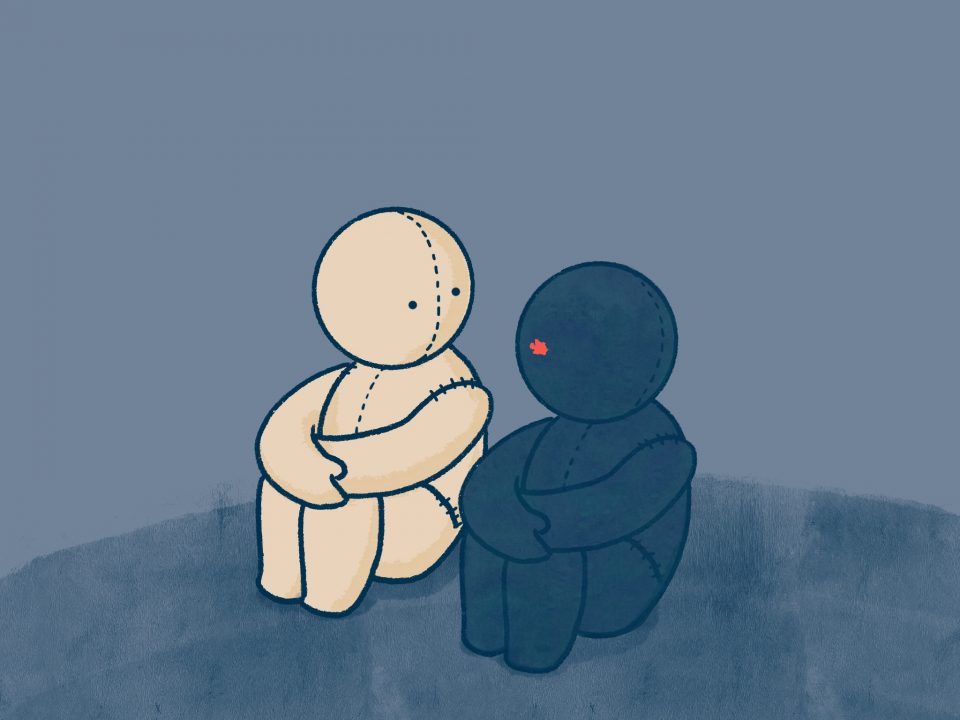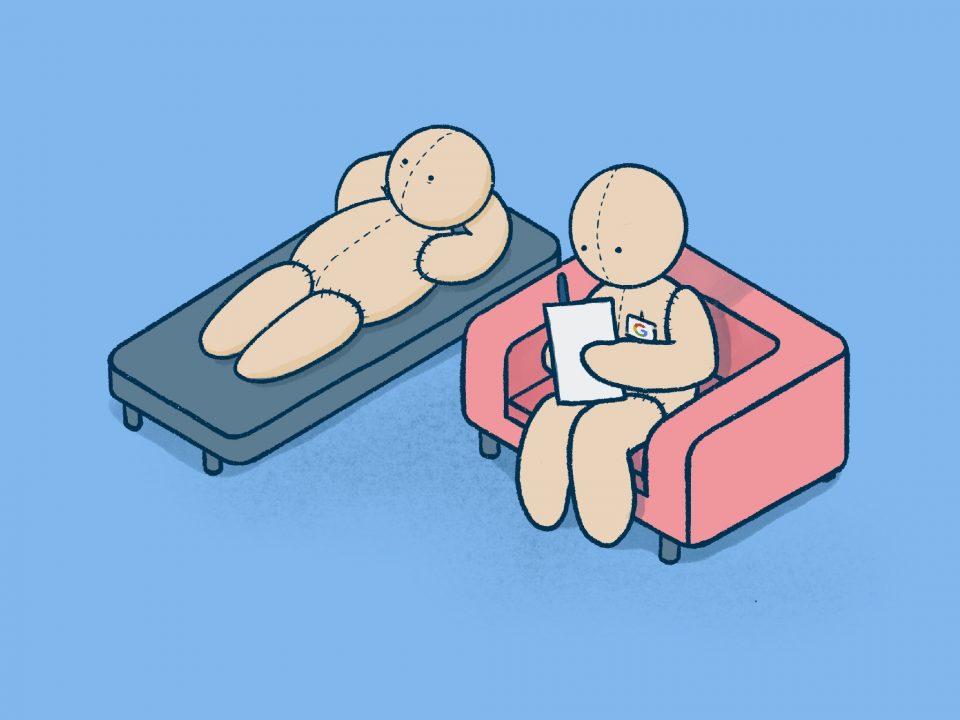Mengapa Kita Harus Belajar Ekonomi Marxisme?
November 13, 2023
Antara Baik dan Jahat: Mempersoalkan Dualitas Sifat Dasar Manusia
December 12, 2023
Photo by Steven Leisher on Unsplash
OPINI
Membincang Kepatuhan dari Perspektif Erich Fromm
oleh M. Ja’far Baihaqi
Saya akan memulai pembahasan ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan: pada siapa seharusnya kita patuh?
Pertanyaan tersebut tentu memiliki beragam jawaban.
Agamawan akan menjawab bahwa apa yang seharusnya kita patuhi adalah Tuhan. Sementara itu, para politikus mungkin akan menjawab bahwa yang seharusnya kita patuhi adalah pemerintah. Lain lagi dengan para budayawan, mereka mungkin akan mengajak kita untuk mematuhi budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Begitu pun dengan para karyawan, mereka mungkin akan mengatakan bahwa yang harus dipatuhi adalah para pemilik modal.
Namun, Erich Fromm, seorang psikolog dan filsuf asal Jerman, punya pandangan yang berbeda. Menurutnya, yang seharusnya kita patuhi adalah otoritas dalam diri, yakni kesadaran kita sendiri.
Apa maksud Fromm ketika mengatakan hal itu?
Tulisan ini sekurang-kurangnya akan mencoba mengelaborasi jawaban atas pertanyaan tersebut dengan merujuk pada bukunya yang berjudul On Disobedience dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tajuk Perihal Ketidakpatuhan.
Patuh pada Kemanusiaan dan Rasionalitas
Mula-mula, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari kepatuhan. Singkatnya, kepatuhan adalah kondisi ketika seseorang memasrahkan otonomi (kebebasan) atas dirinya pada suatu otoritas (kekuatan) tertentu.
Dalam buku ini, Fromm mengatakan bahwa kepatuhan, sekurang-kurangnya, bisa dibagi menjadi dua, yakni kepatuhan heteronom dan kepatuhan otonom.
Kepatuhan heteronom adalah kepatuhan kepada pihak di luar diri kita, seperti patuh kepada orang tua, budaya, agama, negara, dan lain-lain. Sementara itu, kepatuhan otonom adalah kepatuhan terhadap aspek-aspek internal di dalam diri kita, yakni akal budi, nalar, hati nurani, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kepatuhan otonom sebenarnya juga lebih tepat disebut sebagai penegasan atau afirmasi diri.
Fromm ingin kita, sebagai manusia yang bebas dan rasional, menghayati jenis kepatuhan yang kedua, yakni patuh pada diri kita sendiri yang berarti patuh pada akal budi, nalar, dan nurani.
Namun, kesadaran atau nurani kita sendiri pun, kata Fromm, seringkali disusupi oleh otoritas dari luar. Kesadaran semacam ini disebut Fromm sebagai kesadaran otoriter, yaitu suara dari luar yang telah menjelma di dalam diri kita sebagai suatu perintah internal.
Nurani kita seringkali disusupi oleh doktrin-doktrin dan norma-norma yang telah tertanam kuat tanpa kita kritisi sama sekali. Contoh yang tipikal untuk hal ini adalah ajaran agama. Misalnya, ketika kita memaksa seseorang untuk memakai jilbab, kita seolah merasa sudah patuh pada hati nurani kita. Padahal, tanpa kita sadari, yang sebenarnya kita patuhi adalah dogma agama yang telah mengakar kuat di dalam diri.
Berkebalikan dengan itu, kesadaran yang memang seharusnya kita patuhi dan rawat adalah kesadaran humanistik, yaitu kesadaran yang ada dalam diri setiap manusia yang membantu kita menilai mana yang manusiawi dan mana yang biadab. Kesadaran ini bersifat intuitif (berdasarkan suara hati), rasional (bisa dicerna dengan akal sehat), dan universal (diterima secara luas). Misalnya, tanpa harus terlebih dahulu belajar, seorang yang memiliki akal sehat akan tahu dengan sendirinya bahwa membunuh dan memperkosa adalah perbuatan yang biadab. Kesadaran semacam inilah yang dianjurkan Fromm untuk dihayati dan dirawat oleh semua umat manusia.
Meskipun demikian, bukan berarti kita tidak diperkenankan untuk mengamini jenis kepatuhan yang pertama, yakni kepatuhan otoriter. Otoritas yang bisa kita patuhi adalah otoritas rasional dan otoritas yang harus kita lawan adalah otoritas irasional (tidak bisa dicerna dengan akal sehat). Otoritas rasional adalah segala otoritas yang memberikan ruang yang memadai pada pemikiran rasional dan penghormatan yang tinggi pada aspek-aspek kemanusiaan. Sementara itu, otoritas irasional adalah segala otoritas yang mengekang pemikiran rasional dan seringkali menindas aspek-aspek kemanusiaan kita.
Jadi, jika yang coba mengatur kita adalah pemerintah yang korup, agama yang justru menjadi sumber bencana, budaya dan tradisi yang tidak manusiawi, serta juragan yang hanya berpikir tentang keuntungan tanpa peduli pada kesejahteraan para karyawan, hanya ada satu kata: lawan! Sebaliknya, jika otoritas-otoritas itu sudah mampu memberikan cukup ruang bagi kebebasan, nilai-nilai kemanusaian, serta pemikiran rasional, mereka layak untuk kita patuhi.
Sampai di sini, kita seharusnya sudah memahami maksud pernyataan Fromm mengenai kepatuhan pada diri sendiri. Maksudnya adalah patuh pada nilai-nilai kemanusian, nalar, akal budi, dan rasionalitas atau dengan kalimat lain patuh pada kesadaran humanistik.
Kesadaran Humanistik, Mengapa Penting?
Satu pertanyaan pun mengemuka: mengapa kita harus patuh pada kesadaran diri yang humanis (manusiawi) atau kesadaran humanistik?
Sekurang-kurangnya, ada dua alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, kepatuhan pada kesadaran humanistik akan membuat kita lebih mencintai kehidupan yang pada gilirannya akan mampu membawa dunia ini ke arah yang lebih baik, seperti berakhirnya perang. Kesadaran humanistik memungkinkan kita untuk mengakhiri perang yang mengatasnamakan agama maupun kepentingan negara. Sebab, orang-orang akan hidup dengan lebih saling menghargai satu sama lain dan penyelesaian masalah pun dapat dilakukan dengan cara-cara yang humanis dan diplomatis, sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban. Contoh lainnya adalah eksploitasi karyawan oleh para juragan mungkin tidak akan terjadi lagi, karena para juragan tidak lagi hanya memikirkan keuntungan material (profit) semata, melainkan juga memikirkan kesejahteraan karyawannya.
Mari kita patuh pada kesadaran humanistik dan otoritas rasional. Mari menolak segala otoritas irasional yang tidak manusiawi. ~ M. Ja'far Baihaqi Share on XAlasan kedua adalah karena kepatuhan pada kesadaran humanistik merupakan sikap yang dilakukan oleh hampir semua nabi. Nabi Muhammad misalnya, ia menolak patuh pada agama, pemerintah, dan budaya kaum jahiliyah di Mekkah yang irasional dan biadab. Ia pun memilih menyepi dan berkontemplasi, lalu memutuskan untuk patuh pada dirinya sendiri dan pada Tuhan barunya yang ia nilai lebih rasional dan manusiawi. Ajaran ini pun membawa dampak yang sangat baik terhadap kehidupan masyarakat Mekkah, bahkan hingga seluruh jazirah arab, setidaknya pada saat itu.
Orang jahiliyah di Mekkah pun mengatakan bahwa perbuatan Muhammad adalah tindakan buruk dan biadab, karena memberontak pada tradisi dan budaya leluhur. Namun, saya kira, itulah yang terjadi pada seluruh otoritas irasional, di mana mereka menganggap bahwa ketidakpatuhan pada mereka adalah sebuah tindakan biadab. Padahal, mereka sendirilah yang sebenarnya biadab karena telah menindas sisi kemanusiaan, kebebasan, dan rasionalitas.
Catatan Akhir
Terinspirasi oleh Fromm, saya ingin menutup tulisan ini dengan mengajak para pembaca untuk patuh pada kesadaran humanistik dan otoritas rasional. Kemudian, mari bersikap tidak patuh pada segala otoritas irasional yang tidak manusiawi. Karena ketidakpatuhan yang revolusioner, kata Fromm, adalah awal dari terbentuknya sejarah manusia dan, sebaliknya, sejarah kehidupan manusia bisa saja berakhir karena kepatuhan yang buta.
Saya juga ingin menekankan bahwa kepatuhan ataupun ketidakpatuhan sebenarnya hanyalah masalah istilah. Sama sekali tidak penting apakah kita seorang penurut ataupun pemberontak, yang lebih penting sebenarnya adalah menegaskan posisi kita.
Apakah kita berada di pihak kebebasan, kemanusiaan, dan rasionalitas; ataukah kita ada di pihak otoritas irasional yang manipulatif dan tamak? Apakah ketika menjadi seorang penurut kita mampu menjadi penurut yang kritis? Atau sebaliknya, ketika menjadi pemberontak, mampukah kita menjadi pemberontak yang berwatak humanis?
Semua itu kembali pada diri kita: apakah kita memiliki sedikit keberanian untuk berbeda dan dihakimi lalu berkata tidak pada segala jenis otoritas irasional yang biadab? Ataukah, kita lebih senang dan nyaman menjadi seorang “robot” yang hidupnya selalu dikontrol oleh orang lain?

M. Ja’far Baihaqi adalah mahasiswa jurusan Aqidah Filsafat di UIN SATU Tulungagung. Ia senang membuat tulisan sederhana dari beberapa literatur yang telah ia baca.
Artikel Terkait
Memerangi Maskulinitas Beracun, Tanggung Jawab Siapa?
Memerangi maskulinitas beracun bukan berarti mengutuk laki-laki atau atribut laki-laki, melainkan untuk memerangi dampak berbahaya dari maskulinitas tradisional, seperti dominasi dan persainganMenjadi Admin Akun Psikologi: Bukan Sekadar Berbagi, Tapi Juga Menerima
Di Catatan Pinggir ini, Ayu Yustitia berkisah tentang pengalamannya menjadi admin media sosial Pijar Psikologi. Ayu tersadar bahwa bahwa banyak orang di luar sana yang merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Pengalaman ini mendorong Ayu untuk mendorong kita semua untuk lebih baik kepada diri sendiri dan orang di sekitar kita.Tanya Kenapa
Di usianya yang muda, Putri Hasquita Ardala sudah mengenyam banyak pengalaman tentang pentingnya kesehatan mental. Di Catatan Pinggir ini, Putri mengingatkan kita semua tentang panjangnya jalan menghadapi depresi dan bagaimana kita semua perlu meminta bantuan.