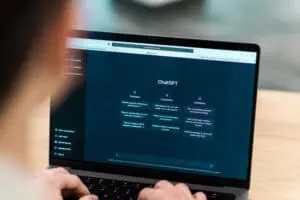Ketika seluruh dunia tengah berancang-ancang untuk ‘menyambut’ pandemi COVID-19, saya justru tengah berjuang menghadapi rasa duka. Sekitar bulan Maret 2020, pasangan hidup saya, Robert, meninggal dunia setelah divonis menderita kanker otak tujuh bulan sebelumnya.
Sekitar satu-dua bulan sebelum Robert wafat, saya terpaksa pergi ke Indonesia untuk memperpanjang visa karena saat itu kami masih tinggal di Chiang Mai, Thailand. Agak berat bagi saya untuk meninggalkannya meski hanya untuk sementara. Untungnya, ada teman baik kami yang bersedia merawat Robert selama saya pergi. Di sisi lain, saya juga menggunakan kesempatan ini untuk ‘liburan’ sejenak.
Kata ‘respite’ dalam bahasa Inggris yang berarti ‘jeda’ atau ‘istirahat’ merupakan satu kata yang sering terpikirkan oleh saya semenjak menjadi caretaker alias perawat Robert. Dari artikel-artikel yang saya baca, mereka yang merawat penderita penyakit terminal (penyakit yang tidak dapat disembuhkan) perlu mendapat ‘jeda’ sejenak. Mungkin, istilah sejenis yang populer sekarang adalah ‘self-care’ alias merawat diri sendiri.
Selama di Chiang Mai, ada beberapa hobi yang saya lakukan untuk rehat sejenak dari tanggung jawab saya sebagai perawat sekaligus pasangan Robert. Di antaranya adalah bulu tangkis dan tenis. Sesekali saya juga nge-gym dan ketemu teman di kedai kopi untuk rehat sejenak. Bagi saya, merawat diri sendiri sangatlah penting karena saya adalah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV).
Sebagai ODHIV, saya harus menjaga badan saya, utamanya dengan meminum obat antiretroviral (ARV) untuk menjaga kadar virus dalam tubuh agar tetap rendah sampai tidak terdeteksi. Dengan begini, saya tidak akan terpapar penyakit-penyakit ‘aneh’ atau bahkan sampai menderita AIDS. Untungnya, sejak terjangkit HIV pada 2013, saya tidak pernah menderita penyakit parah, apalagi sampai harus diopname.
Maka dari itu, di tengah-tengah kesibukan saya sebagai seorang caretaker, saya menggunakan momen memperpanjang visa ini untuk rehat sejenak. Kebetulan, Thailand memiliki Konsulat di Bali. Karena itu, pilihan saya pun jatuh ke Pulau Dewata. Kalau tidak salah, pada bulan Januari tahun 2020 itu, kasus COVID-19 baru mulai muncul di media, meski kebanyakan baru ditemui di Tiongkok.

Karena sadar waktu saya di Bali cuma satu pekan, saya memaksakan diri untuk menemui semua teman saya. Ada yang tinggal di Ubud, ada yang tinggal di Denpasar, ada pula yang di Seminyak. Semuanya ingin saya temui. Tidak peduli itu hujan sekalipun, saya rela berbasah-basahan demi ketemu teman lama.
Pada hari kepulangan saya ke Thailand, saya mulai bersin-bersin dan meriang. Di pesawat, seorang pramugara memperhatikan kondisi saya yang tidak fit. Tidak lama kemudian, muncullah pertanyaan menakutkan itu.
“Pak, apakah Bapak baru-baru ini berkunjung ke China?” tanya si pramugara.
Syok, kaget, tidak terima, dan takut. Campur aduk rasanya. Seketika itu juga, saya bilang bahwa saya tidak berkunjung ke Tiongkok baru-baru ini. Dengan defensif, saya tekankan bahwa saya tidak terkena virus Corona.
Meski demikian, sesampainya di Chiang Mai, saya jadi khawatir juga. Untungnya, dokter di rumah sakit setempat mengonfirmasi bahwa saya tidak terpapar virus Corona. Saya hanya terkena bronkitis. Setelah beberapa hari, saya pun pulih dan bisa kembali melakukan aktivitas sebagai seorang caretaker. Sekitar pertengahan Maret 2020, pada saat yang bersamaan COVID-19 mulai tersebar ke negara-negara lain, Robert mengembuskan napas terakhirnya. Semuanya terjadi dengan begitu singkat namun manis. Walau sampai saat ini saya masih sedih, saya senang bisa hadir di sana sampai akhir hayatnya.
[bctt tweet=”Satu hal yang membuat saya cukup optimis dalam menghadapi masa pandemi adalah mulai adanya tenaga kesehatan yang bersikap terbuka pada ODHIV. ~ Amahl S. Azwar”]
Transisi
Beberapa hari setelah berita menyebarnya COVID-19 ke negara-negara lain, Thailand pun memasuki tahap lockdown karena COVID-19 dikabarkan mulai masuk ke Negeri Gajah Putih tersebut. Bayangkan, saya yang baru kehilangan pasangan harus langsung tinggal di rumah sendirian tanpa bisa bertemu siapa pun. Bahkan, sebetulnya saya harus pindah ke sebuah apartmen yang jauh lebih kecil karena saya tidak mampu membayar sewa rumah yang sebelumnya saya tempati bersama Robert.
Melihat ke belakang, meskipun berat untuk dilakukan, saya akui tindakan pemerintah setempat cukup efisien dalam mencegah penyebaran virus. Memang, saat tulisan ini saya buat, Thailand sedang menghadapi masalah baru dalam penanganan pandemi. Akan tetapi, dari pengalaman saya, apa yang mereka lakukan saat itu memang dibutuhkan dan, pada akhirnya, baik untuk menghalau virus.
Tidak ada gym yang boleh buka. Restoran-restoran pun hanya boleh menerima take away (pesanan bawa pulang) atau pesanan via aplikasi. Selain rumah sakit, hanya supermarket yang boleh buka–itu pun dengan syarat pengunjung harus memakai masker, mencuci tangan, dan memeriksa suhu tubuh. Kita tidak boleh coba-coba melanggar.
Saya sempat baca tentang salah satu orang asing yang marah-marah di supermarket karena tidak diperbolehkan masuk. Si penjaga toko pun tidak segan-segan mengusirnya. Sekalipun ketat, sikap yang cukup tegas ini memang diperlukan.
Tentu, saya bisa bicara seperti ini karena, pada akhirnya, saya juga termasuk ekspat (orang yang menetap di luar negara asalnya). Meski secara internal, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Thailand untuk penduduknya sendiri, saya masih merasa cukup aman tinggal di Thailand meski di tengah pandemi, mengingat status saya sebagai ODHIV.
Stok obat ARV di Thailand juga selalu tersedia, sehingga saya tidak perlu takut. Dokter-dokter di sana pun sudah sangat terbuka pemikirannya sehingga saya tidak perlu sungkan untuk curhat atau sekadar berbagi kekhawatiran saya sebagai ODHIV di tengah pandemi.
Hingga pada akhirnya, tiba waktu untuk saya kembali ke Indonesia.
[bctt tweet=”Kami sama sehatnya, kok, seperti kalian yang bukan ODHIV–selama kami rajin minum ARV dan menjaga kondisi tubuh. ~ Amahl S. Azwar”]
Indonesia
Saya sebetulnya merasa cukup betah di Thailand. Tetapi, rasa duka yang menghantui membuat diri ini ingin pindah dan membuat memori baru. Selain itu, perpanjangan visa di Thailand juga agak mahal. Karena itu, saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Pilihan saya jatuh ke Bali. Setidaknya, dari yang saya dengar, Pulau Dewata cukup ramah untuk orang-orang seperti saya.
Begitu sampai, sungguh saya langsung panik dan jujur, agak takut. Banyaknya orang-orang yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan membuat saya tidak habis pikir. Setelah tiba dari negara yang cukup ketat dalam menjalankan protokol kesehatan, melihat orang-orang cuek berkeliaran tanpa masker dan cuci tangan sebelum masuk kafe membuat saya sungguh tidak nyaman.
Pada akhirnya, peraturan untuk memakai masker dan mencuci tangan memang mulai diperketat. Namun, saya masih sering mendapati orang-orang–di gym, misalnya–yang tidak menggunakan masker. Meski begitu, mereka tidak pernah ditegur oleh para petugas pusat kebugaran.
Bodohnya, saya jadi sempat kurang berhati-hati juga. Meskipun saya masih berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan, nyatanya masih ada hal-hal yang saya lewatkan. Karena itu, bulan lalu, saya pun terkena COVID-19. Karena menderita mild symptoms, saya diminta untuk beristirahat di rumah selama 14 hari. Isolasi mandiri atau isoman, istilahnya.
Jujur, saya termasuk orang yang beruntung. Pekerjaan yang saya lakukan saat ini memungkinkan saya untuk tetap mendapat pemasukan terlepas kondisi medis saya. Sikap saya yang terbuka pun membuat orang-orang tahu akan apa yang saya alami, sehingga mereka tidak sungkan untuk membantu. Selama isoman, saya mendapat banyak sekali bantuan dan dukungan dalam bentuk makanan, minuman, sampai uang.
Lambat laun, saya pun berhasil melewati isoman dan kembali sehat seperti sedia kala. Syukurlah, keputusan saya untuk tetap minum ARV selama delapan tahun terakhir membuat kondisi tubuh ini cukup sehat untuk melawan COVID-19.
Satu hal yang membuat saya cukup optimis dalam menghadapi masa pandemi adalah mulai adanya tenaga kesehatan yang bersikap terbuka pada ODHIV. Tidak seperti dulu, saat saya masih sering mendengar adanya tenaga kesehatan yang bersikap menghakimi saat berurusan dengan ODHIV.
Ketika saya mendapatkan vaksin kemarin, saya menceritakan status saya kepada tenaga kesehatan yang bertugas.
“Oh, tidak apa-apa. Kamu rajin minum obat, kan?” Hanya begitu komentarnya.
Walau belum tentu semua tenaga kesehatan di Indonesia sudah seperti beliau, setidaknya ini sudah menjadi contoh yang baik yang saya harap bisa ditiru oleh mereka yang bekerja di bidang tersebut.
Akhir kata, saya harap pengalaman saya ini bisa memberikan sedikit perspektif dari seorang ODHIV yang turut mengarungi hidup di tengah pandemi COVID-19 seperti yang lain. Kami sama sehatnya, kok, seperti kalian yang bukan ODHIV–selama kami rajin minum ARV dan menjaga kondisi tubuh.
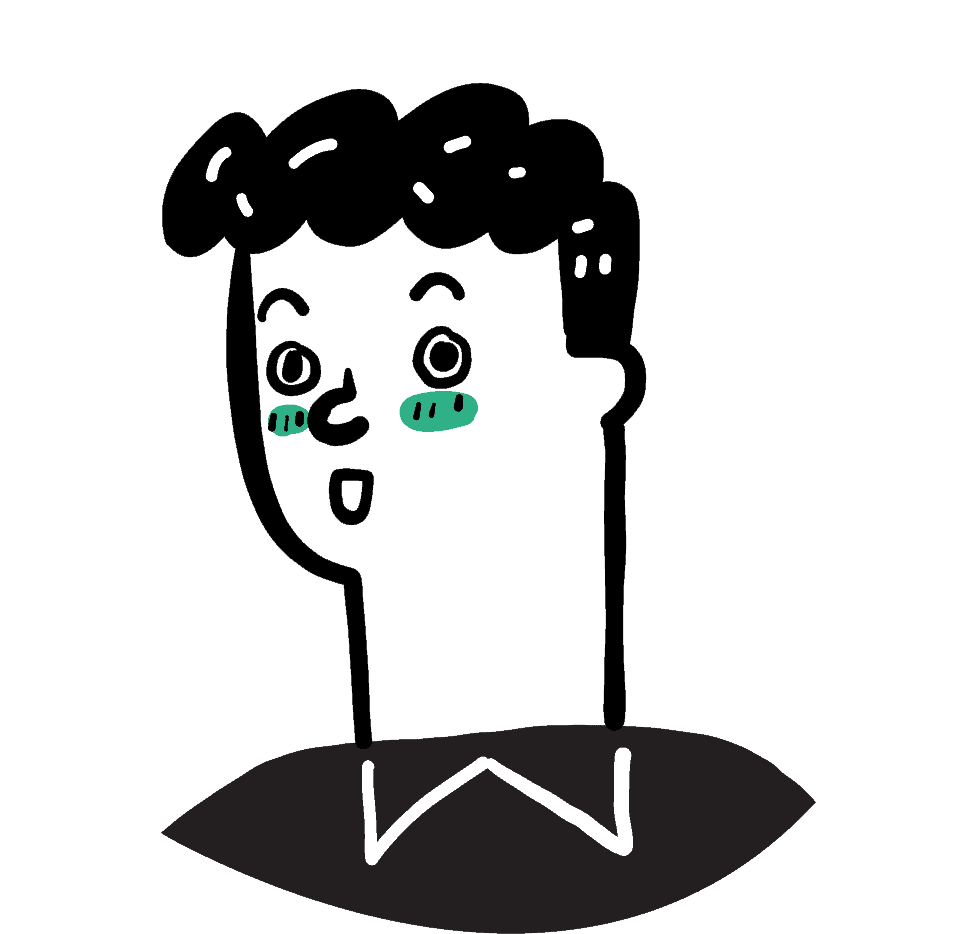
Amahl S. Azwar adalah seorang jurnalis dan penulis lepas yang kini menetap di Bali. Karya tulisannya (jurnalistik, nonfiksi, dan fiksi) sempat dimuat di Media Indonesia, The Jakarta Post, Magdalene, Esquire, Vice, Rappler, The Fix, dan Giddy. Sebagai seorang ODHIV dan pria gay yang sudah melela, Amahl sering membagikan kisahnya melalui Twitter dan Instagram. Dia membentuk situs www.menjadipositif.com sebagai medium untuk kisah-kisah personalnya. Kumpulan esai Amahl tentang kisahnya sebagai pria gay dan ODHIV di Indonesia, The Poz Says OK, bisa didapatkan melalui @EAbooks di Instagram.