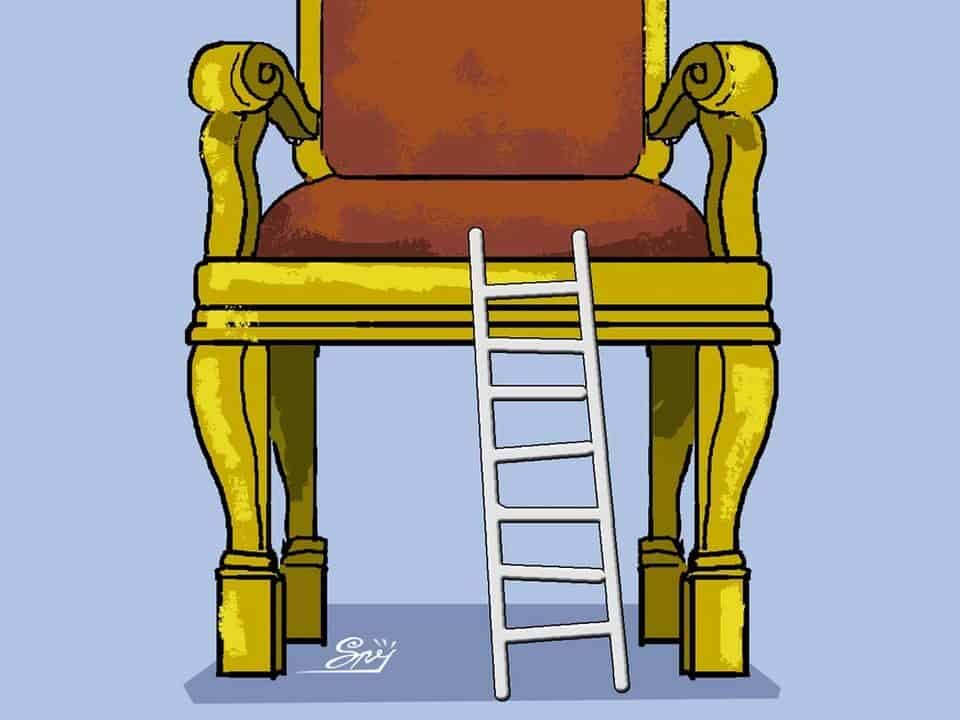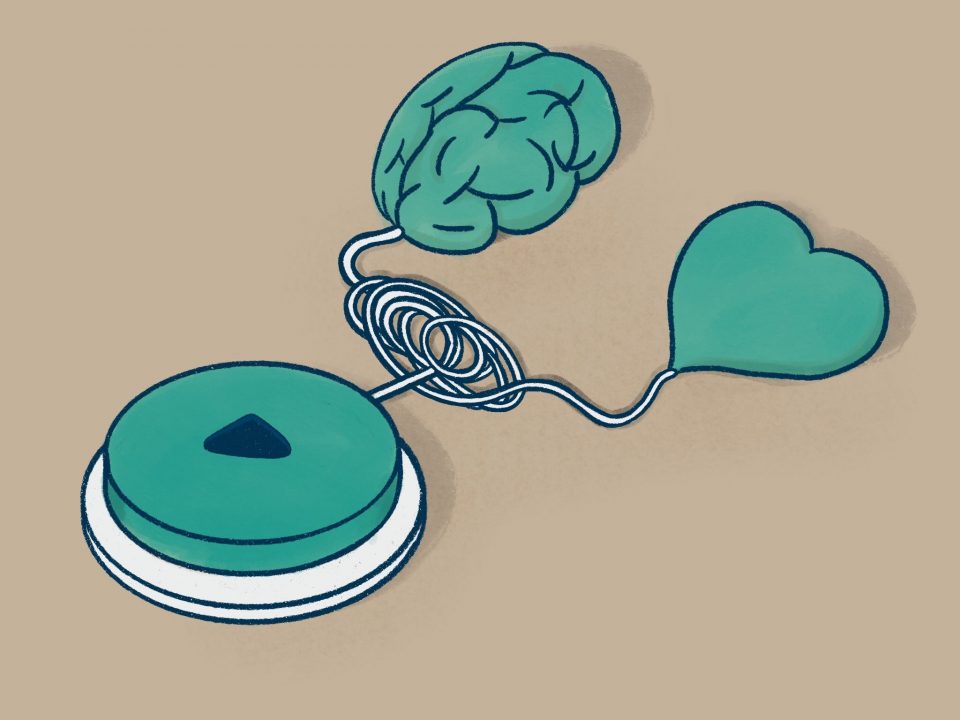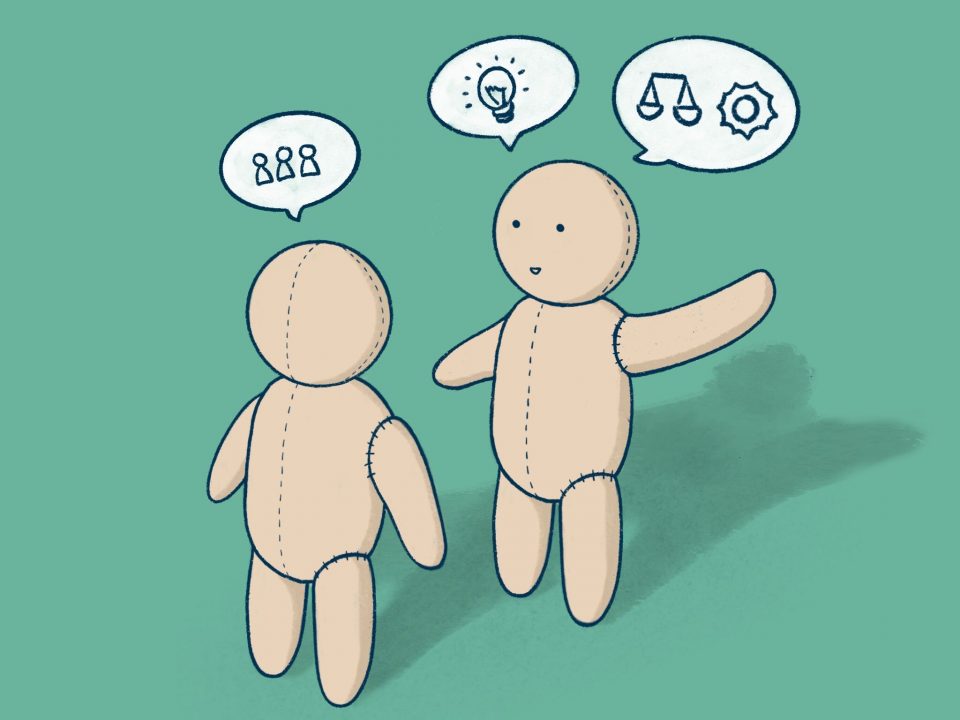Scooby Doo, Artefak Budaya Amerika yang Konsisten Beradaptasi dengan Zaman
July 5, 2024
Memahami Krisis Lingkungan dari Lensa Feminist Political Ecology
July 30, 2024
Photo by Ensiklopedia Sejarah Indonesia
OPINI
Bebas Aktif: Memaknai Kembali Alam Pikiran Bung Hatta
oleh Dinar Maharani Hasnadi
Pada awal 2024, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Gedung Merdeka, Bandung. Retno memaparkan bahwa politik luar negeri Indonesia berprinsip bebas aktif dan berorientasi pada perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi.
Pemilihan lokasi itu bukan tanpa alasan. Spirit Bandung rupanya masih merasuki gedung itu, bahkan setelah hampir 70 tahun Konferensi Asia-Afrika digelar untuk pertama kalinya. Prinsip bebas aktif, yang ditelurkan oleh Mohammad Hatta (wakil presiden pertama Indonesia) pada masa awal kemerdekaan dan kemudian diakui dalam konferensi tersebut, merupakan napas politik luar negeri Indonesia saat ini.
Dalam benak kita, posisi Hatta sebagai peletak dasar hubungan internasional Indonesia kadang tersingkir oleh perannya sebagai proklamator atau wakil presiden pertama. Meski demikian, benih-benih yang ditebarkan Bung Hatta memiliki andil besar dalam penyelenggaraan politik luar negeri (polugri) Indonesia saat ini. Meskipun demikian, pemaknaan dan penerapan prinsip bebas aktif menuai polemik dan perenungan pragmatis.
Sejarah Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Lahirnya prinsip bebas aktif ditandai oleh penolakan Hatta untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet yang nantinya akan diikuti oleh pertukaran konsul. Pada akhir 1947 hingga awal 1948, Soeripno, seorang anggota PKI (Partai Komunis Indonesia), dikirim oleh Presiden Sukarno ke Eropa Timur untuk mengajukan usul tersebut. Walaupun sudah diumumkan oleh Uni Soviet melalui Kantor Berita TASS, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tidak mengakui hubungan diplomatik tersebut. Alasannya, Suripno tidak mendiskusikannya terlebih dahulu dengan menteri di Indonesia. Tindakan tersebut dianggap tidak mewakili Indonesia dan Suripno dianggap tidak memiliki wewenang ataupun kedudukan yang jelas di Uni Soviet. Tokoh yang menyampaikan penolakan terhadap tindakan Suripno di antara lain Agus Salim dan Moh. Hatta.
Menurut Michael Leifer dalam buku Politik Luar Negeri Indonesia, Hatta malu karena perjanjian itu berisiko menimbulkan kemarahan pada kubu seberang, Belanda dan Amerika Serikat (AS), yang memiliki peran strategis kala itu. Belanda adalah lawan berunding Indonesia di Perjanjian Renville, sementara AS adalah mediator keduanya. Dalam keterangannya kepada wartawan Aneta sebagaimana dikutip Pelita Rakjat, 7 Juni 1948, Hatta mengungkapkan, “Indonesia tidak berniat untuk memperluas hubungan”. Hatta kemudian mengungkapkan pada Komisi Jasa-Jasa Baik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa suatu perjanjian konsuler dengan Uni Soviet tidak akan berlangsung selama ia menjabat sebagai perdana menteri (Januari–Desember 1948).
Iktikad baik untuk melaksanakan dasar-dasar Persetujuan Renville turut digerus oleh carut-marut domestik. Fraksi FDR (Front Demokrasi Rakyat; terdiri atas Partai Sosialis pimpinan Amir Sjarifuddin, Pesindo, Partai Buruh, PKI, dan SOBSI), yang awalnya gencar mendukung Renville, malah memutarbalikkan sikapnya dan menjadi oposisi. Hatta mencatat, pada masa itu, FDR mengusulkan pembatalan Persetujuan Renville dan penghentian upaya perundingan dengan Belanda. Tokoh-tokoh Kiri, seperti Nyoto dan Tan Ling Djie, mengusulkan agar Indonesia menegakkan “doktrin Soviet” dan menyatakan keberpihakan pada blok Kiri. Mereka yakin bahwa Indonesia yang tengah melawan imperialisme Barat harus memilih blok komunis yang sama-sama menjunjung tinggi semangat anti-imperialisme.
Hatta menganggap bahwa Indonesia memerlukan suatu “jalan tengah” yang rasional dan realistis dengan berdasar pada kepentingan nasional. Menurutnya, Indonesia harus bisa percaya diri dan berdikari. Pertentangan antara kedua kubu adidaya di Perang Dingin seharusnya dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kepentingan Indonesia, bukan justru menghancurkan Indonesia. Bahkan, dalam sepucuk surat pribadi kepada Presiden Sukarno tertanggal 12 September 1957, ia menulis bahwa kegagalan untuk mewujudkan hal ini sangat berbahaya karena “yang beruntung hanya dua golongan, yaitu Soviet-Rusia dan Amerika”.
Pada Februari 1948, Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengemukakan dasar-dasar awal prinsip nonblok sebagai pernyataan ketidakberpihakan pada Uni Soviet. Kemudian, pada 2 September 1948, Hatta menerangkan di hadapan BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) bahwa Indonesia tidak akan berpihak pada blok mana pun
Dalam buku Mendayung antara Dua Karang, Hatta mengungkapkan:
“Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? … Kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia Merdeka seluruhnya.”
Sejak keterangan itu, politik luar negeri Indonesia disebut bebas aktif. Bebas artinya menentukan jalan sendiri tanpa terikat pada blok mana pun; aktif artinya giat bekerja menuju perdamaian dunia dan persahabatan antarbangsa.
Prinsip Bebas Aktif dalam Alam Pikiran Bung Hatta
Prinsip bebas aktif mencerminkan kehati-hatian dan keengganan Hatta menyinggung blok-blok yang bertikai dalam Perang Dingin. Bagi Hatta, memilih salah satu blok hanya akan memperbesar lingkaran musuh Indonesia. Bila Indonesia berpihak pada salah satu blok, blok yang lain merasa tidak senang dan bisa saja membantu Belanda. Hatta menyebut ini sebagai “politik bunuh diri”. Lebih lanjut, trauma Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah menyadarkan bahwa sudah waktunya Indonesia membebaskan diri dari keberpihakan pada bangsa-bangsa besar.
Prinsip bebas aktif tidak berarti bahwa Hatta apatis terhadap dinamika politik internasional. Hatta menyadari, sejatinya, tiap bangsa tidak boleh hanya bertindak sebagai pengamat pasif dinamika internasional; ia harus aktif membangun persaudaraan dan kesetaraan bangsa-bangsa. Kendati demikian, Hatta lebih menitikberatkan perlunya kesejahteraan domestik sebagai langkah pertama menentukan sikap dalam hubungan internasional.
Hatta meyakini, kosmopolitanisme (keyakinan bahwa semua manusia dan bangsa berasal dari satu komunitas dan memiliki kedudukan yang sama) hanya dapat diwujudkan dengan cara “menyempurnakan lebih dahulu individualistis atau zaman kemanusiaan sendiri, menyempurnakan bangsa sendiri”. Keyakinan foreign policy begins at home (politik luar negeri dimulai dari rumah) ini diungkapkan oleh Hatta melalui sebuah analogi sederhana: “ibarat kue, jangan kita sampai hanya sibuk membagi, yang lebih penting adalah memperbesar kue itu.”
Argumen Hatta ialah betapa lemahnya internasionalisme dalam konteks tertentu. Hatta mencontohkan, gagalnya Partai Buruh Irlandia serta PKI dalam menggalang simpati massa ialah karena visinya terlalu berfokus pada internasionalisme. Padahal, yang betul-betul dibutuhkan rakyat adalah perbaikan nasib di tingkat domestik, misalnya melalui upaya pemerataan pendapatan. Kestabilan domestik nantinya akan menentukan kedudukan negara dalam percaturan politik internasional. Pemikiran ini tertulis dalam Daulat Rakyat No.13: “syarat utama untuk mencapai tingkat paling tinggi ini ialah menyelamatkan dahulu kebangsaan Indonesia dengan tenaga sendiri”.
Negara Indonesia yang merdeka tidak hanya menekankan semangat anti-kolonialisme-imperialisme, tetapi juga kebebasan dari segala bentuk penindasan. Hatta menegaskan bahwa, tidak seperti konsepsi ala Barat yang mengagungkan kebebasan pribadi dan individualisme, nasionalisme Indonesia harus berlandaskan pada kolektivisme “sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat”. Menariknya, dalam surat yang sama, Hatta juga menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip bebas aktif “akan menyukarkan saja pertumbuhan sosialisme di Indonesia” dan “bertentangan dengan kepentingan Indonesia”.
Cita-cita sosialis ini agaknya tidak aneh, mengingat latar belakang Hatta sebagai pemikir berhaluan Kiri. Minat baca Hatta yang tinggi mengenalkannya pada paham-paham sosialisme dan marxisme. Pengalamannya tinggal di Belanda selama bertahun-tahun serta kunjungan-kunjungannya ke negara-negara lain di Eropa yang sudah “melek” politik menyadarkan pentingnya Hatta akan demokrasi. Diduga bahwa Hatta menganut paham sosialisme demokrasi yang marak berkembang di beberapa negara Eropa pasca-Perang Dunia I.
Prinsip Bebas Aktif dalam Hubungan Internasional Kita Kini
Prinsip bebas aktif yang dicetuskan Hatta memperoleh dukungan pada Konferensi Asia-Afrika (1955) di Bandung. Dasasila Bandung melahirkan Gerakan Nonblok dan menyisakan spirit yang masih tersisa dalam praktik politik luar negeri Indonesia dewasa ini. Dalam sejarahnya, memang terkadang politik luar negeri Indonesia lebih mendekat ke salah satu blok atau negara adidaya. Sebut saja Indonesia pada 1960-an, di bawah diplomasi pribadi Sukarno, yang mendekat ke blok Kiri, atau Indonesia pada era Suharto di bawah Menteri Luar Negeri Adam Malik yang mendekat ke Amerika Serikat.
Hatta pun tidak luput dari hal itu. Ia juga sebenarnya diam-diam mengharapkan bantuan Amerika Serikat terhadap Indonesia yang tengah menghadapi Belanda. Namun, Hatta adalah pemimpin dengan politiek fatsoen (kesopanan politik). Dalam berpolitik, ia menyadari bahwa ambisi pribadi wajib dipisahkan. Sebagai upaya konkret mewujudkan dinamika hubungan internasional yang kondusif, Hatta bahkan menolak kerja sama internasional yang melanggar prinsip bebas aktif. Hal itu pernah ia ungkapkan dalam suratnya kepada Presiden Sukarno tertanggal 17 Juni 1963. Hatta mengkritik gagasan pendirian konferensi negara-negara rumpun Melayu (Konfederasi Malaysia-Filipina-Indonesia alias Mafilindo). Hal ini karena Filipina dan Malaysia menyatakan penolakan tegas terhadap komunisme serta dalam beberapa bidang terikat kepada politik blok Barat.
Aspek “bebas”, jika berdiri sendiri, rentan dijadikan tameng pembenaran untuk menjaga jarak dari konflik dan menjadi bystander, sekadar pengamat pasif dinamika dunia. Untuk itu, “bebas” dan “aktif” perlu berjalan bergandengan. Untuk memahami dirinya sendiri, negara perlu membuka jendela dan melihat keluar. Diplomasi kini menjadi hak sekaligus kewajiban nasional. Aktif berdialog dan berpartisipasi dalam dinamika dunia adalah jantung kedaulatan dan keberadaan nasional.
Indonesia memiliki aset untuk mewujudkan itu; sebut saja PDB (produk domestik bruto) Indonesia yang setara dengan sekitar 40% total PDB ASEAN, atau potensi ekonomi kreatifnya yang telah diakui turis mancanegara. Sayangnya, cara kita memaknai dan mengaplikasikan prinsip bebas aktif – disertai oleh bentrokan politik domestik – menghalangi Indonesia untuk benar-benar mempraktikkan perannya sebagai “stabilisator kawasan” sebagaimana yang diidam-idamkan. Kepasifan ini, ironisnya, bertolak belakang dengan apa yang dimaksudkan Hatta saat merumuskan prinsip ini di hadapan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Pertanyaan besar kini tersisa: masih relevankah prinsip-prinsip yang dicetuskan oleh Hatta itu, sedangkan nilai dan prinsip selalu berubah dalam dimensi ruang dan waktu?
Dalam konteks pasca-Perang Dingin dan perubahan-perubahan sosiokultural, pemaknaan “bebas” mungkin telah agak bergeser. Dengan bangkitnya Tiongkok sebagai penyaing hegemoni Amerika Serikat, aspek “bebas” dapat dilihat jelas dalam bidang ekonomi, misalnya, dari banyaknya korporasi multinasional dari kedua negara tersebut yang menjalankan aktivitasnya di Indonesia.
Prinsip bebas aktif memang kurang sesuai jika ditelan mentah-mentah dalam konteks pasca-Perang Dingin. Namun, senyawa dasarnya tetap bertahan: Indonesia tetap berdiri di pihak yang benar dalam sejarah dengan terus berprakarsa mencapai perdamaian internasional. Hal ini memang terkesan utopis selagi kekuatan-kekuatan besar tetap ada. Oleh sebab itu, kewajiban Indonesia adalah menentukan titik tengah antara kepentingan politis dan moralitas. Terlepas dari segala perdebatannya, Indonesia harus senantiasa memperbarui teori, menggalakkan praktik, dan kembali ke esensi murni prinsip bebas aktif dalam alam pikiran Hatta sembari menyesuaikannya dengan tuntutan global saat ini.

Dinar Maharani Hasnadi adalah mahasiswi ilmu Hubungan Internasional yang menulis untuk memahami.
Artikel Terkait
Membangun Dinasti di Negara Demokrasi: Geliat Politik Keluarga di Indonesia
Politik dinasti jadi penyakit demokrasi. Bagaimana demokrasi Indonesia bergulat dengan politik dinasti?Mengapa Kita Tak Bisa Jadi Pemilih yang Rasional
Meskipun dalam teori politik dan demokrasi seorang warga negara sering digambarkan sebagai manusia rasional, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita sering dikuasai emosi. Memikirkan kembali Pemilu 2019 yang baru saja lewat, di Catatan Pinggir kali ini, Laila Achmad membahas mengenai sulitnya menjadi seorang pemilih rasional.Politik: Seni Berpikir Kritis Bukan Apatis
Ini akan terdengar sebagai suatu pembuka bacaan yang klise, namun kata ‘Politik’ sudah menjadi bagian dari makanan sehari-hari kita sebagai masyarakat Indonesia. Namun, apakah Politik itu menjadi asupan yang kita santap dengan penuh antusiasme?