
Dinding Pembatas itu Bernama ‘Warna Kulit’
September 2, 2020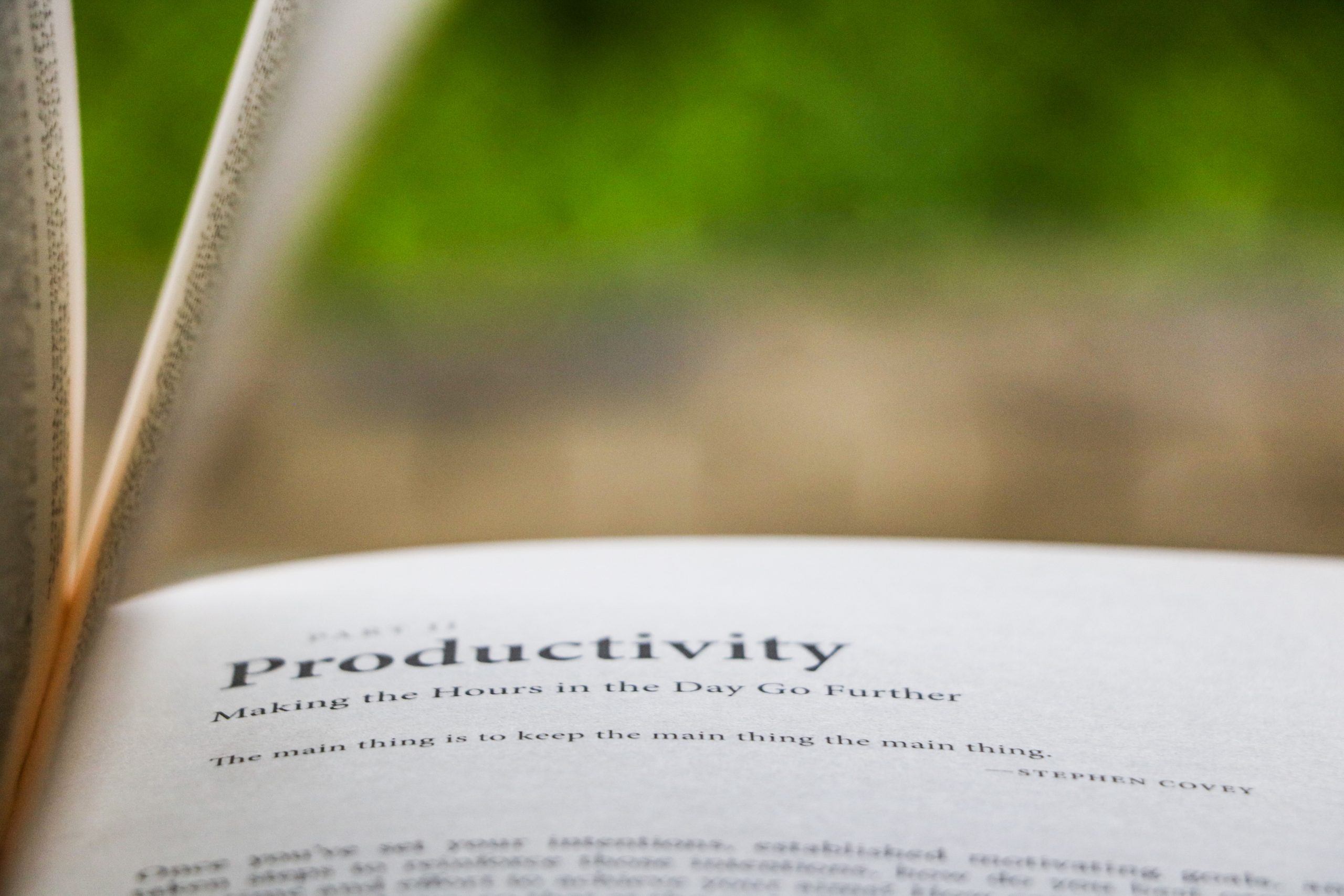
Sibuk Tanda Kesuksesan, Tidak Sibuk Tanda Kemalasan?
September 4, 2020OPINI
Membaca ‘Gilang Bungkus’ dari Kacamata Ilmu Sosial
oleh Abdullah Faqih
Jagat sosial media baru-baru ini ramai membicarakan kasus ‘Gilang bungkus’. Gilang, seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi negeri di Surabaya, diduga telah melakukan pelecehan seksual yang dibumbui dengan tindakan manipulasi, intimidasi, dan kekerasan.
Pembicaraan mengenai kasus itu semakin mengemuka ketika para korban mengaku dipaksa pelaku untuk membungkus dirinya dengan menggunakan kain jarik. Dengan dalih melakukan penelitian akademik, tindakan membungkus korban dengan kain jarik itu rupanya hanyalah siasat pelaku untuk memuaskan hasrat atau fantasi seksualnya. Publik lalu beramai-ramai melabeli tindakan itu dengan sebutan ‘fetis bungkus kain jarik’.
Merespon kasus tersebut, para psikolog menyebut ‘fetis bungkus kain jarik’ itu sebagai parafilia, yaitu ekspresi seksual tidak lazim berbentuk ketertarikan pada benda-benda non-genital untuk merangsang hasrat seksual. Berbagai media arus utama juga banyak mengutip ungkapan para pakar yang menyebut hal itu sebagai kelainan seksual, bukan sebagai ‘fetis’ sebagaimana yang banyak dibicarakan orang-orang kebanyakan. Publik dunia maya pun mengamini hal itu dengan berbondong-bondong menyematkan komentar bernada penghakiman terhadap ‘fetis bungkus kain jarik’.
Pelabelan semacam itu, disadari atau tidak, telah mempolarisasi seksualitas seseorang ke dalam kategori ‘normal-tidak normal’ dan ‘menyimpang-tidak menyimpang’. Cara pandang tersebut cenderung menilai seksualitas secara kaku, parsial, dan hitam putih saja. Pandangan itu juga mereduksi kompleksitas seksualitas ke dalam kategorisasi yang terlalu sederhana. Selain tidak mampu menjelaskan bagaimana fetis seseorang dapat terbentuk, perspektif tersebut juga buta akan makna seksualitas yang cair (fluid) dan dinamis. Kacamata seksologi di ilmu kedokteran dan psikologi berada di balik itu semua. Mereka sebelumnya juga telah melakukan dikotomi serupa terhadap homoseksual yang dilabelinya sebagai bentuk abnormalitas dan heteroseksual sebagai satu-satunya yang normal dan dapat diterima.
Kita perlu mendudukkan persoalan fetis ini dalam kacamata ilmu sosial. Secara awam, fetis dapat kita pandang sebagai suatu kondisi yang mampu membuat hasrat dan kepuasan seksual kita meningkat berkali-kali lipat akibat adanya rangsangan dari objek-objek tertentu. Contohnya, rangsangan dengan menggunakan kaki (foot-fetish), berhadapan dengan partner yang memiliki ketiak berbulu atau kelamin tanpa rambut. Selain dipengaruhi oleh objek genital semacam itu, kenikmatan seksual seseorang juga tidak jarang dipengaruhi oleh objek-objek non-genital di luar tubuhnya. Sebagai misal, fetis mengenakan sepatu hak tinggi (heels), pakaian dalam (lingerie), seragam militer, kaos ketat-transparan, tindik, hingga tindakan-tindakan seperti merekam aktivitas seksual dengan menggunakan telepon genggam.
Lalu, apakah fetis-fetis semacam itu muncul dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Dalam ilmu sosial, fetis dipandang sebagai sesuatu yang tidak pasti (fixed), sudah ditentukan sebelumnya (given), alami, atau ada dengan sendirinya. Hendri Yulius dalam C*bul: Perbincangan Serius tentang Seksualitas Kontemporer menyebut bahwa fetis dibentuk dan dipengaruhi oleh pengalaman individu yang berkaitan dengan keberadaan industri pornografi, kapitalisme, teknologi, dan diskursus tentang seksualitas yang sedang beredar pada konteks tertentu. Sebagai domain seksualitas, fetis juga sering disebut sebagai seni perlawanan. Dalam referensi yang sama, Hendri Yulius menceritakan salah seorang teman laki-lakinya yang memiliki fetis golden shower, yaitu menyiram tubuh dengan air seni. Usut punya usut, fetis itu muncul lantaran laki-laki tersebut memiliki hasrat untuk melawan konstruksi “toilet-training” yang diajarkan oleh orang tuanya ketika dia masih balita. Air seni yang semestinya dibuang malah dijadikan objek untuk memuaskan hasrat seksualnya. Ketika dapat melawan hal-hal yang sudah dikonstruksi semacam itu, dia mengaku merasakan kenikmatan berlipat ganda. Demikianlah pengalaman individu ikut membentuk fetis kita.
Selain itu, fetis dan perilaku seksual kita juga tidak jarang dipengaruhi oleh keberadaan industri pornografi. Hampir tidak ada satu pun orang di dunia ini—baik laki-laki, perempuan, maupun identitas gender lainnya—yang tidak pernah menikmati pornografi. Bisa jadi di ruang publik kita memang mengutuk pornografi karena dinilai tabu, tetapi diam-diam, kita pasti menikmatinya. Dengan menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud, kita juga akan memperoleh jawaban mengenai pengaruh tontonan pornografi terhadap perilaku seksual. Dalam hal ini, keberadaan industri pornografi ikut membentuk preferensi kita terhadap fetis-fetis tertentu. Adegan yang dipertontonkan di dalam film porno juga tidak bermakna tunggal atau berdiri sendirian, melainkan ditopang oleh keberadaan teknologi dan kapitalisme. Sebagai misal, keberadaan layanan wax di pusat perbelanjaan yang ikut diuntungkan oleh konstruksi fetis ketiak tanpa rambut (clean porn). Perusahaan pembuat lingerie dengan beragam model dan warna juga ikut diuntungkan atas fetis tertentu yang dibentuk oleh industri pornografi. Fetis dan perilaku seksual kita dengan demikian tidak benar-benar murni muncul dari dalam diri kita, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kompleksitas tersebut.
Dalam kasus ‘Gilang bungkus’, kita tidak tahu —dan memang tidak harus tahu— bagaimana pengalaman hidupnya membentuk ‘fetis bungkus kain jarik’. Kita juga tidak pernah tahu bagaimana perjumpaan ‘Gilang bungkus’ dengan industri pornografi yang disokong oleh keberadaan teknologi, kapitalisme, maupun konteks sosial-budaya yang ikut membentuk preferensi fetisnya. Dengan demikian, kita tidak perlu terlalu terburu-buru menghakimi ekspresi seksual ‘fetis bungkus kain jarik’ itu sebagai sesuatu yang tidak normal dan menyimpang. Fetis tersebut sama sekali tidak memiliki perbedaan dengan BDSM (Bondage, Discipline, Sadism, Masochism), threesome (hubungan seksual yang dilakukan oleh tiga orang sekaligus), anal (memasukan penis melalui dubur), atau fetis-fetis lain yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. Hanya karena ‘fetis bungkus kain jarik’ terkesan aneh dan asing, saya pun baru pertama kali ini mengetahui seseorang memiliki fetis semacam itu, bukan berarti menjadi justifikasi untuk kita menyebutnya sebagai penyimpangan seksual.
Tidak ada ekspresi seksual yang baik-buruk maupun benar-salah. Tentunya, dengan syarat, disalurkan berdasarkan konsensus dan tidak menimbulkan kerugian apa pun pada seluruh subjek yang terlibat.” ~Abdullah Faqih Share on XKeluar dari dikotomi ‘normal-tidak normal’ menjadi penting sebab menyematkan label semacam itu akan mengungkung kebebasan ekspresi seksual seseorang. Bukan hanya berlaku pada ‘fetis bungkus kain jarik’, melainkan juga pada fetis-fetis lain yang bisa jadi jauh lebih ‘aneh’ daripada itu. Memberikan klaim ‘salah’ dan ‘tidak normal’ semacam itu seolah juga menjadi pembenaran bagi kita untuk mendefinisikan adanya fetis yang ‘benar’ dan ‘normal’. Hal ini amat berbahaya. Sebab, dalam seksualitas, segala bentuk ekspresi seksual itu patut dirayakan. Tidak ada ekspresi seksual yang hitam-putih, baik-buruk, maupun benar-salah. Tentunya, dengan syarat, ekspresi seksual tersebut disalurkan berdasarkan konsensus dan tidak menimbulkan kerugian apa pun pada seluruh subjek yang terlibat.
Dengan demikian, sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita dalam kasus ‘Gilang bungkus’ adalah perilaku manipulatif, intimidatif dan hasrat seksual yang diekspresikannya tanpa konsensus. Tidak menjadi masalah untuk memiliki hasrat seksual ‘fetis bungkus kain jarik’, asal diekspresikan atas dasar kesepakatan. Irisan antara ekspresi seksual ‘fetis bungkus kain jarik’ yang di dalamnya melekat tindak pelecehan seksual itu memang sangat tipis. Namun, kita tetap perlu jeli membedakannya. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengutuk ekspresi seksual seseorang (baca-‘fetis bungkus kain jarik’), tetapi kita lupa bahwa masalah paling substainsial yang harus kita perangi adalah tindak pelecehan seksual yang sarat akan manipulasi, intimidasi, dan kekerasan.

Abdullah Faqih sedang fokus mengerjakan penelitian dengan topik ‘agensi queer Muslim melawan heternormativitas’ sambil diselingi menonton drama Korea. Memiliki hobi membaca, menulis, dan makan donat. Memiliki harapan besar untuk dapat segara menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada.
Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini








