
Benarkah Digital Activism Dapat Mempengaruhi Kesehatan Mental?
October 16, 2021
Pembajakan Buku: Upaya Pembebasan Ilmu Pengetahuan atau Tindak Kriminal Etika Moral?
October 24, 2021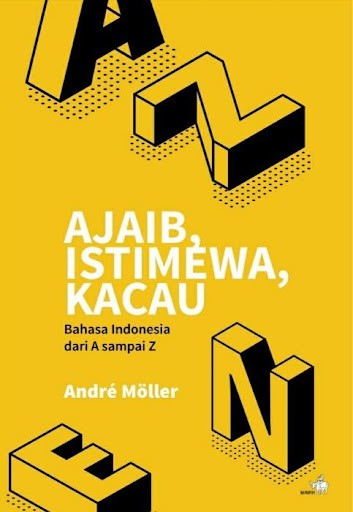
RESENSI BUKU
Mengenal Bahasa Indonesia dan Mengevaluasi Penutur Jatinya dari Sudut Pandang Penutur Asing
oleh Silvy Rianingrum
Mengapa banyak sekali penutur jati bahasa Indonesia yang tidak bisa menggunakan bahasanya dengan baik dan benar? Möller meyakini salah dua alasannya adalah kemalasan dan gengsi.
Saya sering bertanya-tanya, akan dibawa ke manakah bahasa Indonesia? Apakah penutur jati bahasa Indonesia sudah cukup mengenal bahasanya sendiri? Apakah yang sudah, sedang, dan akan diupayakan penuturnya demi kelestariannya?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini seringkali muncul ketika saya menyaksikan beberapa fenomena kebahasaan di media sosial yang menyalahi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), misalnya tren menambahkan prefiks meng- ke morfem yang tidak memiliki bakat menjadi verba atau ke morfem yang justru sudah memiliki bentuk verbanya sendiri. Contohnya adalah “mengsedih.” Setelah membaca beberapa buku, saya mengetahui, ternyata ada banyak orang dan tokoh yang juga mengkhawatirkan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah André Möller.
Möller adalah seorang penutur asing bahasa Indonesia asal Swedia yang menginjakkan kaki di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1995, kemudian menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 1999. Banyak tulisan Möller yang telah dimuat oleh harian Kompas. Melalui bukunya yang berjudul Ajaib, Istimewa, dan Kacau: Bahasa Indonesia dari A sampai Z, Möller mengisahkan perjalanannya mengenali bahasa Indonesia dan, dengan frontal, mengevaluasi penutur jatinya.
Sebetulnya, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi sebagian besar orang Indonesia. Hal ini pun disebutkan oleh Möller. Sekiranya, hanya lima persen dari penduduk Nusantara yang menggunakan bahasa Melayu dalam variasi bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu. Meskipun begitu, saya tetap akan menggunakan istilah penutur jati untuk penutur bahasa Indonesia asal Indonesia, sekalipun bahasa ibu mereka adalah bahasa daerah. Ini berdasar pada pernyataan dosen psikolinguistik saya. Beliau bilang, bahasa daerah dan bahasa Indonesia adalah bahasa ibu masyarakat Indonesia karena keduanya diperoleh penuturnya dalam waktu yang (nyaris) bersamaan.
Sebagai penutur asing, Möller tentu mengarungi arus yang berbeda dari penutur jati. Penulis buku Ajaib, Istimewa, dan Kacau: Bahasa Indonesia dari A sampai Z tersebut melihat apa yang banyak penutur jati tak sadari sebelumnya. Möller berusaha merangkum hal-hal tersebut melalui berbagai kata berawalan huruf A hingga Z secara berurutan. Kata-kata tersebut digunakannya sebagai judul setiap bab dalam buku ini. Alhasil, buku ini memuat 26 bab. Kebanyakan bab dimulai dengan adjektiva yang dianggapnya mendeskripsikan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah “eksotis.”
Adjektiva ini dipilih penulis untuk menggambarkan keterpesonaannya terhadap bahasa Indonesia—atau mungkin bahasa Bali—yang saat itu didengarnya ketika tiba di Bali pada tahun 1995. Saya sempat mengernyitkan dahi saat membacanya. Pasalnya, sependek pengetahuan saya, kata ini mengandung kesan kolonial yang membedakan manusia berdasarkan wilayah, warna kulit serta etnisitas, dan berdasar pada supremasi kulit putih, sebagaimana disebutkan oleh Staszak (2008).
Penulis dalam sekapur sirihnya mengomentari bahwa memanggil seseorang dari Barat “bule” ketinggalan zaman dan tidak tepat karena ada dari mereka yang berkulit gelap, bahkan lebih gelap dibanding orang Papua. Sebetulnya, setelah apa yang dikenal sebagai Bali conflict, sebuah argumen panjang di Twitter yang terjadi pada awal tahun 2021, kata “bule” mengalami perluasan makna, sehingga tidak lagi bersandar pada warna kulit. Selain kata ini, penulis juga mengomentari penggunaan wong Londo. Singkatnya, penulis hendak mengatakan bahwa tidak semua orang kulit putih berasal dari Belanda.
Saya setuju dengan penulis yang secara gamblang menyatakan bahwa pengelompokkan manusia dan penyematan julukan berdasarkan warna kulit sangatlah ketinggalan zaman. Sebagaimana penulis, saya pun mendukung pemaknaan ulang kata-kata tertentu sebagai bentuk dekolonisasi. Namun, mengapa penulis menggunakan adjektiva yang berakar pada kolonialisme dan supremasi kulit putih? Inilah realitanya, tidak sedikit kata berkesan kolonial masih banyak digunakan hingga saat ini. Jadi, apakah sebaiknya kata-kata berkesan kolonial itu dihapuskan, dipersempit, digeser, atau diperluas maknanya sehingga dapat dipahami dengan cara pandang baru? Atau, apakah sebaiknya tidak menggunakan kata itu sama sekali?
Selain “eksotis,” penulis juga mendeskripsikan bahasa Indonesia dengan adjektiva lain. Namun, hanya sedikit yang memang mewakilkan kenyataan. Itu pun karena alasan di balik pemilihan adjektiva tersebut bersifat objektif dan faktual. Misalnya, “dolak-dalik” yang menerangkan ciri bahasa secara umum; hierarkis dan halus, yang mengacu pada karakteristik kelompok pengguna bahasa Indonesia; serta nasional dan resmi, yang menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia dalam negeri. Sementara itu, agar adjektiva lainnya—seperti cukup, istimewa, dan zakiah—menjadi kenyataan, penutur jati bahasa Indonesia perlu dan harus berjuang.
Apakah alasan penutur jati bahasa Indonesia merasa bahasanya terlalu baku, kaku, hingga ketinggalan zaman dan kurang keren di dunia yang katanya modern ini? Mengapa banyak sekali penutur jati bahasa Indonesia yang tidak bisa menggunakan bahasanya dengan baik dan benar? Möller meyakini salah dua alasannya adalah kemalasan dan gengsi.
Kemalasan menyebabkan penutur jati tidak giat mencari padanan dari kata berbahasa asing, pun menyebabkan mereka tak acuh dengan PUEBI. Bagi kebanyakan penutur jati, selama mereka dapat saling mengerti satu sama lain, mereka tidak membutuhkan pengetahuan lebih jauh dan utuh mengenai bahasa mereka sendiri. Segalanya diterima sebagaimana adanya. Mereka pun lebih menerima apa yang sudah familiar dan merasa cukup dengannya, sehingga kesadaran berbahasa pun minim.
Alhasil, banyak penutur jati yang menganggap bahasa Indonesia sebagai produk kelas bawah, padahal mereka sendiri yang tidak menggunakannya dengan baik. Möller yakin, jika penutur jati bahasa Indonesia kreatif dan berpengetahuan mengenai bahasa mereka, maka bahasa Indonesia akan cukup, relevan, dan mutakhir.
Selanjutnya adalah gengsi. Hal ini dianggap Möller sebagai penyebab maraknya penggunaan bahasa Inggris di berbagai tempat di Indonesia, seolah-olah bahasa Indonesia tidak memiliki padanan dan tidak mencukupi kebutuhan berbahasa sehari-hari para penutur jatinya. Untuk mengilustrasikannya, Möller menceritakan pengalamannya memesan minuman. Ketika Möller mengatakan kopi es, pelayan di tempat itu tidak menangkap maksudnya karena lebih terbiasa mendengar dan mengucapkan ice coffee. Möller sampai meminta istrinya yang berasal dari Jawa Tengah untuk mengulangi apa yang dilakukannya.
Menurutnya, penggunaan bahasa Inggris seperti itu menunjukkan ketidakkonsistenan yang rentan menjelekkan bangsa sendiri, pun merendahkan bahasa Indonesia. Bahkan, penulis tidak segan memosisikan bahasa Inggris sebagai salah satu tantangan sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Penulis juga membahas sedikit xenoglosofilia, yakni kesukaan berlebihan terhadap bahasa asing (hlm. 154), sambil mengulas singkat buku Uda Ivan Lanin yang berjudul Xenoglosofilia: Kenapa harus Nginggris? Meskipun saya setuju bahwa ada gengsi yang melatarbelakangi penggunaan bahasa Inggris, saya menyadari adanya faktor lain, seperti paparan media dan desakan institusi.
Tak hanya itu, Möller juga mengingatkan sekaligus menekankan kedudukan penting bahasa Indonesia dengan merunut sejarahnya secara singkat. Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca di Melayu semasa pemerintahan kolonial. Kemudian, bahasa Indonesia menempati peran sangat penting sebagai bahasa pemersatu, bahasa yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Ia pun ditetapkan sebagai bahasa negara secara resmi oleh Soekarno melalui Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 36 bab XV.
Yang terpenting dari semua ini adalah bahwa bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, dan alat pemersatu (hlm. 108). Möller menuturkan bahwa memiliki bahasa nasional adalah sebuah anugerah, nikmat dan kesuksesan bagi sebuah bangsa. Kemudian, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penulis berharap agar penyalahgunaan bahasa oleh pihak tertentu—misalnya perusahaan—pada kesempatan tertentu dapat diancam dengan hukuman denda dan penjara. Penyertaan kilas balik dan dasar hukum ini menunjukkan kedalaman pengetahuan penulis mengenai bahasa Indonesia.
Selain itu, Möller menominasikan keberagaman bahasa daerah sebagai salah satu solusi pencarian padanan dalam bahasa Indonesia dari bahasa asing. Namun, penulis sepertinya tidak memperhitungkannya sebagai salah satu alasan mengapa orang Indonesia kerap membuat kesalahan saat berbahasa Indonesia. Sebagaimana sudah disebutkan di awal, sedikit sekali penutur (jati) bahasa Indonesia yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Bahkan, menurut sensus tahun 2010 lalu, hanya sekitar 19,94% penduduk yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari di rumah. Sebanyak 79,45% persen menggunakan bahasa daerah. Contoh menarik (dalam ranah profesional) dapat dilihat pada cuitan Aan Mansyur berikut ini:
jangan-jangan betul bahwa umumnya pekerjaan pertama penulis berbahasa indonesia adalah penerjemah. tiap kali menulis, saya merasa seperti itu; saya berusaha menerjemahkan bahasa & ‘konsep’ yang ‘bugis’ di kepala saya ke dalam bahasa indonesia.
— m aan mansyur (@hurufkecil) April 7, 2021
Penggunaan bahasa daerah yang memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia sudah pernah dikritik sebelumnya, salah satunya oleh Uda Ivan Lanin dalam bukunya yang berjudul Recehan Bahasa. Meskipun saya setuju, saya sedikit-banyak lebih bersimpati kepada bahasa daerah. Bahasa Indonesia saja seringkali dianggap ketinggalan zaman oleh penuturnya, bagaimana nasib bahasa daerah yang erat kaitannya dengan budaya dan tradisi? Pada tahun 2011 hingga 2019, sebanyak 11 bahasa daerah di Indonesia punah. Sebenarnya, mengenai kerumitan berbahasa ini, Badan Bahasa sudah sangat jelas mengampanyekan pesannya: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
Secara keseluruhan, buku Ajaib, Istimewa, dan Kacau: Bahasa Indonesia dari A sampai Z yang setebal 176 halaman ini menyadarkan penutur jati bahasa Indonesia dan menggebrak semangat mereka untuk tanpa henti mempelajari dan menjunjung bahasa Indonesia. Meskipun terdapat beberapa pengulangan, buku ini memuat cukup banyak informasi baru. Selain ditulis berdasarkan pengalaman pribadi yang mendekatkan pembaca dengan pokok bahasan dan penulisnya, buku ini juga dilengkapi data pendukung yang mengukuhkan pandangan penulis.
Buku ini ditulis dengan lincah dan disusun dengan renyah, sehingga dapat dibaca oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sudah waktunya penutur jati berhenti mengelak dengan tameng tak kokoh mereka, yakni “yang penting, kan, sama-sama ngerti,” dan memulai perjalanan panjang mempelajari bahasa Indonesia. Sudah waktunya penutur jati menyadari bahwa bahasa Indonesia bermartabat. Pada akhirnya, sebagaimana Möller tuliskan, “Tingkat keistimewaan sebuah bahasa antara lain dapat diukur oleh tingkat kebanggaan para penuturnya. Bahasa Indonesia jadi istimewa kalau kita semua mengistimewakannya. Mari, mulai!”
Silvy Rianingrum, mahasiswi Sastra Inggris Universitas Padjajaran. Pembaca poligamis yang suka menulis. Sebetulnya, tidak pernah mengenalkan dirinya selain sebagai penjelmaan Odradek.
Dapat dihubungi melalui akun sosial media Instagram: @svaparesi.
Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini






