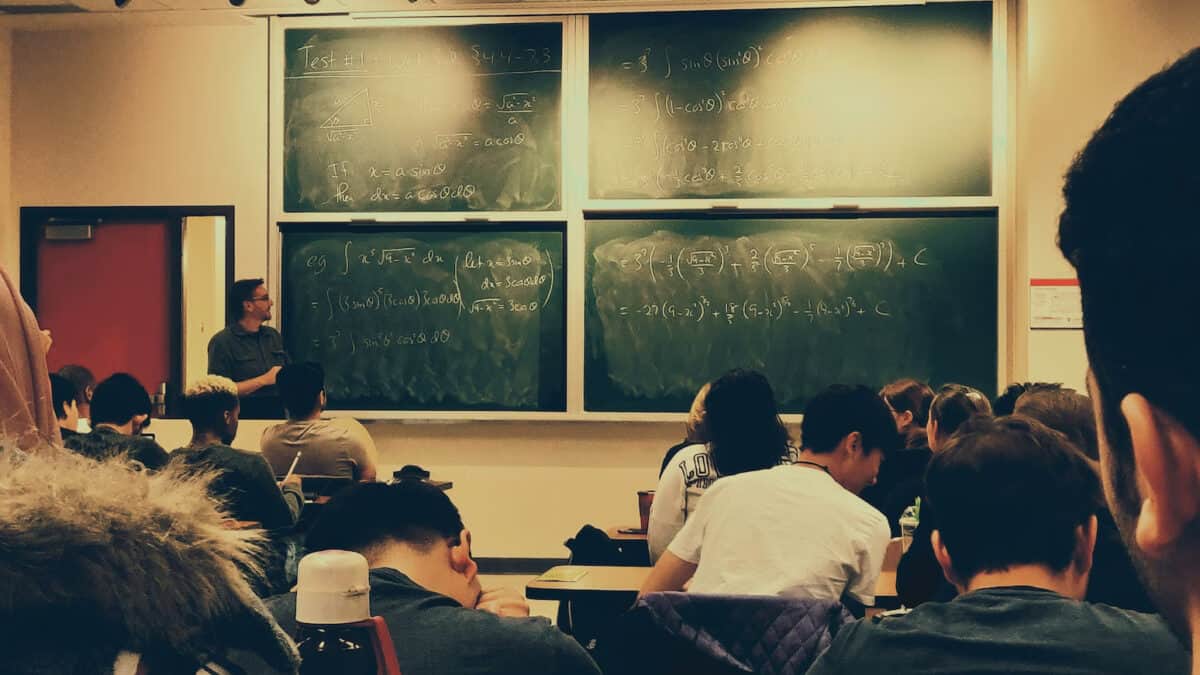COP 27: Aksi dan Pendanaan Iklim
May 9, 2023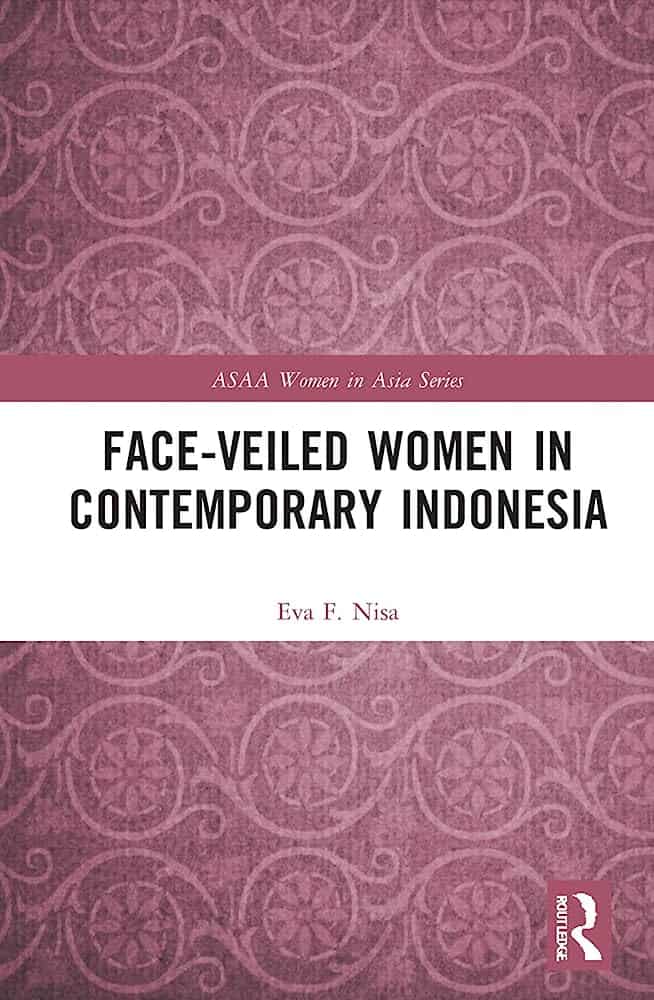
Habitus dan Agensi Ketaatan dalam Kelompok Muslimah Bercadar
June 26, 2023
Photo by Subham Sharan on Unsplash
OPINI
Nasib Pekerja Akademik di Kabupaten
oleh Kasmiati
Narasi tentang kesejahteraan pekerja akademik kembali ramai didiskusikan, termasuk soal pentingnya mereka untuk berserikat. Meskipun agak terlambat, upaya ini perlu didukung.
Pekerja akademik, terutama dosen, perlu menyadari bahwa mereka adalah buruh, dan sialnya, mereka adalah buruh yang dieksploitasi negara atas nama kemuliaan dan kemajuan sumber daya manusia. Embel-embel kerja mulia itu membuat tuntutan atas hak-hak dasar bagi pekerja akademik, termasuk upah yang layak, sering dianggap sebagai bentuk rasa tidak bersyukur. Ujung-ujungnya, pekerja akademik yang menuntut hak-hak dasarnya rentan mengalami serangan secara pribadi (ad hominem).
Termasuk dalam menuliskan artikel ini, serangan secara pribadi tadi sangat mungkin saya alami. Tapi, sebelum berbicara lebih jauh, saya ingin mengatakan apabila ada pekerja akademik dari berbagai institusi yang ternyata juga turut merasakan cerita yang akan saya tuturkan ini, maka kita perlu melihat masalah ini sebagai sesuatu yang sifatnya struktural, bukan gerutu orang per orang semata.
Kita perlu melihat masalah kesejahteraan dosen ini sebagai sesuatu yang sifatnya struktural, bukan gerutu orang per orang semata. ~Kasmiati Share on XMasalah Kesejahteraan Tak Pandang Batas Ruang
Sudah menjadi rahasia umum kalau perbandingan antara upah dan beban kerja dosen memang jauh dari kata sejahtera. Survei nasional tentang kesejahteraan akademisi yang dilakukan oleh dosen dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Mataram menunjukkan bahwa hampir 50% dosen di Indonesia menerima pendapatan tetap di bawah Rp 3 juta per bulan. Angka itu masih di bawah rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sebesar Rp 2,9 juta pada 2023.
Bagi saya yang punya pengalaman bekerja sebagai dosen tetap non-PNS di sebuah perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi sekitar tahun 2017 sampai 2019, gaji pokok yang saya terima malah jauh lebih mengenaskan. Saya dan juga rekan-rekan dosen hanya menerima setengah dari angka tadi, yaitu sebesar Rp.1,5 juta per bulan dengan beban kerja penuh. Kami dituntut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kerja tri dharma–mengajar, meneliti dan mengabdi pada masyarakat–tetapi tidak cukup mampu memberi makan diri sendiri dan keluarga. Saya kira situasi itu belum mengalami perubahan berarti hingga tahun 2023 saat ini.
Saat ini, kritik perihal kesejahteraan dosen lebih banyak disuarakan oleh pekerja akademik dari kawasan Barat Indonesia atau dari institusi mapan yang lebih sering menikmati hak istimewa (privilege), dekat dengan pemerintah, serta sering dijadikan acuan ideal bagi institusi di daerah lain.
Hal itu memunculkan sebuah pertanyaan, “Kalau institusi mapan, besar dan dianggap lebih independen saja dosen-dosennya jauh dari sejahtera, bagaimana dengan kami, pekerja akademik di kabupaten, yang institusinya masih banyak berstatus Satuan Kerja (Satker)?” Belum lagi, kami masih harus berhadapan dengan masalah infrastruktur yang serba terbatas dan mayoritas dosen belum memiliki sertifikasi dengan jabatan fungsional masih rendah.
Bagaimana Kami Bertahan Hidup?
Hari-hari para pekerja akademik di kabupaten, khususnya dosen-dosen muda dari kampus dengan strata terendah, dipenuhi rasa waswas dan cemas tiap kali melewati minggu kedua setiap bulan, terutama apabila uang LP (lauk-pauk) belum masuk ke rekening. Kami mulai harus bersiasat untuk bertahan hingga awal bulan berikutnya dan memastikan cicilan rumah tetap bisa terbayar–tentu saja rumah subsidi yang sumpek, tanpa dapur dan taman.
Bagi kami, uang LP tadi sangat penting, karena itu adalah sumber tambahan uang bulanan satu-satunya yang bisa kami peroleh di luar gaji pokok yang masih di bawah rata-rata UMP. Uang LP itu pun diberikan berdasarkan sistem absensi yang menguras waktu dan bahkan kurang menguntungkan bagi pekerja akademik. Ketika sedang melakukan kerja pengabdian atau penelitian atau tidak hadir di kampus, uang LP tidak akan dihitung, padahal kami sedang menunaikan kewajiban yang lain.
Selain itu, kerja pengabdian dan penelitian bagi dosen adalah kewajiban yang bebannya sama dengan pengajaran. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, ketiga kewajiban tersebut harus bisa dilaksanakan. Melakukan penelitian dan pengabdian, terutama untuk rumpun ilmu sosial yang biasanya mengharuskan perjalanan ke luar kampus tentu saja membutuhkan biaya. Kalau tidak memperoleh dukungan pendanaan, kami terpaksa harus mengeluarkan biaya sendiri yang artinya menambah satu beban pengeluaran bagi dosen. Kami seperti jatuh tertimpa tangga: kehilangan kesempatan memperoleh uang LP dan harus merogoh kocek sendiri untuk menunaikan tri dharma.
Parahnya lagi, banyak pekerja akademik di kabupaten yang jangankan memiliki ruang kerja sendiri, satu meja atau kubikel untuk menyimpan peralatan kerja seperti laptop, tas, berkas, dan bekal pun tidak tersedia. Kami harus menenteng gembolan dari satu ruang kelas ke ruang kelas lainnya. Padahal, kerja dosen adalah kerja memproduksi pengetahuan yang selain turun lapangan untuk meneliti, juga mengharuskan kami untuk duduk membaca, berefleksi dan menulis. Bagaimana kami melakukan tugas itu tanpa ruang yang aman dan nyaman?
Selain itu, universitas di kabupaten juga memiliki infrastruktur yang relatif terbatas: jalan-jalan dalam kampus atau menuju kampus curam, licin dan berbahaya, terutama saat hari-hari hujan. Bahkan, saya sengaja membeli sepatu dengan kualitas tiruan (KW) untuk dipakai mengajar, supaya bisa ‘tenang’ saat menghadapi hari-hari hujan, banjir, dan berlumpur ketika menuju kampus.
Alat peraga juga sering kali masih terbatas. Misalnya saja LCD (Liquid Crystal Display), satu fakultas kadang hanya memiliki dua hingga tiga LCD, padahal ada beberapa dosen yang harus mengajar dalam sehari dan membutuhkan alat tersebut. Selain itu, melihat dosen dan mahasiswa kipas-kipas kegerahan saat berada di kelas karena alat pendingin (AC/air conditioning) mati adalah pemandangan lumrah.
Kerja dosen adalah kerja memproduksi pengetahuan yang selain meneliti, juga mengharuskan kami untuk duduk membaca, berefleksi dan menulis. Bagaimana kami melakukan tugas itu tanpa ruang yang aman dan nyaman? ~Kasmiati Share on XMenatap Masa Depan Dosen di Kabupaten
Tahun ini, negara mencoba merespon masalah kesejahteraan pekerja akademik melalui penghiburan yang tidak adil, yaitu dengan memberi tunjangan profesi tambahan sebesar 50 persen. Namun, tunjangan itu hanya diberikan kepada dosen yang telah memiliki sertifikasi. Artinya, mereka yang setiap bulan telah memperoleh tambahan gaji melalui sertifikasi akan memperoleh uang tambahan sebesar 50% dari gaji pokok mereka. Sementara itu, para dosen yang belum bersertifikasi–yang memiliki pendapatan paling rendah, jumlahnya mayoritas, dan paling membutuhkan bantuan–malah tidak memperoleh dukungan apa-apa. Kebijakan ini jelas menyulut ketimpangan di antara sesama pekerja akademik.
Kami, para pekerja akademik di kabupaten, biasanya hanya bisa menertawakan diri sendiri. Kalau orang-orang biasa menyebut guru di daerah pedalaman sebagai guru tertinggal, barangkali, kami semua, dosen-dosen kabupaten, di kampus-kampus dengan strata terendah, adalah dosen-dosen dengan nasib tertinggal yang masih bersikukuh memimpikan kemajuan di tengah kebijakan negara yang tidak memihak.
Akan tetapi, bagaimana kita akan membicarakan kesejahteraan pekerja akademik dengan situasi harian yang melelahkan seperti itu? Jika hari-hari pekerja akademik dipenuhi kecemasan semacam itu, bagaimana kita bisa berbicara masalah kualitas dan kemajuan yang lebih besar?

Kasmiati adalah seorang pekerja akademik yang sehari-hari meneliti dan belajar-mengajar di Perguruan Tinggi Negeri di kawasan Timur Indonesia, tepatnya di salah satu kabupaten di Pulau Sulawesi. Ia dapat dihubungi melalui [email protected].
Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini