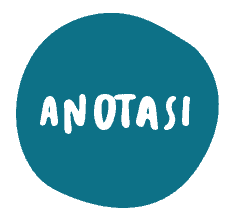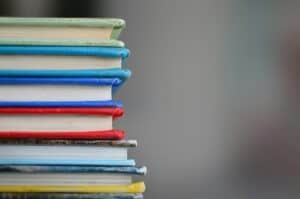Pada awal 2024, media sosial X (sebelumnya Twitter) ramai oleh warganet yang melakukan doxing (menyebarluaskan informasi seseorang tanpa konsen) terhadap mahasiswa-mahasiswa penerima KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah). Mereka dianggap menyalahgunakan program pemerintah yang seharusnya diterima oleh mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah.
Pada kurang lebih waktu yang sama, dosen-dosen mulai banyak memprotes beratnya beban kerja yang tidak berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima melalui tagar #JanganJadiDosen. Selain itu, kasus plagiarisme dan praktik predatorial publikasi artikel ilmiah yang dilakukan oleh dosen demi mengejar peningkatan jabatan fungsional juga naik ke permukaan. Kasus-kasus ini, bagi kami, adalah gejala dari neoliberalisasi perguruan tinggi di Indonesia yang bertemu dengan praktik politik predatorial, atau praktik dengan sengaja mengeksploitasi kesempatan atau orang lain untuk keuntungan sendiri.
Dalam artikel ini, kami akan membahas masalah-masalah struktural yang membentuk praktik kultural perguruan tinggi Indonesia dalam konteks neoliberalisasi global.
Orientasi Pasar
Neoliberalisasi adalah proses-proses reorganisasi (penyusunan ulang) ekonomi dan politik yang ditandai, secara mendasar, oleh berkurangnya peran pemerintah dan meningkatnya peran swasta dalam menyediakan layanan publik. Proses ini terjadi tidak hanya di Indonesia dan ‘negara berkembang’ lainnya, melainkan juga di banyak negara lain di bagian Utara dunia (Global North) dan secara nyata memengaruhi berbagai layanan publik secara sistematis. Neoliberalisasi bisa diamati dampaknya di berbagai sektor, seperti privatisasi air bersih, perumahan, kesehatan dan, tentunya, pendidikan.
Di sektor pendidikan tinggi, neoliberalisasi dapat didefinisikan “sebagai transformasi lembaga pendidikan dan pekerjanya untuk menghasilkan subjek yang dibentuk menjadi sangat individual dan diserahi tanggung jawab, yang menjadi pelaku kewirausahaan di semua dimensi kehidupan mereka”. Konstruksi sosial neoliberalisasi di pendidikan tinggi dapat dilihat dalam setidaknya dua gejala. Pertama, konsep universitas ‘kelas dunia’ yang diukur dengan metrik global yang telah menggeser fokus dari misi ‘mencerdaskan bangsa’ (pendidikan) ke arah pemeringkatan global dan persaingan pasar. Kedua, transformasi manajemen internal pendidikan tinggi yang memperkenalkan praktik manajemen korporat, di mana efisiensi dan efektivitas diukur berdasarkan pencapaian tujuan-tujuan yang lebih terkait dengan orientasi pasar.
Ada fokus besar pada penelitian yang menghasilkan pendapatan bagi universitas. Kami juga mengamati bahwa perubahan-perubahan ini menurunkan prioritas memberi pendidikan kepada yang paling membutuhkan dan menaikkan prioritas pada pembukaan program studi yang dapat menghasilkan pemasukan. Sementara itu, praktik manajemen korporat dalam lingkungan pendidikan memicu ketegangan antara kepentingan akademik dan kontrol atas proses kerja para dosen. Kondisi ini menunjukkan bagaimana neoliberalisasi menggeser dengan sangat efektif paradigma pendidikan tinggi di Indonesia dari lembaga yang memeratakan akses pendidikan ke produksi komoditas pengetahuan dengan logika pasar.
Neoliberalisasi bukan proses linear (satu arah) yang hanya mencakup hubungan antara negara dan pasar. Justru, ia muncul dan semakin menguat dengan dukungan dari negara untuk menjaga pasar beroperasi dengan cara yang menguntungkan (pihak tertentu). Proses ini dijaga oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menunjukkan peran pemerintah dalam mendorong neoliberalisasi pendidikan tinggi. Peraturan-peraturan tersebut mengikat 122 lembaga pendidikan tinggi negeri, termasuk universitas, institut, politeknik, dan akademi, serta 3.171 lembaga pendidikan tinggi swasta, termasuk universitas, institut, sekolah, akademi, perguruan tinggi komunitas, dan politeknik. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa peraturan ini membentuk tiga wacana: otonomi (self-reliance), daya saing (competitiveness), dan kewirausahaan (entrepreneurship).
Yang pertama, otonomi, atau kemampuan lembaga pengetahuan untuk menghasilkan pendapatan dan beroperasi secara efisien, dibentuk oleh PP 61/1999 yang menyatakan bahwa institusi pendidikan tinggi merupakan lembaga yang otonom. Selain itu, UU 20/2003 juga menyatakan bahwa institusi pendidikan tinggi berhak mengumpulkan uang dari masyarakat berdasar prinsip akuntabilitas. Senada dengan itu, UU 9/2009 tentang pendidikan tinggi berbadan hukum juga menghendaki lembaga pendidikan tinggi dapat mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan investasi lembaganya. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan wacana lembaga pendidikan tinggi untuk menghasilkan pendapatan di luar anggaran negara yang secara bertahap menjadikan mereka mandiri dari pendanaan negara dan meningkatkan ketergantungan mereka pada mahasiswa dan riset pasar.
Mahasiswa adalah sumber pendapatan utama dari komodifikasi pendidikan tinggi. Mereka adalah pihak yang menanggung dampak atas kemandirian institusi pendidikan tinggi dengan membayar UKT yang mahal. Kebijakan KIPK merupakan solusi sementara dan tidak efektif, jika tujuannya adalah untuk pemerataan akses pendidikan. Alasannya, KIPK sangat mungkin salah sasaran: bukan saja tidak memperluas akses pendidikan tinggi kepada mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah dengan prestasi akademik baik, melainkan juga dimanfaatkan secara sengaja oleh mereka yang mampu secara finansial. Peraturan mengenai otonomi kampus juga mendorong institusi pendidikan tinggi melakukan efisiensi anggaran, misalnya dengan memberikan gaji rendah dan kasualisasi tinggi pada dosen yang justru paling produktif (sehingga mereka bekerja keras demi mencari kepastian kerja). Dengan keadaan di mana perguruan tinggi tidak lagi bisa memberikan janji pekerjaan tetap, kerentanan kerja akademik (academic precarity) pun meningkat.
Yang kedua, ‘daya saing’ diulang sebanyak enam kali dalam UU 12/2012. Kami berargumen bahwa universitas diarahkan untuk menjadi lebih terintegrasi dalam pasar global dan regional dengan ambisi untuk mencapai ‘status kelas dunia’ dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan aspirasi meningkatkan peringkat global, standar baru kinerja diberlakukan bagi dosen, yang mengharuskan pencapaian akademik seperti publikasi di jurnal-jurnal yang terindeks secara internasional sebagai prasyarat untuk promosi karir.
Mahasiswa adalah sumber pendapatan utama dari komodifikasi pendidikan tinggi. Mereka adalah pihak yang menanggung dampak atas kemandirian institusi pendidikan tinggi dengan membayar UKT yang mahal. ~Nur Rafiza Putri dan Inaya Rakhmani Share on XSelama puluhan tahun di bawah rezim otoritarian (1966-1998), sistem promosi dikenal sebagai kenaikan pangkat yang diorganisasi di bawah lembaga negara (Badan Kepegawaian Negara). Sistem ini berdasarkan syarat administrasi dan tidak mengenai kenaikan pangkat berdasarkan kompetensi (merit-based promotion). Di saat yang sama, korupsi, kolusi dan nepotisme yang membudaya selama puluhan tahun di lembaga-lembaga negara lebih instrumental daripada keterampilan profesional (seperti meningkatkan kapasitas mengajar, meneliti dan melakukan diseminasi publik) untuk menjamin peningkatan pendapatan pekerja kampus. Ini yang kami sebut sebagai titik temu antara neoliberalisasi pendidikan tinggi dengan politik predatorial. Dosen melakukan plagiarisme karena praktik predatorialisme lebih efisien dalam menghindari kerentanan akademik daripada integritas moral.
Ketiga, ‘kewirausahaan’’, yang bersumber dari UU 11/2019 dan Permendikbud 3/2020, mengawal komersialisasi inovasi, invensi, hak kekayaan intelektual yang berorientasi pada riset terapan yang dapat dijual ketimbang riset dasar jangka panjang, dan bentuk pembelajaran di mana mahasiswa didorong melakukan kegiatan-kegiatan di dunia industri. Lembaga pendidikan tinggi, dengan demikian, didorong untuk menghasilkan luaran komersial untuk kebutuhan industri.
Selain itu, mereka juga ditekan untuk menghasilkan lulusan yang ‘siap kerja’, kalau bisa sejak kuliah melalui program magang, untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menunjukkan bahwa peserta magang, dalam studi yang dilakukan oleh Wirman di masa pandemi, menormalisasi eksploitasi waktu dan tenaga dengan ‘imbalan’ pengalaman kerja dan sertifikat yang mereka harapkan berguna ketika mereka melamar pekerjaan.
Ketiga wacana itu semakin menguat dan dibangun oleh peraturan-peraturan pemerintah Indonesia maupun dunia. Tapi, mereka juga memunculkan antagonisme (perlawanan) di antara para pekerja pengetahuan yang mulai menyuarakan kekecewaan dan aspirasi politik mereka terhadap apa seharusnya peran lembaga pendidikan tinggi.
Upaya Perlawanan
Para dosen menginisiasi gerakan digital yang dipicu oleh rasa frustrasi bersama tentang kondisi kerja akademik. Gerakan ini mendapat momentum melalui media sosial dan platform digital yang mengarah pada pembentukan Serikat Pekerja Kampus di Indonesia. Kolaborasi antara platform jurnalisme sains digital seperti The Conversation dan kelompok aktivis seperti KIKA dan IndoProgress membantu memperkuat pesan dan mengungkapkan eksploitasi yang dihadapi oleh para dosen. Serikat pekerja, yang didirikan pada 2023, mewakili pergeseran menuju advokasi untuk upah yang adil, menantang kebijakan neoliberal dalam pendidikan tinggi, dan mempromosikan aktivisme intelektual.
Serikat Pekerja Kampus, melalui kertas kebijakannya yang berjudul “Gaji Minimum, Beban Kerja Maksimum,” menyuarakan lima rekomendasi, yaitu (1) meningkatkan gaji pokok, (2) formulasi upah berdasarkan perhitungan kelayakan per wilayah, (3) re-evaluasi metrik beban kerja, (4) perubahan peraturan yang menyediakan kerangka kerja yang lebih jelas untuk kompensasi dan kesejahteraan dosen, dan (5) pemberdayaan dan transparansi pada tingkat institusi. Gerakan ini adalah yang pertama yang mengorganisasi antagonisme pekerja pendidikan tinggi, yang mungkin tidak akan terbentuk tanpa platform digital.
Tapi, platform digital yang melahirkan dan berperan dalam pengorganisasian niat kolektif untuk melawan neoliberalisasi merupakan instrumen korporat (notabene, lembaga privat penyedia informasi bagi publik) yang juga beroperasi dengan mekanisme pasar. Platform digital juga mengeksploitasi begitu banyak pekerja di sektor kreatif. Pada ruang digital selalu tersemat komodifikasi praktik yang membantu, secara cuma-cuma (free labour), akumulasi keuntungan para pemilih platform (yang tentunya berhubungan secara tidak langsung pula dengan neoliberalisasi pengetahuan).
Gerakan yang menjaga antagonisme pekerja pengetahuan penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia mengorganisasi aspirasi dan frustrasi para pekerja kampus dan mengartikulasikannya dalam tuntutan-tuntutan yang jelas. Di sisi lain, pengorganisasian ini menggunakan platform yang beroperasi dalam logika algoritma yang bekerja di bawah imperatif pasar. Dan dalam kontradiksi itu, praktik sosialisme pengetahuan, atau memastikan bahwa tulisan akademik dan pemikiran dapat diakses siapapun tanpa sekat pasar dan hierarki paradigmatik, bagi kami, merupakan tindakan resistensi (perlawanan) jangka panjang yang tidak kalah bermakna dalam perlawanan terhadap neoliberalisasi pengetahuan. Tulisan ini, semoga, adalah salah satunya.

Nur Rafiza Putri (Riri) adalah pengajar di Ilmu Komunikasi, Universitas Nasional dan peneliti di Asia Research Centre, Universitas Indonesia. Saat ini, Riri sedang mempelajari tentang produksi pengetahuan, kajian budaya, serta gender.

Inaya Rakhmani adalah Direktur Asia Research Centre, dan pengajar di Departemen Komunikasi, Universitas Indonesia. Inaya menggunakan ekonomi politik budaya untuk mempelajari media dan komunikasi serta pengetahuan dan informasi untuk menjelaskan perubahan kapitalis yang lebih luas.