
Menyetip Feodalisme: Jalan Panjang Menuju Reformasi Pendidikan
April 22, 2022
Murakami-esque dan Hikikomori: Refleksi Krisis Eksistensial Masyarakat Jepang Pada Sastra Kontemporernya
May 16, 2022
OPINI
Peniruan Malioboro di Kajoetangan Malang, Kapitalisme Urban, dan Krisis Identitas Kota
oleh Riqko Nur Ardi Windayanto
Transformasi Kajoetangan, yang sebelumnya hanyalah kawasan berarsitektur kolonial, lalu menjadi kawasan “hidup” ala Malioboro, merupakan bentuk pemaknaan atas ekonomi simbolis kota yang secara menggiurkan (mungkin) akan menarik minat wisatawan, pengunjung dari berbagai kota, dan bahkan investor di kemudian hari. Ia dibangun bukan hanya dengan pemaknaan secara kultural sebagai tempat bersejarah yang harus dihidupkan kembali fungsi awalnya, melainkan ruang yang dibangun dengan modal-modal ekonomi dan untuk konsumerisme.
Sudah hampir dua bulan sejak awal tahun 2022 dan ketika saya menyusun tulisan ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membuka kawasan Kajoetangan, Malang dengan pembangunan baru. Kini, kedua sisi di sepanjang jalan tersebut dipasangi dengan lampu-lampu jalan yang menyerupai lampu-lampu di Malioboro, Yogyakarta. Secara personal saya tidak mengetahui motif politis dan kultural dari pembangunan jalan tersebut yang tampak menyerupai kota lain. Semenjak kawasan itu dibuka, muncul berbagai wacana di media yang menyamakan Malang sebagai Yogyakarta dengan ungkapan “Malang Punya ‘Malioboro’”, “Malioboronya Kota Malang”, “Malangboro”, dan sebagainya.
Bahkan, saya masih ingat bahwa ada salah seorang teman saya yang mengunggah video kawasan Kajoetangan pada fitur cerita story Instagram, lalu menambahkan lagu “Yogyakarta” oleh KLA Project. Secara tidak langsung, wacana-wacana tersebut menjadikan Malang sebagai variabel yang terikat pada Yogyakarta, yang identitasnya ditentukan oleh identitas kota tersebut. Secara semiotik, kehadiran lampu-lampu di Kajoetangan makin mengeksplisitkan gagasan Pemkot Malang untuk meniru Malioboro.
Secara semiotik, kehadiran lampu-lampu di Kajoetangan makin mengeksplisitkan gagasan Pemkot Malang untuk meniru Malioboro. ~Riqko Nur Ardi Windayanto Share on XTidak bisa dimungkiri bahwa Malioboro ialah ruang yang ikonis. Ia seakan-akan telah terkenang pada sebagian besar di antara kita sebagai ruang dengan lampu-lampu jalanan yang secara ikonis menandai dan terkait erat dengan Yogyakarta. Namun, ia menjadi simbol dari terang benderangnya perkotaan yang makin terkomersialisasi dan terkomodifikasi pada arus kapitalisme dan ekonomi urban dengan berbagai pusat perbelanjaan dan situs turisme. Itulah mengapa, sebenarnya kita tidak perlu terkejut apabila menjumpai beberapa kota—bukan hanya Malang, melainkan juga, misalnya, Madiun dan Ponorogo—menjadikan salah satu kawasannya seperti Malioboro dengan memasang lampu-lampu jalanan. Persoalannya, apa indikator untuk memastikan bahwa pembangunan Kajoetangan itu meniru Malioboro?
Secara historis, menurut Peter Carey, pada 1917—1921 terjadi peralihan lampu gas menjadi penerangan listrik modern yang mengubah karakter dan mempercepat komersialisasi Malioboro. Artinya, kawasan di Yogyakarta ini memiliki proses dan dinamika yang begitu panjang sehingga ia menjadi ruang yang hegemonik dan dianggap ikonis dari suatu kota. Karena proses dan dinamika yang lebih mula daripada pembangunan Kajoetangan pada 2022, dapat diyakini bahwa ada peniruan Malioboro di Kajoetangan. Dalam “From City Identity to City Branding: Artivistic Initiatives or Top-down Urban Regeneration”, Sesic dan Mihaljinac mengatakan bahwa sepanjang sejarah, masyarakat pada tiap kota mengembangkan nilai dalam kehidupan sehari-harinya untuk memperoleh pengakuan identitas. Pemerolehan itu kadang kala didukung dengan hal-hal yang oleh Sesic dan Mihaljinac disebut sebagai narasi artistik.
Apa yang dilakukan oleh Pemkot Malang pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan identitas tersebut. Kajoetangan, yang merupakan pusat perbelanjaan pada masa kolonial, dikemas sebagai narasi artistik untuk mencapai pengakuan tersebut. Akan tetapi, identitas seperti apakah yang diinginkan oleh Malang menjadi pertanyaan yang perlu diumpankan karena bagaimanapun, Kajoetangan dan Malioboro adalah dua ruang dengan identitas yang berlainan. Jika kita mengacu pada argumentasi-argumentasi sejarah dari Peter Carey, Malioboro pada awalnya merupakan jalan utama kerajaan. Argumentasi itu bisa kita lihat ketika mengunjungi Malioboro yang secara fisik berada dalam satu garis lurus dengan keraton di selatan dan tugu di utara.
Sementara itu, Kajoetangan merupakan pusat perekonomian pada masa kolonial dan bukanlah jalan utama kerajaan. Secara fisik, kita juga bisa menjumpai bangunan-bangunan sisa dan khas arsitektur kolonial di kawasan tersebut. Dan, tentu saja, tidak mungkin Pemkot Malang menjadikan Kajoetangan seperti Malioboro untuk menampakkan kesan jalan utama sebagaimana argumentasi historis di atas. Saya berargumen bahwa motif kapitalisme telah yang mendasari pembangunan tersebut. Dalam tulisannya yang bertajuk “A Spirit of Urban Capitalism: Market Cities, People Cities, and Cultural Justifications”, Smiley dan Emerson menilai bahwa semangat kapitalisme urban dapat dinilai melalui komitmen diskursif dan pengaturan kelembagaan yang mengatur hubungan antara ekonomi dan budaya.
Komitmen diskursif, secara ideologis, tampak pada spirit dan gagasan untuk menghidupkan kembali Kajoetangan, sedangkan secara materialistis, pembangunan dan pembukaan Kajoetangan merupakan implementasi atas spirit dan gagasan tersebut. Hal itu tampak pada pengaturan sedemikian rupa oleh Pemkot Malang dengan memoles wajah Kajoetangan seperti Malioboro. Kawasan yang semula hanyalah jalan protokol kota lambat laun menjadi ruang publik yang memfasilitasi konsumerisme masyarakat. Musikus-musikus lokal juga dihadirkan di kawasan tersebut yang boleh jadi ditujukan bukan hanya untuk menarik hasrat masyarakat, melainkan juga menjadikan kawasan tersebut sebagai ruang bagi ekonomi lokal. Memang, konsumerisme itu belum tampak seperti halnya di Malioboro, tetapi dapat diasumsikan secara imajiner bagaimana Kajoetangan bertahun-tahun berikutnya akan terkomersialisasi seperti Malioboro. Komitmen itu, kemudian, diikuti dengan berbagai pengaturan kelembagaan politik untuk mem-branding Kajoetangan sebagai kawasan yang tidak pernah tandas dan pantas untuk dikunjungi karena ia menawarkan nilai-nilai tertentu tentang Kota Malang.
Dalam Diskusi dan Bedah Heritage Peduli Kotaku di Malang pada 21 Januari 2022 lalu, Pemkot Malang bisa saja memberikan wacana tandingan bahwa pembangunan Kajoetangan bukanlah Malioboro. Pemasangan lampu-lampu pedestrian tersebut ditujukan untuk merevitalisasi kawasan itu sesuai dengan fungsinya pada masa lalu, yaitu pusat perbelanjaan dan tempat kongko. Akan tetapi, tidak berarti bahwa dalam wacana tandingan itu tidak ada semangat kapitalisme urban yang tersembunyi. Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, lampu-lampu jalan secara semiotik mengacu pada Malioboro. Malioboro merupakan situs ekonomi kultural karena memiliki reputasi yang telah mapan sebagai bagian dari “Kota Istimewa” sehingga menarik perhatian turis, pengunjung, pelaku ekonomi, dan berbagai aktor lainnya. Ia telah menjadi suatu branding yang berhasil menyihir siapapun untuk berpikir bahwa “belum ke Yogyakarta kalau belum ke Malioboro”.
Apa yang dilakukan oleh Pemkot Malang sejatinya adalah menjadikan Kajoetangan sebagai situs ekonomi kultural untuk membangun citra suatu kota dengan kawasan bekas kolonial yang kini diubah layaknya Malioboro. Memperkuat dan memfasilitasi pelaku ekonomi lokal seakan-akan menjadi cita-cita luhur yang tengah dibangun melalui Kajoetangan tersebut. Sebagaimana dikutip oleh Barker dalam Cultural Studies: Teori & Praktik, Zukin menyoroti pentingnya masalah ekonomi simbolis kota. Salah satu isu fundamental dari permasalahan itu ialah pembangunan ulang ekonomi.
Transformasi Kajoetangan, yang sebelumnya hanyalah kawasan berarsitektur kolonial, lalu menjadi kawasan “hidup” ala Malioboro, merupakan bentuk pemaknaan atas ekonomi simbolis kota yang secara menggiurkan (mungkin) akan menarik minat wisatawan, pengunjung dari berbagai kota, dan bahkan investor di kemudian hari. Ia dibangun bukan hanya dengan pemaknaan secara kultural sebagai tempat bersejarah yang harus dihidupkan kembali fungsi awalnya, melainkan ruang yang dibangun dengan modal-modal ekonomi dan untuk konsumerisme. Saat ini, pembangunan itu mungkin tidak memberikan dampak yang berarti. Akan tetapi, bertahun-tahun berikutnya, jika tidak diimbangi dengan kebijakan budaya, ruang kota akan menjadi wajah yang paradoks: tersenyum, tetapi menyeringai dengan buas.
Pada satu sisi, Kajoetangan kini bisa dianggap sebagai ruang kesenangan (space of enjoyment), ruang yang menawarkan kebahagiaan bagi warganya untuk menikmati Malang pada malam hari, dengan cahaya-cahaya lampu yang berpendar di waktu malam. Dan, bagi sebagian mereka, Kajoetangan telah memuaskan hasratnya untuk tidak perlu lagi jauh-jauh ke Yogyakarta karena kini Malang telah memiliki “Malioboronya”. Namun, dalam jangka panjang, ia akan memerosotkan Malang pada krisis identitas kota. Saya meminjam pernyataan Huang bahwa identitas kota adalah sesuatu yang subjektif, yang tergantung pada pengalaman inderawi sang pengamat tentang penampilan fisik kota tersebut. Walaupun subjektivitas ini menjadikan tidak adanya tolok ukur yang bersifat tunggal atas identitas suatu kota, identitas membedakan suatu kota dari kota lain. Lebih lanjut Huang juga menyatakan bahwa krisis identitas kota, di antaranya, tampak dari melemahnya identitas asli suatu kota dan munculnya lanskap kota yang bersifat konvergen. Lanskap yang konvergen berarti lanskap yang dalam pembangunannya mengacu dan memusat pada lanskap tertentu. Dalam hal ini, Kajoetangan dibangun dengan mengacu dan memusat pada Malioboro.
Maka dari itu, karena identitas dipahami sebagai suatu pembeda kota yang satu dengan kota yang lain, ketika dipasang lampu-lampu ala Malioboro, timbul wacana yang menolak pembangunan tersebut. Salah satu argumentasinya ialah lampu-lampu itu menjadikan Malang tidak memiliki identitasnya sendiri. Malang telah terjebak dalam kapitalisme urban yang membuatnya menihilkan pentingnya identitas dalam suatu pembangunan kota agar ia tidak sama dengan kota-kota lain. Identitas pada hakikatnya ialah proyek yang terus menerus diproduksi dan direproduksi. Dan, menurut Huang, identitas kota tersusun atas berbagai komponen. Salah satu komponen pembangunnya ialah pengaturan fisik atau penampilan.
Untuk memenuhi hasrat semangat kapitalisme urban, Pemkot Malang sebagai pihak yang berkuasa mengontrol ruang publik telah menihilkan aspek kultural terkait dengan identitas kota. Pengaturan fisik atau penampilan yang ditujukan semata-mata untuk meramaikan Kajoetangan justru menyebabkan kota ini perlahan-lahan menuju krisis identitas karena kota itu tidak lebih dari peniru Malioboro. Tentu saja, selalu ada kesempatan untuk mendesain ulang tata kelola kebijakan ruang publik tersebut. Sebab, ambisi pembangunan tanpa menimbang aspek kultural di dalamnya akan menjadikan ruang kota sebagai wajah yang menyeringai dengan buas, bukan tersenyum.
Pengaturan fisik atau penampilan yang ditujukan semata-mata untuk meramaikan Kajoetangan justru menyebabkan kota ini perlahan-lahan menuju krisis identitas karena kota itu tidak lebih dari peniru Malioboro. ~Riqko Nur Ardi… Share on X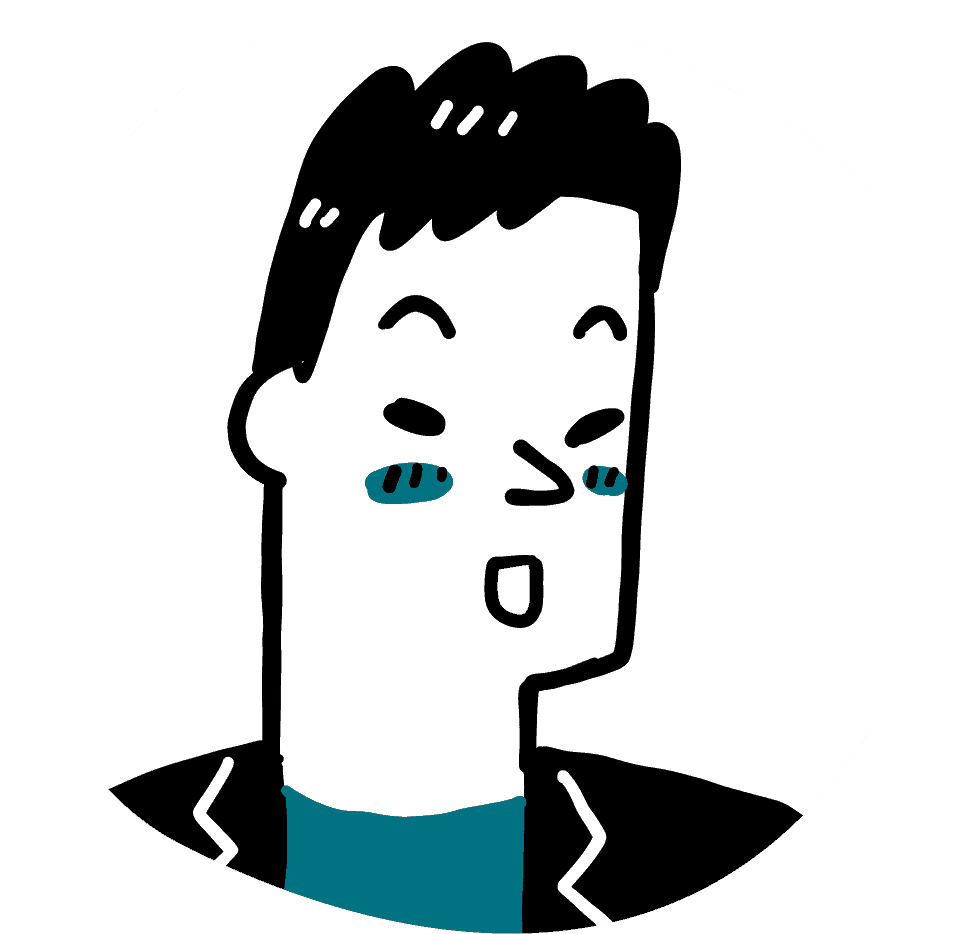
Riqko Nur Ardi Windayanto, bisa dipanggil Riqko, merupakan mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada. Saat ini memfokuskan bidang minatnya pada filologi (kajian pernaskahan kuno), khususnya naskah-naskah Melayu. Sesekali menyempatkan diri untuk belajar dan mendalami cultural studies.
Dapat dihubungi melalui akun sosial media Instagram: @notjustriqko
Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini







