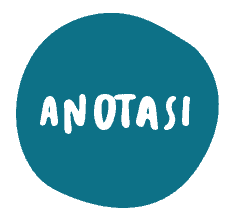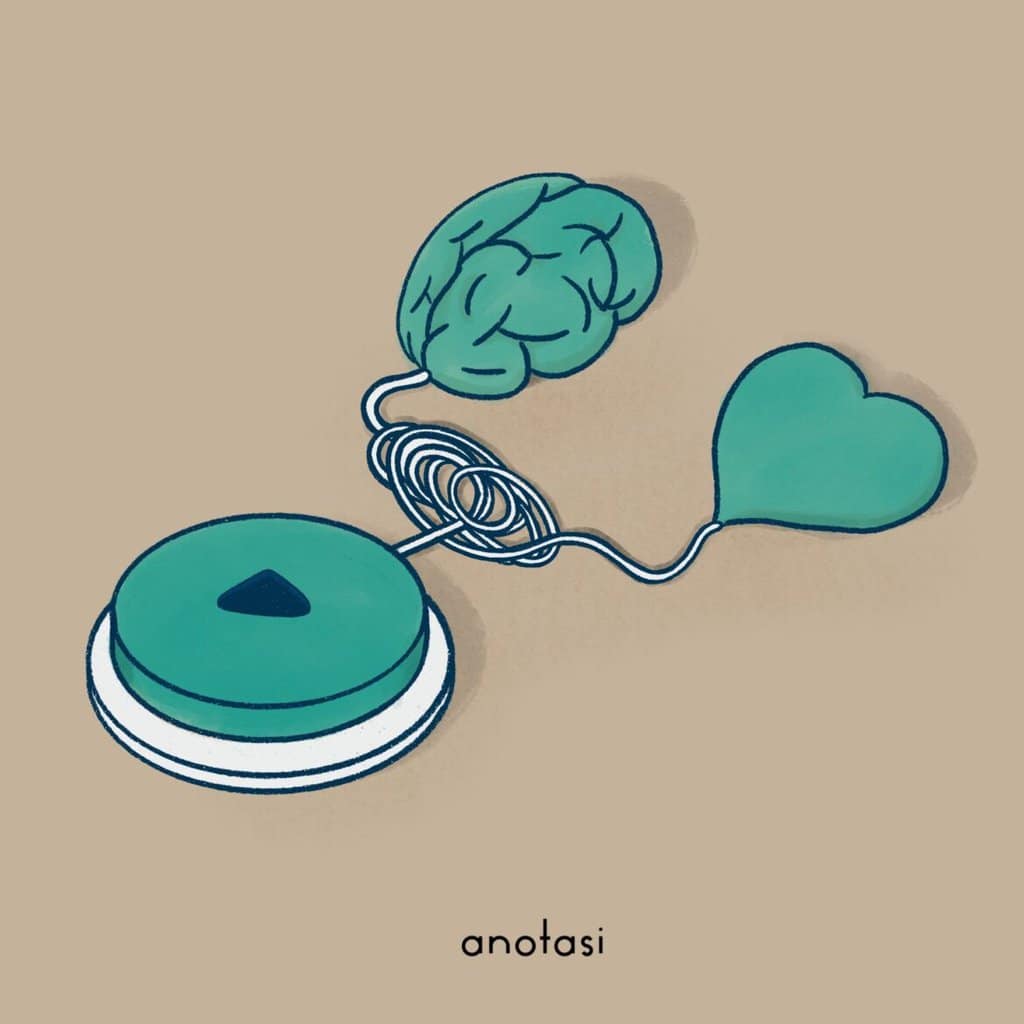Ada sejumlah hal penting—setidaknya penting bagi saya—terjadi di pertengahan April lalu: seri Game of Thrones musim terakhir dimulai, Beyonce meluncurkan film dokumenternya di Netflix, Indonesia melaksanakan pemilu, dan cuitan saya pertama kalinya jadi viral.
Cuitan tersebut menceritakan pertemuan saya dengan Novel Baswedan serta wawancara kami untuk podcast saya. Inti cuitan saya adalah himbauan untuk seluruh rakyat Indonesia agar selalu kritis terhadap Presiden Jokowi, karena ia memiliki sejumlah catatan minus dalam kepresidennya, salah satunya adalah pembiaran kasus Novel Baswedan. Tak lebih, tak kurang.
Halo, banyak bgt yang gak paham dgn Instastory ini ya. Saya gak mendorong Golput, tapi saya mencegah FANATISME. Mencegah mendewakan dan tutup mata pd kelemahan capres PILIHAN KITA. Kepengen 01 / 02 menang? Yuk bgt nyoblos. Tapi setelah beliau menang, ayok kritis thdp kinerjanya. https://t.co/BdyZekRJEt
— LA. (@prin_theth) April 16, 2019
Tak ada informasi yang istimewa atau baru dalam cuitan saya itu, tapi cuitan tersebut menjadi viral. Sialnya, ia viral beberapa hari sebelum pemilu, ketika ketiga kubu rakyat—pendukung paslon 01, paslon 02, dan golput—sedang sensitif-sensitifnya.
Alhasil, cuitan saya mendapat puluhan respon. Pendukung 02 bersorak, “Tuh, Jokowi memang payah soal HAM! Ngapain nyoblos dia lagi?” Sementara pendukung 01 misuh-misuh, “Pakde memang nggak sempurna, tapi dia pilihan terbaik!” atau, “Sok tau banget soal kasus Novel Baswedan! Jokowi sudah beresin, kok!”
Ada juga beberapa komentar yang keluar konteks, seperti, “Ini dia, nih, salah satu bentuk penggalangan Golput!” Padahal dalam cuitan itu, saya malah menyatakan mungkin akan mencoblos Jokowi, dan tidak mengajak orang untuk Golput. Adapun komen yang paling nggak nyambung adalah, “Ngapain, sih, bela Novel Baswedan? Dia Islam konservatif begitu!” (lho?)
Meski hanya sedikit, saya hargai warganet yang berkomentar, “Ya juga, ya. Kita harus kritis, dan nggak boleh asal mendukung Jokowi,” karena itulah inti cuitan saya: kita harus kritis terhadap siapapun presiden kita. Hargailah Jokowi jika ia berbuat benar, gugatlah jika ia berbuat salah.
Hal ini ternyata sulit diterima.
Manusia cenderung mengambil posisi di zona hitam atau zona putih. Susah baginya untuk berdiri di zona abu-abu. Manusia gemar mensimplifikasi, atau memiliki pola pikir yang menyederhanakan logika suatu hal sehingga membuatnya hitam atau putih.
Dalam pola pikir simplifikasi, pemilih Jokowi dicap anti-Islam, tidak nasionalis, bahkan komunis. Sementara pemilih Prabowo dicap mendukung Orde Baru dan politik identitas.
Apa iya, karakter (pemilih) Jokowi dan Prabowo sesederhana itu? Tentu tidak. Di dunia ini, tidak ada hitam atau putih yang hakiki. Tidak ada orang yang betul-betul baik, tidak ada orang yang betul-betul jahat, dan inilah yang berusaha saya sampaikan kepada warganet, namun gagal.
***
Mengapa manusia senang mensimplifikasi?
Pertama, karena simplifikasi lebih mudah diterima oleh akal manusia. Menempatkan diri di area abu-abu itu sulit, karena hal tersebut membutuhkan kedewasaan, kecerdasan emosi, serta sebanyaknya informasi faktual dari berbagai sisi.
Pada pemilu 2014, sosok Jokowi “enak” untuk dipilih, karena ia adalah sosok yang baru, segar, dan bersih dalam kancah politik Indonesia. Tahun ini, Jokowi sudah lima tahun menjabat jadi presiden, dan kepresidenannya terbukti tidak sempurna, misalnya dalam hal pengabaian pelanggaran HAM Novel Baswedan. Jokowi juga mengambil berbagai keputusan yang bertujuan utama mempertahankan posisinya, seperti mengimpor beras tanpa data yang akurat serta memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya, agar ia aman dari tuduhan anti-Islam.
Jika pendukung Jokowi mau objektif dan berdiri di zona abu-abu, mereka akan menerima bahwa Jokowi sama sekali bukan orang jahat, namun juga jauh dari sempurna. Jokowi adalah politikus, dan sebagian langkah-langkahnya sejauh ini adalah langkah-langkah politis belaka. Kita perlu selalu kritis terhadap beliau, agar ke depannya ia bisa menjadi presiden yang lebih sering mementingkan rakyatnya di atas jabatannya.
Kedua, karena pada dasarnya, manusia memang tidak akan bisa (sepenuhnya) rasional.
Seorang pakar neurologis, dr Ryu Hasan, menjelaskan bahwa kerja otak manusia itu sangat jauh dari yang namanya rasional. Kerja otak manusia lebih disetir oleh emosi, ketimbang akal sehat.
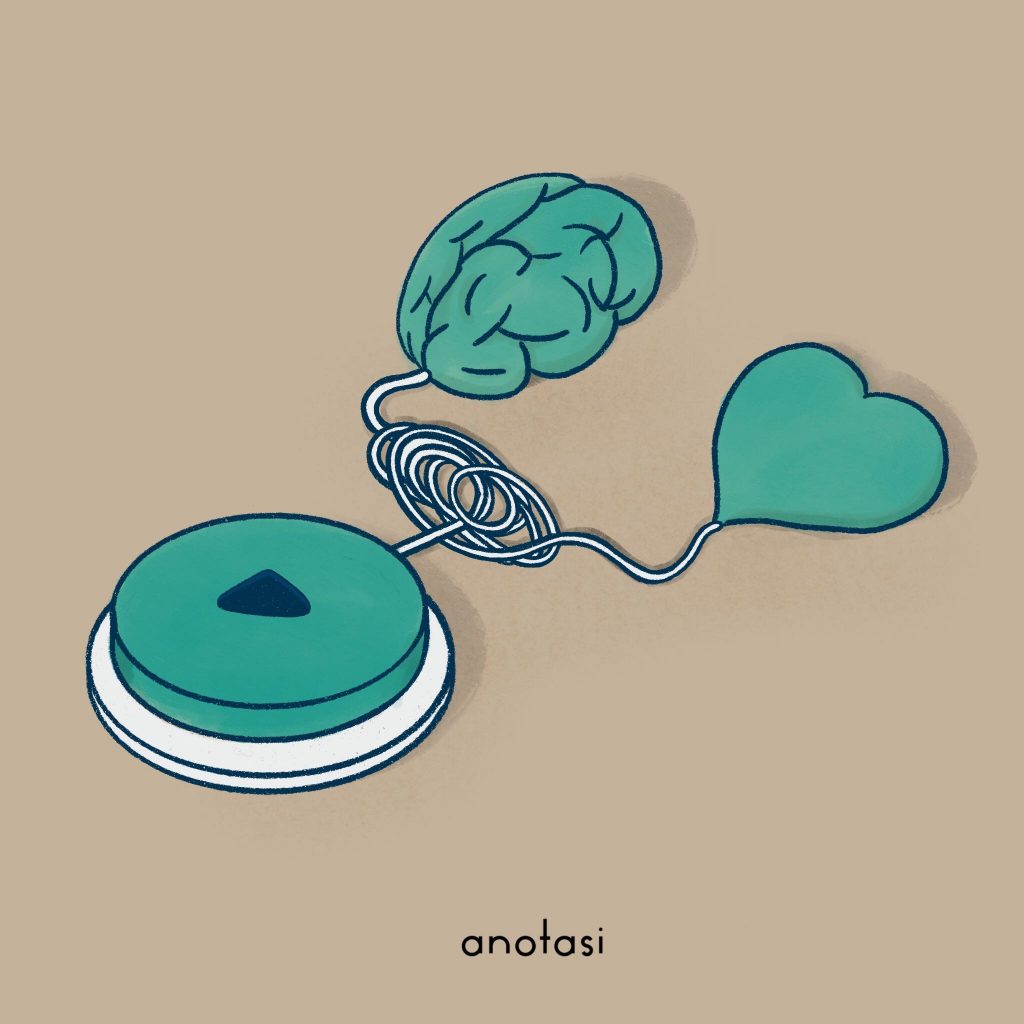
Pada tahun 1979, Universitas Stanford di Amerika Serikat mengadakan sebuah penelitian untuk membuktikan hal ini. Para peneliti mengumpulkan dua kelompok partisipan—kelompok A berisi orang-orang yang menyetujui hukuman mati, sementara anggota kelompok B berisi orang-orang yang menentangnya. Kedua kelompok tersebut diminta merespon dua dua data riset. Data riset pertama menunjukkan keefektivitasan hukuman mati, sementara data riset kedua menunjukkan sebaliknya.
Hasil penelitian mengungkapkan, kelompok A menganggap data riset pertama sangat kredibel, dan menganggap data riset kedua sangat tidak kredibel. Sementara di Kelompok B, terjadi penilaian yang sebaliknya.
Padahal—ini plot twist-nya—kedua data riset tersebut fiktif. Tetapi ketika para responden diberitahu soal ini, anggapan mereka terhadap hukuman mati tak berubah.
Uji coba ini—dan banyak uji coba lainnya—mengisyaratkan bahwa manusia memang tidak berpikir dengan lurus, bahkan tidak bisa merevisi keyakinannya meski mereka diinformasikan bahwa keyakinan mereka salah. In the end, people believe what they want to believe.
Kita percaya apa yang kita mau percayai
Menurut dr Ryu Hasan, keputusan berdasarkan emosi akan menguat ketika manusia menerima gelombang informasi yang sangat banyak. Information overload membuat otak manusia semakin sulit memilah, mana yang benar mana yang salah secara obyektif. Alhasil, manusia jadi memilih informasi yang mengafirmasi selera dan kesenangannya saja. Ia tidak mengkonfirmasi apakah informasi tersebut faktual.
Kita bisa mendukung seorang politikus karena kita menyukai penampilan atau intonasi suaranya saat ia berorasi, bukan karena kita setuju betul atas program-programnya. Menurut para ilmuwan kognitif, manusia akan memilih suatu hal karena ia menyenangi hal tersebut, bukan karena ia punya pertimbangan rasional terhadapnya. Maka, untuk memancing emosi haru masyarakat, Jokowi rutin memunculkan videonya bercanda-canda dengan Kaesang Pangarep atau menggendong-gendong Jan Ethes. Ia juga berusaha mendulang suara generasi muda dengan kerap melakukan hal-hal yang identik dengan mereka—naik chopper, hadir di berbagai festival musik, dan menaruh perhatian besar pada startup.
Tetapi apakah karakter “bapak yang hangat dan asyik” adalah ciri negarawan yang cakap? Belum tentu, tetapi karakter tersebut mudah mengundang simpati.
***
Kadang, kita mengalami sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan kita, dan menurut teori disonansi kognitif, hal ini membuat kita tidak nyaman. Apabila sejak kecil kita terbiasa melihat sosok ibu sebagai perempuan yang hanya mengurus hal-hal domestik di rumah, kita jadi meyakini bahwa ibu = perempuan yang di rumah. Maka, ketika kita menemukan perempuan yang bekerja di kantor, berdampingan dengan lelaki, kita jadi merasa terganggu.
Menurut teori disonansi kognitif, manusia terus-terusan berusaha mencapai keseimbangan kognitif. Maka apabila seorang lelaki meyakini bahwa lelaki tidak menangis kalau nonton film mengharukan, tapi lalu pada kenyataannya ia menangis juga, akan timbul perasaan yang sangat tidak nyaman dalam dirinya. Untuk mencapai keseimbangan kognitif, ia akan membuat banyak alasan, seperti “Ah, saya lagi nggak enak badan, jadi sedang sensitif, nih,” atau mati-matian menyangkal emosi harunya dan menyembunyikan tangisnya. Hal ini timbul karena mekanisme motivated reasoning atau proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi emosi.
Motivated reasoning juga bisa timbul dalam bentuk ngotot memunculkan apa yang ingin kita lihat. Ketika seorang suporter Prabowo sangat yakin bahwa paslon 02 akan menang, ia bisa menolak hasil quick count yang menyatakan kekalahan jagoannya. Apalagi jika ia dikelilingi oleh orang-orang yang juga menjunjung paslon 02. Ia akan heran, “Dukungan kepada Prabowo ‘kan tinggi. Kok bisa kalah, sih?” Ujung-ujungnya, ia akan protes dalam berbagai bentuk, agar keseimbangan kognitif dalam dirinya tercapai.
***
Karena cuitan saya tentang Novel Baswedan tadi, saya “digugat” oleh seorang warganet pendukung Jokowi, lewat direct message. Ia membela Jokowi, dan merasa tak ada bukti bahwa Jokowi tidak membela KPK dan para penyidiknya. Si warganet juga nyinyir terhadap Novel Baswedan karena keislamannya yang konservatif, serta karena ia meyakini rumor Novel Baswedan berafiliasi dengan parpol tertentu.
Manusia memang tidak berpikir dengan lurus, bahkan tidak bisa merevisi keyakinannya meski mereka diinformasikan bahwa keyakinan mereka salah ~ Laila Achmad Share on XMasalahnya, ia tidak bisa memberikan bukti bahwa Novel Baswedan betul memiliki agenda politik. Sebaliknya, berbagai media massa sudah sering mengangkat berita terverifikasi yang menunjukkan keengganan Jokowi untuk mengungkap pelaku kasus Novel Baswedan. Misalnya, alih-alih membuat Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen, Jokowi malah melemparkan kembali kasus Novel ke tim kepolisian yang sama sejak 2017, walau tim tersebut tidak menunjukkan hasil kerjanya selama dua tahun ini.
Namun si warganet menolak keras fakta-fakta terverifikasi yang saya sajikan. Ia malah terus menekankan keyakinannya yang berbasis opini dan rumor. Ia juga tak menjawab ketika saya bertanya, “Kalaupun Mas Novel memang beragama dengan konservatif atau berafiliasi dengan sebuah parpol, tidakkah ia tetap perlu dibela dan dilindungi, dengan cara menangkap pelaku kasusnya? Mas Novel tetap seorang warga negara tak bersalah yang dicoba dibunuh, lho.”
Logikanya, jika seseorang ditusuk maling, orang itu tetap harus ditolong, terlepas agama, suku, gender, dan pandangan politiknya.
Manusia hanya mau menerima informasi kalau sejalan dengan kepercayaannya. Jika manusia menemukan sebuah realita yang bertentangan dengan keyakinannya, ia akan gelisah, lalu mencari-cari justifikasi untuk menenangkan kegelisahannya. Prinsipnya, “fakta harus menyesuaikan saya.” Akibat bias konfirmasi ini, kalau seseorang menemukan fakta yang berbenturan dengan keyakinannya, yang diperbaiki bukan keyakinannya, tetapi faktanya.
Steven Sloman dan Philip Fernbach adalah dua ilmuwan kognitif di Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa jika seseorang sangat suka terhadap sesuatu, ia biasanya tidak punya pemahaman mendalam tentang hal tersebut. Pada tahun 2014, tak lama setelah Rusia menganeksasi Crimea di Ukraina, Sloman dan Fernbach membuat survei. Mereka bertanya kepada para responden, “Apakah Anda setuju jika Amerika melakukan intervensi militer?” Kemudian para responden diminta menunjukkan lokasi Ukraina di sebuah peta buta. Hasilnya, semakin meleset jawaban seorang responden atas lokasi Ukraina, semakin ia setuju atas intervensi militer. Kesimpulannya, responden yang setuju atas intervensi militer sebenarnya malah tak tahu apa-apa soal Ukraina.
Saya rasa, sebenarnya si warganet pendukung Jokowi tadi tidak betul-betul paham tentang keputusan-keputusan politik Jokowi, kasus Novel Baswedan, juga berbagai intrik di dalam KPK. Semakin ia tidak paham, semakin keras ia membela Jokowi.
Saya juga merasa, sebenarnya masyarakat pendukung Prabowo yang menyerang KPU tidak betul-betul paham apa yang terjadi dalam pemilu nasional ini, sehingga mereka menolak hasil quick count serta meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2019.
***
Manusia jarang bersedia mencari tahu informasi selengkap dan sefaktual mungkin, sampai ia mendapatkan gambaran yang paling mendekati kebenaran, lalu berusaha menerimanya. Tentu ada banyak media massa yang mempunyai berita-berita terverifikasi, namun—dengan segala emosinya—manusia seringkali mencomot berita-berita tersebut dengan sepotong-sepotong lalu membingkainya sesuai kepentingan sendiri, atau malah tidak mempercayainya sama sekali.
Keruwetan pandangan akibat sifat emosional manusia ini semakin menjadi ketika ada campur tangan tokoh. Lantarannya, manusia akan menganggap suatu informasi benar jika informasi tersebut didapat dari seseorang yang ia hormati, atau ia anggap lebih tinggi, meski informasinya belum tentu benar. Dalam bukunya 21 Lessons for 21st Century, Yuval Noah Harari menulis:
“Politisi tidaklah jauh berbeda dari musisi. Instrumen yang mereka mainkan adalah emosi dan sistem biokimia manusia. Mereka berpidato dan menyebabkan rasa takut di masyarakat. Mereka menulis cuitan, lalu munculah kebencian…Begitu politisi tahu ia bisa kapan saja memainkan emosi kita dan menimbulkan rasa gelisah, benci, kebahagiaan, dan kebosanan, politik pun menjadi sirkus emosi.”
Yuval Noah Harari
Tak heran jika banyak tokoh masyarakat yang punya kepentingan terus menggempur media dengan pendapat yang memicu emosi—khususnya emosi-emosi negatif—sehingga masyarakat tenggelam dalam kemarahan (misalnya, akibat Amien Rais dan ajakan makarnya) dan ketakutan (misalnya, akibat Prabowo dan segala prediksinya tentang kehancuran Indonesia).
Mengapa begitu? Ternyata ada hubungan antara kemarahan dan bias politik. Sebuah artikel jurnal di Political Psychology menyatakan, semakin seseorang marah, semakin keras penolakannya terhadap fakta yang bertentangan dengan keyakinannya. Saya rasa, itulah mengapa para tokoh politik, juru bicara, dan buzzer dari masing-masing kubu paslon rajin “memelihara kemarahan” simpatisannya dengan terus mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif di media. Misalnya, belakangan ini, beberapa oknum dari pihak paslon 02 rajin membakar semangat simpatisannya untuk melakukan people power dengan terus menjelek-jelekkan KPU dan pemerintah. Jika kemarahan mereka terus membara, pendukung paslon 02 bisa-bisa semakin menolak fakta.
***
Dalam buku Denying to the Grave: Why We Ignore the Facts That Will Save Us, psikiater Jack Gorman dan putrinya, Sara Gorman, seorang spesialis kesehatan masyarakat, mempelajari kesenjangan antara fakta ilmiah dengan keyakinan pribadi manusia. Mereka mengkhawatirkan orang-orang yang keyakinannya bisa berakibat fatal karena tidak didasari bukti saintifik. Misalnya, keyakinan bahwa vaksin imunisasi berbahaya.
Pasalnya, Jack dan Sara Gorman menemukan tak ada gunanya memberikan informasi yang akurat kepada orang-orang yang sudah mengimani hal-hal sebaliknya, sebab mereka akan mengabaikan informasi tersebut. Lebih lanjut lagi, Jack dan Sara Gorman mengutip penelitian yang membuktikan bahwa jika seseorang mendapatkan informasi yang mendukung keyakinannya—meskipun informasi itu salah—ia akan mendapatkan efek dopamine, senyawa alami tubuh yang bisa menghasilkan perasaan puas dan bahagia.
Sara dan Jack Gorman menyimpulkan, tantangannya adalah mencari cara mengatasi kecenderungan yang mengarah pada kepercayaan ilmiah yang keliru.
Sains mengungkapkan bahwa manusia memang “gelagapan” menghadapi dampak teknologi yang berkembang lebih cepat daripada evolusi manusia ini. Internet dan media sosial adalah platform sempurna untuk menyebarkan berbagai informasi—faktual ataupun tidak—dengan sangat cepat dan masif, sementara otak manusia belum cukup berevolusi agar “siap” mencerna informasi tersebut. Ilmu neurologi pun menunjukkan kecenderungan irasionalitas manusia yang tinggi, dan sepertinya susah untuk diturunkan.
Pada akhirnya, slogan “jadilah pemilih rasional” memang muskil untuk dijalankan.

Sehari-hari, Laila Achmad mengajar olahraga, menulis lepas, memproduksi podcast bersama Kejar Paket Pintar, dan menjadi ibu dari seorang anak lelaki.