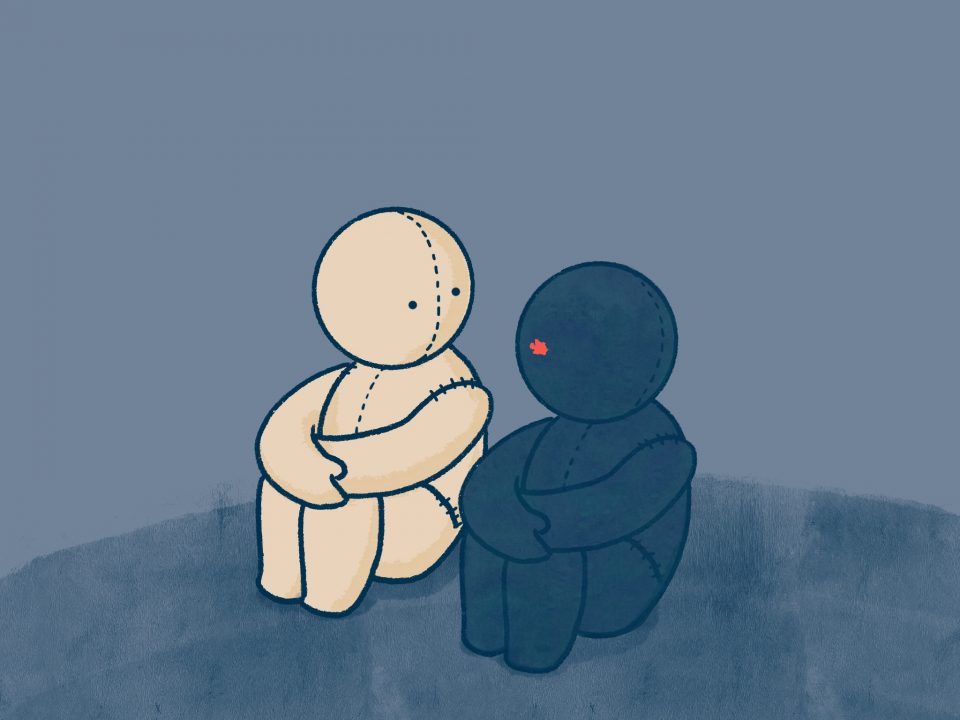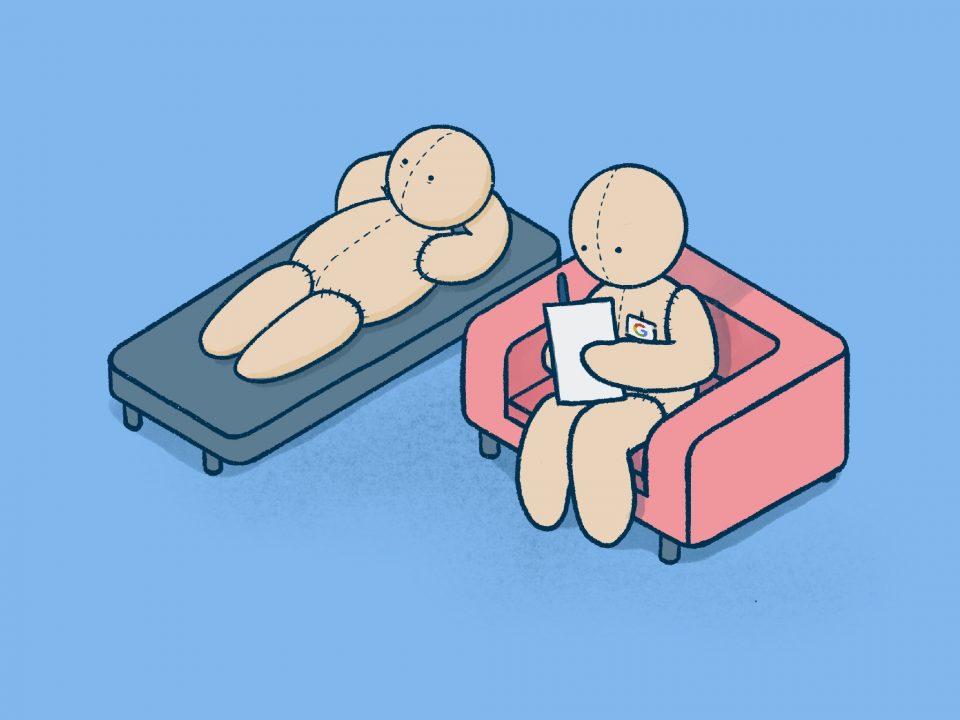Persoalan Bahasa dan Budaya pada Nama-Nama Kafe di Malang Raya
September 12, 2023
Mengingat Peristiwa 1965: Jalan Terjal Mencari Keadilan
September 30, 2023
Photo by Photoholgic on Unsplash
OPINI
Bersiasat di Tengah Kabut Asap: Polusi dan Bisnis Udara Bersih di Indonesia
oleh Khumairoh
Udara bersih kian sulit dihirup ketika industri berlomba-lomba menebang pohon, memoles kota dengan keindahan semu (artifisial), dan menyulap pohon dengan tenaga baterai. Penduduk kota pun dikompori untuk membeli oksigen isi ulang dalam galon-galon plastik, sebab udara di kota sudah sangat tercemar.
Tapi, jangan dulu naik pitam. Cerita di atas adalah gambaran polusi dan upaya berdagang udara bersih di Thneedville, sebuah kota imajiner yang dipimpin Walikota O’Hare dalam kartun animasi hasil adaptasi buku berjudul The Lorax. Buku itu ditulis oleh penulis cerita anak kondang, Dr. Seuss, yang diterbitkan pertama kali pada 1971.
Viralnya sambatan warganet tentang langit kelabu di Jakarta, konten edukasi bahaya polusi udara, dan iklan air purifier (alat pembersih udara) yang bertebaran di media sosial membuat film animasi lawas yang saya tonton satu dekade silam menjadi relevan dengan masa kini. Peristiwa ini tidak lagi sebatas cerita animasi di buku dan layar kaca atau pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tentang gas rumah kaca yang hanya lewat sepintas saat sekolah menengah, melainkan sudah terjadi hari ini dan dekat sekali dengan kita semua.
Polusi dalam Pusaran Sejarah Dinamika Kota
Kita mundur sejenak. Pada 1996, Adam W. Rome, seorang pakar sejarah lingkungan Amerika, menelusuri akar kemunculan istilah polusi dan memaparkan kajiannya dalam tulisan berjudul Coming to Terms With Pollution: The Language of Environmental Reform, 1865-1915. Menurut temuannya, arti dari istilah baru yang muncul pada 1814 ini kerap berubah-ubah. Pada mulanya, istilah polusi digunakan oleh kelompok pembaharu kesehatan sanitasi Amerika yang merujuk pada sesuatu hal yang tidak bersih dan kondisi sungai kotor, sehingga menyebabkan penyakit pada masyarakat.
Seiring dengan semakin banyaknya penelitian terhadap dampak lingkungan pada kurun waktu tersebut, penggunaan istilah polusi juga semakin bervariasi untuk menyebut kondisi udara yang terkontaminasi hasil pembakaran, bahan kimia lain yang tercampur di udara, dan proses industri lainnya.
Mayoritas penyebab polusi abad 19 sampai 20 tidak terlepas dari revolusi industri yang menandai modernisasi dalam dinamika kota di dunia. Beberapa aktivitas penyumbang polusi udara pada masa itu di antaranya adalah pembangunan smelter (pemurnian biji logam hasil tambang) di Georgia, pembangunan jalur kereta api di Chicago, dan aktivitas pertambangan di Inggris.
Efek polusi tak hanya berdampak pada manusia. Bahaya polusi udara juga mengintai hewan ternak dan tanaman pangan yang ada di kawasan pedesaan Inggris. Melihat penyebab dan dampaknya yang mulai kompleks, selepas 1915, isu polusi udara bukan lagi milik sektor kesehatan saja. Warga kota jadi sadar mengenai kondisi kotanya dan isu polusi udara pun bergulir di lingkaran para aktivis, pejabat publik, serta sektor swasta industri konsumen batubara. Mereka membentuk organisasi bernama The Smoke Prevention Association untuk mencari jalan keluar guna menekan polusi udara.
Jakarta Kota Kelabu
Polusi tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang baru. Polusi udara yang terjadi di Indonesia saat ini tak jauh beda kondisinya dengan gelombang awal modernisasi tahun 1970an. Jakarta, misalnya, sudah kadung mendapat label stinky city (kota yang bau) sejak masih bernama Batavia karena kanal-kanalnya yang mampet dan bikin bau tak sedap.
Arsip lawas Kompas yang digunakan oleh Debora Laksmi dalam artikelnya memuat berita polusi udara Jakarta pada Juli 1980. Ketika itu, kadar karbon monoksida (CO) mencapai 71-111 ppm (standar normal 40 ppm) karena emisi kendaraan bermotor dan debu jalanan membumbung ke udara yang akhirnya menempatkan Jakarta sebagai kota terpolutan nomor tiga di dunia.
Fenomena langit kelabu, udara yang sesak, dan unggahan foto dan video oleh warga soal polusi udara menyadarkan warga Jakarta dan sekitarnya bahwa udara yang mereka hirup bukanlah embun pagi yang menyegarkan, melainkan smog, yaitu gabungan antara asap (smoke) dan kabut (fog). Asap kendaraan kini bukan faktor tunggal penyebab smog, tetapi juga disumbang oleh sektor manufaktur, pembakaran sampah, emisi gas transportasi, dan lain sebagainya. Selain itu, partikel udara 2,5 µm atau seukuran 2,5 mikron ini ramai disebut-sebut sebagai partikel yang berbahaya dan berdampak serius ketika masuk ke saluran pernapasan.
Tahun ini, label “World’s Most Polluted City” yang disandang oleh Jakarta sejak Mei 2023 silam telah menyedot perhatian dunia. Mengingat Jakarta adalah salah satu kota paling vital di Indonesia, melonjaknya kasus infeksi saluran pernapasan di Jakarta, membuat media internasional berbondong-bondong menyorot polusi di Ibu Kota Jakarta dalam berbagai sudut pandang. Meskipun udara bergerak cepat dan partikel mikron amat fluktuatif, sampai saat artikel ini ditulis, Jakarta masih masuk 10 besar kategori udara tidak sehat.
Membaca pemberitaan media massa selama beberapa tahun belakangan membuat saya tersadar bahwa isu polusi udara memiliki polanya sendiri. Ia senantiasa datang berulang tiap tahun (biasanya antara Juni-Oktober) selama empat dekade terakhir, apalagi ketika musim kemarau yang kering sedang bertandang.
Tapi, kita juga perlu sadar kalau Indonesia itu bukan hanya tentang Jakarta.
Menghimpun Cerita Polusi Udara dari Kalimantan
Sama halnya dengan polusi yang terjadi di Jakarta, asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia juga menjadi persoalan serius yang juga perlu penanganan secara holistik.
“Aku masih ingat betul langit Kalimantan yang berwarna oranye pekat pada 2015, banyak anak yang collapse (tumbang) saat perjalanan berangkat ke sekolah. Pada tahun yang sama, bibiku meninggal dunia karena gagal napas,” begitu ujar Emanuella Shinta dengan suara tercekat.
Pertemuan saya dengan Shinta secara daring lewat platform media sosial pekan lalu menjungkirbalikkan semua citra ‘biasa-biasa saja dan lazim’ tentang kabut asap yang terjadi di Kalimantan sejak 1997.
Bahkan, pemudi Dayak yang tergabung dalam Ranu Welum Foundation ini juga punya pengalaman pribadi dengan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kesehatannya. Ia sempat kehabisan suara selama tiga minggu karena terpapar asap ketika berbulan-bulan turun ke lapangan untuk memadamkan titik api dan mengadvokasi isu karhutla.
Karena udara bersih adalah hak semua warga, agak janggal rasanya ketika itu harus dimonetisasi atau sekadar menjadi alat gaya-gaya-an di media sosial. ~ Khumairoh Share on XHal yang sama juga dialami oleh Daurie Bintang, salah seorang relawan karhutla di Kalimantan. Meski ‘hanya’ selama satu bulan berkegiatan di lapangan, dampak paparan asap bersemayam di paru-parunya selama lebih dari dua tahun. Beruntung ia kembali ke Jawa dan mengakses fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni. Meski saya berada di jarak ratusan kilometer dari Kalimantan, saya ikut merasakan sesak setiap kali memutar cerita mereka.
Tahun ini, pemberitaan media tentang kabut asap di Kalimantan hanya sebatas selingan. Tak banyak yang membicarakannya di media sosial. Jangankan jadi sorotan nasional, porsi beritanya mungkin hanya sekitar 0,11 persen dari isu-isu lingkungan lainnya, terutama kalau dibandingkan dengan yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. Padahal tingkat kabut asap di sana hampir setara dengan menghirup 672 batang rokok tiap harinya.
Membandingkannya dengan berita tentang protokol kesehatan di Jakarta, kebijakan Work From Home (WFH) yang diberlakukan kembali, dan pembatasan kendaraan ganjil genap, itu menunjukkan betapa cepatnya pemerintah dan dunia menanggapi isu polusi di Jakarta.
Senternya pembicaraan polusi udara Jakarta belakangan ini menjadi momentum yang tepat bagi kaum muda di Kalimantan untuk mengingatkan warga lokal tentang bahaya 2,5 µm, membangun harapan sekali lagi untuk menghirup udara bersih, sekaligus mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan penanganan dampak karhutla secara lebih serius.
Bukan kebelet viral, mereka hanya ingin menghirup udara bersih yang sama dengan kawasan lndonesia lainnya.
Berbisnis Udara di Indonesia
Barangkali, kita bisa memproyeksikan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan berupa kabut asap, sebagaimana yang terjadi di Hong Kong pada awal 2000-an yang kerugiannya mencapai 487 juta dollar/tahun. Mereka kehilangan produktivitas warga negara, harus membeli udara bersih, dan melakukan upaya-upaya lainnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pengabaian pemerintah terhadap masalah polusi udara selama empat dekade belakangan justru jadi peluang besar bagi sektor swasta untuk mengembangkan inovasi dan berbisnis udara bersih. Jangan kaget jika berjualan udara kemasan seperti O’Hare di film The Lorax bukan sekadar lelucon di dunia nyata. Perusahaan seperti Vitality di Kanada dan Aethaer telah mulai berbisnis udara bersih kemasan dalam toples sejak 2016 silam.
Ribuan kilometer dari Kanada dan Hong Kong, Piotr Jakubowski (yang kini dikenal sebagai pendiri NAFAS Indonesia) mulai mendalami masalah polusi di Indonesia sejak 2016 serta mempersiapkan teknologi yang terintegrasi dengan data. Agustus 2020, ia bersama rekannya, Nathan Roestandy, meluncurkan aplikasi Nafas Indonesia Air Quality.
Sebelumnya, AirVisual milik IQ Air juga meluncurkan aplikasi serupa pada 2015. Saat era digital dan banyak orang mendewakan data, aplikasi-aplikasi baru ini seolah menjadi angin segar bagi publik. Mereka merespon isu kualitas udara Jakarta sekaligus membantu warga Jakarta untuk mengakses laporan kualitas udara berbasis data secara real time (sesuai waktu yang sebenarnya).
NAFAS.id memang tidak tiba-tiba ‘berjualan udara bersih’ saat pertama kali diluncurkan. Dalam istilah pemasaran (marketing), mereka sedang menjalankan strategi creative marketing (pemasaran kreatif). NAFAS.id memulai bisnisnya dengan menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah Jakarta, terhadap akses informasi kualitas udara dengan data yang langsung dan akurat.
Mereka kemudian mulai memperkenalkan isu kualitas udara melalui cuitan di sosial media Twitter dengan konsisten mengkampanyekan isu langit kelabu menggunakan tagar (#) ITUBUKANKABUT. Itu menjadikannya penting dan mendesak bagi orang yang ingin mengetahui ambang batas normal udara bersih hingga berbahaya bagi kepentingan kesehatan pernapasan.
Tidak berhenti sampai di situ, kerja sama multi-pihak juga diperlukan untuk menghasilkan pemecahan masalah kabut asap secara lebih menyeluruh dan menyentuh akar permasalahan. NAFAS kemudian menggandeng individu atau perusahaan untuk turut peduli dengan isu lingkungan melalui agenda sponsorship. Itu diwujudkan dalam pengadaan Clear Air Zone berbasis aplikasi di sekolah prestise di bilangan Jakarta Selatan dan pendanaan dari lembaga keuangan (purchase-advocacy).
Sebenarnya NAFAS tak hanya sekadar mengedukasi tentang pentingnya pengetahuan kualitas udara. Belakangan NAFAS juga menggarap unit bisnis teknologi untuk menjual alat monitor kualitas udara indoor dan smart air purifier dengan rentang harga berkisar antara 2-4 juta/unit. Data dari Emerge Research memperkirakan ceruk pasar industri pemurni udara dari berbagai merek dunia ini bisa mencapai 18,15 miliar dollar Amerika pada 2027 mendatang dengan tingkat pertumbuhan gabungan sejak 2020 sebesar 10,7 persen. Naiknya minat pasar untuk mengadopsi pembersih udara tak terlepas dari masyarakat yang resah terhadap peningkatan polusi di daerah perkotaan di negara-negara padat penduduk guna mengantisipasi bahaya kesehatan yang mengintai.
Karena udara bersih adalah hak semua warga, agak janggal rasanya ketika itu harus dimonetisasi atau sekadar menjadi alat gaya-gaya-an di media sosial.
Semestinya Langit Biru Luas dan Kita Bisa Bernapas Bebas
Indeks kualitas udara di atas 140 menjadi indikasi udara tidak sehat bagi kelompok rentan (memiliki komorbid), terutama kelompok usia anak-anak dan lansia.
Dua kawan saya, Yuanita dan Utami, sering menghadapi masalah pernapasan ketika pulang kampung atau pindah ke Jakarta. Dalam sebulan, Utami harus bolak-balik fasilitas kesehatan dan berbagi peran dengan suaminya untuk mengobati anak mereka yang mengalami sakit pernapasan.
Bagi Utami yang baru beberapa bulan pindah ke Ibu Kota dan menghadapi kondisi polusi udara yang kian buruk, ia jadi lebih rajin mengumpulkan informasi seputar kesehatan pernapasan. Jika kondisi udara tak kunjung bersih, atas saran dokter anak, ia memutuskan berinvestasi pada air purifier untuk mendukung aktivitas dan pemulihan buah hatinya.
Sedangkan bagi Yuanita, ia harus rajin minum obat untuk menyesuaikan diri dan meringankan napas ketika di Jakarta. Padahal, selama di Yogyakarta ataupun di kota lain dengan langit biru dan udara segar, ia jarang sekali mengalami gangguan pernapasan.
Alat pembersih udara memang jadi salah satu solusi masalah polusi. Namun, jangan sampai hal itu membuat kita ‘menormalisasi’ masalah asap dan polusi yang akarnya sistemik ~ Khumairoh Share on XBerkaca dari Hong Kong dan beberapa negara berkembang lainnya yang dulu sempat menghadapi polusi dan kabut asap yang parah, risiko kelas ekonomi atas terpapar polusi adalah sebesar 40-45 persen lebih rendah dari kelas ekonomi bawah. Begitu pula di Indonesia, akses udara bersih juga tak lepas dari persoalan kelas. Beberapa kalangan menengah atas, terutama di Jakarta, bisa dengan mudah mengakses air purifier sebagai barang individu. Namun, di Kalimantan justru berlaku kebalikan. Dalam satu ruangan Rumah Singgah Aman Asap misalnya, satu unit teknologi tersebut harus digunakan secara komunal dan hanya diprioritaskan untuk balita dan lansia. Padahal, masalah polusi udara di Kalimantan akibat karhutla tidak kalah serius dibandingkan dengan Jakarta.
Tanpa perlu beranjak ke Kalimantan, di Jakarta sendiri, kita bisa melihat kalau akses terhadap teknologi air purifier maupun masalah polusi udara secara umum tidak pernah lepas dari dimensi kelas sosial. Misalnya saja, kelompok informal yang harus berjualan sepanjang hari di jalanan ibu kota lebih rentan terpapar polusi udara dibandingkan kelompok kerah putih yang bekerja di dalam gedung bertingkat dengan fasilitas air purifier memadai. Bagi kelompok miskin yang setiap hari gelisah harus mengisi perut, membeli air purifier demi bernafas bebas tentu menjadi satu lapisan beban kehidupan yang semakin memberatkan.
Di tengah masalah polusi udara yang terlanjur memburuk seperti sekarang ini, menggunakan air purifier memang bisa menjadi salah satu solusi. Namun, jangan sampai hal itu membuat kita ‘menormalisasi’ masalah asap dan polusi yang akarnya sistemik. Alih-alih semakin menguntungkan bisnis para pemilik modal, sudah sepatutnya kita menggugat dan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. Misalnya, bagaimana pemerintah menanggulangi masalah asap pembakaran, aktivitas pabrik yang kelewat batas, transportasi yang belum terintegrasi, dan penyebab-penyebab lainnya?
Namun, sekali lagi, melihat carut-marutnya penanganan kabut asap karena kebijakan pemerintah yang masih ‘coba-coba’, warga biasa seperti kita bisa apa tanpa harus menggadai kesehatan demi dampak kerusakan lingkungan?

Khumairoh, suka sobo pasar dan baca isu lingkungan.
Artikel Terkait
Memerangi Maskulinitas Beracun, Tanggung Jawab Siapa?
Memerangi maskulinitas beracun bukan berarti mengutuk laki-laki atau atribut laki-laki, melainkan untuk memerangi dampak berbahaya dari maskulinitas tradisional, seperti dominasi dan persainganMenjadi Admin Akun Psikologi: Bukan Sekadar Berbagi, Tapi Juga Menerima
Di Catatan Pinggir ini, Ayu Yustitia berkisah tentang pengalamannya menjadi admin media sosial Pijar Psikologi. Ayu tersadar bahwa bahwa banyak orang di luar sana yang merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Pengalaman ini mendorong Ayu untuk mendorong kita semua untuk lebih baik kepada diri sendiri dan orang di sekitar kita.Tanya Kenapa
Di usianya yang muda, Putri Hasquita Ardala sudah mengenyam banyak pengalaman tentang pentingnya kesehatan mental. Di Catatan Pinggir ini, Putri mengingatkan kita semua tentang panjangnya jalan menghadapi depresi dan bagaimana kita semua perlu meminta bantuan.