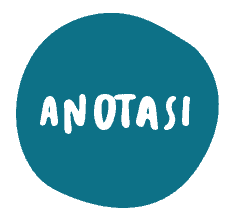Setelah penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949 dan berdirinya Perusahaan Film Nasional Indonesia (PERFINI) pada 1950, tidak kurang dari 20-an film tentang perang kemerdekaan Indonesia telah dibuat hingga saat ini.
Dari sekian banyak film tentang perang kemerdekaan, sebagian besarnya berlatar masa revolusi (1945-1949), yaitu masa awal kemerdekaan yang ditandai dengan peristiwa kekalahan tentara Jepang atas Amerika Serikat, proklamasi kemerdekaan Indonesia, agresi militer Belanda, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Jika dibandingkan, film tentang kemerdekaan yang bersinggungan dengan peristiwa perang merebut kemerdekaan jumlahnya tidak seberapa.
Melalui film-film tersebut, kita bisa menelusuri bahwa gaya film yang ditampilkan selalu menginduk pada zamannya. Ini tidak terlepas dari kedekatan zaman dengan realitas yang ingin ditampilkan. Selain itu, konteks dan babak perpolitikan juga turut mempengaruhi karakteristik film-film yang berkembang.
Masa Awal Kemerdekaan
Masa awal kemerdekaan Indonesia dibuka dengan sebuah film yang menjadi cikal bakal perfilman nasional, Darah dan Doa. Film yang tanggal syuting pertamanya (30 Maret 1950) kelak menjadi Hari Film Nasional ini disutradarai oleh Bapak Film Nasional, Usmar Ismail. Melalui keterbatasan dalam segala hal, Darah dan Doa digarap dengan keyakinan bahwa film ini akan menjadi tonggak awal kelahiran film Indonesia dalam cara pandang kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Hal tersebut karena pada saat itu, bioskop lokal masih kebanjiran film-film koboi dari Amerika.
Dengan bujet yang bisa dibilang terbesar pada zamannya, Darah dan Doa menjadi salah satu film berkualitas pertama dalam negeri. Pertanyaan besarnya, apa sebabnya Darah dan Doa menjadi film dengan kualitas yang (saat itu) dianggap cukup mumpuni untuk disaingkan dengan film-film impor dari luar negeri?
Dalam artikelnya “Hari Film Nasional adalah Saat Usmar Ismail Mengambil Gambar Pertama Darah dan Doa,” VOI menuliskan bahwa film Darah dan Doa mampu menampilkan nilai patriotisme dan kemanusiaan dalam paduan yang menarik. Dalam menceritakan Sudarto (tokoh utama) misalnya, konsep kemanusiaan tergambar jelas dari beberapa dialognya. Misalnya saja, dialog di babak awal film, “Aku tidak mau tentara dipakai sebagai alat pembalasan dendam.”
Dialog itu terjadi antara Kapten Sudarto dan Kapten Adam perkara dibunuh atau tidaknya seorang pemimpin pemberontak yang juga dikenal oleh Sudarto.
Konsep kemanusiaan juga tergambar pada dialog lainnya, yaitu sesaat sebelum Kapten Sudarto dibunuh (di akhir film) oleh orang tak dikenal. Ia mengatakan, “Lebih baik aku mati daripada membunuh saudaraku. Itu prinsip hidup. (…) Bunuhlah aku.” Lalu orang tersebut menembak Sudarto. Sudarto pun melanjutkan bicaranya, “Jangan diulangi lagi. Biar aku saja.”
Namun, jangan kira film Darah dan Doa hanya fokus pada nilai kemanusiaan dan patriotisme. Tengok saja karakter yang coba ditampilkan Usmar Ismail melalui tokoh Kapten Adam misalnya. Sebagai kebalikan (antitesis) dari tokoh Sudarto, Adam diceritakan sebagai sosok yang tegas dengan segala pikiran, keputusan dan tindakannya. Nilai yang menekankan pada keberadaan tokoh (eksistensi) jelas menjadi poin penting yang ingin ditampilkan, dan itu berhasil.
Di tangan Usmar Ismail juga lahir karya macam film Enam Djam di Djogja (1953) yang bercerita tentang peristiwa Serangan Umum Satu Maret. Melalui Enam Djam di Jogja, Usmar Ismail menggambarkan kondisi sosial masyarakat pada agresi militer Belanda kedua dengan apik. Ketika tentara Belanda dan pejuang kemerdekaan Indonesia berada pada posisi yang jelas (saling bermusuhan), tidak dengan masyarakat sipil.
Film perang kemerdekaan pada awal terbentuknya republik biasanya juga sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaan tokoh serta pergolakan yang terjadi dalam diri masing-masing tokohnya. Hal semacam ini menjadi magnet besar bagi para penonton dan kritikus film yang bahkan menjadi diskursus hingga hari ini.
Masa Orde Baru
Film tentang perang kemerdekaan pada masa Orde Baru punya ciri yang cukup mudah dikenali. Film di masa ini biasanya punya skenario yang bisa dibilang sangat sederhana. Mungkin karena penggambaran perang adalah tentang kebaikan dan kejahatan, dua nilai ini selalu dipakai menggambarkan moralitas dalam perang kemerdekaan.
Dalam film Pasukan Berani Mati (1982) karya Imam Tantowi misalnya, kita bisa melihat para pemainnya digambarkan terbatas pada nilai “baik” dan “buruk.” Bahwa semua orang Belanda (tentara atau warga sipil) adalah buruk wataknya, sedangkan pribumi adalah pihak tidak bersalah yang sudah sepatutnya dibela.
Latar penokohan yang tidak mendalam ini menjadikan film Pasukan Berani Mati tidak menampilkan peran “abu-abu.” Penokohan yang “membelot”, misalnya dari tokoh baik menjadi jahat atau sebaliknya, terjadi begitu saja tanpa adanya latar belakang kuat. Ini bisa kita temui misal dari tokoh Willem (Barry Prima) yang seorang keturunan Belanda dan menjadi gerilyawan tanpa penceritaan mendalam. Atau tokoh Jabar (El Manik) yang berubah baik dan membantu revolusi setelah tiga “sahabat malingnya” terbunuh di tangan Belanda. Hanya tokoh Suci (Dana Christina) yang mungkin masih punya sedikit pembelaan untuk melakukan pengkhianatan. Itu terjadi setelah Willem menembak orang tuanya yang hampir saja memberitahukan lokasi persembunyian pasukan gerilya.
Pengenalan tokoh yang memegang teguh nilai “baik” dan “buruk” tanpa ada peran abu-abu atau peran tanda tanya semacam ini memang menjadi ciri dalam film perang kemerdekaan di era Orde Baru. Konflik terjadi hanya antara hitam dan putih sehingga kita sebagai penonton hanya akan punya dua pilihan, ikut arus atau berpihak pada peran antagonis (tokoh dengan karakter jahat).
Mengenai konsep hitam dan putih atau baik dan buruk ini juga bisa kita temui dalam film tentang perang kemerdekaan era Orde Baru macam Mereka Kembali (1975), Djanur Kuning (1979), dan Kereta Terakhir (1981).
Terbatasnya peran yang ditampilkan dalam sebuah film pada masa Orde Baru jelas berhubungan dengan pembersihan besar-besaran film yang bertema Partai Komunis Indonesia (PKI). Orde Baru memang memiliki agenda politik untuk menggeser peran film yang semula memiliki kecenderungan politik sesuai kepentingan sang pembuat film (sineas) menjadi sebatas produk budaya saja. Ini dipertegas dengan dikeluarkannya Kode Etik Film oleh Badan Sensor Film (BSF) pada 1981.
Masa Reformasi
Pada masa reformasi, film perang kemerdekaan menemukan cara yang lebih baru. Selain penceritaannya, jenis filmnya juga juga punya jalan alternatif. Ini bisa ditemukan dalam cerita keberhasilan para kader Akademi Angkatan Udara (AAU) yang menyerang pos-pos Belanda di Semarang, Salatiga dan Ambarawa melalui pesawat tempur dalam film Kadet 1947. Kadet 1947 menjadi satu-satunya film perang kemerdekaan yang menampilkan tentara Indonesia menyerang Belanda menggunakan pesawat tempur.
Trilogi Merdeka (Merah Putih, Darah Garuda, Hati Merdeka) sejauh ini adalah representasi film perang kemerdekaan yang cukup mencuri perhatian. Dalam setiap filmnya, Trilogi Merdeka menampilkan porsi perang dan drama dalam porsi yang pas. Latar belakang yang jelas pada setiap tokoh punya peran serta terjalin dengan baik.
Sebagai film dengan cerita trilogi yang harus saling sambung, sang sutradara paham bahwa puncak dari film yang satu harus menjadi pertanyaan besar untuk memulai film selanjutnya. Ini bisa dilihat ketika film pertama ditutup dengan tertangkapnya Mayor Van Gaartner (Rudy Wowor) oleh sepasukan kecil pejuang Indonesia dan bersiasat untuk menggunakan Mayor Belanda tersebut menembus pertahanan Belanda. Maka, tercipta pertanyaan besar untuk memulai film selanjutnya, “Berhasilkah strategi yang digunakan para pejuang Indonesia tersebut?”
Alternatif lain datang dari sineas negeri kincir angin. Pada September 2020 misalnya, muncul film De Oost. Film yang dibuat oleh gabungan beberapa rumah produksi dan disutradarai oleh sineas berdarah Indo-Belanda ini mengambil sudut pandang dari tentara Belanda pada agresi militer Belanda. Film ini berhasil menggambarkan perang kemerdekaan dengan narasi yang jelas sangat jauh berbeda dari yang selama ini ditampilkan oleh film dari dalam negeri.
Jika film perang kemerdekaan dalam negeri biasanya terkungkung dalam narasi patriotisme, nasionalisme dan keberadaan manusia dan negara, De Oost menampilkan narasi kemanusiaan dan kekejaman perang sebagai hal penting. Film ini lantas membikin geger publik Belanda, FIN (Federatie Indische-Nederlands) yang merupakan federasi veteran perang di Hindia Belanda (dulu) adalah salah satunya.
Narasi dalam Film Perang Kemerdekaan
Selain narasi tentang patriotisme dan nasionalisme, film perang kemerdekaan sarat akan pengaruh kondisi perpolitikan pada masanya. Film-film di era awal kemerdekaan sampai sebelum Orde Baru berkuasa didominasi oleh narasi dari kubu sayap kiri (PKI) vs kanan (Masyumi).
Dalam penokohan misalnya, sineas dari Masyumi (organ kebudayaan Masyumi) lebih banyak menciptakan narasi tentang ketokohan dibandingkan dengan sineas dari Lekra (organ kebudayaan PKI) yang fokus pada permasalahan sosial macam ketimpangan kelas, gender dan lainnya.
Memasuki era Orde Baru, narasi film terutama yang berhubungan dengan perang kemerdekaan terlalu fokus pada patriotisme dan nasionalisme serta meninggalkan area abu-abu seperti yang diciptakan sineas di era awal kemerdekaan. Ini tentu berhubungan erat dengan apa yang ingin dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, yakni stabilitas nasional. Namun, meski terkesan berhasil dalam hal stabilitas politik secara nasional, ini justru membuat narasi film perang kemerdekaan tidak bisa berkembang lebih jauh. Hal ini diperparah dengan munculnya kode etik mengenai sensor film.
Setelah Orde Baru tumbang, film perang kemerdekaan tidak lantas berubah sepenuhnya. Beberapa film memang menampilkan narasi yang berbeda mengenai kemerdekaan. Namun begitu, bahkan ketika sineas tidak lagi perlu berpikir seribu kali mengenai afiliasi politik dan sensor berlebihan, film perang kemerdekaan tetap menampilkan nilai patriotisme dan nasionalisme yang sayangnya, kadang kelewat berlebihan.

Taufik Hidayat adalah penulis lepas di beberapa media alternatif. Ia senang menonton dan menulis film secara acak.