
Komunikasi Risiko: Membantu atau Membebani?
October 9, 2024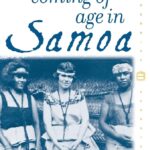
Menjalani Masa Remaja Lebih Mudah Jika Tinggal di Samoa
October 15, 2024
Photo by Cytonn Photography on Unsplash
OPINI
Sembilu Bermata Ganda: Dilema Sertipikat Tanah
oleh Iqbal Abizars
Pertama-tama, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak salah tik saat menulis sertipikat. Dalam konteks hukum pertanahan nasional, istilah legal yang dipakai memang sertipikat bukan sertifikat.
Sertipikat tanah adalah surat tanda bukti atas suatu hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sederhananya, siapa yang mempunyai dan mampu menunjukkan suatu sertipikat tanah yang sah secara hukum, maka dialah pemegang hak atas sebidang tanah tertentu.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo tampak menggenjot ‘produksi’ sertipikat tanah di berbagai daerah. Pendaftaran tanah di Indonesia memang secara masif dilakukan selama dua dekade kepemimpinan beliau. Salah satu contohnya—yang memiliki kesan kolosal—adalah pada Kamis (01/12/2022) ketika Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.552.450 sertipikat tanah secara hybrid di Istana Negara. Menteri ATR/Kepala BPN kala itu, Hadi Tjahjanto, yang turut hadir menyampaikan laporan bahwa pembagian sertipikat tersebut terdiri atas 1.423.750 sertipikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 119.699 sertipikat hasil redistribusi tanah yang masuk dalam skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Menteri Hadi Tjahjanto juga melaporkan bahwa di tahun 2022, dari sekira 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendata dan mendaftarkan sebanyak 100,14 juta bidang tanah. Sebanyak 82,5 juta bidang tanah di antaranya telah bersertipikat.
Tujuan Pendaftaran Tanah
Syarat terbitnya sertipikat adalah melakukan pendaftaran tanah. Tujuannya ada tiga, yaitu kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Khusus kepastian hukum dan perlindungan, dua unsur tersebut memiliki dua dimensi. Selain sebagai tujuan pendaftaran tanah, juga sebagai manfaat utama yang diterima oleh pemegang hak atas tanah. Dua unsur tersebut mempermudah tiap pemegang hak atas tanah untuk melakukan pembuktian bahwa dirinya adalah sebenar-benarnya pemegang hak atas tanah tertentu. Dengan kata lain, tujuannya untuk menghindarkan pemegang hak atas tanah dari klaim-klaim pihak lain yang ingin merampas tanahnya atau mengambil manfaat darinya dengan cara yang ilegal.
Tujuan dan manfaat tersebut sejalan dengan apa yang disebut eksklusi oleh sejumlah ilmuwan, seperti Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li dalam buku Kuasa Eksklusi, yaitu bagaimana pihak-pihak tertentu dicegah untuk mendapat manfaat dari sesuatu. Kenapa dicegah? Karena yang paling berhak untuk mendapat manfaat dari suatu objek tanah adalah pemegang haknya.
Dilema Sertipikat Tanah
Jika tujuan pendaftaran tanah—yang pada akhirnya melahirkan sertipikat tanah—tercapai, maka akan muncul sebuah manfaat khas: pemegang hak atas tanah memiliki kewenangan untuk menjual, mengalihkan, dan menjadikan tanahnya sebagai jaminan utang. Kelahiran sertipikat tanah menjadi titik mula bagi perjalanan baru suatu bidang tanah: resmi menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan di pasar. Motif ekonomi tersebut muncul karena kepastian hukum dan perlindungan. Dampaknya adalah calon pembeli tidak ragu untuk membeli tanah yang pasti siapa pemiliknya. Selain itu, pihak yang ingin menyewa juga mantap hatinya jika tanah yang akan disewa jelas kedudukan hukumnya. Kreditur pun yakin untuk menyalurkan kredit dengan agunan tanah yang dijamin dapat disita jika debitur wanprestasi (tidak mampu memenuhi kewajibannya).
Di sinilah dilema itu menyembul. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pendaftaran tanah mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah. Namun, di saat yang bersamaan, terbitnya sertipikat justru membukakan jalan bagi pemegang hak untuk kehilangan tanahnya. Sertipikat bagai sembilu bermata ganda: melindungi sekaligus berpotensi menghilangkan.
Kemudahan untuk mengalihkan kepemilikan hak atas tanah adalah akibat lain—jika tidak bisa disebut sebagai akibat buruk—dari sertipikat tanah. Bagi orang-orang tertentu, khususnya mereka yang rentan secara sosial dan ekonomi, pengalihan tersebut bisa menjadi alternatif atau bahkan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan hidup dari berbagai impitan keadaan. Motifnya pun beragam: hal yang paling kentara adalah kebutuhan akan uang yang begitu mendesak. Misalnya, butuh dana darurat untuk berobat karena sakit keras, tercekik utang, atau penghasilan yang tidak lagi mencukupi untuk sekadar bertahan hidup.
Kelahiran sertipikat tanah menjadi titik mula bagi perjalanan baru suatu bidang tanah: resmi menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan di pasar. ~ Iqbal Abizars Share on XAkademisi Tania Murray Li dan Pujo Semedi memaparkan fenomena tersebut dengan bagus dalam buku mereka yang berjudul Hidup Bersama Raksasa. Keduanya menjelaskan kehidupan petani plasma di suatu perkebunan sawit di Kalimantan yang begitu rentan. Para petani menggantungkan hidup hanya pada satu jenis tanaman (sawit), satu perusahaan yang membeli hasil panen, dan satu ekosistem ekonomi yang lebih banyak merugikan petani. Di sisi lain, banyak petani hanya memiliki kapling sawit seluas dua hektare. Dalam konteks perkebunan sawit, luasan tersebut tergolong sangat sempit sehingga berpengaruh ke penghasilan yang sedikit. Banyak rumah tangga petani yang kemudian perekonomiannya tidak berkembang atau malah jatuh miskin. Jika kemudian datang suatu keadaan yang sangat darurat, petani harus siap merelakan kapling sawit mereka untuk digadaikan atau dijual.
Dalam kadar tertentu, menjadikan hak atas tanah sebagai jaminan untuk mendapat utang memang tidak buruk. Bagi mereka yang dapat mengelola utang dengan baik untuk kegiatan produktif, utang bisa menjadi pilar dalam memperkuat perekonomian sebagai instrumen modal. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang menjaminkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk modal produksi. Namun, tak semua pemegang sertipikat tanah di Indonesia punya literasi keuangan yang mumpuni—lebih-lebih di tingkat rumah tangga. Kita juga harus sadar, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidupnya rentan, sebagaimana para petani plasma sawit di Kalimantan. Pihak-pihak yang rentan tersebut mengalihkan hak atas tanah miliknya karena terjepit keadaan, sedangkan mereka tidak dilindungi oleh jaminan sosial dan ekonomi yang memadai. Barangkali, kehilangan tanah adalah proses berpindah dari suatu penderitaan menuju ke penderitaan yang lainnya bagi orang-orang yang rentan. Mereka coba menyelesaikan masalah dengan melepas aset yang justru sangat berpotensi melahirkan masalah baru.
Sertipikat tanah kemudian menjelma menjadi pelumas yang melancarkan perpindahan kepemilikan dan penguasaan tanah dari seseorang kepada yang lainnya. Memang benar jika menjual dan menggadaikan tanah tak terbatas hanya pada tanah-tanah yang bersertipikat saja. Praktik di pedesaan—khususnya masyarakat yang tak terikat oleh hukum adat dengan sistem kepemilikan tanah komunal—banyak tanah tidak bersertipikat diperjualbelikan dan dijadikan jaminan utang. Namun, praktik yang demikian lingkupnya bersifat terbatas.
Ketimpangan Akibat Tanah sebagai Komoditas
Memandang tanah bukan lagi sebagai hak dasar rakyat, tetapi sebagai barang komoditas yang bisa diperjualbelikan memiliki konsekuensi. Dampak buruk dari pandangan tersebut ialah membuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya akumulasi kepemilikan dan penguasaan tanah pada pihak tertentu. Artinya, sangat mungkin mayoritas tanah di Indonesia akan dimiliki oleh segelintir orang saja. Tanah-tanah milik kaum yang rentan siap diambil alih oleh mereka yang mapan finansial. Momentum saja yang menentukan.
Masalah ketimpangan tersebut sebenarnya sudah dan masih terjadi. Berdasarkan publikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2022, ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58 (gini ratio). Angka tersebut menunjukkan bahwa 1% penduduk menguasai 58% sumber daya agraria berupa tanah dan ruang. Angka riilnya mungkin bisa lebih banyak alias lebih timpang karena BPN tidak memasukkan kawasan hutan dalam perhitungan mereka.
Ketimpangan tersebut jelas berkorelasi dengan buruknya kesejahteraan rakyat. Sebanyak 99% penduduk harus saling berebut tanah yang jumlahnya tersisa 42% saja dari total tanah yang ada di Indonesia. Contoh nyatanya begitu dekat dengan kehidupan kita: mulai dari rumah tangga petani yang berlahan sempit hingga generasi muda yang kesulitan mempunyai hunian. Keadaan itu diperparah oleh kehadiran para spekulan (pencari keuntungan besar dalam perdagangan) yang membeli tanah di mana-mana untuk tujuan investasi. Tanah benar-benar menjadi komoditas dengan harga yang tak terkendali. Hak dasar rakyat pun tak terpenuhi.
Bung Hatta telah mewanti-wanti jauh-jauh hari terkait tanah sebagai komoditas. “Apabila tanah dipandang sebagai faktor produksi yang terutama pemakaian tanah—selain daripada pekarangan tempat tinggalnya—hanya boleh sebagai faktor produksi pula. Tanah tidak boleh lagi menjadi objek perniagaan, yang diperjualbelikan semata-mata untuk mencari keuntungan.” Pesan tersebut disampaikan oleh Bung Hatta melalui pidatonya pada pembukaan Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari 1946. Apa yang disampaikan Bung Hatta menemukan konteksnya pada saat ini: tanah yang menjadi objek perniagaan dan diperjualbelikan semata-mata untuk mencari keuntungan ternyata benar-benar membawa masalah bagi segenap rakyat.
Pada akhirnya, program pendaftaran tanah yang melahirkan sertipikat akan menimbulkan apa yang disebut Derek Hall dan rekan sebagai ‘dilema pertanahan’. Sertipikat tanah mempunyai wajah ganda: satu wajah adalah kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah, wajah yang lain justru memberi peluang bagi pemegang hak untuk kehilangan tanahnya. Dilema yang lain adalah sertipikat tanah secara tak langsung ikut andil dalam proses ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah.
Dilema seperti itu tak patut disingkirkan, tetapi harus diberikan ruang untuk terus dipikirkan jalan keluarnya. Potensi buruknya nyata, meskipun mungkin prosesnya senyap dan tidak dramatis: tanah-tanah akan terus diakumulasi oleh sedikit orang, sehingga ketimpangan yang awalnya akan diatasi oleh pemerintah justru makin menjadi-jadi. Ingin punya tanah susahnya setengah mati, setelah punya pun mempertahankannya mati-matian. Huft.
*Pengungkapan: versi pertama artikel ini telah diterbitkan di platform pribadi penulis.

Iqbal Abizars adalah penulis lepas dan petani dari lereng Gunung Sumbing, Temanggung. Agraria, pangan, pertanian, dan ekonomi kerakyatan adalah isu-isu yang menjadi perhatian utamanya. Abizars juga menekuni kepenulisan fiksi-sejarah. Ia bisa disapa di @idabizars (Instagram & X)
Artikel Terkait
Bedol Desa dan Kisah Pengorbanan Masyarakat Wonogiri
Pembangunan waduk Gajah Mungkur di Wonogiri tidak lepas dari pengorbanan masyarakat lokal. Mereka terpaksa menerima gagasan pembangunan dengan mengikuti program transmigrasi bedol desa.Menilik Krisis Iklim dari Ketinggian 35.000 kaki
Di Catatan Pinggir ini, Brurce Mecca yang bekerja di sebuah lembaga wadah pemikir (think tank) internasional terkait kebijakan iklim, menggambarkan pandangannya tentang krisis iklim dari kacamata seorang penumpang di sebuah penerbangan rute Jakarta – Kalimantan Timur.Di Balik Kontroversi Pengembangan Wisata Superpremium
Mengapa pengembangan pariwisata superpremium selalu ditentang, ditolak, dan menimbulkan kontroversi? Pengembangan Taman Nasional Komodo (TNK) tahun lalu memperlihatkan pentingnya pemahaman mendalam tentang alam, ekologi, dan juga pariwisata.






