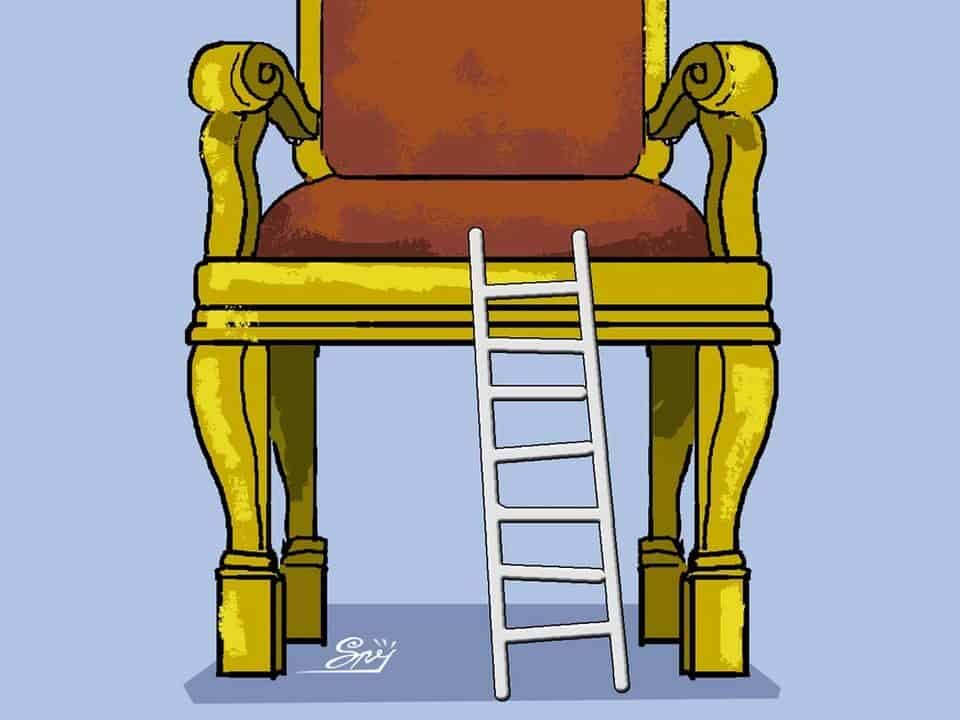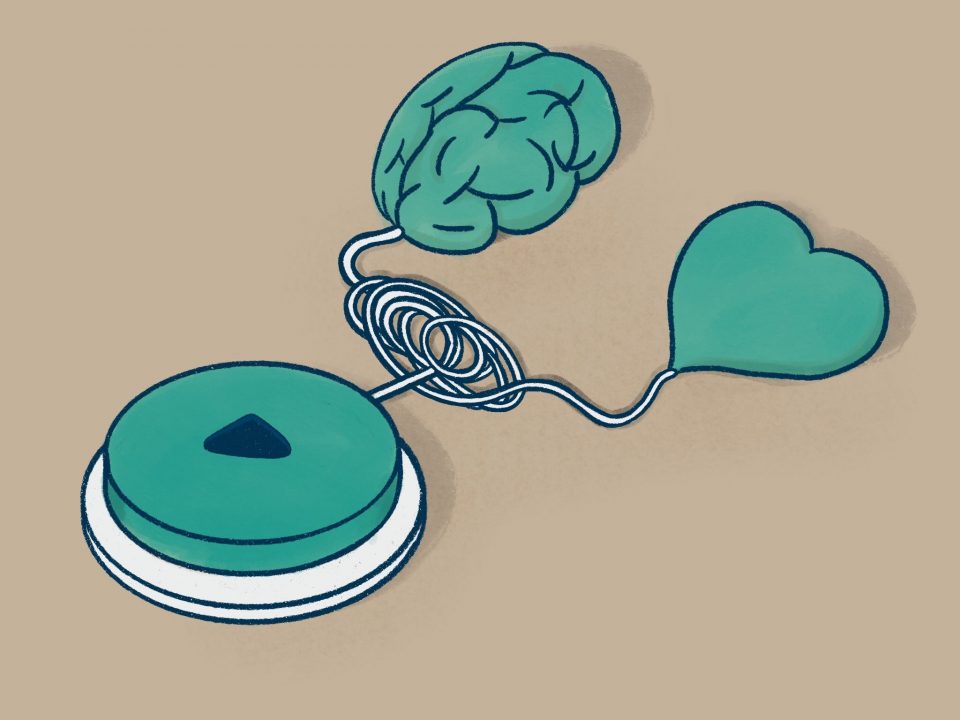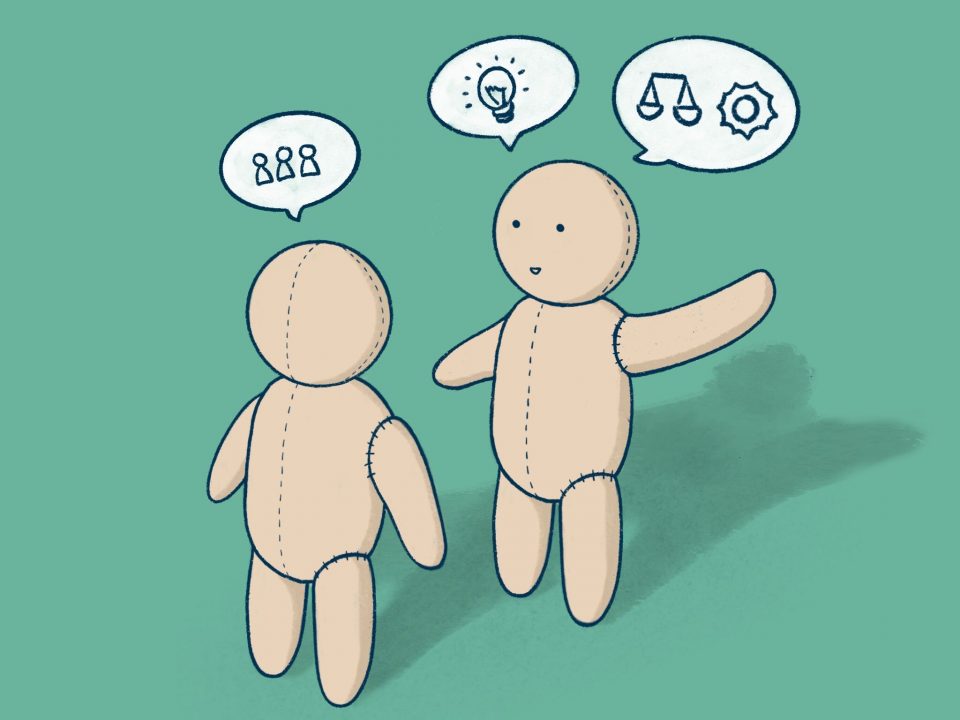Vasektomi, Otonomi Tubuh Laki-laki, dan Pemberontakan Maskulinitas
November 1, 2024
Memerangi Maskulinitas Beracun, Tanggung Jawab Siapa?
November 20, 2024
Photo by Patrick Tomasso on Unsplash
OPINI
Sistem Demokrasi yang tidak Demokratis: Pelajaran dari Politik Duopoli Amerika Serikat
oleh Fikri Haikal Panggabean
Sama seperti Indonesia, 2024 menjadi tahun politik bagi penduduk Amerika Serikat (AS). Pemilihan Presiden (Pilpres) di AS menjadi topik menarik bagi seluruh dunia karena besarnya pengaruh AS pada tatanan internasional dan penjenamaan dirinya sebagai pembela demokrasi.
Namun, kondisi sebenarnya tidak selalu sejalan dengan citra yang digaungkan selama ini. Seperti apa itu?
Dua Partai Satu Wajah
Secara garis besar, politik domestik AS dikenal dengan sebutan ‘two party system’ karena didominasi oleh dua partai utama, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Sistem ini sudah lama mendapatkan kritik dari para konstituen karena dinilai tidak membawa perubahan yang berarti, melainkan hanya mengandalkan fear-mongering atau manipulasi emosi kepada pendukungnya. Fear-mongering itu misalnya adalah ancaman Partai Demokrat terkait terenggutnya hak-hak kelompok minoritas apabila Partai Republik terpilih. Tak hanya itu, kedua partai juga tidak memiliki perbedaan signifikan, selain Partai Demokrat dikenal lebih progresif mendukung kelompok minoritas, termasuk gender dan orientasi seksual, dibandingkan Partai Republik.
Sekalipun dikenal progresif, dalam kenyataannya, Partai Demokrat ternyata tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan brutalitas polisi terhadap kelompok minoritas, terutama kelompok kulit hitam Amerika. Demokrat juga gagal melindungi hak aborsi setelah pembatalan Roe V. Wade, yaitu keputusan tingkat nasional terkait hak aborsi. Demokrat beralasan bahwa mereka bukan mayoritas di pemerintahan. Padahal, kesempatan untuk mengkodifikasi Roe V. Wade sudah berlangsung bertahun-tahun, termasuk ketika Demokrat menjadi mayoritas pada masa administrasi Presiden Obama.
Lebih jauh lagi, baik Demokrat maupun Republik, keduanya gagal memperjuangkan isu-isu penting di AS, seperti kebijakan Medicare atau jaminan kesehatan bagi seluruh warga AS, pembatalan pinjaman pendidikan, dan permasalahan hak masyarakat pribumi AS, serta reparasi atas perbudakan di AS. Sikap yang sama juga terlihat dalam kebijakan terkait imigran dan pencari suaka, termasuk terkait permasalahan penahanan anak-anak pencari suaka yang dipisahkan dari orang tua mereka di perbatasan AS-Meksiko.
Kedua partai juga tidak memiliki kebijakan yang pro-kelas pekerja. Keduanya tidak membahas isu soal upah layak, fenomena pembredelan serikat pekerja, penyediaan perumahan terjangkau, dan strategi untuk mengatasi biaya hidup yang semakin meningkat. Dari segi pengalokasian anggaran, kedua partai mengalokasikan anggaran terbesar mereka untuk sektor militer. Anggaran yang dialokasikan kepada kepolisian selalu meningkat, terlepas dari brutalitas yang dilakukan polisi terhadap kelompok minoritas yang semakin marak. Seluruh kesamaan itu semakin terlihat dalam debat presiden terbaru, ketika kedua kandidat dan partai saling ‘berlomba’ terkait kebijakan menentang imigrasi dan pengiriman senjata ke Israel.
Sistem politik Amerika mengizinkan pendanaan dari kelompok kepentingan atau lobi. Pendanaan ini memungkinkan agenda kelompok tersebut terwakilkan dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan. Lobi-lobi itu diantaranya berasal dari perusahaan atau kelompok pemilik modal seperti Elon Musk (melalui Tesla), George Soros, dan lainnya. Lobi-lobi ini memungkinkan para kandidat mengambil pro-perusahaan termasuk kebijakan yang anti-buruh dan pro-bailout perusahaan seperti pada krisis finansial 2008.
Keputusan ini kemudian diprotes oleh rakyat AS yang menilai bantuan tersebut seharusnya dialokasikan untuk sektor publik, terutama rakyat miskin. Jajak pendapat yang dilakukan Pew Research Institute pada 2010 menemukan setidaknya 68% masyarakat AS yang tidak menyetujui skema pembiayaan kampanye kandidat oleh kelompok lobi kepentingan.
Dari segi kebijakan luar negeri, kedua partai juga tidak jauh berbeda. Keduanya mendukung dibangunnya ratusan pangkalan militer AS di seluruh dunia dan mendorong bantuan finansial tanpa syarat kepada Israel yang sudah berlangsung sejak masa administrasi Presiden Clinton hingga Biden yang sampai saat ini mencapai 3,8 miliar Dolar Amerika setiap tahunnya. Kebijakan itu semakin dipertanyakan oleh beberapa konstituen, terutama di tengah genosida (pembunuhan manusia besar-besaran) yang terjadi di Palestina dan prioritas mengenai kondisi domestik ekonomi AS yang memburuk.
Memperjuangkan Opsi Alternatif
Kejengahan terhadap sistem duopoli politik itu mendorong hadirnya pilihan politik alternatif atau biasa disebut sebagai ‘partai ketiga’. Salah satu partai ‘ketiga’ yang belakangan ini cukup menyita perhatian adalah Partai Hijau Amerika.
Partai Hijau membawa angin segar sebagai satu-satunya partai yang menaruh perhatian pada isu yang selama ini diabaikan oleh kedua partai utama, yaitu isu lingkungan, jaminan kesehatan, pembatalan pinjaman belajar (student loan), pemotongan anggaran militer, reparasi terhadap keturunan budak kulit hitam, serta dukungan terhadap Palestina dan embargo pengiriman senjata ke Israel. Partai Hijau mengusung Jill Stein, seorang dokter dan aktivis, dan Rudolph BIlal Ware, seorang aktivis sekaligus akademisi sejarah Afrika dan Islam. Selain itu, terdapat berbagai kandidat ‘ketiga’ lainnya yang berlaga dalam kontestasi politik AS 2024, seperti Cornel West, seorang akademisi yang maju sebagai kandidat independen.
Sayangnya, kandidat-kandidat ‘ketiga’ itu menghadapi tantangan pelik—salah satunya adalah nama mereka tidak selalu muncul di kertas pemilihan suara. Mereka dikenai berbagai syarat yang rumit jika ingin namanya muncul di kertas pemilihan. Syarat-syarat itu misalnya mengharuskan mereka untuk mengumpulkan dukungan dalam jumlah tertentu, menyetorkan dokumen pendukung, dan membayar biaya administrasi yang tidak murah. Tidak berhenti sampai di situ, mereka kemudian juga harus melalui proses pengesahan yang panjang hingga namanya berhasil muncul di kertas suara. Aturan-aturan semacam itu dinilai tidak berpihak pada kandidat politik alternatif.
Baik di Indonesia maupun AS, keduanya sebenarnya memperlihatkan bahwa politik merupakan kendaraan para pemodal untuk memuluskan akumulasi kekayaan mereka melalui lobi proses pengambilan kebijakan. ~ Fikri Haikal Panggabean Share on XDalam beberapa kasus, kedua partai utama bahkan ikut menuntut agar nama kandidat ‘partai ketiga’ dihapuskan dari kertas suara. Hal itu seperti yang terlihat dalam kasus Partai Demokrat yang menuntut agar Negara Bagian Montana menghapus nama Jill Stein dari kertas suara sebagai kandidat presiden. Situasi itu menambah daftar pelik tantangan yang harus dihadapi oleh partai ‘ketiga’, mengakibatkan suara mereka tetapi kecil, baik dalam pemilihan lokal dan nasional maupun pemilihan presiden. Dampak lebih lanjutnya, tidak ada pendanaan yang bisa diguyurkan negara kepada partai ‘ketiga’, mengingat pendanaan hanya bisa diberikan kepada partai dengan jumlah suara minimal 5 persen di tingkat nasional.
Refleksi Terhadap Kondisi Indonesia
Kita bisa merefleksikan sistem duopoli politik domestik Amerika Serikat dengan kondisi di Indonesia, negara yang juga menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Di Indonesia, terdapat kejengahan terhadap partai-partai terpilih yang dianggap tidak memiliki haluan dan arah kebijakan yang jelas. Partai-partai di Indonesia juga terkesan tidak menggunakan prosedur kaderisasi yang jelas. Akibatnya, proses pencalonan kandidat politik seringkali tidak berdasarkan pada meritokrasi (prestasi kinerja), melainkan nepotisme.
Sama seperti kegagalan kodifikasi Roe V. Wade, sebagaimana yang disinggung di muka, perumusan kebijakan yang mewakili aspirasi rakyat di Indonesia juga berlangsung berlarut-larut. Misalnya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) dan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sampai sekarang tidak pernah dijadikan prioritas utama. Perwakilan partai-partai di pemerintahan justru meloloskan undang-undang yang memungkinkan tenaga kerja dan alam Indonesia dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan. Meskipun sedikit berbeda dengan sistem lobi AS yang memiliki transparansi jelas, baik di Indonesia maupun AS, keduanya sebenarnya memperlihatkan bahwa politik merupakan kendaraan para pemodal untuk memuluskan akumulasi kekayaan mereka melalui lobi proses pengambilan kebijakan.
Sama seperti sistem duopoli di AS, sistem multi-partai di Indonesia juga tidak menggambarkan keberagaman pilihan (opsi) bagi konstituennya. Refleksi ini bahkan sangat berhubungan dengan kondisi terkini di Indonesia, yaitu terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah. Keputusan ini menjadi angin segar bagi rakyat, karena semakin beragamnya alternatif calon kandidat pemimpin yang mereka bisa pilih, tidak melulu berasal dari partai besar.
Tentu, masih banyak kritik yang perlu diartikulasikan terkait sistem politik Indonesia, termasuk ketiadaan haluan ideologi atau kebijakan yang jelas dan keberadaan partai yang kerap dijadikan alat bagi kelompok pemodal untuk memasuki pemerintahan. Sama seperti upaya partai ‘penguasa’ di AS yang sering menghadang pilihan alternatif, Keputusan MK juga hampir dijegal oleh perwakilan partai-partai penguasa melalui pembelotan yang melanggar nilai konstitusi Indonesia.
Agaknya, ancaman akan selalu ada bagi kita yang mengupayakan agar suara kita benar-benar terwakilkan, dimana pun kita berada. Namun, ancaman itu juga menunjukkan bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan. Tentu kita akan terus berharap agar aspirasi politik kita semakin terwakilkan ke depannya.

Fikri Haikal Panggabean akrab dipanggil Gabé. Gabé merupakan seorang pekerja swasta dengan latar belakang Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia. Gabé memiliki ketertarikan pada isu sosial-politik, kajian kebijakan publik, pendidikan dan pop culture. Gabeé memiliki project sampingan mengulas dan menerjemahkan literatur di instagram @belajarprogresif. Gabé dapat dihubungi melalui akun media sosialnya di Instagram @fikrihaikalik.
Artikel Terkait
Membangun Dinasti di Negara Demokrasi: Geliat Politik Keluarga di Indonesia
Politik dinasti jadi penyakit demokrasi. Bagaimana demokrasi Indonesia bergulat dengan politik dinasti?Mengapa Kita Tak Bisa Jadi Pemilih yang Rasional
Meskipun dalam teori politik dan demokrasi seorang warga negara sering digambarkan sebagai manusia rasional, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita sering dikuasai emosi. Memikirkan kembali Pemilu 2019 yang baru saja lewat, di Catatan Pinggir kali ini, Laila Achmad membahas mengenai sulitnya menjadi seorang pemilih rasional.Politik: Seni Berpikir Kritis Bukan Apatis
Ini akan terdengar sebagai suatu pembuka bacaan yang klise, namun kata ‘Politik’ sudah menjadi bagian dari makanan sehari-hari kita sebagai masyarakat Indonesia. Namun, apakah Politik itu menjadi asupan yang kita santap dengan penuh antusiasme?