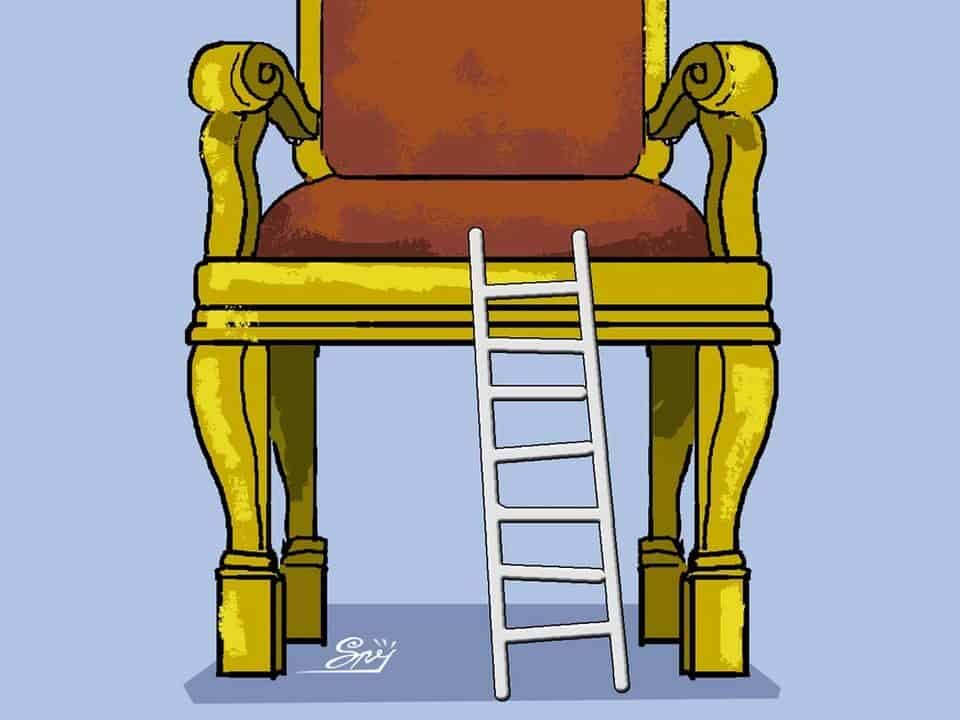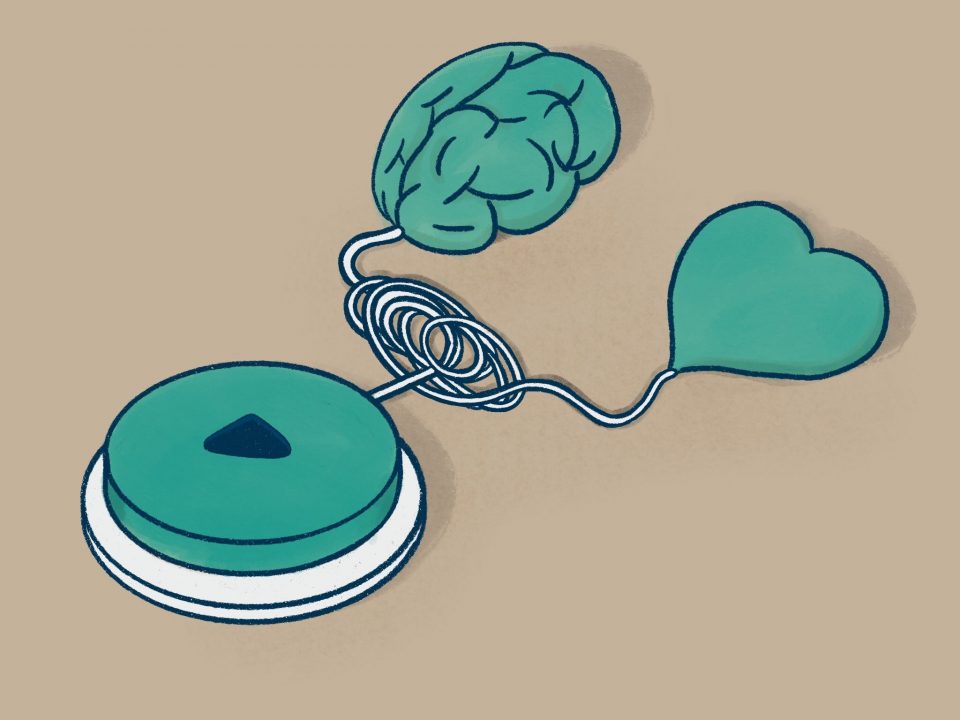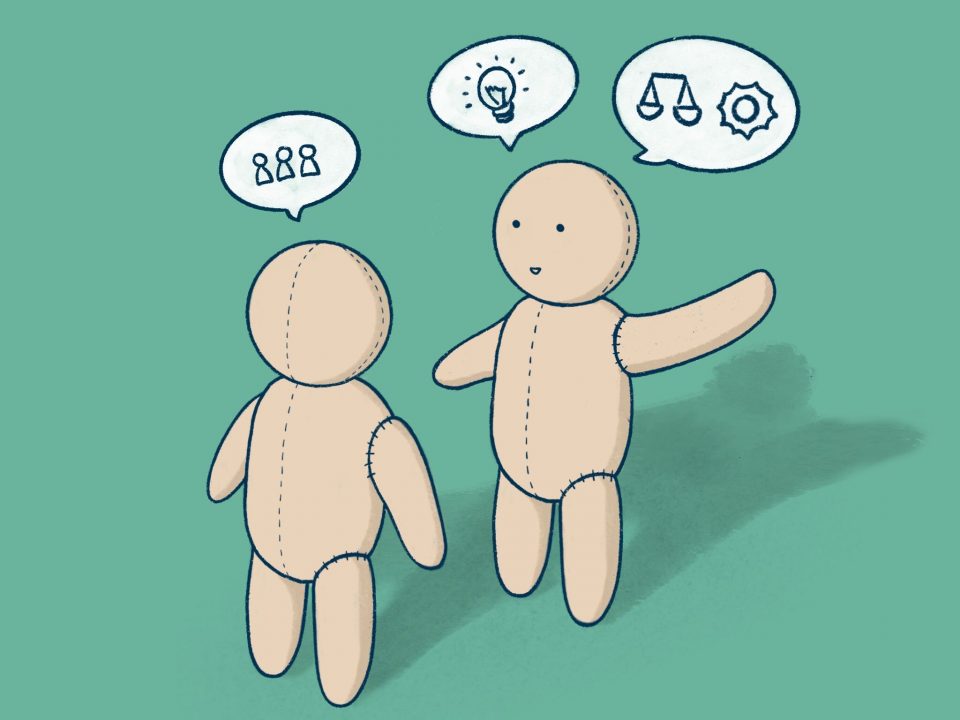Kritik untuk Ulil Abshar Abdalla: Menormalisasi Penindasan Menggunakan Sosok Jokowi
May 27, 2024
Reproduksi dan Resistensi: Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia yang Terdigitalisasi
May 29, 2024
Photo by Brian Wertheim on Unsplash
OPINI
Sistem Politik Indonesia Nilainya D
oleh Frido Yoga
Masa Ujian Akhir Semester (UAS) di kampus saya bertepatan dengan masa kampanye Pemilihan Umum 2024. Saat nilai UAS saya keluar pertama kali, saya hanya melihatnya sekilas dan tak terlalu menggubrisnya. Lagi pula, saya adalah tipikal mahasiswa yang tak terlalu ambil pusing soal nilai—yang terpenting bagi saya adalah lulus mata kuliah.
Pada 28 Februari 2024, masuk pesan singkat dari kampus, mengingatkan saya untuk melakukan registrasi pada semester selanjutnya. Lagi-lagi, saya tidak menghiraukannya. Pada 4 Maret 2024, pesan dengan nada yang lebih menekan kembali masuk ‘memaksa’ saya untuk segera melakukan registrasi dan pembayaran. Saya pun terusik. Saya kemudian melihat mata kuliah yang ditawarkan pada semester depan dan, mau tidak mau, kembali membuka nilai semester sebelumnya. Saya perhatikan nilai mata kuliah satu per satu. Mata saya tertuju pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Nilai saya pada mata kuliah tersebut adalah D (amat buruk).
Nilai D yang saya peroleh pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia membuat saya merenung, merefleksikan diri, sekaligus kebingungan. Ada apa dengan sistem politik Indonesia?
Riwayat Orde Baru
Membicarakan sistem politik Indonesia kontemporer tidak bisa dilepaskan dari tumbangnya rezim militer Orde Baru (1966-1998) dan masuknya Indonesia ke era demokratisasi.
Setelah rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto terjungkal, sistem politik Indonesia dibangun kembali karena tuntutan demokratisasi. Runtuhnya Soeharto melalui gerakan reformasi 1998 tak lantas melahirkan kepemimpinan rakyat dan organisasi kerakyatan yang kuat. Hal itu tidak lepas dari konteks historis di masa Soeharto berkuasa yang dengan sengaja melakukan genosida (pembunuhan massal) kepada orang-orang dari organisasi progresif ‘kiri’ yang kerap diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kegagalan melahirkan kepemimpinan rakyat yang kuat juga disebabkan oleh penerapan sistem politik otoriter yang represif selama 32 tahun lamanya.
Reformasi tak membawa sistem politik Indonesia ke arah demokrasi sejati yang ramah terhadap berbagai spektrum politik. Karakteristik itu menyumbat kebebasan ekspresi politik yang demokratis yang ditandai dengan keterlibatan aktif setiap elemen masyarakat untuk berpartisipasi menentukan jalannya republik. Dengan kata lain, Reformasi tak sejalan dengan semangat diruntuhkannya rezim Orde Baru. Presiden Republik Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), misalnya, pernah melakukan aksi heroik dengan mencoba mendongkel unsur kekuatan Orde Baru yang bersemayam dalam TAP MPRS XXV/1966 terkait larangan PKI. Sayangnya, upaya itu gagal dan ia pun tumbang setelah dimakzulkan dari kursi presiden pada 23 Juli 2001.
Turunnya Soeharto dari kursi presiden tak koheren dengan struktur jaringan dan pendukungnya. Para pendukung Orde Baru masih saja eksis. Mereka bahkan mengkonsolidasikan kekuatan dengan membangun partai politik sebagai institusi demokrasi dan alat untuk merebut tampuk kekuasaan. Akibatnya, aktor-aktor pelaku kejahatan semasa Orde Baru yang seharusnya diadili tetap saja menghirup udara segar.
Dari Demokrasi ke Otoriter Birokratik
Di awal era reformasi, tepatnya pada Pemilu 2009, terjadi anomali politik ketika Megawati Soekarnoputri maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Saya menyebutnya anomali karena sosok yang pernah terlibat dalam kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat justru maju untuk berkuasa bersama. Lebih anehnya lagi, keduanya kembali berseberangan dan berkonfrontasi dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 dengan catatan Megawati diwakili oleh Joko ‘Jokowi’ Widodo dan Ganjar Pranowo..
Baru-baru ini, dalam Pemilihan Presiden 2024, konstelasi politik tidak jauh berubah di mana partai politik dan aktor-aktor yang terlibat masih sama saja. Bedanya, ada aktor lain yang turut ‘memeriahkan’ hingar bingar dinamika politik Indonesia. Adik ipar Jokowi, Anwar Usman, yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi menggunakan wewenangnya untuk meloloskan sang keponakan, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto. Hal itu ia lakukan dengan mengeluarkan putusan terkait batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden.
Akrobat politik Anwar Usman, tentunya dengan dukungan dari Jokowi, merupakan ironi demokrasi yang seharusnya tak terjadi dalam sejarah Indonesia. Bagaimana mungkin lembaga negara semacam Mahkamah Konstitusi dijadikan alat sabotase demokrasi? Bagaimana bisa lembaga penyeimbang kekuasaan justru menjadi kroni politik dan seolah menghina pemikir trias politica terkait pentingnya pembagian kekuasaan melalui mekanisme check and balance (pemeriksa dan penyeimbang)?
Lebih ironisnya lagi, Jokowi secara terang-terangan juga mempertontonkan keterlibatan dan dukungannya pada sang putra—indikasi terjadinya praktik nepotisme dalam Pemilu 2024. Pemilu yang seharusnya dilaksanakan secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) pun diciderai.
Melihat segala situasi politik yang serba menjemukkan kini, sistem politik Indonesia layak untuk diberi nilai D. ~ Frido Yoga Share on XStrategi taktik pemenangan Prabowo-Gibran yang didukung oleh Jokowi melemahkan kewibawaan pemerintahan. Itu juga menciptakan kesadaran semu (pseudo consciousness) partisipasi politik masyarakat untuk memilih pemimpin secara bebas melalui mekanisme pemilu. Lebih jauh lagi, dukungan Jokowi semakin membawa sistem politik kita pada jurang pragmatisme politik laten yang menjadi preseden buruk bagi politik elektoral ke depan, terlepas dari siapa pun yang kelak berkuasa.
Mengingat kembali pemikiran David Easton, ilmuwan politik asal Amerika Serikat, tentang unsur-unsur sistem politik secara umum, rezim politik di Indonesia hanya memproses input yang datang dari dukungan kroni semata dan menanggalkan demokrasi substansial serta agenda pro-rakyat. Fenomena ini dapat kita lihat pada diabaikannya, bahkan cenderung direspon dengan represi dan kriminalisasi, berbagai tuntutan rakyat dalam menanggapi isu krusial yang sedang terjadi.
Dari Ideologis ke Kartel
Situasi politik saat ini tidak bisa dilepaskan dari deideologisasi partai politik pasca-1965 yang membuat partai politik tak lagi memiliki ideologi yang tegas, melainkan pragmatisme politik semata. Koalisi politik yang terbentuk di sistem politik Indonesia kontemporer bukan lagi didasari oleh ideologi partai, akan tetapi kepentingan elit partai dan keuntungan yang mungkin mereka dapatkan. Maka, tak heran kalau kita menyaksikan ada banyak aktor politik yang semula menjadi lawan sengit, kemudian bersatu dalam satu kabinet setelah pemilu berakhir. Fenomena itu saya sebut sebagai koalisi-oposisi palsu yang ditandai dengan banyaknya “politisi kutu loncat.” Partai politik pun tumbuh bak perusahaan agensi pengelola negara tanpa ideologi yang jelas.
Lebih jauh lagi, menjadi nyata bahwa spektrum dan keberagaman partai politik dalam sistem politik Indonesia kontemporer tereduksi dalam satu koalisi politik besar. Politisi berlomba-lomba meminta jatah kekuasaan dan sebisa mungkin bersatu dengan penguasa untuk mengontrol penuh sumber daya negara serta menciptakan berbagai produk hukum yang sesuai dengan kepentingan politik mereka. Tujuan akhirnya sudah jelas: memastikan sumber daya ekonomi-politik dapat terakumulasi dan terdistribusi di kalangan mereka saja. Artinya, sistem multi-partai yang kuat sebagai penyeimbang kekuasaan dan penjaga gawang demokrasi kini tinggal riwayat.
Terkait hubungan antara partai politik dengan rakyat, partai politik kini juga semakin elitis dan menjauh dari kepentingan rakyat. Hal itu cukup masuk akal, sebab partai politik nir-ideologis tersebut memang didirikan oleh segelintir elit, bukan atas kehendak rakyat banyak. Tidak heran kalau partai politik menjadi sekadar alat untuk melayani kepentingan elit dalam rangka menguasai sumber daya negara. Sementara rakyat hanya dibutuhkan sebagai pendukung ketika masa pemilu datang alias tanpa partisipasi yang berarti. Karakteristik partai politik tanpa ideologi semacam itu disebut dengan istilah partai politik kartel. Partai kartel memang tidak membutuhkan ideologi, sebab yang mereka perlukan hanyalah peluang untuk memperoleh keuntungan politik dengan menjadi kroni penguasa dan bergabung ke dalam koalisi besar serta menghilangkan fungsi oposisi dan check and balance pada pemerintah.
Leo Agustino, akademisi asal Indonesia, dalam bukunya Sistem Kepartaian dan Pemilu menjelaskan bahwa dalam sistem partai kartel, semua partai politik besar melakukan kongkalikong guna memperoleh banyak keuntungan dalam berbagai bentuk, seperti jabatan, proyek pemerintah, dan patronase lainnya. Menurut logika ini, partai-partai politik di legislatif sebenarnya tidak terlalu peduli dengan kebijakan dan agenda presiden: yang terpenting bagi mereka adalah mendapat keuntungan politik dan ekonomi bagi keberlangsungan partai mereka.
Perenungan panjang saya soal mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang memperoleh nilai D membuat saya berpikir bahwa bukan saya yang kesulitan memahami dinamika politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Mungkin, melihat segala situasi politik yang serba menjemukkan kini, justru sistem politik Indonesia lah yang layak untuk diberi nilai D.

Frido Yoga sedang menempuh kuliah Ilmu Pemerintahan di Surabaya dan tertarik dengan isu sosial-politik.
Artikel Terkait
Membangun Dinasti di Negara Demokrasi: Geliat Politik Keluarga di Indonesia
Politik dinasti jadi penyakit demokrasi. Bagaimana demokrasi Indonesia bergulat dengan politik dinasti?Mengapa Kita Tak Bisa Jadi Pemilih yang Rasional
Meskipun dalam teori politik dan demokrasi seorang warga negara sering digambarkan sebagai manusia rasional, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita sering dikuasai emosi. Memikirkan kembali Pemilu 2019 yang baru saja lewat, di Catatan Pinggir kali ini, Laila Achmad membahas mengenai sulitnya menjadi seorang pemilih rasional.Politik: Seni Berpikir Kritis Bukan Apatis
Ini akan terdengar sebagai suatu pembuka bacaan yang klise, namun kata ‘Politik’ sudah menjadi bagian dari makanan sehari-hari kita sebagai masyarakat Indonesia. Namun, apakah Politik itu menjadi asupan yang kita santap dengan penuh antusiasme?