
Pembubaran FPI dan Masa Depan Demokrasi Kita
January 8, 2021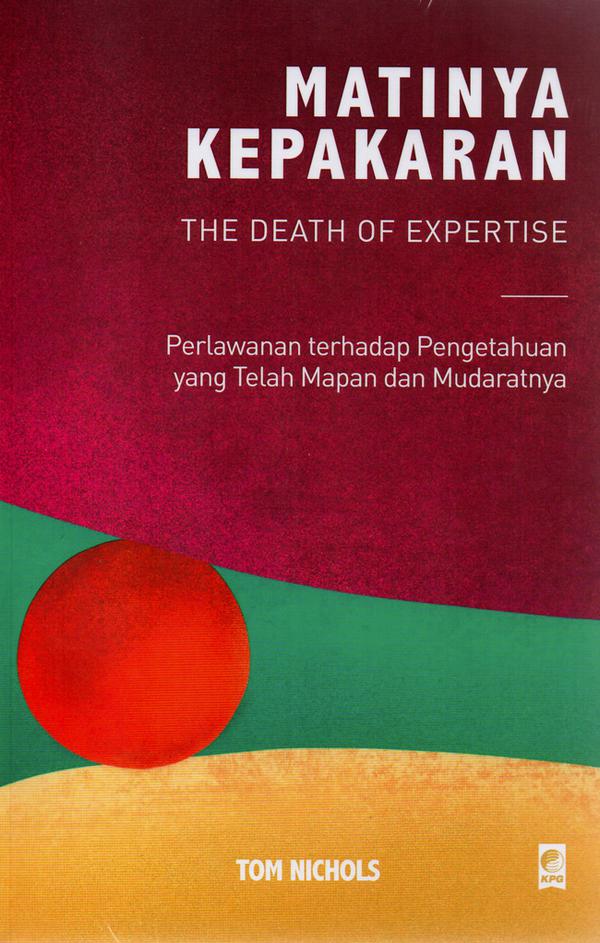
Mencegah Matinya Kepakaran dengan Membuka Pikiran
February 11, 2021
OPINI
Vaksinasi dan Tubuh yang Didisiplinkan
oleh Abdullah Faqih
Indonesia kewalahan melawan wabah korona adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sampai 14 Januari 2021, kasus terkonfirmasi positif virus korona di Indonesia sudah mencapai angka 858.043 dengan tingkat kematian sebanyak 24.951 jiwa.
Berkat angka itu, Indonesia menjadi negara dengan tingkat penyebaran dan kematian akibat virus korona tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Pencapaian ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menerapkan kebijakan penanganan wabah korona, terutama dalam melaksanakan kebijakan 3T (testing, tracing, dan treatment).
Di tengah situasi yang mengundang pesimisme semacam ini, vaksinasi digagas sebagai senjata terakhir yang bisa kita harapkan. Perbincangan soal vaksinasi pun ramai mewarnai ruang publik kita. Berdasarkan pengamatan saya, diskursus yang paling banyak beredar soal vaksinasi didominasi oleh pandangan-pandangan yang cenderung bersifat ‘membangun’ (konstruktivis), yaitu soal aspek efektivitas dan ekuitas (keadilan). Pandangan itu ditujukan untuk mendukung terbentuknya 70% tingkat kekebalan kolektif (herd immunity) dalam waktu sesingkat mungkin.
Sudut pandang tersebut memang tidak keliru. Tanpa vaksinasi, kita tidak tahu lagi bagaimana harus berperang menghadapi wabah korona. Namun, meski penting perannya dalam membantu melawan wabah, saya rasa penting juga untuk membaca vaksinasi dari sudut sosial. Mengadopsi pandangan para pemikir kritis, terutama Michel Foucault, Jonathan Moreno, dan Emily Martin, saya melihat bahwa vaksinasi ternyata tidak hanya bisa dipandang sebagai fenomena kedokteran dan biologi modern biasa. Vaksinasi juga terkait erat dengan aspek sosial, budaya, politik, dan agama.
Karena itu, artikel ini menawarkan pandangan yang lebih bersifat dekonstruktif, yaitu melihat vaksinasi bukan hanya menjadi senjata untuk menghadapi wabah korona, melainkan juga menjadi instrumen kekuasaan dan praktik pendisiplinan tubuh oleh negara.
Vaksinasi bukan hanya produk yang berada dalam lingkup ilmu kedokteran dan biologi modern saja, melainkan telah pindah ke area di mana dua lingkup itu bertemu dengan lingkup sosial, budaya, politik, bahkan agama. ~ Abdullah Faqih Share on XInterseksi Vaksin
Dalam The Body Politics: The Battle Over Science in America, Jonathan Moreno menghadirkan perdebatan soal vaksinasi. Perdebatan tersebut melibatkan dua kubu, yaitu kubu pendukung vaksin yang cenderung mempercayai kebenaran ilmiah dan kubu anti-vaksin yang cenderung menolak otoritas ilmu pengetahuan.
Perdebatan semacam itu juga terjadi di Indonesia, bahkan wacananya ikut dipengaruhi pula oleh institusi keagamaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat fatwa-fatwanya ikut mempengaruhi penerimaan masyarakat atas vaksinasi. Hal itu pernah dibahas oleh Ratih Ayu Atika (dkk) dalam studinya mengenai pengaruh fatwa MUI terhadap penerimaan ibu untuk melakukan imunisasi difteri kepada bayinya.
Penerimaan dan penolakan atas fatwa MUI, termasuk fatwa soal vaksinasi korona, juga bukan tiba-tiba muncul tanpa sebab. Hal itu dipengaruhi pula oleh lanskap politik (demokratisasi), kekakuan dalam membaca kitab suci, Islamisasi ilmu pengetahuan, dan penyebaran teknologi media baru. Berbagai pandangan yang muncul kemudian membuat umat Islam di Indonesia menjadi lebih berdaya dalam mendefinisikan praktik kesalehan mereka, termasuk soal keputusannya untuk menerima atau menolak vaksin serta untuk menuruti atau menantang otoritas keagamaan.
Sejalan dengan pandangan Moreno, penjelasan di atas menunjukkan bahwa vaksinasi bukan hanya produk yang berada dalam lingkup ilmu kedokteran dan biologi modern saja, melainkan telah pindah ke area di mana dua lingkup itu bertemu dengan lingkup sosial, budaya, politik, bahkan agama.
Jika diterapkan, komersialisasi vaksin berpotensi akan menimbulkan segregasi kelas sosial atas tubuh. ~ Abdullah Faqih Share on XVaksin dan Politik Imunitas
Pembicaraan sekitar vaksinasi Covid-19 di Indonesia juga diwarnai oleh diskusi seputar keadilan. Wacana itu mucul setelah pemerintah membuka vaksinasi jalur mandiri yang dinilai oleh masyarakat sipil akan mengacaukan pengaturan mengenai prioritas penerima vaksin. Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan vaksinasi gratis untuk 32 juta penduduk miskin, sementara 74 juta penduduk lainnya diharuskan melakukan vaksinasi mandiri (berbayar). Kebijakan vaksinasi yang didasarkan pada kemampuan finansial warga negara, bukan berdasarkan pertimbangan epidemiologi, menunjukkan bahwa vaksinasi merupakan fenomena politik yang sarat akan permainan kekuasaan: dilancarkan berkat adanya kerjasama antara negara, perusahaan farmasi dan otoritas ilmu pengetahuan.
Jika diterapkan, komersialisasi vaksin berpotensi akan menimbulkan segregasi (pemisahan) kelas sosial atas tubuh. Tubuh warga negara akan dibedakan menjadi tubuh yang berasal dari kelas menengah (mampu membayar vaksin secara mandiri) dan tubuh dari kelompok miskin (memperoleh vaksin subsidi dari pemerintah).
Konsekuensi dari segregasi tersebut berbuntut panjang. Dalam buku Flexible Bodies, Emily Martin mengajukan konsep politik imunitas. Menurut Martin, imunitas tubuh yang terbentuk lewat vaksinasi bukan hanya fakta biologi yang lepas dari variabel budaya dan politik, karena juga berpotensi melahirkan stigmatisasi (pemberian asumsi negatif) dan eksklusi (penolakan). Misalnya, tubuh yang dianggap kuat dan memiliki imunitas dianggap superior karena si pemilik tubuh mampu melakukan vaksinasi. Sebaliknya, tubuh yang lemah dan memiliki imun yang buruk akan dianggap bersalah karena tidak mampu melakukan vaksinasi.
Stigmatisasi semacam itu berpotensi muncul, sebab tidak ada yang mampu menjamin 74 juta penduduk peserta vaksinasi mandiri akan benar-benar melakukan vaksinasi, begitu pula dengan 32 juta penduduk miskin lainnya. Bagaimanapun, divaksinasi atau tidaknya orang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi (kemampuan finansial), budaya, bahkan juga agama dan politik. Menambahkan satu lagi rintangan dengan meminta mereka untuk melakukan vaksinasi mandiri tentu tidak akan membantu.
Tidak hanya terjadi pada mereka yang melakukan atau tidak melakukan vaksinasi, stigmatisasi semacam itu juga dapat terjadi pada tubuh yang mengonsumsi vaksin berbeda. Misalnya, Singapura memberikan warganya vaksin gratis berjenis Pfizer yang efikasinya mencapai 95 persen. Sementara itu, Indonesia menggunakan vaksin Sinovac yang efikasinya hanya sebesar 65,3 persen. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan stigmatisasi atas tubuh orang Indonesia yang imunitasnya dinilai tidak sebaik imunitas tubuh orang Singapura.
Vaksin dan Disiplin Tubuh
Saya juga berpendapat bahwa nalar negara dalam program vaksinasi korona hampir bisa dibaca dengan membandingkannya dengan program Keluarga Berencana (KB) yang pernah dilancarkan oleh rezim militer Orde Baru. Lewat program KB, aspek-aspek biologi menyangkut tubuh perempuan, kelahiran, dan kualitas populasi didisiplinkan negara melalui berbagai kebijakan politik. Dalam program vaksinasi korona—terlepas dari baik-buruk dan perlu-tidaknya vaksin—tubuh warga negara juga didisiplinkan dalam rangka meraih imunitas kolektif. Menurut konsep biopolitik yang digagas filsuf dari Perancis Michel Foucault, praktik pendisiplinan tubuh semacam itu biasanya memiliki tujuan untuk mendukung rasionalisasi negara terkait tercapainya akumulasi ekonomi.
Investigasi Tempo berjudul “Paket Kilat Vaksin Impor” membahas terburu-burunya agenda vaksinasi korona di Indonesia—bahkan ketika negara-negara lain sedang sibuk melakukan uji efikasi. Keterburu-buruan ini diduga disebabkan oleh adanya kepentingan ekonomi yang melibatkan negara dengan para pengusaha dari Tiongkok. Selain itu, Sulfikar Amir, akademisi dari Nanyang Technological University Singapore, juga mengatakan bahwa komersialisasi vaksinasi korona terjadi berkat adanya kerjasama antara para pengusaha dan politisi yang dengan sengaja mengesampingkan peran para pakar kesehatan.
Dalam artikel “Kuasa Bahasa di Balik Kebijakan Penanganan Covid-19”, saya juga pernah mendiskusikan rasionalisasi negara dalam membentuk berbagai kebijakan penanganan wabah korona. Sejak pandemi ini muncul, kebijakan-kebijakan yang digagas negara memang ditujukan untuk mengamankan kepentingan ekonomi, bukan untuk menyelamatkan nyawa warga negara. Kebijakan vaksinasi yang terburu-buru juga mengisyaratkan bahwa negara ingin wabah korona segera menemui titik akhir agar aktivitas ekonomi dapat lekas pulih. Padahal, kebijakan vaksinasi saja tidak cukup, apabila tidak dibarengi dengan upaya pelacakan dan pencegahan yang adekuat.
Agar efektif, pemerintah perlu mendampingi kebijakan vaksinasi dengan sejumlah peraturan yang bersifat politis dan koersif. Contohnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Dalam kebijakan tersebut, warga negara yang menolak vaksinasi akan dikenai denda sebesar Rp5.000.000. Kebijakan itu tentu berpotensi mengebiri otoritas warga negara atas tubuhnya sendiri. Warga negara ‘dipaksa’ mengonsumsi vaksin tanpa diberikan ruang untuk melakukan pertimbangan berdasarkan rasionalitas mereka masing-masing.
Upaya merampas otoritas tubuh warga negara juga tercermin dalam sikap koersif Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan, “Vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan atau meragukan keamanan vaksin.”
Sebagai perbandingan, Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru, mendekati topik otoritas tubuh dalam agenda vaksinasi secara lebih persuasif lewat pernyataannya bahwa vaksin akan diberikan secara gratis untuk semua orang di Selandia Baru dan negara-negara kepulauan Pasifik yang berkenan untuk divaksinasi.
Dengan demikian, selain menjadi instrumen untuk mengendalikan wabah korona, kebijakan vaksinasi di Indonesia juga menjadikan tubuh warga negara sebagai ‘ruang kerja medis’ yang dapat diakses kapan saja oleh negara. Lewat kebijakan vaksinasi pula, tubuh warga negara didisiplinkan dan dijadikan alat untuk mencapai tujuan negara terkait imunitas kolektif, kualitas populasi, akumulasi ekonomi, serta kepentingan politik.
Posisi
Sebagaimana wacana lain dalam ilmu sosial, wacana mengenai vaksinasi juga diwarnai oleh berbagai sudut pandang. Dalam artikel ini, saya berusaha mengetengahkan fenomena vaksinasi sebagai sesuatu yang bukan hanya merupakan produk yang berada di area ilmu kedokteran dan biologi modern biasa, melainkan telah bertemu pula dengan aspek sosial, budaya, agama dan politik. Bagi saya, memunculkan diskursus tersebut penting sebagai penyeimbang di ruang pembicaraan soal vaksinasi yang saat ini didominasi oleh pandangan-pandangan yang cenderung bersifat konstruktivis (membangun). Perlu digarisbawahi pula bahwa posisi artikel ini bukan hendak menolak agenda vaksinasi, melainkan sebagai upaya untuk mengangkat sisi dari diskusi seputar vaksinasi yang mungkin luput kita perhatikan.

Abdullah Faqih sedang bersekolah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini







