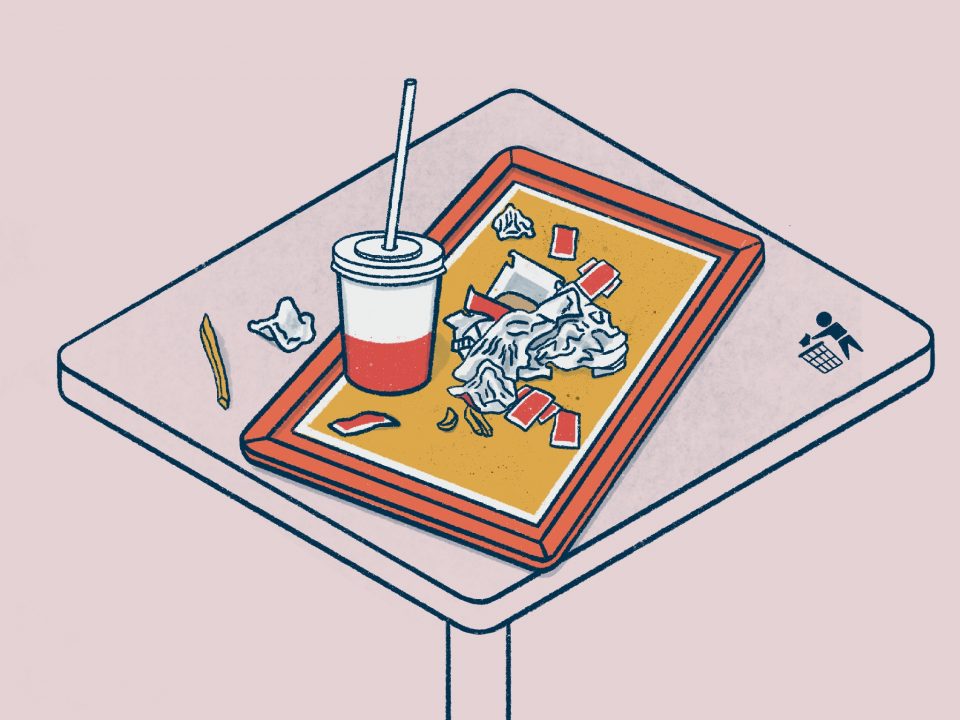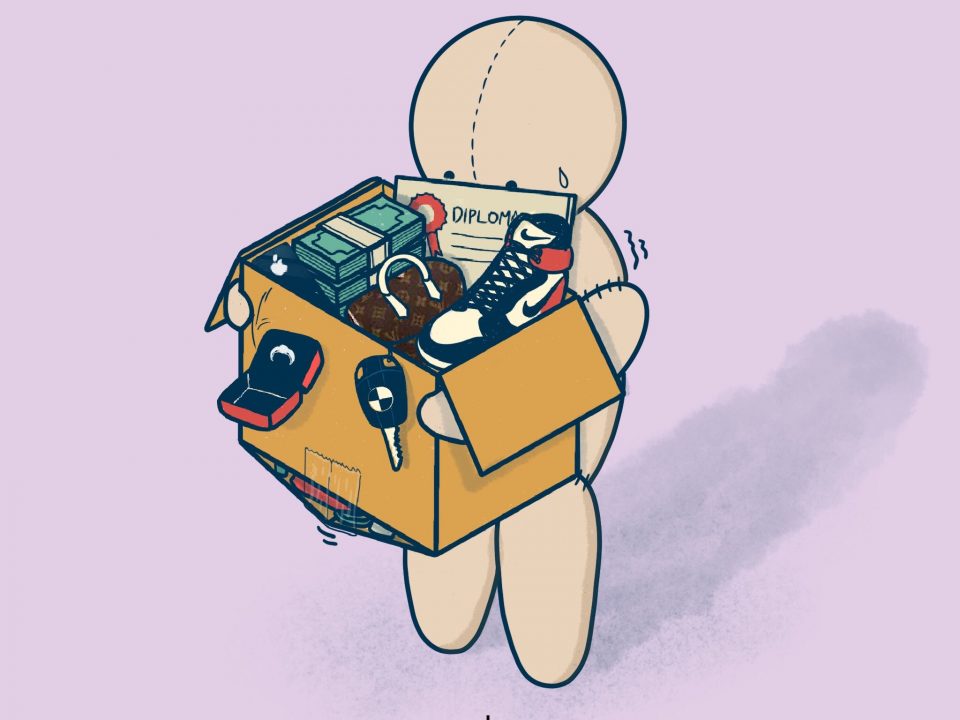Jomblo: Sebuah Interpretasi Kemanusiaan
August 27, 2019
Dari Dangdut hingga Frankfurt
October 17, 2019Makna
Budaya dan Konstruksi Sosial: Bagaimana Kita Memahami Dunia
oleh Rifda Amalia
Pernahkah kamu bertanya, bagaimana kita bisa menilai suatu hal, perilaku, atau fenomena sosial tertentu sebagai baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas? Misalnya, mengapa dekorasi kamar dan pakaian bayi laki-laki sering diasosiasikan dengan warna biru, dan bayi perempuan diasosiasikan dengan warna merah muda? Mengapa laki-laki tidak boleh memakai rok, dan mengapa perempuan ingin memiliki tubuh langsing dan kulit putih? Atau, sedikit lebih abstrak, dari mana kita mendapatkan pengetahuan dan membentuk opini akan sesuatu? Siapa yang menentukannya?
Jawabannya ada di teori konstruksi sosial (social constructionism). Teori ini dapat membantu kita untuk secara kritis medalami dan mempertanyakan bagaimana manusia memproduksi pengetahuan, mendistribusikannya hingga meresapinya sebagai sebuah “kebenaran” yang alami.
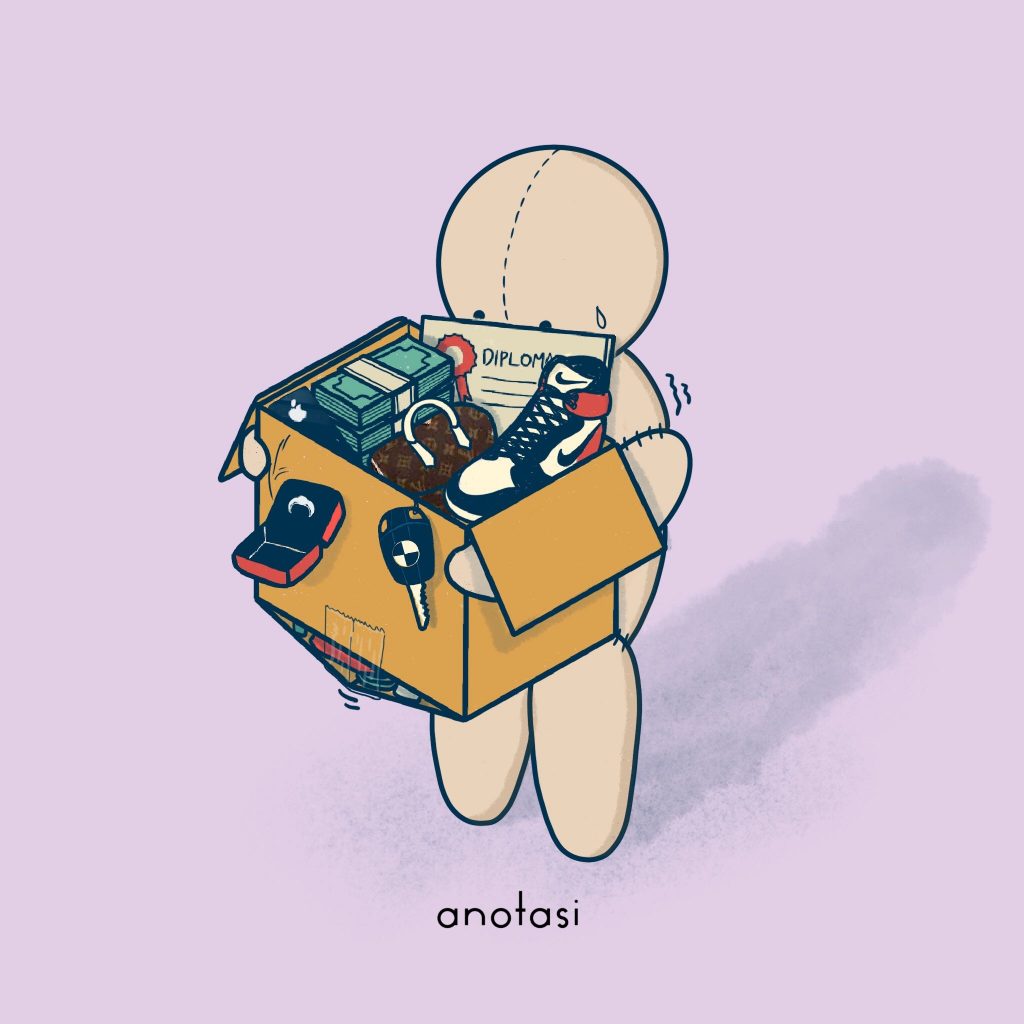
Konstruksi sosial dengan mudah dapat diartikan sebagai sebuah pemahaman kolektif mengenai sebuah konsep yang terbentuk dalam tatanan masyarakat. Banyak hal-hal yang kita anggap lumrah dan masuk akal hari ini sebenarnya dibentuk, dikonstruksi, dan disepakati dalam ranah sosial pada masa tertentu, misalnya konsep uang, kewarganegaraan, atau seni. Fokus utama teori konstruksi sosial adalah mengupas dan mengkaji cara-cara individu dan kelompok masyarakat tertentu berpartisipasi dalam menciptakan pengetahuan dan kenyataan sosial di sekitar mereka. Teori konstruksi sosial memercayai bahwa manusia memaknai dunia di sekitarnya melalui sebuah proses sosial, melalui interaksinya dengan orang lain dalam kelompok sosial. Ini berarti tidak ada suatu kebenaran yang bisa dianggap tunggal dan objektif.
Perkembangan teori konstruksi sosial tidak bisa ditarik hanya dari satu garis lurus sejarah pemikiran tertentu. Namun, untuk mudahnya, kita bisa saja menarik perkembangannya hingga sejauh masa pencerahan (Enlightenment Era) di pertengahan abad ke-18. Semangat masa pencerahan di Eropa adalah pencarian kebenaran, mencari cara memahami realita melalui pemikiran rasional di mana sebelumnya apa yang dianggap ‘benar’ selalu diatur oleh institusi agama Kristiani. Immanuel Kant, seorang filsuf abad pencerahan asal Jerman, pernah menuliskan pada tahun 1784 bahwa manusia tidak akan sepenuhnya bebas dari ketidakdewasaan jika belum berani menggunakan pemikirannya sendiri dalam memaknai dunia disekitarnya, tanpa bantuan dari pihak lain selain dirinya sendiri.
Cara kita memahami sesuatu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, kultural dan politik di tempat kita hidup, beserta relasi kuasa dibaliknya. Ini merupakan salah satu fokus yang dibahas dalam teori konstruksi sosial. ~ Rifda Amalia Share on XDalam empat puluh tahun belakangan ini sudah banyak tulisan yang membahas pemikiran-pemikiran mengenai teori konstruksi sosial. Namun kontribusi paling signifikan terhadap pemahaman mengenai teori konstruksi sosial datang dari buku The Social Construction of Reality oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann tahun 1966. Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann berakar salah satunya dari teori ‘interaksi simbolik’ yang dimulai oleh George Herbert Mead di sekitar akhir tahun 1920an. Pemikiran dasar dari teori ‘interaksionisme simbolik’ adalah manusia membentuk identitas dirinya dan orang lain melalui pertemuan sehari-hari dengan orang lain dalam interaksi sosial, yang kemudian juga menghasilkan simbol bersama yang lalu disetujui, diatur, dan definisikan ulang bersama orang di sekitarnya. Eksplorasi mengenai aspek sosiologis dari pengetahuan atau Sociology of Knowledge juga sudah mulai dibahas oleh beberapa filsuf dan sosiolog di Eropa dan Amerika Utara seperti Èmile Durkheim dan Marcel Mauss pada awal abad ke-20. Semangatnya adalah mencari tahu bagaimana pengetahuan, bahasa, dan logika dipengaruhi oleh kondisi sosial dimana mereka tercipta.
Berger dan Luckmann percaya bahwa manusialah yang bersama-sama membuat dan mempertahankan seluruh fenomena sosial melalui praktik-praktik sosial mereka. Berger dan Luckmann menyatakan bahwa ada tiga tahap yang memungkinkan terbentuknya konstruksi sosial, yaitu proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Proses eksternalisasi terjadi ketika sebuah pemikiran diwujudkan ke dunia oleh seseorang melalui bahasa, baik berupa tulisan, cerita, puisi, atau bentuk karya seni lain. Kemudian proses objektifikasi terjadi ketika hal-hal tersebut masuk ke dalam dunia sosial, lalu menjadi bagian dari kesadaran orang lain, dan perlahan-lahan mulai dianggap sebagai kebenaran. Terakhir, proses internalisasi terjadi ketika generasi berikutnya lahir ke dunia ketika pemahaman ini sudah ada, sehingga mereka kemudian menerimanya sebagai bagian dari cara mereka melihat dan memahami dunia sekitarnya. Proses ini terjadi melalui ajaran-ajaran orang tua, pendidikan, ataupun konsumsi kebudayaan popular.
Bahasa memiliki peran sentral dalam proses produksi pengetahuan dan bagaimana kita mengerti dunia di sekitar kita. Dari sudut pandang ini, bahasa bukan terbentuk untuk mendeskripsikan dan merepresentasikan dunia saja, namun justru sebagai cara untuk mengkonstruksi dunia sebagai sebuah aksi sosial. Pemahaman ini dapat dilihat dari proses seorang anak yang baru belajar bicara dalam memahami konsep suatu kata dan mengasosiasikannya dengan benda tertentu. Seorang ibu mengenalkan mobil kepada anak batitanya dengan menunjuk kepada sebuah mobil lalu berkata: “Mobil.” Di waktu lain, sang anak melihat sebuah gerobak atau benda beroda lain dan menyebutnya, “Mobil.” Tentunya sang ibu akan mengoreksi anaknya. Kemudian sang ibu akan kembali menunjukkan berulang kali kepada sang anak bahwa bunyi “mobil” yang mereka ucapkan terasosiasi dengan fitur-fitur yang hanya dimiliki mobil dan membedakannya dengan fitur-fitur sepeda atau gerobak, sehingga sang anak akhirnya menginternalisasi konsep “mobil” ke dalam dirinya.
Melalui contoh ini, teori konstruksi sosial memungkinkan kita untuk berpikir bahwa bahkan hal sehari-hari yang kita anggap akal sehat dan dunia sosial yang objektif juga merupakan hasil konstruksi yang dihasilkan oleh aksi dan interaksi manusia dengan manusia lainnya. Cara kita memahami dunia merupakan sebuah kesepakatan yang diobjektifikasi melalui bahasa atau simbol, kemudian diinternalisasi ke dalam diri individu. Sama halnya dengan banyak benda dan konsep lain di dunia, seperti konsep mengenai uang, peran gender hingga orientasi seksual.
Lokasi, waktu dan situasi dimana sebuah pengetahuan terbentuk juga harus dikaji dengan kritis jika kita ingin melihat suatu fenomena dari kacamata teori konstruksi sosial. Sosiolog Vivien Burr menekankan pentingnya kesadaran bahwa cara kita mengerti dunia, kategori-kategori dan konsep-konsep yang kita gunakan, merupakan hal yang spesifik dengan sejarah dan kebudayaan di tempat tertentu. Untuk mengerti maksud Burr lebih baik, perlu untuk membahas apa sebenarnya makna kebudayaan.
Jika kita melihat pengertian kebudayaan menurut Bapak Antropologi Indonesia, Koentjaraningrat, kebudayaan adalah “keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Kata belajar di akhir kalimat perlu di garis bawahi karena berhubungan dengan pemikiran teori konstruksi sosial bahwa pengetahuan dan pemahaman kita mengenai dunia ini didapatkan dari hasil belajar, kegiatan ‘ajar-mengajar’ ini terjadi antara satu individu dengan orang lain disekitarnya di waktu dan tempat yang spesifik.
Misalnya, usia minimal yang dianggap ‘pantas’ untuk menikah telah berubah dari puluhan tahun yang lalu dengan sekarang. Baru beberapa tahun belakangan ini saja diterima bahwa usia tiga puluh tahun merupakan usia lazim bagi perempuan untuk menikah dan pernikahan anak di usia remaja dianggap sesuatu yang buruk karena dapat menghambat kesempatan anak perempuan untuk mengenyam pendidikan wajib 12 tahun. Menimbang apa yang dikatakan Burr, konsep mengenai usia nikah ini juga merupakan sebuah konstruksi sosial yang bergantung pada latar belakang sosial dan spasialnya (e.g. kota dan desa), berarti semua pemahaman dan pengetahuan itu sifatnya relatif bergantung pada sejarah dan kebudayaan kelompok masyarakat yang mengonstruksinya.
Jika kita menarik aplikasi sudut pandang teori konstruksi sosial untuk memahami bagaimana kita memahami suatu ideologi kita akan melihat bahwa keyakinan kita terhadap suatu ideologi, misalnya, tidak semerta-merta muncul dari dalam diri kita sendiri. Dengan lebih kritis kita dapat melihat bahwa cara kita memahami sesuatu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, kultural dan politik di tempat kita hidup, beserta relasi kuasa dibaliknya. Ini merupakan salah satu fokus yang dibahas dalam teori konstruksi sosial.
Seperti yang sudah disebutkan, bahasa memegang peran sentral untuk proses penyampaian pengetahuan. Karya seni juga merupakan salah satu bentuk bahasa yang digunakan manusia untuk menyampaikan pengalaman, perasaan dan ideologi. Karena itu lah sejak lama karya seni selalu digunakan sebagai alat yang efektif sebagai penanaman ideologi. Seni dapat memasuki ranah pengalaman terdalam seorang individu, sehingga penanaman ideologi atau proses internalisasi subjektif akan lebih mudah dilakukan tanpa harus menggunakan kekerasan. Salah satu contohnya adalah pembentukan LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) pada tahun 1950, sebuah lembaga kesenian yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Mengusung sudut pandang Marxisme, LEKRA bertujuan untuk “memperlihatkan ketidakadilan yang ada di masyarakat dan mempromosikan proses perubahan revolusioner” sejalan dengan tendensi pemikiran dari pemegang kuasa saat itu, Presiden Soekarno.
Teori konstruksi sosial memungkinkan kita untuk berpikir bahwa bahkan hal sehari-hari yang kita anggap akal sehat dan dunia sosial yang objektif juga merupakan hasil konstruksi. ~ Rifda Amalia Share on XSementara itu, penanaman ideologi anti-komunisme pada masa order baru melalui pemegang tampuk kuasa juga hadir melalui berbagai bentuk seni. Banyak budayawan dan peneliti yang telah membahas soal ini, salah satunya Wijaya Herlambang melalui bukunya Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film mengupas bagaimana karya sastra dan film berperan dalam menanamkan ideologi anti-komunis dan normalisasi kekerasan yang dilakukan pemerintahan order baru terhadap anggota dan simpatisan PKI. Dalam bukunya, Herlambang membahas beberapa cerita pendek yang diterbitkan oleh majalah Horison pasca terjadinya perburuan besar-besaran terhadap simpatisan PKI. Dia juga mengupas relasi kuasa yang berada di baliknya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana relasi kuasa yang terjadi mempengaruhi konstruksi sebuah paham atau ideologi yang dianggap benar oleh kelompok tertentu.
Teori konstruksi sosial memungkinkan manusia menyadari bahwa mereka yang membentuk pemahaman mengenai dunia. Namun, disaat yang bersamaan mereka juga memahami hal-hal diluar dirinya yang sudah ada seakan-akan itu hal yang alami. Museum merupakan contoh yang baik untuk membicarakan teori konstruksi sosial. Dalam museum, praktik eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi terjadi. Kita dapat melihat bagaimana manusia mengeksternalisasi pengetahuan melalui artifak-artifak hasil kebudayaan atau karya seni. Kemudian benda-benda tersebut di objektifikasi ketika dipamerkan di museum. objek-objeknya dipilih dan disusun sedemikian rupa untuk menyampaikan suatu sejarah, peradaban, atau narasi tertentu oleh seorang kurator. Namun, walau manusia menyadari sepenuhnya bahwa museum adalah buatan manusia lainnya, manusia tetap menerima informasi yang diterima dari museum sebagai fakta atau kebenaran yang sahih dan alami, karena narasi tersebut mungkin telah hadir sebelum dirinya lahir. Kekuatan legitimasi yang dimiliki museum, serupa dengan kekuatan yang dimiliki oleh bentuk budaya lainnya sangat penting untuk membangun pengertian manusia akan dunia.
Di tengah derasnya arus informasi yang dimungkinkan oleh sosial media, serta maraknya perbincangan mengenai dunia pasca-kebenaran atau post-truth, sikap kritis dalam memahami bagaimana pengetahuan terbentuk menjadi sangat penting. Karena itu, teori konstruksi sosial dapat memberikan kita sudut pandang alternatif untuk dapat melihat suatu fenomena yang dianggap benar oleh mayoritas dengan kacamata kritis. Cara pandang ini memungkinkan kita untuk mengerti sudut pandang orang lain yang ras, etnis, agama, orientasi seksual maupun sikap politiknya berbeda dengan kita. Teori ini mementingkan keberagaman sudut pandang yang membentuk dunia untuk menemukan cara mendamaikan keberagaman pemahaman dan realitas. Bukan untuk mencari yang mana yang paling benar, namun untuk mencari cara hidup bersama di masa depan.
Bacaan lebih lanjut
| Berger, Peter and Thomas Luckmann. (1966). The Social Construction of Reality. Garden City, New York: Anchor Books. Blumer, Herbert (1969). Symbolic interactionism: perspective and method. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall Burr V. (2003). Social constructionism (2nd Ed.). New York, NY: Routledge. Elder-Vass, D. (2012). The Reality of Social Construction. Cambridge, University Press Galbin, Alexandra. (2014). An Introduction to Social Constructionism. Social Research Reports, vol. 26, pp. 82-92 Foucault, Michel. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Edited by Colin Gordon. Great Britain: The Harvester Press. Gergen K. J. (1994). Realities and relationships. Cambridge, MA: Harvard University Herlambang, Wijaya. (2019). Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film (3rd ed). Serpong: Marjin Kiri |

Rifda Amalia adalah seorang kurator dan ahli museum lulusan Fakultas Seni Rupa di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Museum Studies Graduate Program di New York University. Dia pernah berkontribusi dalam berbagai proyek seni di Indonesia, contohnya sebagai sekretaris untuk 7th Asian Art Museum Directors’ Forum dan asisten kurator di Galeri Nasional Indonesia untuk Manifesto #4 dan Indonesia Art Award. Rifda juga terlibat sebagai anggota tim artistik untuk Art Jakarta 2019. Setelah bertugas sebagai asisten dosen di Departemen Estetika dan Ilmu-ilmu Seni di ITB (2014-2015), Rifda bekerja sebagai program officer di departemen seni British Council Indonesia, dimana dia mengembangkan proyek-proyek seni rupa, film, dan sastra dari 2015 hingga 2016. Saat ini, Rifda bekerja sebagai programming and community partnerships manager di ke:kini ruang bersama, pusat komunitas yang bertujuan untuk mendukung inisiatif sosial, seni, dan budaya di Jakarta. Rifda aktif meneliti pengaruh karya seni dan aktivisme di ruang publik untuk mendorong transformasi sosial.