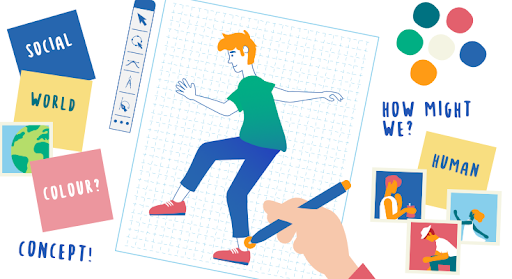
Merangkai Bahasa Visual untuk Ilmu Sosial
September 4, 2020
Perkembangan Sistem Perekonomian Modern: Kapitalis, Komunis, Sosialis, dan Campuran
September 16, 2020
KATALIS
Pembangunan tanpa Gerakan Perlawanan
oleh Abdullah Faqih
Tahun 2019 yang lalu, saya melakukan penelitian lapangan di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini mengkaji hegemoni dan kekuasaan (power) dalam proyek pembangunan mega-industri Global Hub.
Global Hub adalah proyek pembangunan prioritas nasional berbentuk kawasan kota baru yang akan dibangun di atas lahan seluas 7000 hektar. Nantinya, proyek tersebut akan diintegrasikan dalam satu lokasi dengan proyek pembangunan lainnya, seperti pelabuhan dagang internasional, tambang kilang minyak, kawasan bisnis, dan kawasan industri.
Ketika saya mulai melakukan studi lapangan, pembangunan proyek tersebut baru memasuki tahap ground-breaking, sehingga dampak-dampak dan perkembangannya belum begitu terlihat. Meskipun nampak adem-ayem, wilayah yang akan dibangun itu sebenarnya sedang menempuh perjalanan menuju suatu perubahan besar-besaran. Kurang lebih 20 tahun dari sekarang, jika didasarkan pada cetak biru (blueprint) yang dirancang oleh pengembang, wilayah itu akan berubah menjadi kawasan kota modern yang didominasi oleh gedung pencakar langit, jalanan beraspal, hingga moda transportasi modern, seperti kereta gantung, LRT (Light Rail Transit) dan MRT (Mass Rapid Transit). Itu artinya, segala hal yang masih bisa saya lihat pada waktu itu—sawah, kebun, hutan, rumah adat—semuanya akan musnah. Saking prestisiusnya, para aktor pembangunan bahkan menyebut proyek itu sebagai “Singapura Besar” di Indonesia.
Sebagai mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik, pikiran saya langsung tertuju pada hal-hal yang berbau penindasan, penggusuran, penghancuran lahan pertanian, hingga pencerabutan ruang hidup masyarakat—sebagaimana yang selama ini telah banyak dilakukan oleh negara-korporasi. Pikiran itu semakin terafirmasi ketika melihat respon Bapak Kepala Desa yang terkesan sangat antusias menyambut agenda besar pembangunan Global Hub. Dia dan sebagian besar masyarakat di sana menaruh optimisme bahwa proyek Global Hub akan mendatangkan kesejahteraan bagi desa mereka: mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, dan masalah infrastruktur yang serba ‘tertinggal’.
“Proyek Global Hub akan menjadi sumber penghidupan baru bagi anak cucu orang-orang Gumantar. Mereka akan sejahtera berkat pembangunan itu”, begitu katanya.
Sependek yang saya tahu, tidak banyak—bahkan tidak ada sama sekali—janji-janji kesejahteraan yang ditawarkan negara-korporasi dalam suatu proyek pembangunan dapat benar-benar terwujud secara ideal, sebagaimana yang dibayangkan oleh masyarakat. Meminjam gagasan Tania Murray Li dalam The Will to Improve, selalu ada jarak antara apa yang ingin dibangun oleh negara-korporasi dengan apa yang benar-benar terjadi di masyarakat. Hal itu disebabkan oleh para aktor pembangunan yang tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan politik. Begitu pula masyarakat yang akan dibangun, mereka tidak hidup di ruang hampa, melainkan memiliki agensi dan pikirannya sendiri dalam memaknai pembangunan dan kesejahteraan. Pada posisi itu, banyak sekali masyarakat lokal, baik yang mengorganisasi kekuatan secara swadaya maupun yang dibantu oleh organisasi masyarakat sipil, melakukan gerakan perlawanan terhadap proyek pembangunan.
Contohnya, perlawanan petani di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah yang menolak operasi industri ekstraktif tambang semen; perlawanan masyarakat di Kulonprogo, Yogyakarta menolak pembangunan bandara internasional; perlawanan masyarakat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur menolak operasi tambang emas; dan masih banyak lagi. Alih-alih mendatangkan kesejahteraan, proyek pembangunan industri justru dinilai lebih banyak menghadirkan konflik agraria, perusakan lingkungan, penggusuran, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan berbagai macam dampak destruktif lainnya.
Saya kemudian mengajukan pertanyaan, “Mengapa masyarakat di Lombok Utara tidak melakukan gerakan perlawanan atas pembangunan proyek Global Hub?” Pertanyaan itu bagi saya penting, mengingat dampak-dampak pembangunan Global Hub diproyeksikan akan sangat destruktif: menghancurkan lahan pertanian produktif, membabat hutan, menggusur rumah adat, menggiring para petani masuk ke dalam industri (tentunya juga menempatkan mereka pada posisi terbawah dalam struktur industri), dan lain sebagainya. Sementara itu, melakukan gerakan perlawanan menjadi penting sebagai respon kritis dan sebagai bentuk negosiasi untuk memperkecil dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari proyek pembangunan. Mengingat proyek pembangunan yang tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi-politik, saya pun mempertanyakan, “Bagaimana negara-korporasi membangun legitimasi atas proyek pembangunan tersebut, sehingga diterima begitu saja oleh masyarakat?”
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya menggunakan konsep hegemoni Laclau dan Mouffe sebagai pisau analisis. Laclau dan Mouffe mendefinisikan hegemoni sebagai totalitas terstruktur yang dihasilkan melalui berbagai praktik artikulasi. Bahasa sederhananya, hegemoni dapat dipandang sebagai suatu penanaman pengaruh atau gagasan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi satu makna yang dianggap normal. Sesuatu dapat menjadi hegemoni ketika gagasan atau pengaruh yang ditanamkan (biasanya dilakukan oleh kelompok berkuasa) berubah menjadi imaji atau angan-angan yang diterima secara luas serta tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk menggugat atau mempertanyakan gagasan itu.
Dalam kasus ini, negara-korporasi menetapkan satu makna tunggal mengenai wacana kesejahteraan di balik pembangunan industri Global Hub. Mula-mula, negara-korporasi menjadikan isu tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Lombok Utara, masalah ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian Barat dan Timur, dan masalah terpuruknya sektor maritim di tingkat nasional sebagai titik krisis. Titik kritis tersebut bertemu dengan kondisi bentang alam strategis di Selat Lombok yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia II atau melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, dan Laut Flores. Pesisir Kabupaten Lombok Utara. Lokasi ini dinilai berpotensi menjadi pusat transshipment (atau praktik pergerakan barang antar-kapal) dan ekonomi baru karena letak geografisnya melintang dari utara ke selatan. Lokasi tersebut juga dinilai ideal karena berada tepat di urat nadi pelayaran internasional dan pusat tujuan wisata termasyur di dunia, seperti Kawasan Pariwisata Gili Trawangan dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika.
Potensi geografis itu membuat negara-korporasi merasa memiliki ruang untuk merumuskan sebuah solusi dalam rangka merespon berbagai titik krisis yang ada. Dalam tahap itu, gagasan mengenai pembangunan industri Global Hub dinilai relevan untuk mengurai masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, hingga masalah keterpurukan sektor maritim. Dalam artian, selama titik krisis semacam itu masih ada, legitimasi mengenai pembangunan proyek Global Hub akan terus dianggap memiliki arti penting.
Setelah wacana kesejahteraan di balik pembangunan Global Hub ditetapkan, negara-korporasi bekerja untuk membuat wacana itu menjadi hegemoni agar dapat diterima secara luas. Berbagai argumen yang berserak (oleh Laclau dan Mouffe disebut sebagai penanda mengambang atau floating signifiers), seperti penetapan visi “Indonesia Poros Maritim Dunia” dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 dimana Global Hub ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional menjadi justifikasi yang memperkuat legitimasi perlunya dibangun proyek Global Hub. Selain itu, proyek Global Hub juga dibangun tanpa kucuran dana dari kas negara, melainkan dibiayai penuh oleh investor asing. Investor dari Belanda, Rusia, Korea Selatan, dan China berencana akan menyuntikan investasi sekitar 500 Triliun Rupiah dalam proyek tersebut.
Selain investor asing, aktor-aktor penting yang juga terlibat dalam proyek pembangunan mega-industri Global Hub adalah PT Diamar Mitra Kayangan sebagai pelaksana proyek, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Aktor-aktor tersebut berada pada satu titian jalur perjuangan untuk mengukuhkan wacana kesejahteraan di balik pembangunan mega-industri Global Hub. Hal itu dimanifestasikan ke dalam berbagai peraturan, seperti pemberian saham kepada masyarakat yang menjual tanah untuk kepentingan proyek industri, penyerapan tenaga kerja lokal untuk mengurai masalah pengangguran, hingga melakukan framing media mengenai janji-janji kesejahteraan yang ditawarkan lewat pembangunan mega-industri Global Hub. Lewat berbagai penanda mengambang (floating signifiers) yang terserak dan kemudian dikumpulkan serta disedimentasikan menjadi sebuah makna tunggal itulah, wacana kesejahteraan di balik pembangunan mega-industri menjadi hegemoni yang diterima dan diamini begitu luas oleh berbagai kalangan.
Penelitian yang saya lakukan telah menjelaskan bagaimana aktor-aktor pembangunan mengorganisasi kekuatan untuk membuat suatu gagasan diterima secara luas. Namun demikian, penelitian ini belum cukup mampu menjelaskan mengenai alpa-nya gerakan perlawanan masyarakat lokal atas proyek pembangunan. Padahal, proyek hegemoni yang dibangun negara-korporasi itu memiliki banyak sekali celah. Misalnya, relevansi pemberian saham dengan kehidupan masyarakat petani, posisi para pekerja lokal bila terserap ke dalam industri, keuntungan ekonomi antara ketika masih menjadi petani yang menggarap sawah dengan ketika menjadi buruh industri, dan lain sebagainya. Pada konteks kehidupan petani di Kendeng, Kulonprogo, dan Manggarai, adanya ruang semacam itu membuat mereka mampu mengorganisasi gerakan perlawanan atas proyek pembangunan—terlepas dari berhasil atau tidaknya gerakan tersebut.
Tidak masalah apabila masyarakat memilih mempertukarkan ruang hidupnya untuk kepentingan industri dan kapitalisme, asalkan keputusan itu lahir dari pikiran dan agensi mereka sendiri—tentunya dengan pemahaman menyeluruh” ~A. Faqih Share on XDengan demikian, permasalahan yang saya teliti itu masih membuka ruang untuk dapat digali lebih dalam. Saya juga harus mengakui bahwa ketika memulai penelitian ini, saya fokus dengan desain dan pikiran saya sendiri, yaitu mempertanyakan ketidakhadiran gerakan perlawanan masyarakat atas proyek pembangunan. Saya belum mempertimbangkan agensi dan alam pikir masyarakat sendiri dalam memaknai arti pembangunan dan kesejahteraan—nalar semacam ini yang menurut saya harus dihindari oleh para perencana kebijakan. Pemaknaan masyarakat atas pembangunan dan kesejahteraan itulah yang perlu dilihat lebih lanjut. Kalau mereka memaknai ‘menjadi sejahtera’ sebagai integrasi dengan masyarakat industri, bukan dengan tetap menjadi petani sebagaimana masyarakat di Kendeng dan Kulonprogo, ketidakhadiran gerakan perlawanan itu bisa kita nilai sebagai sesuatu yang ‘wajar’. Begitu pun, tidak menjadi masalah apabila masyarakat memang lebih memilih mempertukarkan ruang hidupnya untuk kepentingan industri dan kapitalisme, asalkan keputusan itu lahir dari pikiran dan agensi mereka sendiri—tentunya juga dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai akibat-akibat yang harus mereka tanggung di kemudian hari.
Tapi, kalau penerimaan itu ternyata adalah bentuk dari ketidaktahuan mereka atau merupakan buah dari bekerjanya nalar kapitalisme yang sedang memperdaya mereka, maka para ilmuwan-aktivis sosial harus mulai menyiapkan amunisi untuk berjuang bersama masyarakat demi melawan kepentingan bisnis-industri-kapitalisme yang sepanjang sejarahnya selalu melempar masyarakat lokal ke dalam jurang penderitaan.
Mumpung proyek Global Hub masih berada di tahap ground-breaking, kita masih punya banyak sekali waktu untuk menimbang baik-buruk rencana pembangunan itu sekaligus untuk meredam berbagai dampak destruktif yang dihadirkannya. Jangan sampai, nasib orang-orang lokal di sana sama seperti tetangganya: masyarakat di sekitar kawasan pembangunan Kuta Mandalika, Lombok Tengah yang tanahnya kini dikuasai oleh broker dari Hongkong.
Referensi
- Ardianto, Hendra Try. (2016). Mitos Tambang untuk Kesejahteraan. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government
- Laclau, E. dan Mouffe, C. (2008). Hegemoni dan Strategi Sosialis Postmarxisme + Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book
- Li, Tania Murray. (2012). The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia. Tangerang: Marjin Kiri
- Smith, Anthony Oliver. (2002). Displacement, Resistance and the Critique of Development: From the grass-roots to the global. Oxford: Refugee Studies Centre of University of Oxford
Abdullah Faqih sedang fokus mengerjakan penelitian dengan topik ‘agensi queer Muslim melawan heternormativitas’ sambil diselingi menonton drama Korea. Memiliki hobi membaca, menulis, dan makan donat. Memiliki harapan besar untuk dapat segara menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada.
Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini







