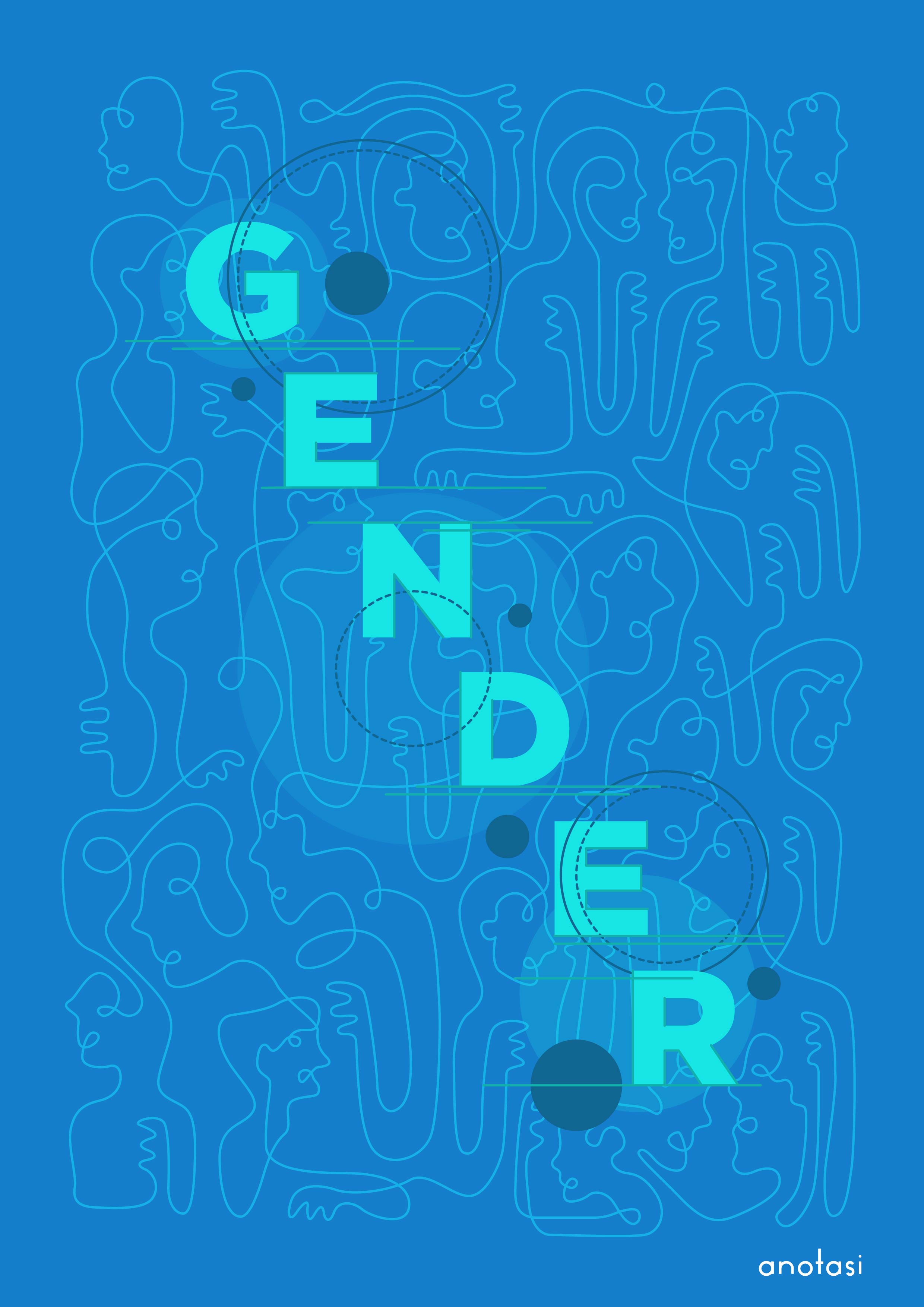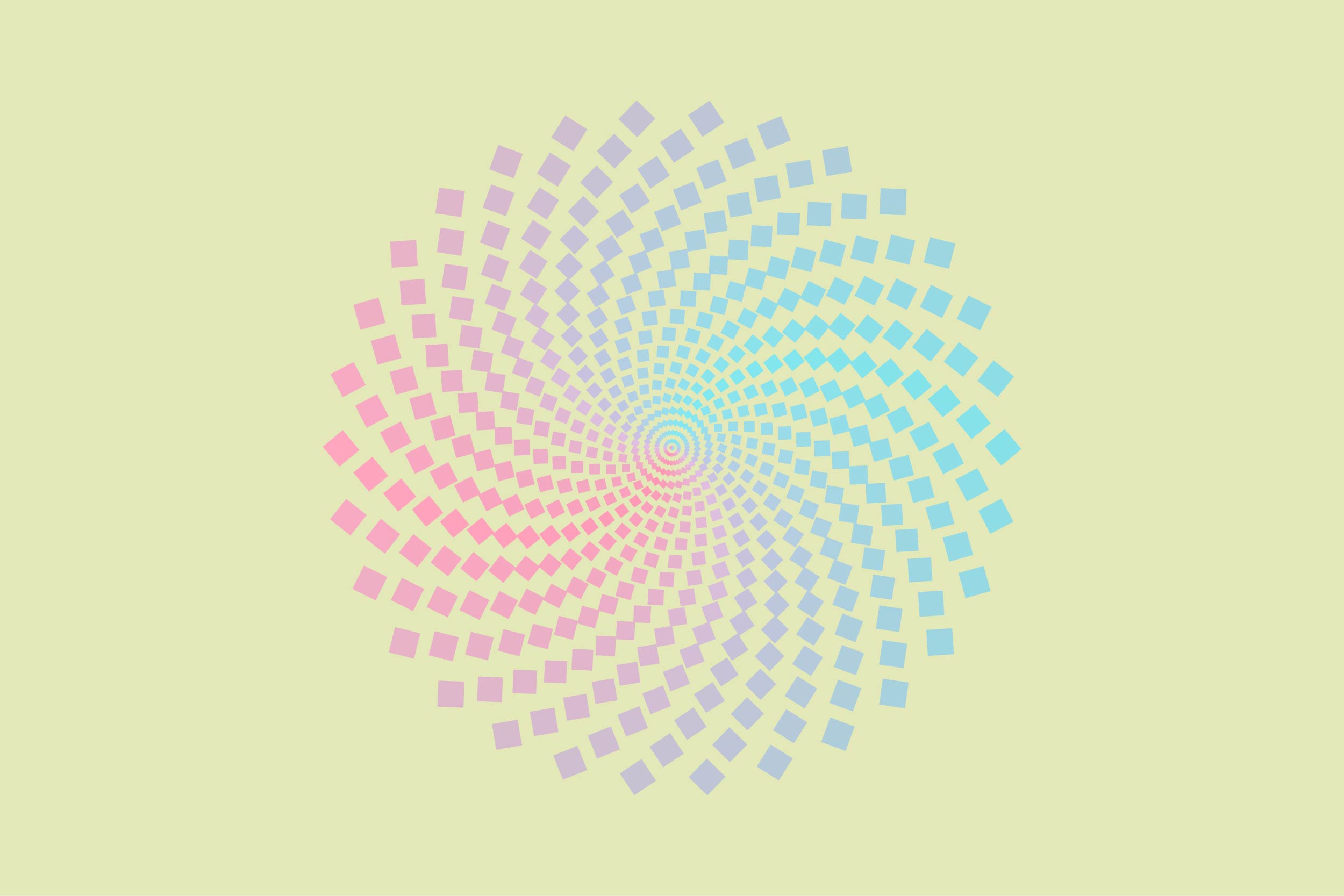
Melerai Kekusutan Gender dan Jenis Kelamin
May 30, 2018
Menjadi Ayah dan Hidup Seperti Seharusnya
September 15, 2018
Catatan Pinggir
“XX” & “XY”
dan Segala Sesuatu yang Mengikutinya
oleh Naomi Jayalaksana
Pengantar Redaksi:
Di artikel ini, Naomi menekankan pentingnya mempertanyakan kembali gagasan-gagasan mengenai gender dan seksualitas yang sering dianggap sudah berterima dan wajar-wajar saja di keseharian kita. Berawal dari pengalamannya ketika SMA, Naomi menyodorkan cara pandang berbeda mengenai apa yang sebenarnya kita maksud dengan maskulin dan feminin dan juga konsekuensi dari anggapan enteng mengenai keajegan aturan masyarakat mengenai bagaimana setiap orang harus bertindak hanya karena label gendernya.
“Permasalahan gender adalah ketika orang terlalu sibuk memberikan saran tentang seperti apa harusnya kita berlaku daripada bagaimana kita bisa mengenal jati diri kita yang sesungguhnya. Bayangkan, betapa kita bisa lebih bahagia, dan betapa lebih bebasnya kita menjadi diri kita yang sesungguhnya, ketika kita tidak dibebani oleh segala ekspektasi gender.”
― Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All Be Feminists
“Kalian pikir saya tidak tahu kalau kalian menertawai saya, mengejek saya banci. Saya seorang suami, saya seorang bapak, saya punya anak-anak,” ungkap guru Biologi saya di muka kelas. Nadanya penuh kemarahan dan kekecewaan. Suaranya parau menahan luapan emosi dan tangis yang tertahan di tenggorokan. Ia lalu membanting bukunya, dan pergi meninggalkan kelas.
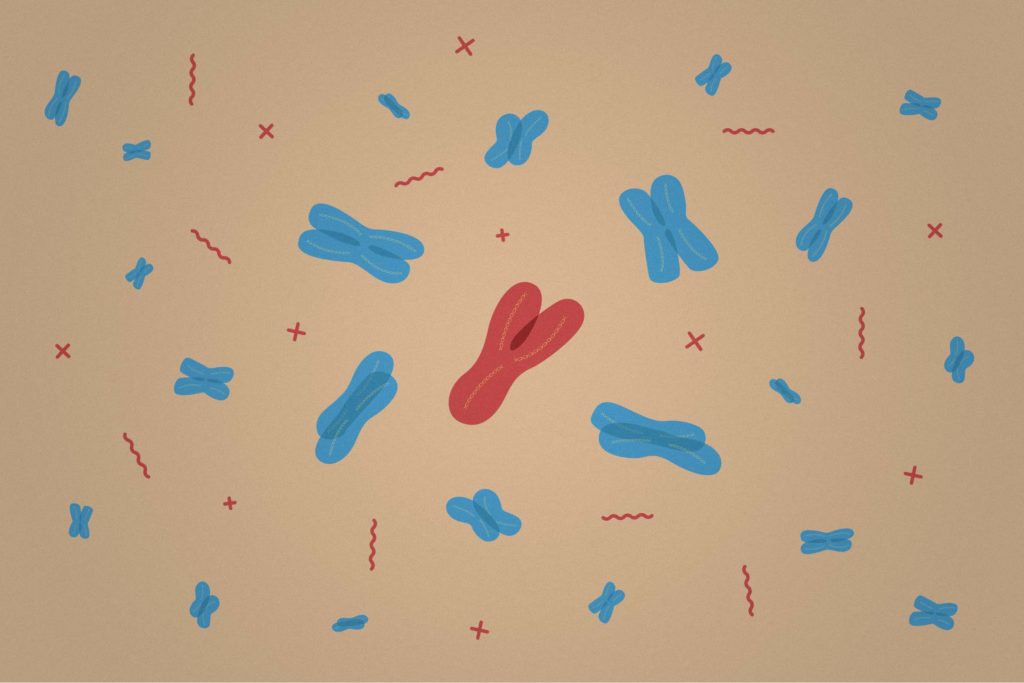
Cara berjalan dan gerak gerik beliau yang feminin, cara bertuturnya yang lembut, semua ini sudah cukup membuat segerombolan anak SMA yang sedang ribut mencari jati diri menjuluki beliau sebagai banci. Bahkan, ketika saya sendiri tidak yakin bahwa mereka benar-benar memahami apa yang sedang ditertawai saat itu.
Di tengah luapan rasa bersalah itu, jelas terngiang suara beliau saat menjelaskan teori genetika. Bagaimana sel telur dan sperma bertemu dan membuahkan sekumpulan sel kompleks yang terbelah hingga menjadi bakal bayi. Sel-sel tersebut terus membelah dengan bekal berpasang-pasang kromosom yang membawa segala informasi genetik di dalamnya.
Setiap manusia – kecuali dalam kasus-kasus penyimpangan genetik – dibekali jumlah kromosom yang sama, 23 pasang. Termasuk di dalamnya sepasang kromosom penentu jenis kelamin – XX untuk jenis kelamin perempuan dan XY untuk jenis kelamin laki-laki. Dalam hal ini Tuhan cukup jelas. Hanya saja, manusia dengan segala ekspektasinya membuat semuanya menjadi lebih rumit.
Bermula dari absennya pendidikan seks di sekolah-sekolah. Bagaimana perbedaan jenis kelamin ini dalam kesehariannya bertautan dengan ekspektasi kultural yang memisahkan perempuan dan laki-laki berdasarkan konteks budaya, sosial, dan nilai-nilai kepatutan lainnya. Orang mengenalnya dengan istilah gender.
Anak laki-laki tidak menangis, dan anak perempuan memakai baju merah muda. Laki-laki berburu, dan perempuan membesarkan anak. Perempuan boleh sukses, tapi jangan sampai kesuksesan itu membuat para lelaki terancam atau terusik harga dirinya. Boleh juga menuntut ilmu tinggi-tinggi, tapi jangan lupa menikah dan punya anak. Laki-laki itu harus agresif, tegas dan tidak lembek, tidak gampang terbawa perasaan. Pendek kata: macho! Laki-laki membuat keputusan, perempuan hanya menerima.
Betapa rumit dan tertekannya hidup dalam konstruksi gender seperti di atas. Celakanya lagi, ketika persepsi gender ini kemudian diteruskan dan dilembagakan dalam norma masyarakat, masuk ke jalur pendidikan, kelas-kelas agama, dan institusi pemerintah serta politik. Mereka yang tidak hidup dalam rel normalitas ini menjadi sebuah anomali yang layak dipertanyakan, digugat, dan dihakimi!
Seperti ketika sekelompok transgender pekerja salon kecantikan beserta pengunjung salon di Kabupaten Aceh Utara digelandang ke kantor polisi. Mereka dikriminalisasi dengan tuduhan penyebab rusaknya moral anak-anak tanpa melalui proses peradilan. Rambut mereka digunduli, diminta berlari keliling lapangan sambil berteriak-teriak hingga “suara laki-laki” mereka keluar (tirto.id, 3 Februari 2018).
Setiap manusia...dibekali jumlah kromosom yang sama...Dalam hal ini Tuhan cukup jelas. Hanya saja, manusia dengan segala ekspektasinya membuat semuanya menjadi lebih rumit. ~ Naomi Jayalaksana Share on XTindakan tidak menyenangkan yang melanggar HAM dan diskriminatif bahkan terjadi juga dalam institusi negara. Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur (Jatim), misalnya, mengatakan bahwa secara proporsional akan membatasi kuota CPNS perempuan di proses rekrutmen 2018. Alasannya, perempuan cenderung berhalangan saat mereka hamil, sehingga mengurangi performa kerja tim (Sumber: Lowongan CPNS 2018, Pemrov Jatim Batasi Kuota Perempuan).
Sementara itu Kejaksaan Agung RI dalam pengumuman rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) menyebutkan prasyarat pelamar “tidak cacat mental, termasuk kelainan orientasi seksual (transgender). Ada banyak kesalahan fatal dalam naskah dan proses rekrutmen dari lembaga negara tersebut. Kesalahan fatal pertama adalah pengkategorian orientasi seksual sebagai gangguan jiwa. Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III/1993 jelas menyebutkan bahwa orientasi seksual bukanlah jenis gangguan jiwa. Sementara Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) yang menjadi panduan penggolongan gangguan jiwa internasional sejak tahun 1987 menegaskan bahwa orientasi seksual tidak masuk dalam kategori gangguan jiwa.
Kesalahan fatal kedua adalah memasukkan transgender sebagai contoh orientasi seksual. Padahal, transgender bukan merupakan orientasi seksual, tapi adalah istilah awam yang diberikan kepada seseorang yang identitas gender, ekspresi gender, atau perilakunya tidak mengacu pada tipikal tertentu yang biasa diasosiasikan dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Seorang transgender pria bisa saja berperilaku dan berdandan cantik ala wanita, tapi tetap berorientasi heteroseksual atau biseksual.
Bagaimana pula kita membenci sesuatu yang tidak kita kenal? Bisa dibilang, akar kebencian ini bersumber asumsi sepihak yang belum tentu teruji kebenarannya dan tumbuh menjadi bentuk kebencian dan paranoia. ~ Naomi Jayalaksana Share on XNamun, di antara semua itu, kesalahan yang paling utama adalah pelanggaran terhadap HAM. Pasal 38 Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuannya. Setiap orang juga berhak atas syarat ketenagakerjaan yang adil.
Meski tidak bisa ditolerir, hal-hal seperti ini bisa dimaklumi. Sebab, pendidikan di Indonesia tidak memasukkan pendidikan gender dan seksualitas dalam kurikulumnya. Sehingga, segala kerancuan dan gagal paham ini saling berkelindan dan berpotensi besar menciptakan generasi yang seksis dan intoleran.
Wahid Foundation dalam surveinya “10 Kelompok Yang Paling Tidak Disukai” di tahun 2017 dan 2018 memberikan hasil yang menggelitik. Tiga urutan teratas di tahun survei 2017 diduduki oleh LGBT (26,1%), Komunis (16,7%), dan Yahudi (10,6%). Sementara tiga teratas di tahun 2016 adalah Komunis (21,9%), LGBT (17,8%) dan Yahudi (7,1%).
Saya sebut menggelitik karena sebenarnya tiga kelompok teratas paling dibenci ini di keseharian tidak hadir dalam bentuk yang nyata. Bagaimana pula kita tahu seseorang adalah LGBT, Komunis, atau Yahudi, jika seseorang itu tidak mengakuinya sendiri atau secara kasat mata seorang lesbian atau gay tepergok melakukan hubungan seksual. Saya rasa orang Yahudi juga tidak hidup dan berkomunitas di lingkungan keseharian kita.
Lalu, bagaimana pula kita membenci sesuatu yang tidak kita kenal? Bisa dibilang, akar kebencian ini bersumber asumsi sepihak yang belum tentu teruji kebenarannya dan tumbuh menjadi bentuk kebencian dan paranoia.
Jawabannya kembali pada pengetahuan dan pendidikan. Sebab, pada dasarnya, orang takut pada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Melalui jalur pendidikan, masalah ketidaktahuan yang menakutkan ini bisa dipecahkan dengan ilmu pengetahuan maupun bagaimana kita menyikapinya dalam koridor kehidupan bersama sebagai warga negara yang berpayungkan hak asasi manusia dan konstitusi.
Permasalahan gender adalah ketika orang terlalu sibuk memberikan saran tentang seperti apa harusnya kita berlaku daripada bagaimana kita bisa mengenal jati diri. ~ Naomi Jayalaksana Share on XSaya sendiri terbilang sangat beruntung. Besar di era tahun 80-an di sebuah kota kecil Mojokerto, Jawa Timur, pendidikan gender dan seksual ini saya dapatkan di kelas 6 SD. Saat itu, Sekolah Dasar Katolik Wijana Sejati tempat saya belajar memberikan pendidikan ini melalui sebuah kegiatan retret. Di usia kelas 6 itu, memang sudah banyak murid perempuan yang mengalami menstruasi, termasuk saya.
Jauh dari unsur pornografi seperti yang ditakutkan pejabat departemen pendidikan nasional dewasa ini, waktu itu, kami mendapat pendidikan tentang sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Bagaimana proses akil balik anak laki-laki dan perempuan. Bagaimana seorang wanita mengandung dan melahirkan bayi. Bagaimana anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam mengejar cita-cita. Bahwa laki-laki dan perempuan adalah rekanan setara.
Semua rangkaian pembelajaran selama dua hari satu malam ini kemudian ditutup dengan malam perenungan mengharu biru. Di dalamnya ada pembacaan puisi terima kasih kami kepada orang tua, terutama ibu yang telah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan kami ke dunia. Kami juga diberikan waktu untuk menuliskan komitmen kami dalam selembar kertas sebagai pengingat.
Perubahan terjadi! Murid laki-laki yang awalnya suka kasar saat bermain, sejak mendapatkan pembelajaran itu berubah menjadi lebih lembut kepada kami. Mereka menaruh hormat dan memperlakukan murid-murid perempuan dengan lebih setara. Fase pembelajaran pengenalan diri ini membukakan sebuah wawasan baru yang penting dalam proses pertumbuhan jati diri anak.
Lebih dari sekadar teori Biologi yang merumuskan XX sebagai perempuan dan XY sebagai laki-laki, kejadian kita dirangkai sedemikian rupa secara ajaib oleh Sang Pencipta. Berawal dari bertemunya sel sperma dan sel telur hingga proses pembentukan bakal bayi. Bagaimana 250.000 sel saraf baru terbentuk dalam hitungan menit untuk membangun otak yang menjadi bilik akal kita.
Bukankah pengetahuan ini saja harusnya mendorong kita untuk memahami bahwa masing-masing kita adalah karunia. Pribadi yang bebas berkarya, berkontribusi maksimal, dan mengekspresikan diri sesuai dengan HAM dan konstitusi. Namun, sulit untuk bisa berada pada tahapan ini jika kita bersikeras membangun pemahaman hanya berdasarkan asumsi yang belum tentu teruji.
Maka benarlah apa yang diungkapkan oleh Chimamanda Ngozi Adichie, penulis dan feminis asal Nigeria dalam esainya yang berjudul We Should All Be Feminists. Ia mengatakan bahwa permasalahan gender adalah ketika orang terlalu sibuk memberikan saran tentang seperti apa harusnya kita berlaku daripada bagaimana kita bisa mengenal jati diri. “Bayangkan, betapa kita bisa lebih bahagia dan bebas menjadi diri kita yang sesungguhnya ketika kita tidak dibebani oleh segala ekspektasi gender,” ungkap Chimamanda.
Saya 100% setuju dengan pendapatnya ini. Orang yang bahagia menjadi dirinya sendiri memiliki perspektif hidup yang lebih positif. Kita tidak lagi menghakimi orang lain, tapi saling menerima dan fokus pada kualitas yang baik pada diri sesamanya. Untuk yang satu ini, saya ingin mengutip ucapan akademisi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum:
“Dunia, termasuk manusia, fitrahnya beragam. Jadi betapa indah kalau kita dapat menerima dan menghargai keberagaman. Hanya yang bisa menerima dan menghargai keberagaman yang dapat hidup nyaman dan mampu bekerja sama dengan orang-orang lain tanpa melihat apa agama, suku, ras, identitas atau ekspresi gender mereka.”
Artikel Terkait
Seksualitas: Pencarian makna tiada henti
Ketika tulisan tentang seksualitas berhamburan, berbagai pandangan berlomba-lomba menentukan apa itu sebenarnya seksualitas. Tentu saja, beberapa kelompok tertentu akan melihat seksualitas sebagai urusan antara lelaki dan perempuan serta hubungan sah antara keduanya yang tidak boleh diganggu gugat. Akhirnya, kita terjebak dalam pergulatan panjang dan labirin yang penuh tanya.“XX” & “XY” dan Segala Sesuatu yang Mengikutinya
Di artikel ini, Naomi menekankan pentingnya mempertanyakan kembali gagasan-gagasan mengenai gender dan seksualitas yang sering dianggap sudah berterima dan wajar-wajar saja di keseharian kita.Melerai Kekusutan Gender dan Jenis Kelamin
Sebelum seorang bayi lahir, kita sangat terbiasa untuk menanti ‘jenisnya’. Laki-lakikah? Atau perempuan? Begitu tahu, kita sesegera mungkin menentukan warna barang untuknya. Tapi, apa iya jenis kelamin harus menjadi tolak ukur kejantanan atau kewanitaan seseorang?