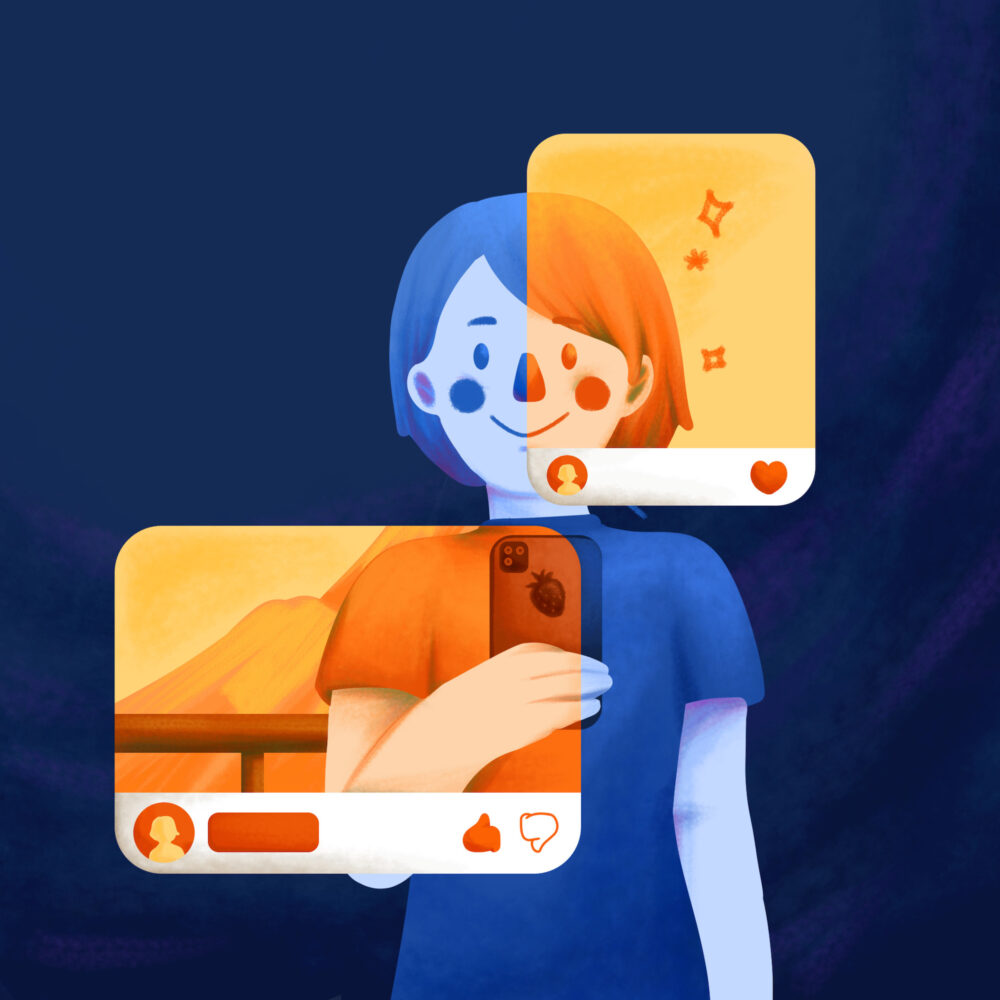
Tubuh Digitalku, Milik Siapa?
June 27, 2021
Slacktivism atau Clicktivism: Bisakah Perubahan Datang dari Protes Digital?
June 27, 2021Makna
Budaya Populer: Pembodohan Massa atau Ruang Daya Laku Konsumen?
oleh Shuri Mariasih Gietty Tambunan
Pada akhir Mei 2021 lalu, McDonald’s mengeluarkan BTS Meal sebagai menu khusus yang sudah sangat dinantikan oleh para Army (sebutan untuk penggemar BTS) di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, BTS Meal baru dirilis pada tanggal 9 Juni 2021. Berdasarkan pengamatan di akun Twitter McDonald’s Indonesia, antusiasme fans BTS terhadap produk ini sangat tinggi. Lebih menarik lagi, bungkus makanan cepat saji bertema BTS ini bahkan dijual di e-Bay dengan harga yang cukup tinggi.
Apabila dikaitkan dengan fenomena BTS sebagai bagian dari budaya populer dan makanan cepat saji sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bagaimana kita dapat memaknai antusiasme ini? Apakah membeli bungkus makanan cepat saji di e-Bay sebagai bagian dari praktik fandom dapat dibaca sebagai bukti bahwa budaya populer merupakan “opium of the masses (candu)”?
Dengan kata lain, apakah budaya populer hanya produk kapitalisme yang membodohi massa, yang bahkan telah membuat para fans kehilangan agensi/daya laku (kemampuan individu untuk berubah sesuai dengan pilihan pribadi) mereka?
Budaya populer pada dasarnya adalah teks dan praktik budaya yang dibuat dan disebarkan oleh dan/atau untuk banyak orang. Cara sederhana memahami budaya populer, seperti yang dikemukakan oleh Ariel Heryanto, adalah dengan membandingkannya dengan budaya lain. Perbandingan ini bisa dilakukan dengan budaya tradisional, budaya avant-garde (tidak lazim), maupun budaya nasional yang dibentuk oleh negara seperti yang bisa kita temui di Taman Mini Indonesia Indah.
Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, jenis-jenis budaya di atas juga bisa saling berhubungan. Misalnya, saat lagu tradisional dari etnis Batak diaransemen ulang menjadi lagu rock oleh musisi Vicky Sianipar. Meskipun memiliki unsur budaya tradisional, lagu ini lalu dikonsumsi orang banyak dan kini dapat dikategorikan sebagai budaya populer.
Sayangnya, budaya populer masih sering diremehkan karena dianggap hanya memiliki nilai komersial. Padahal, budaya populer juga memiliki kekuatan ideologis dan politis. Misalnya, di masa kampanye, biduan dangdut atau musisi pop seringkali digunakan partai untuk menarik perhatian massa. Contoh lain, film seringkali digunakan sebagai alat penyebar propaganda yang dapat mempengaruhi cara orang berpikir mengenai suatu hal. Pertanyaannya adalah: Apakah benar budaya populer hanya bisa dilihat sebagai produk kapitalisme yang membodohi massa?

Pandangan ini muncul dari kegagalan menyadari bahwa konsumen memiliki daya laku. Padahal, nyatanya konsumen mampu berperan aktif dalam memaknai teks dan praktik budaya tersebut. Bahkan, proses konsumsi aktif ini juga dapat mengarah ke proses reproduksi (pembuatan ulang). Dari sinilah muncul istilah prosumer–producer (pembuat) dan consumer (penikmat). Seorang prosumer secara aktif menciptakan makna baru dari suatu produk budaya. Nyatanya, seorang prosumer bahkan bisa membalikkan makna utama yang ditawarkan oleh suatu produk budaya populer.
Sebagai contoh, ada sekelompok anak muda di Bandung yang membuat parodi video klip girlband dan boyband dari Korea Selatan. Video-video tersebut diunggah di akun YouTube mereka yang bernama eJ Peace. Salah satu unggahan mereka yang memparodikan video klip Blackpink yang berjudul “DDU DU DDU DU” kini sudah ditonton sebanyak 27.635.083 kali sejak dirilis pada 20 Januari 2019.
Dalam video tersebut, Blekjek (sebutan untuk 4 remaja laki-laki asal Bandung ini) menyederhanakan narasi dari lagu Blackpink ini melalui perubahan elemen visual dan lirik. Di video tersebut, mereka menonjolkan keseharian mereka sebagai anak SMA yang hobi tidur selama pelajaran matematika atau uji nyali makan Samyang (merk mie pedas asal Korea Selatan). Bahkan, dalam video tersebut Blekjek juga memasukkan bahasa Sunda sebagai bagian dari lirik lagu ketika bicara mengenai Samyang.
Walaupun Blekjek meniru elemen-elemen yang ada di dalam klip, secara visual, video tersebut tampak jauh berbeda dengan video Blackpink untuk lagu yang sama. Adaptasi ini dapat dibaca sebagai hasil daya laku prosumer Indonesia terhadap produk budaya populer dari Korea Selatan yang bukan sekedar menjadi copycat. Lagu “DDU DU DDU DU” yang melalui lirik dan tariannya menonjolkan femininitas dan seksualitas keempat personel Blackpink, dalam video ini dibongkar dan dipresentasikan lewat tarian keempat remaja laki-laki yang kaku. Dengan demikian, tarian tersebut tidak lagi terlihat sebagai tarian yang sexualized (bersifat seksual) atau dianggap memancing.
Lagu yang sama dapat dilihat dalam parodi lagu yang sama oleh empat anak-anak di Thailand. Video yang diunggah pada tahun 2018 oleh akun YouTube DEKSORKRAO เด็กเซราะกราว ini kini sudah ditonton sebanyak 72.346.857 kali. Berbeda dengan Blekjek, Deksorkrao hanya mengubah aspek visual video tersebut. Audio yang digunakan pun tetap lagu asli milik Blackpink. Dalam video ini, tiara, anting berlian, dan baju mewah yang digunakan Blackpink di video asli diubah menjadi shower cap (topi mandi), anting dari jepit jemuran, dan jubah dari handuk.
Lagi-lagi, gambaran kemewahan yang ditawarkan Blackpink disederhanakan dan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari prosumer. Modernitas, kemewahan, femininitas, dan konsep perempuan sempurna yang direpresentasikan Blackpink dalam video “DDU DU DDU DU” bukan hanya direproduksi, tapi juga dibongkar dan diputarbalikkan.
Contoh yang dijelaskan di atas menunjukkan kompleksnya budaya populer, terutama di era digital ini. Perkembangan teknologi memungkinkan produk budaya populer untuk disebarkan dari satu negara ke negara lain dengan sangat cepat. Akibatnya, praktik konsumsi pun menjadi sangat berlapis. Kini, produk budaya populer bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat di tempat teks dan praktik budaya itu diproduksi, tapi juga masyarakat di seluruh dunia.
Selain itu, media digital juga membuka ruang bagi para konsumen untuk menjadi prosumer. Kegiatan mengkonsumsi budaya populer tidak lagi dilakukan secara pasif. Konsumen juga dapat berstrategi dengan kreativitas mereka, seperti yang dilakukan kedua akun Youtube yang dijadikan contoh di atas.
Lantas, bagaimana sebaiknya kita menyikapi kedua sisi budaya populer? Walaupun dapat membodohi massa, budaya populer juga memiliki potensi untuk membangkitkan kesadaran dan memberdayakan konsumennya. Kuncinya adalah dengan menjadi konsumen yang aktif tapi juga kritis. Budaya populer akan selalu menjadi tempat pelarian dari kehidupan kita sehari-hari.
Dalam konteks ini, membeli dan mengoleksi bungkus BTS Meal adalah cara para Army untuk merasa terhubung dengan idolanya. Sama saja dengan menonton episode terbaru serial Bridgerton di Netflix yang bisa membuat penonton terpesona dan terlibat dalam konflik asmara antara tokohnya, Simon dan Daphne.
Dengan proses interpretasi yang kritis dan praktik fandom yang memberdayakan audiensnya, konsumsi budaya populer tidak harus menjadi bagian dari pembodohan massa. ~ Shuri Mariasih Gietty Tambunan Share on XAkan tetapi, kini konsumen tidak hanya berperan sebagai fans yang mendukung idolanya. Dalam konteks Army, banyak di antaranya yang ikut aktif dalam sejumlah kampanye. Salah satu contohnya adalah kampanye Love Myself yang dilakukan boyband asal Korea Selatan ini dengan bekerja sama dengan UNICEF. Melalui media sosial, tagar #LoveMyselfBTS telah digunakan 11.000.000 kali untuk menyebarkan “message of positivity (pesan positif)”. Sampai bulan Agustus 2020, kampanye ini telah menghasilkan 2,2 juta USD yang didonasikan langsung oleh BTS dari hasil penjualan album, merchandise, dan sumbangan dari para Army di seluruh dunia.
Selain Army yang berperan aktif dalam kampanye, penonton serial televisi Bridgerton juga dapat aktif mempelajari representasi ras di serial ini. Di satu sisi, Bridgerton dianggap sebagai produk televisi yang sekedar menampilkan karakter dari berbagai latar belakang ras. Tetapi, apabila dibandingkan dengan drama periode dari Inggris lain seperti Downtown Abbey, serial ini sebetulnya memulai diskusi baru mengenai representasi multi-ras dalam konteks produk budaya populer di Inggris atau bahkan di dunia.
Dengan proses interpretasi yang kritis dan praktik fandom yang memberdayakan audiensnya, konsumsi budaya populer tidak harus menjadi bagian dari pembodohan massa. Silahkan menikmati BTS Meal dan episode terbaru serial kesukaanmu di Netflix! Tapi, pastikan kamu mengonsumsi dengan bijak dan berpikiran kritis yaa!
Bacaan Lebih Lanjut
| Heryanto, A. (Ed.). (2008). Popular culture in Indonesia: Fluid identities in post-authoritarian politics. Routledge. Storey, J. (2006). Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. New York: PearsonPrenticeHall. |

Shuri Mariasih Gietty Tambunan adalah dosen di Program Studi Sarjana Sastra Inggris dan Program Studi Pascasarjana Ilmu Susastra, Peminatan Cultural Studies di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Saat ini, Gietty juga merupakan anggota Komite Film, Dewan Kesenian Jakarta periode 2020-2023. Gietty memperoleh gelar magister di bidang Literary and Cultural Studies di University of Groningen (2010) dan di Universitas Indonesia (2007). Setelah menyelesaikan studinya dari Belanda, Gietty melanjutkan studi Doktor di Lingnan University, Hongkong, dari tahun 2010 dan mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Cultural Studies di tahun 2013. Dalam karir akademisnya, area penelitian yang didalami adalah penelitian mengenai arus dan produk budaya populer transnasional seperti film Bollywood dan drama televisi Asia Timur serta kajian-kajian dalam bidang Cultural Studies lain seperti kajian media sosial dan praktik kuliner.
Artikel Terkait
Media, Kita, dan Kebenaran
Kenyataan hidup (realitas) kita sekarang tidak cuma dibentuk oleh keluarga, teman, ataupun lingkungan sekitar. Media memainkan peran penting dalam menentukan apa yang kita anggap benar atau salah. Dengan kemasan ciamik, media membuat kita menuruti ideologi tertentu. Lalu gimana caranya kita bisa memahami media secara kritis? Yuk, baca artikel ini.Media, Ideologi, dan Memori Kolektif
Media bukan cuma sesuatu yang kita tonton, baca, atau bagikan ke teman-teman. Di artikel ini, Regina Widhiasti menjelaskan peran penting media dalam mengubah pola pikir, ideologi, dan memori kolektif.Minoritas Seksual di Media: Sudahkah Tampil Akurat dan Terhormat?
Kelompok minoritas seksual banyak mengalami representasi media yang tidak hanya salah, tapi juga tidak adil dan punya risiko menyakiti serta mendorong munculnya kekerasan. Lalu, bagaimana kita bisa merepresentasikan kelompok minoritas seksual secara adil?







