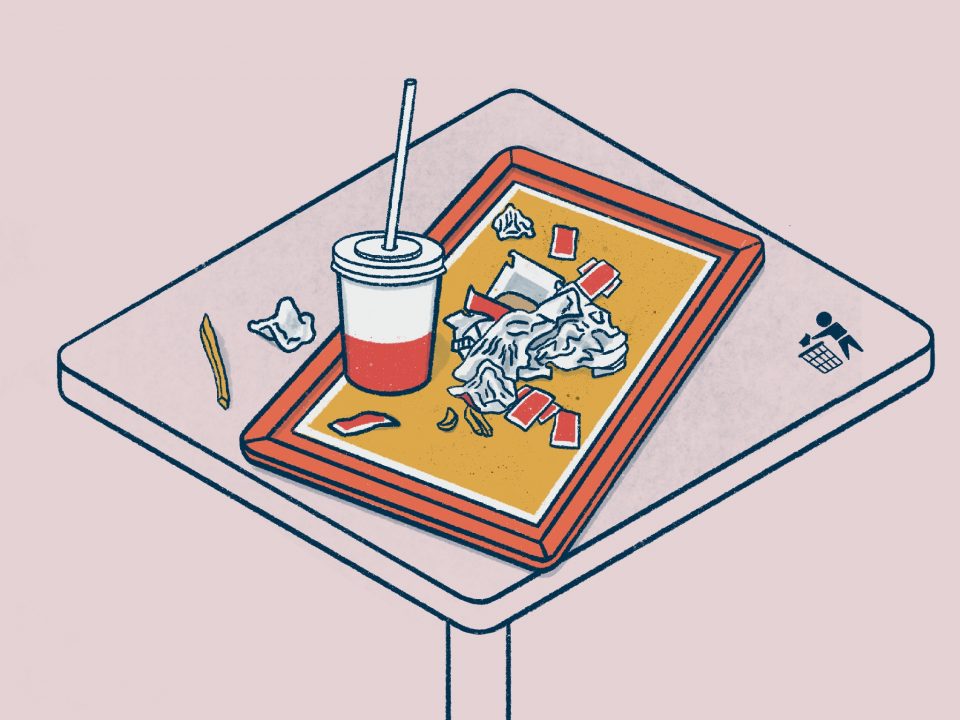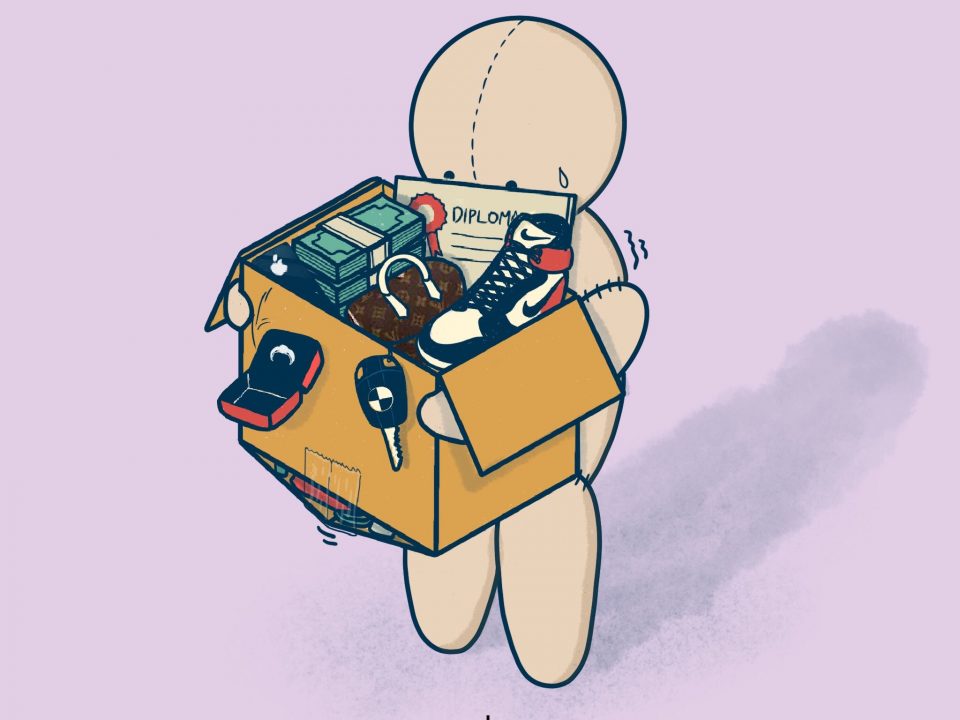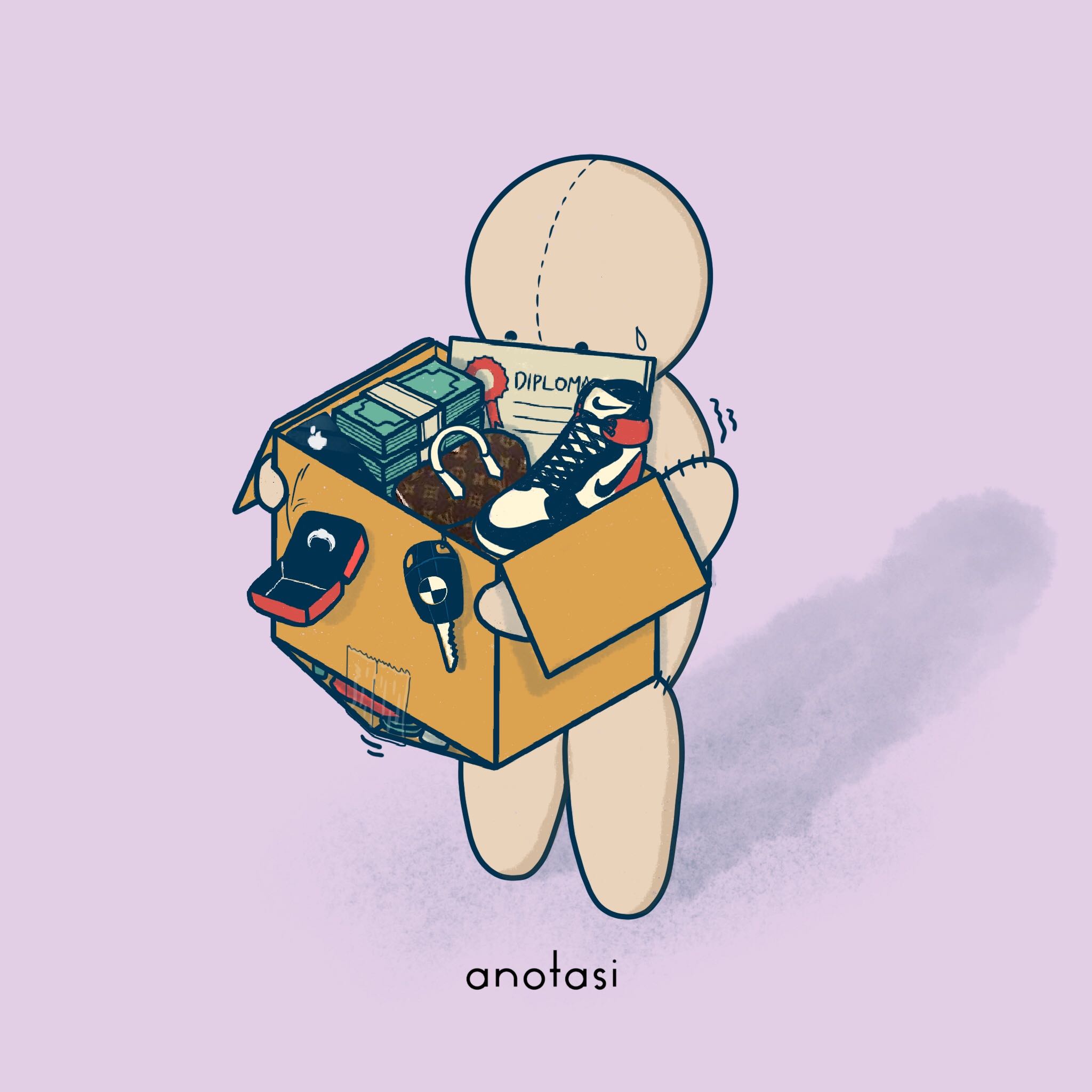
Budaya dan Konstruksi Sosial: Bagaimana Kita Memahami Dunia
October 17, 2019
Mendudukkan Lagi Budaya, Sebelum Terlalu Jauh
October 17, 2019Makna
Dari Dangdut hingga Frankfurt
Oleh Fitria Sis Nariswari
“Suka dengerin musik apa?” suatu saat teman kencansaya bertanya seperti itu. Saya diam sejenak. Sempat terpikir untuk menyebutkan Cigarettes After Sex, Slowdive, atau Danilla Riyadi, mungkin juga Dialog Dini Hari—yang lagu-lagunya enak sekali didengarkan saat senja dan ditemani kopi, atau bisa juga sebagai lagu-lagu pengantar tidur yang estetik. Lalu, saya juga terpikir untuk menyebut bahwa saya adalah penggemar musik-musik pop Barat, seperti Ed Sheeran, Maroon 5, Adele, atau yang agak lawas Westlife, tapi nyatanya saya jarang mendengarkan mereka.

“Dangdut. Sekarang, sih, lagi suka dengerin Via Vallen atau Nella Kharisma. Kadang kalau lagi ingin nostalgia, dengerinnya yang versi campur sari Didi Kempot,” jawab saya pada akhirnya. Toh, pada kenyataannya, lagu-lagu dangdut yang menemani saya bertumbuh dan mendewasa. Playlist musik di ponsel saya, ya, memang mayoritas diisi oleh Via Vallen, Nella Kharisma, Didi Kempot, Cita Citata, dan penyanyi dangdut lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Lalu, saya melihat raut muka teman kencan saya sedikit berubah. Tiba-tiba dia mengajak saya pulang. Setelah itu, seingat saya, tidak ada lagi percakapan dan kencan selanjutnya.
Apakah saya sedih? Pada saat itu iya, tapi kesedihan saya bukan karena dia yang tidak lagi mengajak kencan, tetapi lebih kepada ketidakmampuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan, “Adakah yang salah dengan dangdut?” Apakah kemudian pencinta dangdut memiliki selera yang tidak lebih tinggi dibandingkan dengan pencinta genre musik lainnya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian menjadi problematis.
Jauh sebelum dangdut berkembang di negara ini, dunia memang sudah penuh dengan oposisi biner: jika tidak A, maka B. Begitu juga dengan musik yang bisa dibilang menjadi bagian dari kebudayaan. Kebudayaan tiba-tiba saja terbagi atas konsep high culture dan low culture yang telah ada sejak masa Yunani Kuno. Belakangan, muncul juga istilah popular culture alias budaya pop yang digunakan sebagai padanan atau kata yang lebih “sopan” daripada low culture.
High culture dapat dikatakan sebagai budaya yang dijunjung tinggi dan mengacu pada aristrokat dan intelegensia, yang mencakup karya seni dan produk budayanya. Budaya ini dianggap elite sehingga tidak semua orang dapat menikmatinya. Sementara itu, definisi ini dikontraskan dengan low culture, yaitu budaya yang mengacu pada masyarakat kurang berpendidikan dan sifatnya lebih umum, misalnya majalah gosip, musik populer, reality show, dan sebagainya. Secara sederhana, popular culture dapat disamakan dengan low culture.
Garis pembeda antara high culture dan low culture sudah sangat tipis untuk sekarang ini sebab pembedaan tersebut tidak hanya berdasarkan estetika, tetapi lebih pada kepentingan politis. ~ Fitria Sis Nariswari Share on XPembagian yang tajam antara high culture dan low culture juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Mahzab Frankfurt dari Eropa yang menyatakan bahwa budaya sedang mengalami krisis. Akar dari krisis budaya adalah kegagalan karya seni memainkan posisi kritis. Dalam buku Krisis Seni Krisis Kesadaran , Greg Soetomo memaparkan beberapa pemikir Frankfurt ini, misalnya Walter Benjamin dan Theodor W. Adorno. Dalam buku tersebut, Walter Benjamin mengatakan bahwa karya seni dapat diproduksi kembali, tetapi reproduksi ini akan menyebabkan esensi dari karya seni itu tidak tersentuh. Hal ini juga kemudian dikuatkan oleh Theodor W. Adorno. Ia menyatakan bahwa penyebaran karya seni secara besar-besaran membuat seni tidak kurang dan tidak lebih hanya merupakan setetes air di samudra raya.
Mahzab Frankfurt menganggap bahwa seni yang diproduksi secara massal akan kehilangan maknanya. Ia tidak lagi bisa digunakan sebagai penanda luhurnya sebuah kebudayaan. Meskipun setelah itu, ada banyak kritik pada konsep tersebut. Garis pembeda antara high culture dan low culture sudah sangat tipis untuk sekarang ini sebab pembedaan tersebut tidak hanya berdasarkan estetika, tetapi lebih pada kepentingan politis. Namun, sisa-sisa pembedaan tersebut masih terasa hingga sekarang.
Saya kemudian bisa memahami mengapa musik dangdut dianggap sebagai musik rakyat dan bukan musik yang berasal dari budaya “tinggi” jika berkaca pada konsep-konsep pembedaan budaya tersebut. Dangdut mengalami kesejarahan yang panjang. William H. Frederick dalam salah satu artikelnya menyebutkan bahwa musik serupa dangdut telah muncul dari abad kolonial ketika paduan alat-alat musik Indonesia, Arab, dan Barat dimainkan bersama-sama dalam tanjidor. Istilah dangdut baru dikenal pada tahun 1970-an yang berasal dari onomatope bunyi gendang. Akan tetapi, pada saat itu, penikmat dangdut bukanlah dari kalangan yang terpelajar.
Sementara itu, Bettina David, salah satu peneliti yang banyak membahas dangdut, menyatakan bahwa dangdut banyak dipengaruhi oleh film dan musik India. Banyak lagu dangdut yang terpengaruh, bahkan meniru, lagu-lagu India. Dangdut pada masa pasca-Soeharto merupakan musik gabungan antara India, Melayu, dan Arab. Karena itu, dangdut dapat disebut sebagai transformasi dalam multietnik. Pada mulanya, dangdut dan Bollywood sama-sama dianggap musik kelas bawah oleh kalangan perkotaan elite yang berkaca pada Barat. Akan tetapi, hal ini tidak berlangsung selamanya. Dangdut dan Bollywood menjadi berterima di dalam masyarakat menengah atas setelah muncul film Kuch Kuch Hota Hai. Setelah film ini booming, masyarakat Indonesia mengalami “demam India”. Hal ini dapat terlihat ketika terdapat unsur India pada banyak aspek hiburan.
Masyarakat menengah atas tidak menyadari bahwa film Kuch Kuch Hota Hai mencerminkan dunia Barat. Masyarakat mengira bahwa Indonesia dan India masih merupakan “teman” yang sama sehingga “culture” dari film dan musik India dapat dengan mudah diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, dangdut dan Bollywood merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang dapat dilihat dalam konteks yang lebih lebar pada keanekaragaman pengaruh globalisasi yang sedang terjadi pada cakupan media massa kontemporer di Indonesia.
Meskipun demikian, masih ada segelintir orang yang memandang sebelah mata pendengar musik dangdut, sementara dangdut sudah berkembang dengan sangat pesat. Orang-orang tersebut jelas membuat batas yang tajam karena merasa bahwa musik dangdut bukanlah musik yang layak didengarkan dalam “kelas”-nya saat ini. Hal ini sangat bisa dimaklumi karena konsumsi budaya tertentu dapat menjadi penanda kelas sosial seseorang meskipun penanda ini pun tidak telak.
| Referensi David, Bettina. 2008. “Intimate Neighbors: Bollywood, Dangdut Music, and Globalizing Modernities in Indonesia” in Global Bollywood: Travels of Hindi Song and Dance, Sangita Gopal and Sujata Moorti (ed.). Minnesota: University of Minnesota Frederick, William H. 2005. “Goyang Dangdut Rhoma Irama: Aspek-Aspek Kebudayaan Pop Kontemporer” dalam Lifestyle Ecstasy: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia, Idi Subandy Ibrahim (ed.). Yogyakarta: Jalasutra, h. 234—264 Soetomo, Greg. 2003. Krisis Seni Krisis Kesadaran. Yogyakarta: Penerbit Kanisius |
| Bacaan Lanjutan David, Bettina. 2014. “Seductive Pleasures, Eluding Subjectivities: Some Thoughts on Dangdut’s Ambiguous Identity” in A History of Popular Music, Social Distinction and Novel Lifestyles (1930s –2000s), Bart Barendregt (ed.), Brill Publishing Holden, John. 2010. Culture and Class. London: Counterpoint Wallach, Jeremy dan Clinton, Ester. 2013. “History, Modernity, and Music Genre in Indonesia: Introduction to the Special Issue” in Asian Music, Vol. 44, No. 2, Constructing Genre in Indonesian Popular Music: FromColonized Archipelago to Contemporary World Stage: A special issue (SUMMER/FALL 2013), pp. 3-23, University of Texas Press Weintraub, Andrew N. 2008. “Dance Drills, Faith Spills: Islam, Body Politics, and Popular Music in Post-Suharto, Indonesia” in Popular Music, Vol. 27, No. 3 (Oct., 2008), pp. 367-392, Cambridge University PressWeintraub, Andrew N. 2013. “The Sound and Spectacle of Dangdut Koplo: Genre and Counter-Genre in East Java, Indonesia” in Asian Music, Vol. 44, No. 2, Constructing Genre in Indonesian Popular Music: From Colonized Archipelago to Contemporary World Stage: A special issue (SUMMER/FALL 2013), pp. 160-194, University of Texas Press |

Fitria Sis Nariswari adalah seorang perempuan yang sedang berjuang menyelesaikan disertasi. Titik berat minat penelitiannya adalah kajian tentang sastra, kajian budaya, sejarah, hingga dunia supranatural. Ketertarikannya dalam dunia supranatural dimulai ketika ia menulis tesis tentang ritual ngalap berkah di Gunung Kawi. Selain itu, ia juga tertarik pada kajian tentang budaya populer. Budaya populer dan supranatural itu kemudian bersatu dalam disertasinya, yaitu tentang kekerasan dan seksualitas dalam cerita-cerita horor Abdullah Harahap. Hasil kerja ilmiahnya telah dipresentasikan di beberapa seminar nasional maupun internasional. Di sela-sela kesibukannya menyelesaikan disertasi, ia juga mengajar di Program Studi Indonesia, FIB UI, sesekali diselingi dengan mengedit buku. Email: [email protected]. Instagram: rainiku. Facebook: Fitria Sis Nariswari