
Feminisme: Mitos, asumsi, dan kenyataan
May 30, 2018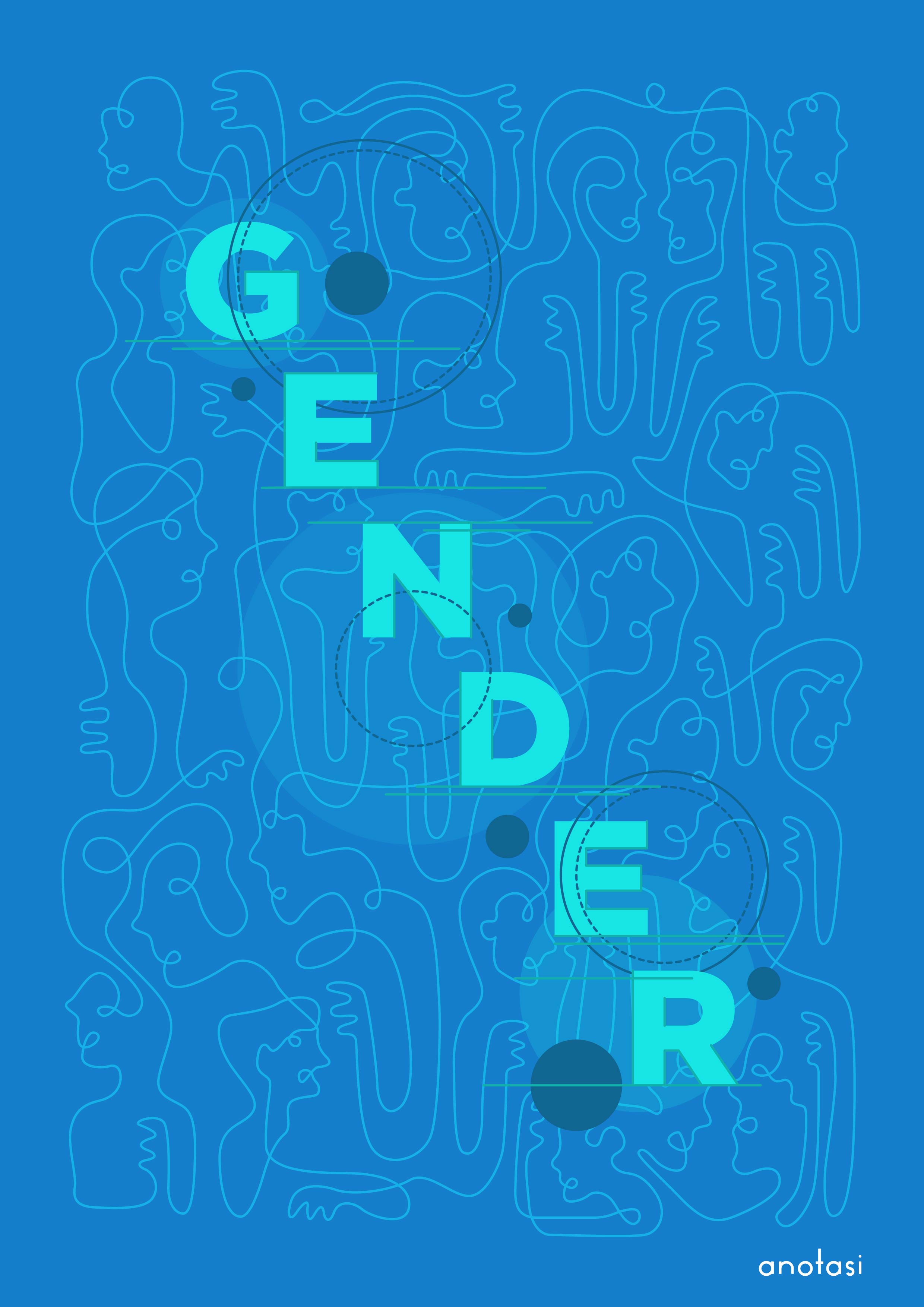
“XX” & “XY” dan Segala Sesuatu yang Mengikutinya
May 30, 2018Makna
Melerai Kekusutan Gender dan Jenis Kelamin
oleh Marissa Saraswati dan Annisa R. Beta
Sebelum seorang bayi lahir, kita sangat terbiasa untuk menanti ‘jenisnya’. Laki-lakikah? Atau perempuan? Begitu tahu, kita sesegera mungkin menentukan warna barang untuknya. Anak laki-laki cenderung dihiasi warna biru, sedangkan perempuan warna merah jambu. Contoh lain adalah tradisi Mitoni yang dirayakan kebanyakan orang Jawa di bulan ketujuh kehamilan. Di setiap bagian tradisi ini terdapat berbagai ritual yang mewakili keperempuanan atau kelaki-lakian si jabang bayi dan juga sang calon ibu dan bapak. Begitu lahir, jenis kelaminnya segera diumumkan. Ketika si bayi tumbuh besar, ia kemudian diperkenalkan dengan apa yang seharusnya ia sukai dan lakukan. Kerumitan kemudian muncul ketika si anak berperilaku berbeda dari yang seharusnya. Terkadang anak perempuan disebut tomboy, yang laki-laki ‘cengeng’ atau ‘melambai’. Tapi, apa iya jenis kelamin harus menjadi tolak ukur kejantanan atau kewanitaan seseorang?
Dalam ilmu sosial, jenis kelamin tidaklah sama dengan gender. Jenis kelamin terkait dengan hal-hal biologis dalam tubuh seseorang, terutama organ reproduksinya. Walaupun di banyak kelompok masyarakat hanya ada dua jenis kelamin, sebenarnya orang yang lahir dengan jenis kelamin yang tidak bisa dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan tidaklah sedikit. Orang-orang ini sering disebut kelompok interseks dan data terakhir menunjukkan bahwa dari 2000 bayi yang lahir, dapat dipastikan ada 1 bayi interseks (Intersex Society of North America 2013). Fenomena ini memperlihatkan bahwa sebenarnya kita tidak bisa hanya terpaku pada penis sebagai pertanda kelaki-lakian dan vagina untuk perempuan. Belum lagi jika kita mempertimbangkan kromosom dan hormon. Sebagai contoh, atlet lari asal Afrika Selatan Caster Semenya meskipun terlihat seperti perempuan ternyata memiliki kromosom khas ‘laki-laki’.
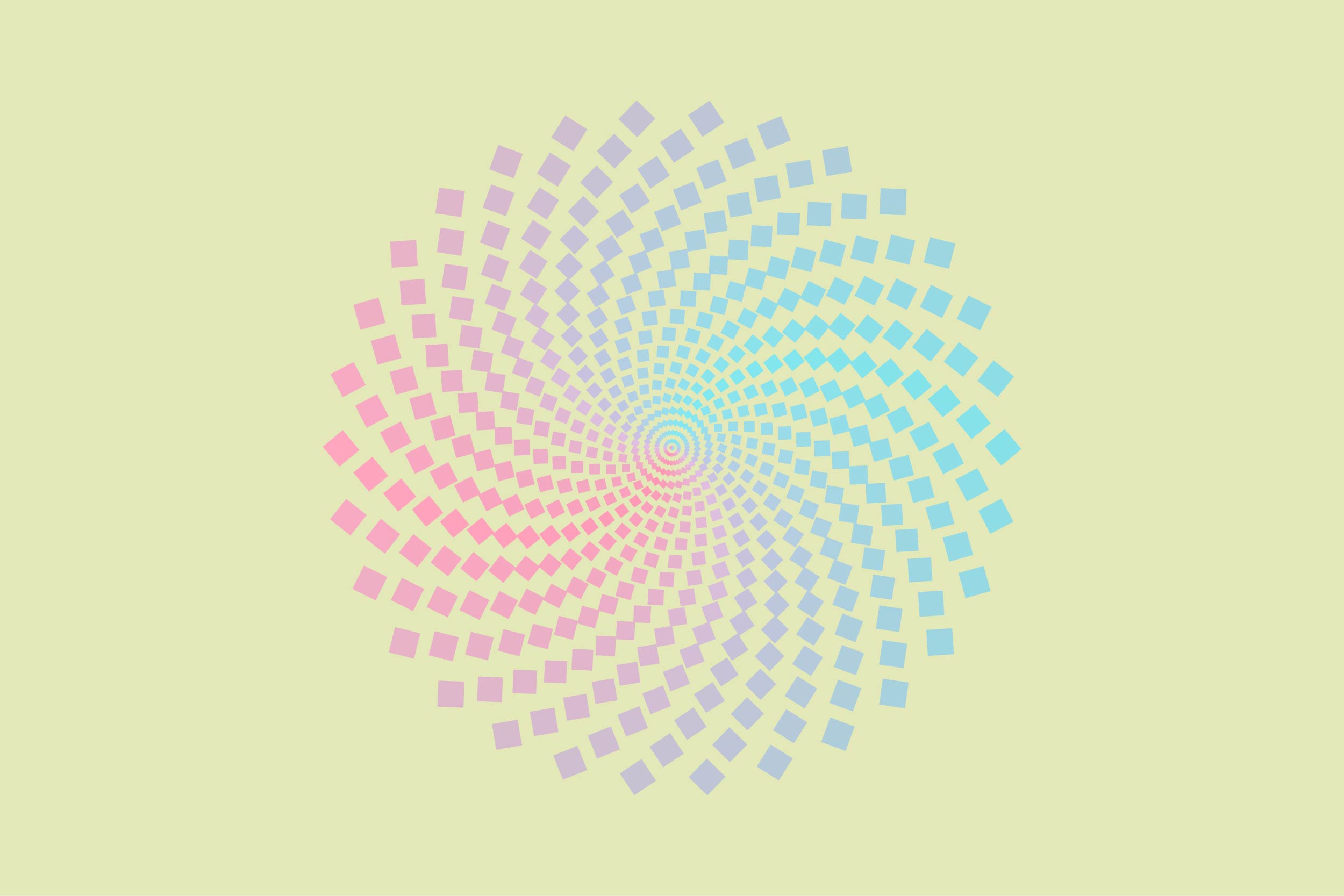
Jika jenis kelamin sering ditentukan berdasarkan kondisi biologis, gender ditentukan oleh masyarakat. Kecenderungannya, jenis kelamin selalu dikait-kaitkan dengan gender. Maka, untuk menjadi maskulin, seorang laki-laki tidak boleh menangis, tidak wajib bisa masak, haram memakai perhiasan ataupun dandanan, dan tidak perlu paham bagaimana cara merawat anak. Untuk menjadi feminin, seorang perempuan harus sensitif, pintar memasak, pandai berhias dan merawat diri, juga siap melahirkan dan membesarkan anak.
Pemikir feminis asal Amerika Serikat, Carole S. Vance, dalam tulisannya yang berjudul “Social Construction Theory: Problems in the History of Sexuality” mengatakan bahwa konsep dan ide seputar gender dan seksualitas seharusnya tidak dipahami sebagai sesuatu yang “alami” atau “kebenaran” yang mutlak dan tidak dapat berubah, tapi sebagai sebuah konstruksi sosial. Menurutnya, konstruksi sosial adalah ide-ide yang dihasilkan dalam masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Dengan melihat gender bukan sebagai sesuatu yang alamiah, biologis atau sebagai sebuah kodrat, Vance mengajak kita untuk memahami gender sebagai hasil dari perkembangan sejarah dan tindakan manusia. Pandangan ini juga membantu kita melihat bahwa ada motif kekuasaan yang berperan untuk menentukan bagaimana gender dibentuk. Misalnya, Julia Suryakusuma dalam bukunya Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru mengatakan bahwa pada masa Orde Baru, pemerintah memiliki kuasa dalam menentukan peranan wanita sebagai ibu dan istri yang baik tidak hanya di ruang lingkup keluarga dan rumah tapi juga di masyarakat, termasuk dalam kehidupan bernegara. Efeknya, sampai sekarang perempuan Indonesia masih sulit lepas dari ekspektasi ini.
Melalui normalisasi, misalnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, kita menjadi begitu terbiasa dengan peraturan yang menentukan identitas gender kita. Normalisasi adalah proses sosial yang menentukan apa yang normal atau tidak normal di masyarakat. Ketika kita kecil, orang tua dan keluarga biasanya paling rajin memperkenalkan aturan-aturan gender ini. Di sekolah, kita belajar dari teman-teman berbagai kebiasaan baru yang mempertebal identitas gender ini. Apakah semua orang bisa mencapai idealisme ini? Tentu tidak. Kemudian yang terjadi biasanya adalah cemooh, olok-olok, atau pertanyaan-pertanyaan memojokkan. Laki-laki yang tidak paham olahraga sering dipertanyakan maskulinitasnya. Perempuan yang tidak segera hamil setelah menikah juga dipertanyakan kewanitaannya. Bukan hanya melalui keluarga dan teman, berbagai barang yang kita pakai sehari-hari juga memiliki karakter feminin atau maskulin. Deodoran, sampo, dan produk kecantikan dianggap hanya diperlukan oleh perempuan, makanya perlu ‘edisi khusus’ laki-laki. Di toko pakaian pun harus ada dua bagian khusus laki-laki dan perempuan.
Normalisasi tentang konsep gender tidak hanya tampak jelas di kehidupan sehari-hari yang bisa saja dianggap ‘subjektif’. Emily Martin, seorang antropolog Amerika Serikat, mengatakan bahwa dalam bidang yang sepertinya sangat ‘objektif’ dan bergantung pada fakta mutlak seperti sains dan dunia medis pun, normalisasi tentang gender sering terjadi. Dengan menganalisa tulisan-tulisan jurnal ilmiah tentang karakter sel telur dan sperma, Martin menunjukkan bagaimana gambaran tentang sel telur dan sperma dipengaruhi oleh stereotipe gender tentang laki-laki dan perempuan serta apa yang dianggap feminin dan maskulin di masyarakat. Misalnya sperma digambarkan memiliki sifat aktif sementara sel telur dianggap pasif. Ini berujung pada penggambaran proses biologis perempuan yang dianggap tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan proses biologis laki-laki.
Melihat gender dan jenis kelamin sebagai dua hal yang berbeda dapat membantu mengurangi diskriminasi. ~ Marissa Saraswati & Annisa R. Beta Share on XMenariknya, tidak semua orang mengikuti semua aturan tentang identitas gender yang dicampuradukkan dengan jenis kelamin. Masyarakat sendiri pun terus mengganti norma mengenai laki-laki atau perempuan ideal. Mungkin kita tidak ingat, tapi dalam sejarah, masyarakat Indonesia sering mengubah peraturan tentang bagaimana perempuan seharusnya. Sebelum tahun 1900an, tidak banyak perempuan yang dapat mengenyam pendidikan karena tidak dianggap perlu. Laki-lakilah yang dianggap berhak bersekolah setinggi-tingginya. Sekarang? Tidak ada yang mempertanyakan pentingnya sekolah baik untuk perempuan atau laki-laki.
Intinya, melihat gender dan jenis kelamin sebagai dua hal yang berbeda dapat membantu mengurangi diskriminasi, tidak hanya terhadap kelompok marginal seperti waria atau transgender, tapi juga mengurangi tekanan untuk diri kita sendiri. Kita tidak perlu lagi terkungkung oleh tuntutan konstruksi gender yang mengharuskan wanita bersikap feminin atau laki-laki memiliki kualitas maskulin.
Referensi
- Martin, Emily. “The egg and the sperm: How science has constructed a romance based on stereotypical male-female roles.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 16.3 (1991): 485-501.
- Suryakusuma, Julia. Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru. Depok: Komunitas Bambu (2011).
- Vance, Carole. “Social construction theory: problems in the history of sexuality.” Social perspectives in lesbian and gay studies: A Reader (1998): 160-172.
Bacaan Lanjutan
- Butler, Judith. Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Routledge, 2011.
- Kimmel, Michael S. The Gendered Society. Sixth ed., 2017.
- McClintock, Anne, and American Council of Learned Societies. Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest. Routledge, 1995.
- Ridgeway, Cecilia L. Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World. Oxford University Press, 2011.
- Risman, Barbara J. “Gender As a Social Structure.” Gender & Society, vol. 18, no. 4, 2004, pp. 429–450.
Artikel Terkait
Kesadaran Diri
Akhir-akhir ini kita banyak dihadapkan dengan pertanyaan sulit mengenai makna identitas dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari fenomena-fenomena sosial politik yang terjadi di sekitar kita. Situasi ini telah mendorong berbagai pihak untuk berpikir keras apa sebenarnya yang menyebabkan kuatnya sentimen berbasis identitas? Dan bagaimana cara kita menjelaskan fenomena ini?Musik, Murakami, dan “Ma”
Renungan Bayu tentang identitasnya sebagai seorang jurnalis, penulis fiksi dan skenario di artikel ini sangatlah menarik. Ia menegaskan betapa konsep diri bisa berbeda, tergantung dari kacamata mana kita melihat.Agensi: Kemampuan berpikir dan bertindak
Hidup itu penuh dengan pilihan. Rangkaian pilihan dalam kehidupan kita merupakan warisan dari nenek moyang yang sudah mengkristal dalam keluarga, pertemanan, masyarakat, bahkan negara.






