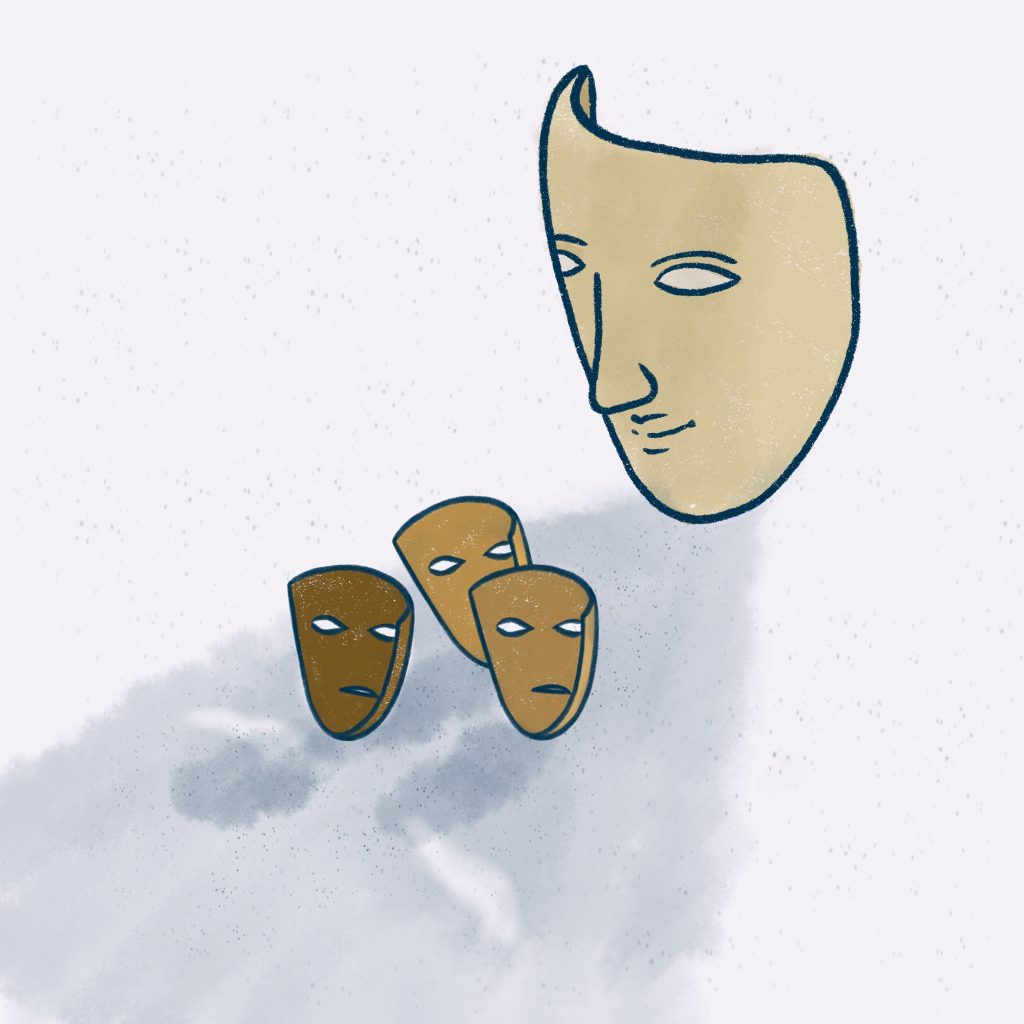
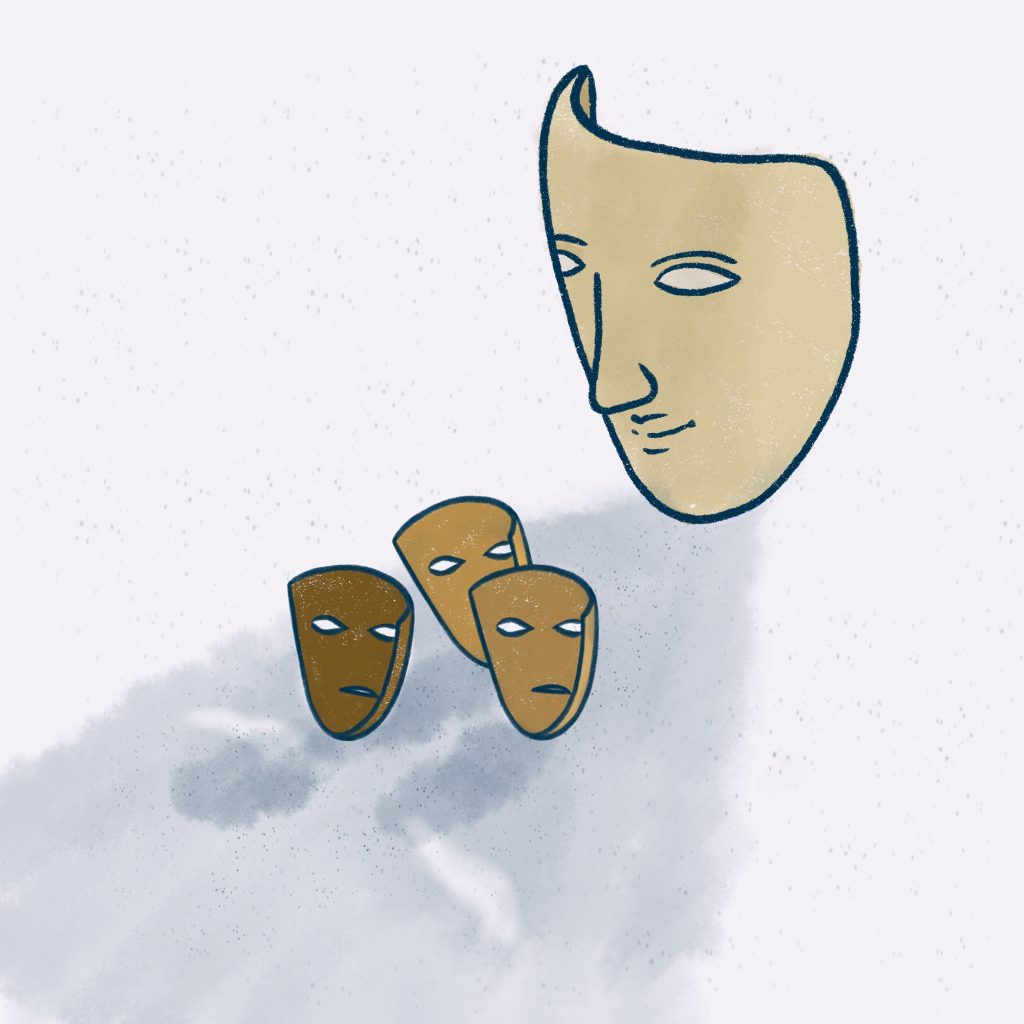
Konsep Mini
1. Diskriminasi
Pembedaan perlakuan yang didasari oleh adanya prasangka atau stereotip negatif mengenai identitas seseorang atau suatu kelompok, misalnya terkait dengan ras, etnis, suku, agama, kepercayaan, gender, orientasi seksual, usia, bahkan juga pilihan politik.
2. Etnis
Identitas budaya bersama di antara sekelompok orang berdasarkan kesamaan nenek moyang, bahasa, sejarah, tradisi, dan terkadang ciri-ciri fisik yang sama.
Dalam konteks yang lebih luas, diskriminasi dapat terjadi terhadap suatu kelompok masyarakat yang diposisikan lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Pembedaan perlakuan ini didasari oleh adanya prasangka atau stereotip negatif mengenai identitas seseorang atau suatu kelompok, misalnya terkait dengan ras, etnis, suku, agama, kepercayaan, gender, orientasi seksual, usia, bahkan juga pilihan politik.
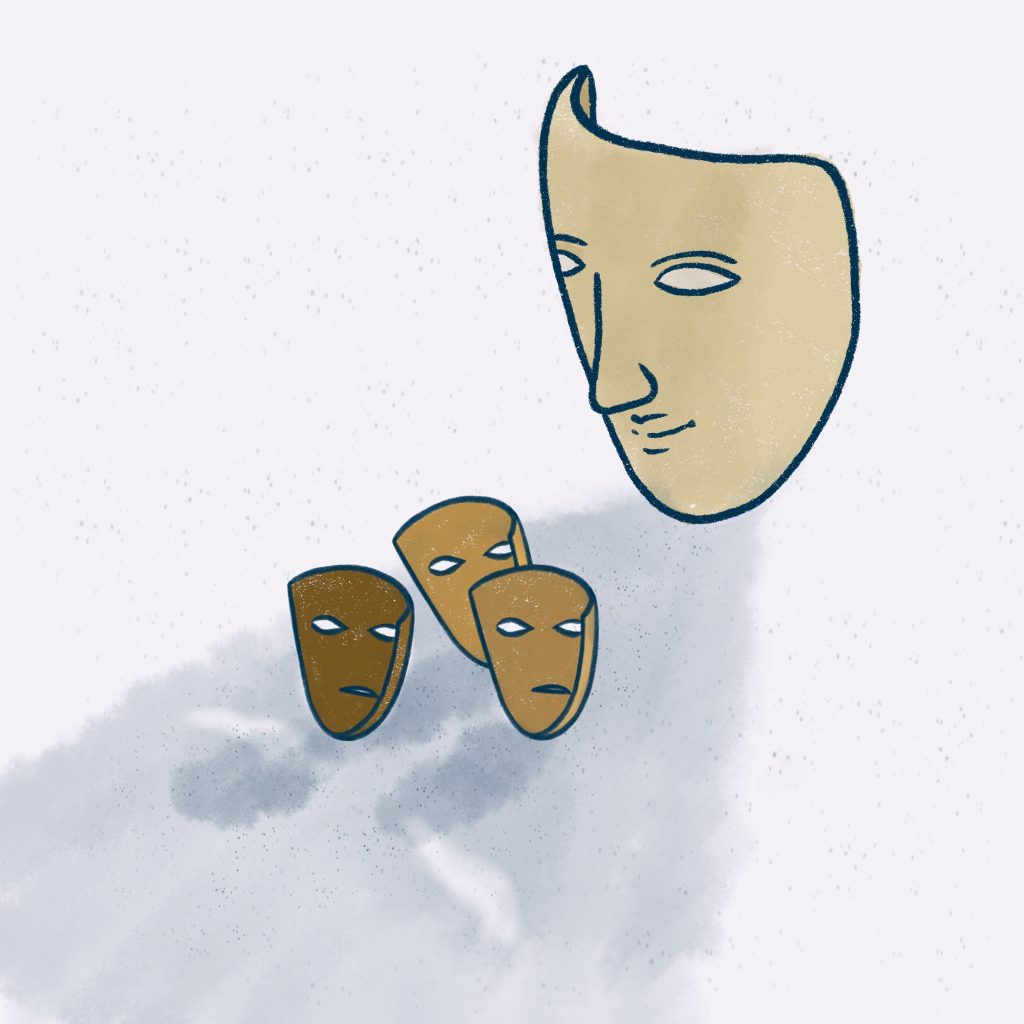
Diskriminasi pada umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok dominan, yaitu pihak yang memiliki kekuasaan, hak istimewa, atau status sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, objek diskriminasi adalah pihak yang diposisikan berbeda, lebih rendah dan dengan sengaja dipinggirkan. Dengan adanya diskriminasi, kelompok ini mendapatkan batasan yang tidak perlu dihadapi oleh kelompok lain.
Diskriminasi juga sering membuat kelompok yang menjadi objek diskriminasi tidak berdaya, terutama bila situasi diskriminatif ini didukung atau diatur oleh pihak pemegang kekuasaan. Situasi ini disebut sebagai diskriminasi struktural, yaitu ketika serangkaian peraturan dan regulasi hanya menguntungkan suatu kelompok dan merugikan kelompok lainnya.
Banyak peristiwa yang tercatat dalam sejarah dunia menunjukkan diskriminasi struktural, misalnya perdagangan budak dari Afrika ke Amerika dan Inggris, penerapan kebijakan anti-semitis yang diterapkan pemerintah Nazi terhadap kelompok Yahudi, politik Apartheid di Afrika Selatan, serta penyingkiran etnis Rohingya di Myanmar.
Diskriminasi terjadi ketika perbedaan – dalam bentuk apapun – dilihat sebagai pembenaran untuk memberikan perlakuan yang juga berbeda. ~ Yudi Bachrioktora Share on XDi Indonesia, praktik diskriminasi dalam berbagai bentuk juga masih terus berlangsung. Salah satu bentuk diskriminasi yang sudah terjadi sejak masa kolonial adalah diskriminasi rasial. Pada masa penjajahan, pemerintahan kolonial Belanda berusaha mempertahankan posisi istimewa yang mereka miliki di Hindia Belanda dengan menempatkan kelompok masyarakat Timur asing dan pribumi sebagai warga negara kelas dua dan tiga. Bagi kelompok pribumi yang ditempatkan pada posisi paling bawah, sistem ini mempersempit akses mereka terhadap pekerjaan dan pendidikan. Sedangkan kelompok priyayi dan masyarakat Timur asing seperti orang Tionghoa dan Arab mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan pribumi rendahan, meskipun tetap tidak sama dengan kelompok kulit putih yang menempati posisi tertinggi.
Setelah kemerdekaan, diskriminasi rasial masih dipraktikkan di Indonesia. Pemerintah Orde Baru bahkan membuat kebijakan rasial yang khusus ditargetkan bagi kelompok Tionghoa. Dalam catatan ELSAM, sebuah lembaga nirlaba mengadvokasi isu hak asasi, yang di tahun 2010, selama pemerintahan masa orde baru tercatat 54 peraturan skala nasional yang bersifat diskriminatif dengan 35 diantaranya secara khusus ditujukan untuk etnis Tionghoa. Melalui berbagai peraturan mengenai agama, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya tersebut, pemerintah mencampuri aspek pribadi dalam kehidupan masyarakat.
Banyaknya peraturan yang secara khusus dibuat untuk membatasi hak-hak etnis Tionghoa mempertebal pembedaan antara pribumi dan ‘nonpribumi’. Salah satu peraturan yang sangat diskriminatif, yang ditujukan khusus untuk etnis Tionghoa di Indonesia adalah diberlakukannya pembuktian berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI). Imbas perlakuan diskriminatif ini adalah semakin dalamnya prasangka dan kecurigaan terhadap anggota masyarakat yang berasal dari kelompok yang berbeda – atau lebih tepatnya, kelompok yang diposisikan berbeda. Manifestasi pembedaan ini adalah tertanamnya kebencian terhadap etnis Tionghoa, yang berujung pada pecahnya konflik rasial dan pengusiran terhadap kelompok masyarakat Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.
Tanpa cara berpikir yang adil dan tidak berprasangka maka diskriminasi akan selalu ada. ~ Yudi Bachrioktora Share on XSelain diskriminasi rasial, pembedaan perlakuan terhadap suatu kelompok di Indonesia juga didasari pada agama. Pemerintah Indonesia yang hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu, secara langsung membatasi perkembangan agama atau kepercayaan di luar enam agama tersebut. Padahal, banyak masyarakat adat di berbagai tempat di Indonesia memiliki sistem kepercayaan tersendiri.
Dengan hanya diakuinya enam agama, pemerintah Indonesia mengeksklusi (dan mengabaikan) hak warganya yang berada di luar kelompok enam agama tersebut. Pengabaian hak ini misalnya terlihat dari pernikahan yang tidak dianggap legal bila dilakukan oleh individu yang tidak menganut salah satu agama yang diakui oleh negara. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak dapat memiliki akta kelahiran, yang merupakan dokumen pokok bagi warga negara. Dalam konteks agama yang secara resmi diakui pun, perlakuan diskriminatif kerap ditemui, misalnya dalam kasus pengusiran terhadap Jemaah Ahmadiyah atau proses mendapatkan izin mendirikan tempat ibadah bagi pemeluk agama Kristen yang dipersulit.
Praktik diskriminasi juga terjadi terhadap perempuan. Dalam siaran persnya , Komnas Perempuan menyatakan terdapat 421 kebijakan yang diterapkan di Indonesia merugikan perempuan. Kebijakan tersebut berupa 235 Peraturan Daerah dan surat edaran serta keputusan kepala daerah, mulai dari tingkat kelurahan hingga desa. Sebanyak 333 kebijakan tersebut secara khusus ditujukan untuk perempuan, misalnya larangan keluar malam dan kewajiban penggunaan jilbab.
Kelompok LGBTQ+ juga kerap mendapat perlakuan diskriminatif karena keberadaan mereka saat ini masih mendapat tentangan yang cukup kuat dalam masyarakat. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh LBH Masyarakat, sepanjang tahun 2017 terdapat 973 orang yang menjadi korban stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT di berbagai tempat di Indonesia.
Baik secara sistematis melalui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah maupun perilaku dalam keseharian yang didasari oleh prasangka yang secara simultan direproduksi dan disebarluaskan melalui media, diskriminasi terjadi ketika perbedaan – dalam bentuk apapun – dilihat sebagai pembenaran untuk memberikan perlakuan yang juga berbeda. Relasi kuasa memungkinkan salah satu pihak merasa berhak untuk mengabaikan hak pihak lain untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Pada prinsipnya, negara harus melindungi setiap orang dari tindakan diskriminatif tanpa memandang ras, suku, agama atau jenis kelamin. Namun, pada kenyataannya berbagai bentuk diskriminasi masih menjadi bagian dari keseharian di Indonesia.
Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer yang paling dikenal adalah bahwa kita “harus belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Dengan kata lain, Pram mengingatkan bahwa tanpa cara berpikir yang adil dan tidak berprasangka maka diskriminasi akan selalu ada terhadap orang-orang yang kita anggap berbeda.
| Brigitta Hauser-Schaublin and David D. Harnish (Eds). Between Harmony and Discrimination. Negotiating religious identities within majority-minority relationship in Bali and Lombok. Leiden: Brill, 2014 Karla Perez Portilla. Redressing Everyday Discrimination. London: Routledge, 2016 Tim Lindsey and Helen Pausacker (Eds). Religion, Law and Intolerance in Indonesia. London: Routledge, 2016 Leo Suryadinata. Dilema Minoritas Tionghoa. Jakarta: Grafiti Press, 1986 |

Yudi Bachrioktora adalah mahasiswa S3 di Institute of Social Anthropology, Universitas Bern, Swiss. Ia adalah pengajar di Departemen Sejarah FIB UI dan peneliti di Agrarian Resources Center (ARC), Bandung. Sejak tahun 2000 mulai aktif menggeluti isu-isu agraria dan lingkungan hidup di Indonesia.
Siapa pun bisa punya pengalaman, pemikiran, dan gagasan. Kirim dulu pikiranmu, overthinking belakangan.
© 2024 Anotasi. Dibuat dengan hati dan puluhan gelas kopi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart