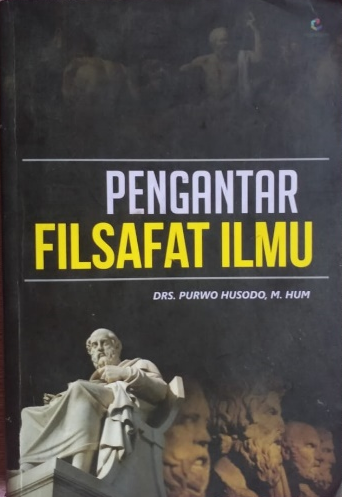
Pengantar Filsafat Ilmu: Mengenal Filsafat
December 4, 2020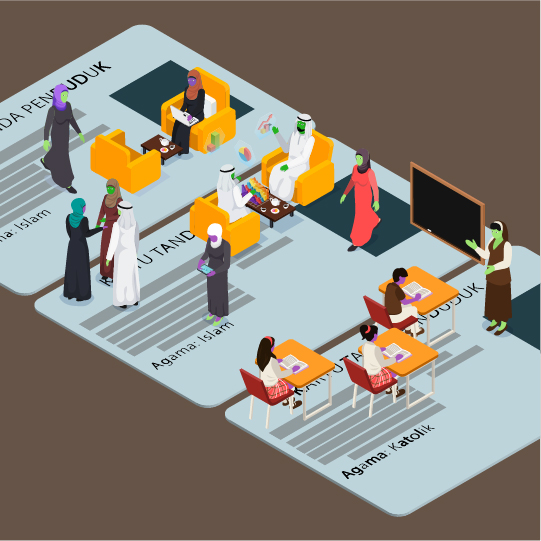
Fungsi Agama di Masyarakat
December 16, 2020Makna
Cari Suara dengan Agama: Apa, Kenapa, Harus Bagaimana
oleh Nathanael Sumaktoyo
Saya menulis ini November 2020, saat sedang ramai-ramainya berita tentang Habib Rizieq Shihab (HRS). Setelah tiga tahun tinggal di Saudi Arabia, petinggi Front Pembela Islam (FPI) ini kembali ke Indonesia pada 10 November 2020. Simbolisme yang luar biasa, karena 10 November juga diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Ada banyak alasan kenapa HRS membuat ramai. Ia dijemput di bandara oleh ribuan pendukung. Pernikahan putrinya juga dihadiri ribuan orang. Hal-hal ini ramai bukan hanya karena melibatkan banyak orang, tapi juga karena terjadi di saat negara sedang menghadapi COVID-19 yang mudah sekali menyebar lewat kerumunan massa.
Kemampuan HRS menarik massa memang menarik. Tapi yang lebih menarik bagi saya adalah kemampuannya menarik politisi. Beberapa hari setelah tiba di Indonesia, HRS langsung menerima kunjungan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Bahkan ketika masih di Saudi, HRS sering kali dikunjungi politisi, misalnya Fadli Zon, Amien Rais, hingga Prabowo Subianto.
Kenapa politisi merasa perlu untuk mendekat ke HRS? Atau, lebih luas lagi, kenapa kita sering melihat politisi mencari dukungan dari tokoh agama atau menggunakan retorika agama dalam kampanye? Kenapa agama seakan sulit lepas dari politik? Apa sebenarnya hubungan politik dan agama?
Politisasi Agama sebagai Politik Identitas
Politik, seperti kata ilmuwan politik Harold Lasswell, adalah soal siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana (who gets what, when, and how). Akan panjang kalau kita bahas setiap komponennya (siapa, apa, kapan, bagaimana). Kita fokus ke bagian “bagaimana” saja karena agama terkait dengan bagian ini.
Pada prinsipnya, politisi mau menang. Entah menang pemilu atau memenangkan jabatan tertentu. Untuk menang, dalam demokrasi, kuncinya adalah mendapatkan dukungan pemilih. Setidaknya ada dua cara untuk menarik pemilih. Pertama, lewat program. Politisi membuat program yang diyakini akan disukai orang banyak, misalnya program jaminan sosial atau program perluasan lapangan kerja. Logikanya, ketika pemilih menyukai program seorang politisi, maka mereka akan memilih politisi tersebut dalam pemilu sehingga programnya bisa terwujud.
Cara kedua adalah lewat politik identitas. Manusia adalah makhluk sosial. Kita senang terhubung dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok. Semakin banyak teman kita atau semakin kita merasa menjadi bagian dari kelompok sosial yang besar dan signifikan, maka semakin kita merasa hidup kita bermakna dan semakin puas kita dengan hidup. Singkatnya, koneksi dan kelompok sosial penting bagi manusia.

Karena itu, masuk akal kalau politisi kemudian mencari dukungan dengan cara mengasosiasikan dirinya dengan kelompok identitas tertentu (misal, pemilih Muslim, pemilih Jawa, pemilih Batak). Harapannya, anggota-anggota kelompok tersebut akan melihat si politisi sebagai bagian dari kelompok mereka dan karenanya mendukung si politisi dalam pemilu atau kontes politik lain.
Ilmuwan sosial menyebut strategi ini politik identitas. Identitas di sini bisa bermacam-macam. Dalam konteks kunjungan politisi ke HRS, identitasnya adalah agama (Islam), khususnya pemilih Muslim konservatif yang mungkin bersimpati dengan FPI atau HRS. Dalam Pilkada Jakarta 2017, identitas agama berbaur dengan identitas etnis dalam bentuk sentimen anti-Tionghoa.
Kenapa Agama?
Bila politik identitas bisa memakai identitas apapun, kenapa agama yang paling sering dipakai kampanye di Indonesia? Ada tiga alasan.
Pertama, di Indonesia agama merupakan identitas yang dominan dan kentara. Rumah ibadah ada di mana-mana. KTP pun mencantumkan agama. Karena identitasnya sendiri sudah ada dan sudah dominan, politisi tidak perlu lagi membentuk identitas itu dari nol. Politisi hanya perlu menunjukkan bahwa dirinya adalah anggota yang baik dari kelompok identitas tersebut. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditunjukkan antara lain dengan meminta dukungan HRS atau ulama lain, dengan mengutip ayat saat kampanye, atau dengan mendukung peraturan daerah bernuansa syariah.
Kita perlu membudayakan mengkritik, mengoreksi, bahkan mengecam pihak yang memakai agama, etnisitas, atau identitas lain untuk kepentingan politik. ~ Nathanael Sumaktoyo Share on XAlasan kedua adalah agama memang identitas yang kuat. Berbeda dengan identitas lain seperti etnisitas atau gender, agama mengatur bukan hanya kehidupan di dunia ini tapi juga kehidupan setelah dunia ini. Agama juga melintas batas negara. Karena kesamaan agama, seorang Muslim di Indonesia bisa merasa bersaudara dengan Muslim lain di Palestina atau di Eropa. Seperti dijelaskan di atas, semakin kuat identitas kelompok, semakin besar efeknya bagi perilaku pemilih.
Alasan ketiga adalah agama memberi ruang penyangkalan. Politik identitas, meskipun populer, bisa berbalik menyerang politisi yang melakukannya. Misalnya, pemilih bisa tidak suka dan menganggap seorang politisi rasis karena memanfaatkan etnisitas untuk menyerang lawan politik. Tapi agama berbeda. Bila seorang politisi memakai agama untuk menyerang lawan politik (misalnya, lewat anjuran untuk tidak mendukung politisi yang berbeda agama), si politisi bisa beralasan bahwa ia hanya menjalankan perintah agama. Retorika agama dengan demikian memberi politisi ruang penyangkalan yang melindunginya dari potensi kritik pemilih.
Harus Bagaimana?
Kita sudah lihat apa itu politik identitas dan kenapa politik identitas berbasis agama laris manis di Indonesia. Bagaimana kita harus menyikapi politik identitas ini? Ada berbagai strategi tentang bagaimana kita harus merespon politik identitas. Saya akan fokus pada dua strategi.
Strategi pertama terkait dengan penjabaran di atas bahwa politisasi agama pada dasarnya adalah upaya politisi untuk mendapatkan dukungan publik. Dengan kata lain, politisi melakukan politik identitas karena menganggap politik identitas menguntungkan.
Kita bisa merespon politik identitas dengan memodifikasi kalkulasi politik ini. Secara spesifik, kita perlu membangun budaya kontra politik identitas. Kita perlu membudayakan mengkritik, mengoreksi, bahkan mengecam pihak yang memakai agama, etnisitas, atau identitas lain untuk kepentingan politik, terutama bila identitas-identitas ini dipakai untuk menyerang lawan politik.
Budaya ini bisa dimulai dari para elit, dari media massa, atau bahkan lewat media sosial kita. Logikanya, bila budaya kontra politik identitas ini semakin kuat, ia akan mengubah kalkulasi politik para politisi. Politisi akan dipaksa berpikir dua kali bila ingin memakai agama untuk kepentingan politik karena alih-alih mendapat suara, ia mungkin malah akan menuai kecaman dan kehilangan pendukung.
Strategi kedua terkait dengan pandangan bahwa larisnya politik agama menunjukkan masyarakat kita belum rasional dan karenanya pendidikan adalah solusi mujarab untuk politik identitas. Strategi ini benar, tapi kurang lengkap. Yang kita butuh bukan sekedar pendidikan. Yang kita butuh adalah pendidikan yang membangun budaya berpikir kritis.
Pembedaan ini perlu karena nyatanya pendidikan kita belum menanamkan budaya berpikir kritis. Menurut Program untuk Penilaian Siswa Internasional (PISA), siswa sekolah di Indonesia memiliki kemampuan matematika, membaca, dan ilmu pengetahuan alam yang sangat rendah. Sebagai contoh, kemampuan membaca siswa Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara. Kemampuan membaca yang rendah ini sangat menyedihkan karena ia menunjukkan bahwa peserta didik di negara kita bisa membaca, tapi kesulitan memahami secara kritis apa yang dibaca.
Budaya berpikir kritis akan membantu mengerem dampak negatif politik identitas. Politik identitas mengandalkan keanggotaan kelompok dan retorika kita versus mereka. Tujuan politik identitas adalah membangkitkan emosi. Tujuan ini akan lebih sulit tercapai bila masyarakatnya kritis dan tidak menelan mentah-mentah retorika identitas oleh politisi. Politik identitas juga akan melemah bila masyarakatnya kritis dan menilai politisi berdasar pada program dan rekam jejak, bukan hanya kesamaan etnis atau agama.
Soekarno pernah menulis, “Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.“ Politik identitas yang berlebihan mengancam ide kebangsaan ini. Tidak mungkin mewujudkan Indonesia untuk semua bila sejak dalam pikiran kita sudah tidak adil dan membagi-bagi Indonesia berdasar agama, etnisitas, atau identitas lain.
Indonesia untuk semua membutuhkan usaha dari semua. Butuh negara dan aparat yang berani menindak politisasi identitas yang mengarah ke kekerasan. Butuh media yang bebas untuk memberitakan fakta selugas-lugasnya. Butuh sistem pendidikan yang menanamkan sikap kritis. Serta butuh masyarakat yang mau dan berani mengecam politisi yang memakai kesamaan identitas sebagai cara utama mengumpulkan dukungan.
Bacaan Lebih Lanjut
| Bacaan Lanjutan Buehler, Michael. 2016. The Politics of Shari’a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. Menchik, Jeremy. 2016. Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism. New York, NY: Cambridge University Press. Monroe, Kristen Renwick, James Hankin, and Renée Bukovchik Van Vechten. 2000. “The Psychological Foundations of Identity Politics.” Annual Review of Political Science 3(1): 419–47. Putnam, Robert D., and David E. Campbell. 2010. American Grace: How Religion Divides and Unites Us. New York, NY: Simon & Schuster. |

Nathanael Sumaktoyo adalah peneliti sosial politik di University of Konstanz, Jerman. Ia menyelesaikan program doktor ilmu politik di University of Notre Dame, Amerika Serikat. Riset-risetnya berkutat pada isu agama, etnisitas, toleransi, perilaku politik, dan metodologi kuantitatif. Tulisan-tulisannya (baik di jurnal ilmiah maupun di outlet popular) bisa diakses di website http://nathanael.id atau melalui akun Twitter @nathanaeldotid.
Artikel Terkait
Mungkinkah Teologi Baru Berkembang di Tanah Air?
Teologi adalah ilmu tentang ketuhanan untuk memahami Tuhan dan ajaran keagamaan melalui penalaran intelektual. Artikel ini membahas bagaimana setiap agama memaknai teologi secara berbeda-beda dan ada upaya untuk memperluas maknanya untuk mengikuti perkembangan zaman.Memahami dan Memaknai Minoritas
Walau Indonesia adalah negara yang beragam, masih banyak orang yang merasa hidupnya terancam. Di Catatan Pinggir ini, Dyah Kathy, seorang analis untuk studi konflik di Jakarta, berbagi tentang pengalamannya menghadapi dan mengkaji kekerasan berbasis agama.Fungsi Agama di Masyarakat
Agama dan ide-ide keagamaan berfungsi sebagai jembatan bagi obsesi spiritual manusia untuk bisa memahami tuhan terhadap diri dan dunianya. Artikel ini melihat bahwa agama juga perlu dibahas dari sudut pandang yang lebih ‘membumi’, yaitu dari sudut pandang sosial.





